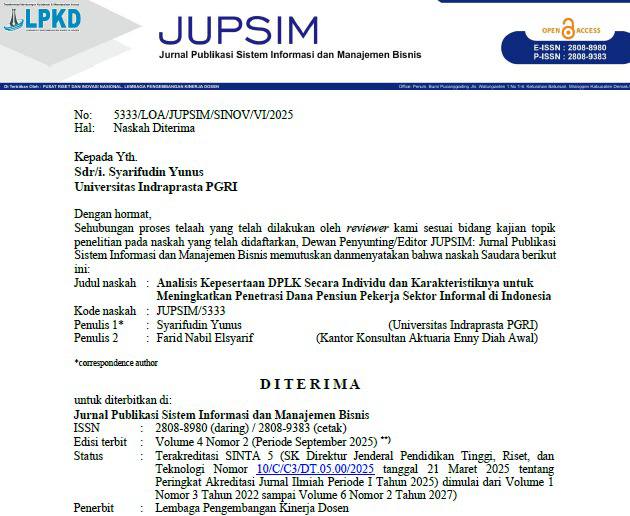Perempuan Bali dalam Citraan dan Laku Berkesenian
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Mengapa belakangan lebih banyak bermunculan penulis sastra perempuan dari Bali? Adakah latar historis mempengaruhinya?
Belum lama ini saya diundang dalam sebuah acara pertemuan sastra di Padang, diberi tajuk sangat menarik: Padang Literary Biennale. Panitia menawarkan satu topik diskusi yang sangat menarik kepada saya, yakni ‘Perempuan dan Puisi’—bukan tentang penyair perempuan ataupun perempuan yang menyair. Ini artinya, panitia telah secara baik mempertimbangkan agar bahasan dialog tidak larut pada wacana gender dalam kepenyairan, seolah-olah ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan yang menulis sajak—hal-hal yang pada perkembangan susastra terakhir agaknya lebih berkembang sebagai perbincangan yang personal sifatnya.
Tema ini bisa dikembangkan dalam konteks yang lebih luas. Pertama, bagaimana para perempuan era kini mengekspresikan dirinya lewat puisi. Kedua, sejauh mana puisi kita merepresentasikan isu-isu perempuan di dalamnya. Ketiga, bagaimana tatanan sosial masyarakat lokal kita yang patrilineal maupun matrilineal menyediakan ruang kreasi bagi perempuan. Atau keempat, mungkinkah karya-karya puisi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi kaum perempuan dewasa ini.
Selama beberapa kurun waktu belakangan, muncul nama-nama pengarang perempuan dari Bali. Ada yang menyair. Tak sedikit juga yang membuat prosa cerpen ataupun novel. Penulis seperti Oka Rusmini, Cok Sawitri, Pranita Dewi, Frischa Aswarini, Sudiani, Rastiti, Sonia Piscayanti, dan lain sebagainya mengemuka lebih intens bagai hendak menyalip kreativitas para pengarang laki-laki di Bali. Adakah kondisi sosiologis seperti anutan garis patriarkhi mendorong perempuan Bali dalam mengeskpresikan diri? Saya tidak bisa menjawabnya secara pasti. Terus terang, ada banyak penulis laki-laki di Bali, dan mengapa nama mereka tak mewangi seperti yang wanita, memerlukan kajian yang lebih mendalam lagi. Dugaan awal saya, barangkali kondisi ini berpulang pada persona penulis tadi, meliputi intensitas daya cipta serta nilai-nilai estetis karya-karyanya.
Namun, tulisan ini tidak akan menyinggung secara eksplisit perihal keterkaitan perempuan dan puisi. Saya bermaksud meluaskan bahasan konteks perpuisian, khususnya yang berkembang di Bali, tanah lahir saya, ke dalam ranah kepengarangan dewasa ini. Yang menjadi acuannya tentu saja adalah perempuan, sebagai subyek sekaligus obyek berkesenian di Bali dalam perspektif historis-sosiologisnya.
Dari Budak Bali ke Politik ‘Baliseering’
Bila melihat secara historis, sebenarnya ini bukan kali pertama pulau Bali tercitrakan lewat para perempuannya. Untuk itu, saya lebih ingin membagi pengalaman historis dan sosiologis Bali, di mana perempuan seringkali dihadirkan sebagai cerminan molek pulau ini.
Kita awali pada masa kerajaan Bali Kuno, antara masa penaklukan Majapahit terhadap Bali sekitar tahun 1344 M hingga paruh akhir 1890an. Di masa ini, wanita Bali jauh lebih terkenal sebagai budak belian. Pasalnya, kerajaan-kerajaan kecil di Bali—yang juga cikal bakal kabupaten-kabupaten setempat—sering sekali berperang dan menguasai segala taklukannya, entah tanah, hasil alam, serta juga penduduknya.
Beberapa penelitian Bali, termasuk Clifford Geertz dalam buku ‘Negara Teater’-nya menyebutkan persaingan antar kerajaan ini tidak hanya ditunjukan lewat berperang, namun juga penyelenggaraan upacara ritual besar-besaran, dan guna memenuhi biaya-biaya ‘kompetisi’ itu dilangsungkanlah beberapa kegiatan, termasuk di antaranya penjualan candu (opium) serta perdagangan budak sampai keluar pulau.
Salah satu cerita budak Bali yang terkenal adalah kisah Untung Suropati. Mulanya ia budak belian yang dijual di pasar Batavia, yang belakangan berhasil menebus harga kepada majikan sehingga mampu ‘memerdekakan’ diri. Kemudian ia bergabung dengan Kompeni, memiliki sekumpulan pasukan, lantas melakukan pemberontakan, sebelum lantas ditumpas di daerah Bangil, Jawa Timur.
Budak-budak perempuan Bali di masa itu mahal harganya dan selalu dicari-cari. Sebabnya, menurut kajian Dennys Lombard, ini karena mereka dikenal gigih, kuat, dan patuh, meskipun seringnya bersikap kurang teliti. Perempuan yang tidak dijual di pasar budak dan menetap di Bali pun dinilai punya karakter demikian. Hampir seluruh pekerjaan rumah tangga, aktivitas ekonomi, kegiatan sosial dan ritual dikerjakan oleh mereka. Bahkan Geertz pernah menulis: karena seolah tak punya pekerjaan—sebab semua dilakukan oleh para istri maupun saudara perempuannya—para laki-laki Bali seakan selalu punya waktu untuk aktivitas berkesenian atau bahkan judi sabung ayam.
Selain sebagai budak, perempuan Bali dari kerajaan yang ditaklukan juga dipilih sebagai selir sang raja pemenang. Satu cerita yang tragik bahkan terjadi sekitar abad ke-19 di satu kerajaan kecil di Bali. Seorang raja dikabarkan meninggal dan diupacarai dalam ritual pengabenan nan agung. Kala itu masih berlaku adat mesatya, di mana para selir diharuskan terjun ke dalam api pengabenan sang raja sebagai tanda kesetiaannya. Sayangnya, sang raja punya selir berpuluh-puluh banyaknya, sebagian bahkan masih sangat remaja, dan mereka harus terjun dari tempat tinggi untuk menyatu bersama jenazah sang raja….
Awal tahun 1990-an pemerintah kolonial Belanda akhirnya menghapuskan tradisi mesatya ini. Termasuk pula penjualan candu dan perdagangan budak. Namun, apakah dengan kebijakan ini berakhir pula citraan tentang wanita Bali? Ternyata tidak.
Politik 'Baliseering' dari pemerintah kolonial Belanda, diawali tahun 1910an, bertujuan menampilkan citra Bali sebagai pulau surgawi ke masyarakat internasional. Promosi digencarkan melalui publikasi media dan juga aktivitas pameran di berbagai negara Eropa. Sebut saja di antaranya Paris International Exhibition tahun 1931, terbitan buku karya penulis Miguel Covarrubias 'The Last Paradise', serta kartu-kartu pos eksotis tentang Bali. Khusus kartu pos, kebanyakan menampilkan sosok perempuan Bali yang molek: berpose begitu rupa dengan busana setengah telanjang.
Citraan-citraan sensual ini dikemukakan juga oleh pelukis Nieuwenkamp, yang menerbitkan ilustrasi-ilustrasi lengkap mengenai kehidupan sehari-hari orang Bali, termasuk kesenian dan keindahannya yang memikat. Di sisi lain, ada pula seorang akademisi asal Jerman yang bekerja untuk Kolonial Belanda tahun 1912-1914 di Bali, yang berkontribusi penting bagi pelaksanaan promosi-promosi pariwisata Bali, bernama Gregory Krause, yang menulis buku dengan 400 foto keseharian masyarakat Bali. Pada buku ini, sensualitas perempuan Bali menjadi hal yang ditonjolkan, termasuk adegan-adegan fantastis ketika mereka mandi di sungai atau pancuran, layaknya cerita-cerita tradisi seperti kisah Rajapala dan Ken Sulasih (cerita rakyat yang hampir mirip kisah Jaka Tarub). Pada pengantarnya, Krause menyebutkan:
“Penduduk Bali begitu rupawan. Keindahan mereka hampir-hampir tidak dapat dipercaya. Siapa pun yang sekadar duduk di pinggir jalan dan menyaksikan tingkah polah orang-orang di Bali, pastilah akan menyangsikan: sungguhkah hal yang dilihatnya itu benar-benar nyata? Semuanya begitu elok dan molek, baik bentuk tubuh, pose dan setiap geraknya. Bagaimana mungkin orang-orang ini mencapai keselarasan keindahan yang begitu luar biasa, berpadu dengan suasana sekitarnya, yang bila terus dipandang akan membikin rasa penat pelancong manapun seketika lenyap? Bali akan membuat mata siapapun terpikat, selama ia cukup beruntung menghindar dari kemajuan, dengan rumah-rumah pejabat dari pedagang Eropa dan industri pariwisata, hal yang satu-satunya akan mengubah Bali ke dalam dunia ‘peradaban’. (Krause 1930:9-10 dalam Picard, 2006:37).
Khusus mengenai para perempuannya yang jelita, Krause juga menambahkan:
“Perempuan Bali amat cantik, melebihi aneka kecantikan fisiologis yang dapat dibayangkan. Mereka penuh dengan kemuliaan dunia Timur, dengan kesucian yang alami…Semua ini, membuat saya menjadi dendam kepada Tuhan, mengapa saya tidak dilahirkan di Bali.” (Krause 1988:55 dalam Picard, 2006:40)”
Sementara Miguel Covarrubias, yang datang ke Bali setelah sempat membaca tulisan Krause, membuat deskripsi yang kurang lebih serupa. Ia juga menyebutkan, bahwa Bali telah mengambil-alih posisi Tahiti sebagai mitos lokasi pulau-pulau pesisir selatan yang paling digemari. Ia menandaskan:
“Pulau kecil terpencil ini menjadi berita di dunia Barat, setelah beberapa tahun lalu muncul film tentang Bali dengan penekanan khusus pada daya tarik sensualnya. Film-film itu mengemparkan dan kini semua orang tahu bahwa gadis-gadis Bali bertubuh indah dan bahwa penduduk-penduduk pulau ini hidup seperti dalam komedi musikal, penuh dengan upacara mitis nan indah. Judul dari salah satu film tersebut adalah ‘Gonna-gonna’, yang berarti guna-guna dalam bahasa Bali. Bahkan di New York, pulau ini sempat menjadi identik dengan daya tarik seks. Surga terakhir yang baru ditemukan itu menjadi konsepsi romantis abad ke-19 tentang utopia primitif.” (Covarrubias 1937:391).
Jadi, ketika bicara tentang Bali, salah satu yang terbayang seketika oleh masyarakat internasional adalah kemolekan perempuannya. Hal ini terbukti dari betapa antusiasnya para seniman untuk menjadikan perempuan sebagai obyek kreativitas. Film-film seperti Virgin of Bali, Legong, serta dokumentasi visual sebagainya, menghadirkan rupa-rupa perempuan Bali telanjang dada. Begitu juga dengan lukisan, serta beberapa ulasan antropologis. Bahkan, di tahun 1936, menurut Adrian Vickers dalam buku 'Bali, Paradise Created', di satu sudut kota New York, terdapat kafe malam bernama Bali yang saban waktu menampilkan tari telanjang.
Publikasi yang menampilkan perempuan Bali itu memikat begitu banyak turis datang ke pulau ini. Bedanya dengan wisatawan yang kini melancong, orang-orang asing yang berkunjung di masa 1920-1940an itu kebanyakan adalah kalangan intelektual. Mereka terdiri dari peneliti, penulis, pelukis, aktor, sampai politikus, yang masing-masing berinteraksi cukup panjang bersama orang Bali, yang lantas menginspirasi mereka mencipta aneka karya yang terkenal dan makin menambah citra perihal pulau ini. Interaksi lintas pengetahuan antara Timur dan Barat yang memperkaya kreativitas pun terjadi, memunculkan generasi baru seniman Bali—suatu hal yang jarang ditemui dalam dunia pariwisata Bali kini.
Ekspresi Seni
Kecuali susastra, ekspresi para wanita Bali era kini dalam bidang seni rupa, film, musik, fotografi, pertunjukan dan sebagainya, terbilang sedikit dilakukan. Namun, bagaimana cikal bakal tampilnya para penulis Bali?
Kita awali bahasan ini pada tahun 1920an, tatkala media massa lokal mulai tumbuh di pulau ini. Sekitar kurun tersebut, beberapa media seperti Surya Kanta, Bali Adnjana, Djatajoe dan sebagainya telah memperkenalkan nama-nama penulis perempuan yang mengulas tema-tema kontekstual, seperti revolusi kemerdekaan, budaya patriarkhi, serta hak-hak perempuan Bali[1].
Nama mereka memang tak tedengar dalan lingkup nasional, namun tetap tercatat dalam sejarah sastra Bali modern. Hanya saja memang kemudian yang lebih terdepankan muncul sebagai sastrawan adalah kebanyakan penulis laki-laki Bali—yang sebagian secara sadar mengangkat tema perempuan Bali dalam karyanya. Sebut saja novelis Panji Tisna dengan Sukreni Gadis Bali, I Wayan Gobiah sang pelopor sastra Bali modern, dan sebagainya.
Tema-tema yang diangkat tersebut (kasta, ketimpangan hak wanita Bali, sampai dekonstruksi konsep tubuh perempuan) dilanjutkan oleh penulis-penulis Bali dewasa ini. Mereka mengusung satu semangat kesetaraan pria-wanita, serta dipadukan dengan pertautan khazanah lokal dengan konteks Bali yang makin menginternasional lewat promosi pariwisatanya. Kesadaran ini memungkinkan tumbuhnya pandangan baru: bahwa persoalan perempuan Bali pun bisa jadi terjadi di berbagai tempat di dunia. Bahwa masalah mereka adalah soal kemanusiaan secara luas--hal yang membedakan mereka dari penulis Bali sebelumnya.
Berikutnya, apakah tantangan penulis perempuan Bali dalam berkarya? Problem klasik seperti ketegangan urusan domestik (rumah tangga), aktivitas sosial-ritual dan kreativitas berkesenian masih mendominasi. Patut diakui, nama-nama penulis perempuan yang muncul kini adalah mereka yang notabene masih belia usia, dengan tuntutan sosial yang belum banyak terjadi. Mereka—khususnya penulis generasi saya—masih memiliki kebebasan waktu dan peluang dalam berkreasi, sejalan dengan akses pendidikan yang melengkapi ekspresi berkeseniannya.
Penulis dari Bali angkatan kelahiran 1980an dan seterusnya memperoleh nasib yang lebih baik dibandingkan pengarang sebelumnya. Ruang-ruang kebudayaan publik di Bali terus bertumbuh dan memungkinkan kami membuat perbandingan olah kreatif lintas bidang. Akses informasi terbuka lebih luas, seiring dengan cairnya interaksi sosial di titik-titik pertemuan kebudayaan semacam Kuta, Denpasar, Ubud, dan sebagainya.
Tantangan atas kondisi sosial-budaya Bali tentu tetap ada. Etnosentrisme yang menguat dalam wacana nasionalisme dan globalisasi. Lingkungan yang terdegradasi akibat aneka motif kepentingan. Terkikisnya kultur agraris yang tecermin salah satunya dari alihfungsi lahan subur menjadi pemukiman padat penduduk. Atau persoalan perihal pemerataan pendapatan ekonomi pariwisata bagi segenap lapis masyarakat. Dan sebagainya.
Tinggal berikutnya bagaimana penulis-penulis muda ini berkutat menyikapinya, agar tidak semata lena pada citra eksotisme atas Bali dan mulai merespon masalah senyatanya dalam karya-karya kreatifnya. Maka dari itu, saya kira para penulis Bali, tanpa memandang gender apapun, harus mampu meluaskan pandang dan membuka medan kesadaran baru: menjadikan tema ketidaksetaraan antara pria dan wanita sebagai permasalahan kemanusiaan yang lebih luas lingkupnya, sekaligus mengolah topik kelokalan guna menemukan nilai keglobalan yang universal.
2015
Foto: seorang perempuan Bali tempo dulu membantu pelaksanaan ritual agama (hasil karya J. Kersten)
[1] Simak kajian Nyoman Darma Putra ‘Perempuan Bali Tempo Doeloe’ dan riset terbarunya A Literary Mirror; Balinese Reflections on Modernity and Identity in the Twentieth Century (KITLV Press, 2011),
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Di Ketinggian Penjara Lampau
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Lumut Mengikis Batuan
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0




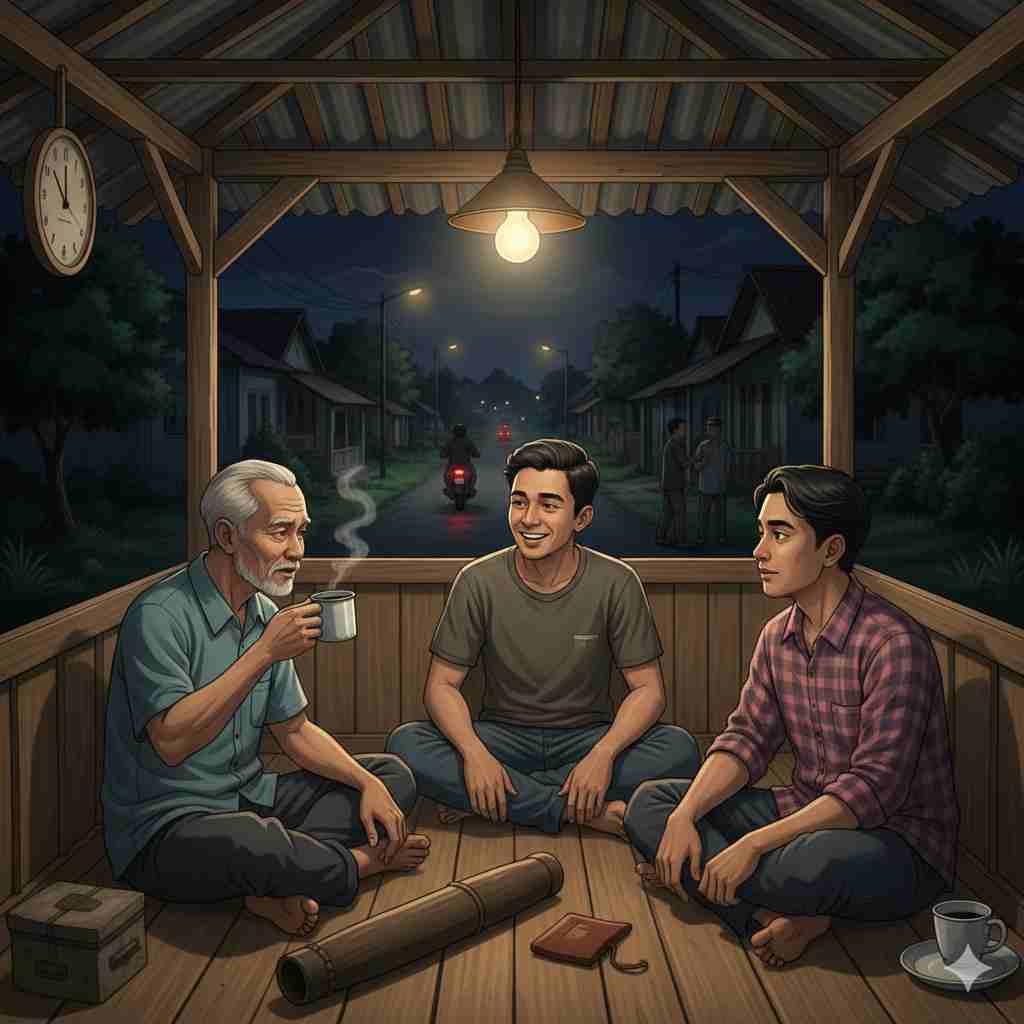

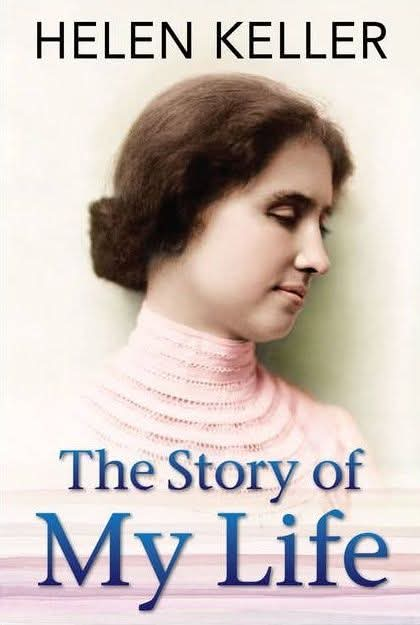
 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 97
97 0
0