Chairil dan Warisan yang Puitik di Sudut Cikini
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Sudut Cikini sore itu pun terbuat dari rasa penasaran sekelompok manusia –termasuk saya- yang mengolonikan diri demi satu nama.
Jakarta sebetulnya teduh dan asyik jika seperti minggu sore lalu. Saat petrichor tercium nyaris samar sebagai anti-klimaks atas hujan yang bersambung gerimis. Hampir seharian. Roda-roda kendaraan yang menggilas aspal Jalan Cikini Raya melaju harmonik, seakan memainkan putaran yang puitik. Jauh dari umpatan para pengendara yang berebut tak sabaran saat lalu lintas padat pada hari-hari normal.
Sebuah ruang bersama dengan luas hanya beberapa hasta, menjadi kubus yang sebenarnya tidak menarik. Jika disandingkan dengan kebingaran disekitarnya: julangan hotel-hotel mentereng, café-café yang mendisplay menu aduhai, atau toko-toko retail dengan selasar yang nyaman untuk berselancar. Tetapi, toh akhirnya, ruang kubus dengan kaca bening hampir yang memenuhi sisi depannya, cukup menarik langkah saya untuk jauh-jauh kesana. Setelah melewati sepuluh stasiun kereta, sebelum akhirnya menyambung dengan ojek. Ruang bersama yang terletak di sudut Cikini itu bernama Ke:Kini.
Sudut Cikini sore itu pun terbuat dari rasa penasaran sekelompok manusia –termasuk saya- yang mengolonikan diri demi satu nama yang kelampauannya dan relevansinya dengan masa kini begitu tarik-menarik kuat: Chairil Anwar. Membaca Chairil menjadi tajuk utama yang menaungi tiga seri acara. Pertama, tur sejarah yang digawangi oleh Jakarta Good Guide. Kedua, diskusi buku biografi Chairil Anwar karya Hasan Aspahani yang dimoderatori oleh Gagas Media selaku penerbit buku tersebut. Ketiga, -sekaligus mungkin yang paling puncak- malam puisi gelaran Komunitas Malam Puisi Jakarta. Siapapun yang menyukai sejarah dan sastra akan sulit menghapus nama Chairil Anwar untuk tidak ditelisik dan didalami lebih jauh.
Saya terlambat datang. Jika ingin mengikuti serangkaian acara secara utuh, seharusnya saya datang sejak dua jam lalu. Walhasil, ketika memasuki Ke:Kini, saya hanya menemukan beberapa orang panitia acara. Ada satu orang yang juga terlambat, tapi lebih dulu datang ketimbang saya. Sementara beberapa orang berdiri di depan pintu masuk. Satu-dua orang terlihat gemas mengamati layar ponselnya. Satu-dua lagi seperti sedang berbasa-basi. Saya ketinggalan tur sejarah, dan hanya bisa menunggu seri acara selanjutnya: diskusi buku.
“Mbak, silahkan masuk! Sepatunya dibuka, ya. Nanti kita lesehan disini. Arah duduknya menghadap sana, ya!” Sapa seorang panitia begitu saya hendak masuk dengan tergesa-gesa dan turut melibatkan pula alas sepatu saya.
Saya nyengir sambil membayangkan, diskusi buku yang akan berlangsung ala-ala lesehan? Asyik juga kedengarannya. Tentu saja ada bangku dan meja untuk moderator dan si penulis buku. Di sisi kanan perangkat tamu tersebut, ada banner buku biografi Chairil karya Hasan Aspahani. Buku yang diklaim sebagai buku biografi Chairil terlengkap berikut dengan intrik-intrik rinci drama kehidupan penyair yang menyebut dirinya sebagai Binatang Jalang itu.
Beberapa buku tertata diatas meja, sampulnya dominan putih dengan efek seperti lekukan kertas. Sederhana saja judulnya, “CHAIRIL” diikuti oleh dua kata lainnya: Sebuah Biografi. Cover tersebut sekilas mirip lukisan, kata “CHAIRIL” seperti dilukis dengan cat merah, kemudian ditindih oleh kuningnya tandatangan Chairil. Bagian tengah adalah ilustrasi sepotong wajah Chairil yang populer di kepala kita. Monokrom, tapi seperti berada diatas tumpahan cat merah campur jingga yang encer.
Ruangan samakin ramai dengan datangnya peserta tur sejarah yang baru saja mengkhatami rute RS Cipto Mangunkusomo-Kampus UI Salemba-Metropole-TIM-dan Ke:Kini. RS Cipto Mangunkusumo yang dulunya bernama RSUP CBZ, menjadi bagian dari rangkaian tur tersebut tersebab disanalah tempat-tempat terakhir Chairil. Penyair yang terkenal dengan banyak penyakit yang menjangkitinya itu dulu sering bolak-balik RSUP CBZ. Kemudian, Kampus Salemba menjadi tempat yang cukup sering dicumbu oleh jejak kaki Chairil. Sebab disanalah ia sering menyambangi Ida Nasution, mahasiswa FS UI, sekaligus menjadi perempuan pertama yang disebut dalam sajaknya. Selanjutnya, Metropole (yang pada zaman itu belum menjadi bioskop) adalah -jika meminjam istilah generasi milenial- tempat ‘nongkrong’ Chairil. Seketika saya membayangkan, seorang tirus, kurus, menenteng buku-buku puisi karya sastrawan dunia, mengampit rokok, dan berjam-jam duduk anak tangga atau selasarnya: mungkin bayangan Chairil berpuluh-puluh tahun lalu. TIM sebenarnya tidak ada hubungan historis-linear dengan Chairil, tapi perjalanan kembali ke Ke:kini memang melewati TIM. Sehingga TIM menjadi tempat mampir sejenak untuk mengenalkan Raden Saleh, sang pelukis kenamaan.
“Kita masih nunggu satu rombongan tur sejarah lagi, ya. Udah menuju kesini sih dari TIM.” Ujar pembawa acara untuk menenangkan kami. Kami yang mulai gusar karna rasa penasaran yang tambah mengepung di ruangan itu.
Sambil menunggu, saya teringat dengan seorang teman pernah begitu mengkritisi “pemujaan” yang berlebihan terhadap Chairil. Ia sampai menyimpulkan "pemujaan" karena kentara banyak sekali acara-acara yang masih mengedepankan Chairil sebagai bintang utamanya. Baik acara sastra sendiri, maupun acara-acara berbau nasionalis.
"Kenapa masih Chairil? Itu karena generasi sekarang ini yang susah move on, yaz. Kurang percaya diri. Senang berdiri dibalik nama besar seseorang. Bukannya banyak-banyakin karya, malah masih betah mendewakan orang yang sudah gak relevan lagi dengan zaman.”
Kurang lebih begitulah pendapatnya. Saya tak lantas mengiyakan atau mendebat. Iya, ada benarnya. Ketimbang bertungkus-lumus dengan terus menerus mendiskusikan Chairil, kenapa bukan lebih banyak menghasilkan karya saja? Sudah saatnya menjadi bangsa yang percaya diri, bukan bangsa kerdil yang melulu berdiri dibalik nama-nama besar nan legendaris. Atau memang seorang master dalam suatu bidang hanya lahir satu abad sekali?
Pendapat teman saya itu pun layak didebat, karena setelah saya mempelajari sejarah Chairil, bagi saya, mewariskan Chairil artinya mewariskan semangat pembebasan jiwa. Saya pernah menulis juga soal Chairil Muda, Ikon Kemerdekaan Jiwa. Meski banyak tokoh pembebasan jiwa lainnya, namun barangkali Chairil lah yang menjadi paling kontras. Disaat ada pilihan lain, ia menjadi satu-satunya penyair benar-benar menggantungkan hidup dari puisi-puisinya. Dengan sangat sadar, Chairil mengambil pilihan dengan konsekuensi yang tidak datar, penuh onak dan tragedi di dalamnya: bukti kemerdekaan jiwanya. Totalitas, ekstrimis, atau apalah. Barangkali benar kata Hasan Aspahani, tak lagi ada penyair yang menulis puisi seperti Chairil menulis puisi.
Setelah semua rombangan genap kembali, diskusi buku dibuka oleh pembacaan puisi. Dua orang dari Komunitas Malam Puisi Jakarta yang menyelinap diantara kami, bergantian membacakan “Penerimaan” dan “Cintaku Jauh di Pulau”.
Hasan Aspahani yang menjadi penghubung antara kami dan Chairil sore itu, mengawali cerita tentang proses penulisan buku dan drama-drama yang pernah terjadi di kehidupan Chairil. Diskusi sore itu lumayan cair dengan moderator yang punya wawasan luas soal sastra, selain wawasan untuk melucu, tentu saja. Sebenarnya untuk sekedar tau mengenai garis besar biografi Chairil, mudah saja mencari lewat studi literatur di internet. Tetapi yang membuat buku itu komplit adalah cerita-cerita yang diunggah langsung oleh Hasan dari saksi sejarah Chairil – yang masih hidup. Terkhusus untuk Evawani, anak tunggal Chairil, Hasan mendatangi Eva justru ketika naskah bukunya sudah selesai.
Hasan dalam diskusi itu menguliti sedikit demi sedikit isi bukunya: dari masa kecil Chairil, perempuan-perempuan Chairil, sampai isu plagiarisme. Satu jam berlalu, setelah sesi tanya-jawab, diskusi tersebut ditutup dengan (lagi-lagi) pembacaan puisi oleh Hasan.
Aku berkisar antara mereka sejak terpaksa
Bertukar rupa di pinggir jalan, aku pakai mata mereka
pergi ikut mengunjungi gelanggang bersenda:
kenyataan-kenyataan yang didapatnya.
(bioskop Capitol putar film Amerika,
lagu-lagu baru irama mereka berdansa)
Kami pulang tidak kena apa-apa
Itulah penggalan “Aku Berkisar diantara Mereka” yang diakui Hasan sebagai puisi Chairil favoritnya.
Sebenarnya ada yang paling membuat saya resah. Saat bagian cucu Chairil (yang datang pada diskusi itu), ditanya soal Chairil. Ia yang memang tidak pernah mendapat banyak cerita dari ibunya (Evawani) mengenai siapa Chairil. Karna Evawani pun hanya sempat mengenal ayahnya sampai usia setahun lebih. Apa yang diingat bayi sebegitu mudanya tentang sosok Ayah? Evawani memang tak memiliki ingatan yang memadai tentang Chairil. Bahkan ia tau bahwa Chairil adalah ayahnya ketika kelas 3 SD saat ada wartawan yang mendatanginya dan bilang, “Kamu anak Chairil.”
Cucu Chairil, yang bersila sambil memangku anak perempuannya, mengaku bahwa sampai saat ini dialah yang memang masih sering menemani Evawani –atau bahkan dia sendiri- untuk menghadiri undangan-undangan yang berkaitan dengan ‘acara’ Chairil. Termasuk wawancara dan sebagainya. Saya lebih tertarik memperhatikan anak perempuan dalam pangkuannya. Cicit Chairil itu berambut hitam lurus sebahu, mungkin usianya tiga tahunan. Dia mungkin tak mengerti sedang apa dan dimana. Kecuali berhasil mengenali pemandangan meja dihadapannya, yang diatasnya adalah tumpukan buku dengan ilustrasi sepotong wajah laki-laki. Atau mungkin banner yang menampilkan potongan wajah itu dengan skala lebih besar, yang lebih menarik perhatiannya. Cicit Chairil, yang berjarak ribuan hari dari masa hidup Chairil, di hari itu dia datang untuk sekedar mengenal kakek buyutnya. Ia hadir untuk menyaksikan bahwa betapa kakek buyutnya pernah menjadi orang yang amat berpengaruh, dan masih dianggap berpengaruh hingga hari ini. Ibunya, bahkan neneknya (Evawani) pun saya kira mengenal Chairil dari puisi-puisi Chairil, buku-buku tentang Chairil, atau dari cerita-cerita yang diwariskan dan bersumber dari saksi-saksi hidup Chairil. Mereka mengenal Chairil dari tulisan-tulisan Chairil, atau dari tulisan yang menceritakan Chairil. Maka, pemandangan sudut Cikini kala itu seperti satu fragmen dari dramaturgi penyampaian warisan yang paling puitik dari 'Chairil' kepada cucu dan cicitnya.
Inilah yang akhirnya membuat saya resah. Apakah kelak akan ada tulisan-tulisan saya (yang bisa menjadi representasi dari jiwa saya sesungguhnya) yang akan dibicarakan turun-temurun? Representasi yang menjadi gerbang pengenal untuk anak saya-cucu saya-cicit saya-yang tidak sempat mengenal siapa ibunya-neneknya-nenek buyutnya? Atau pertanyaannya akan semakin menjadi rumit ketika berbunyi: adakah tulisan-tulisan yang bercerita tentang saya dan akan menjadi representasi saya untuk keturunan-keturunan saya kelak?
Keresahan semacam itu yang akhirnya menggema di kepala saya, sedangkan paralel di dunia nyata, adzan magrib lah yang menggema: menandai berakhirnya diskusi buku malam itu.
Sebenarnya masih ada satu babak lagi dari Membaca Chairil, yaitu Malam Puisi. Dan akan dimulai kembali selepas istirahat: pukul tujuh malam. Tetapi melihat orang disebelah saya yang menemani saya sejak di stasiun kelima, tak begitu antusias untuk melanjutkan bersila disana, kami pun kabur saja ke toko buku. Lagipula, saya sudah cukup puas dengan menyaksiakan beberapa penampil yang membacakan puisi di acara diskusi buku.
Bau petrichor sudah tak terendus lagi. Saya menuju Matraman. Jakarta sebetulnya teduh dan asyik jika seperti minggu malam itu: kalau saja keresahan-keresahan di kepala saya sedikit mereda gemanya.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Melimpah Hadiah di Bekasi Wedding Exhibition #4
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Petani-petani Kendeng dan Kebebasan
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
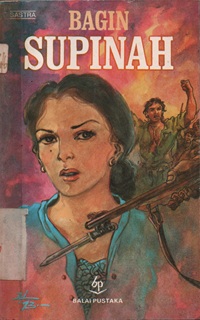






 97
97 0
0



 Berita Pilihan
Berita Pilihan










