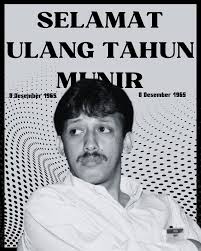Makna Substantif Kerugian Keuangan Negara
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Sekiranya pemerintah gagal memberantas korupsi yang terus menggurita, negeri ini akan terus terjajah oleh koruptor secara berkepanjangan.
Makna Substantif Kerugian Keuangan Negara
Oleh Marwan Mas
Guru Besar Ilmu Hukum dan Pengajar Tindak Pidana Korupsi
Universitas Bosowa, Makassar
Dalam membuktikan akibat dari suatu perbuatan tindak pidana korupsi (korupsi) acapkali menjadi perdebatan dalam praktik. Ini terjadi akibat perbedaan persepsi terhadap makna tindak pidana korupsi atau delik korupsi. Terutama pembuktian telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 3/1999 yang diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi).
Rumuan kedua pasal tersebut sesungguhnya menganut “delik formil”, yaitu tindak pidana korupsi dianggap sudah terjadi apabila unsur-unsur perbuatan yang dilarang sudah terpenuhi, tanpa memperhitungkan timbulnya suatu akibat. Hal itu dapat dilihat pada kata “dapat” merugikan keuangan dan perekonomian negara dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi. Korupsi dianggap telah terjadi apabila perbuatan tersebut “berpotensi” menimbulkan kerugian keuangan negara. Ada atau tidaknya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti jumlahnya, tidak menjadi ukuran telah terjadinya korupsi, bahkan tidak perlu dibuktikan di sidang pengadilan.
Kerugian keuangan negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah pada “adanya potensi kerugian negara”. Tulisan ini merupakan tindak lanjut sekaligus perbaikan terhadap tulisan saya sebelumnya “Kerugian Keuangan Negara” (Indonesiana.tempo.co, Jumat 8 Juli 2016), lantaran adanya perkembangan baru berdasaarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2017 terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi terkait kata “dapat” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan MK itu menempatkan delik korupsi bukan lagi “delik formil” melainkan “delik materiil” yang harus dibuktikan adanya akibat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi. MK dalam pertimbaangan hukumnya mengubah penilaian konstitusional dalam Putusan MK sebelumnya Nomor Perkara: 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa “pemaknaan kerugian keuangan negara atau perekonoian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi”, sehingga terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah “untuk mengubah penilaian konstitusional karena penilaian sebelumya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi”.
Audit BPK
Dengan demikian, penyidik perkara korupsi sebelum suatu perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, harus ada audit kerugian keuangan negara yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini mengantisipasi audit kerugian keuangan negara dari BPK dijadikan objek praperadilan penetapan tersangka.
Dalam Pasal 1 butir-22 UU Perbendaharaan Negara mengartikan kerugian keuangan negara sebagai “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai”. Dalam teori hukum pidana, pengertian tersebut termasuk “delik materiil” sesuai Putusan MK di atas lantaran memberi syarat adanya kerugian negara “yang benar-benar nyata dan pasti jumlahnya” sebagai akibat suatu perbuatan yang dilarang dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.
Makna “keuangan negara” dalam Pasal 1 butir-1 UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara adalah ‘semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut’. Pada dasarnya UU Korupsi memberi penekanan bahwa korupsi selain identik dan melekat pada jabatan pegawai negeri dan penyelenggara negara, juga melekat pada penerimaan dan pengeluaran dana APBN/APBD serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Untuk mengembalikan keuangan negara (asset recovery), maka Pasal 18 Ayat (1) huruf-b UU Korupsi mengatur pidana tambahan berupa “pembayaran uang pengganti” yang jumlahnya sebanyak dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Termasuk perusahaan milik terpidana di mana korupsi dilakukan, serta harga dari penggantian barang-barang tersebut. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu satu bulan sesudah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti. Hal ini juga sejalan dengan putusan MK karena hakim hanya akan mejatuhkan putusan “pembayaaran uang pengganti” apabila penuntut umum membuktikan adanya kerugian keuangan negara di depan sidang pengadilan berdasarkan audit BPK.
Sebetulnya ketentuan itu juga mendesain pemiskinan koruptor (terpidana), karena jumlah kerugian negara yang dikorupsi harus diganti. Apalagi dijatuhi juga ‘pidana denda’ sehingga terpidana terkuras hartanya selain dari harta yang dikorupsi. Namun, Pasal 18 Ayat (3) UU Korupsi kembali mementahkannya dan memberi toleransi. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, diganti (subsidair) dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang ditentukan dalam putusan hakim.
Di sinilah penyidik dan penuntut umum mengharuskan adanya hasil audit BPK atau juga dapat dilakukan BPKP mengenai kepastian jumlah kerugian negara yang diduga dikorup oleh terdakwa. Tujuannya agar hakim dapat dengan pasti menjatuhkan pidana “pembayaran uang pengganti” sesuai jumlah kerugian keuangan negara yang terbukti dikorupsi.
Langkah Progresif
Mengimplementasi langkah pemberantasan korupsi secara progresif selain upaya pencegahan yang sistematis. Setidaknya ada empat langkah progresif dalam memberantas korupsi. Pertama, menjatuhkan pidana maksimal oleh hakim sesuai ancaman pidana pasal UU Korupsi yang dilanggar. Tentu dimulai dari penerapan pasal dan tuntutan pidana maksimal oleh penuntut umum.
Kedua, sebaiknya penyidik melakukan penahanan sejak ditetapkan tersangka, karena penahanan memiliki “batas waktu” sehingga mendorong keseriusan penyidik untuk secepatnya menyelesaikan berkas perkara. Selama ini banyak perkara korupsi di daerah tidak ketahuan rimbanya. Meskipun sudah ada tersangka, tetapi berkas perkara tidak sampai ke pengadilan akibat masih lemahnya alat bukti yang ditemukan. Jika memang penyidik yakin pada alat bukti yang ada, sebaiknya langsung melakukan penahanan, sebagai salah satu langkah progresif atau tindakan luar biasa penanganan korupsi.
Ketiga, menerapkan UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang). Yang dijerat dalam UU Pencucian Uang bukan hanya terdakwa yang mengalirkan uang (pelaku aktif), melainkan juga yang menerima hasil korupsi (pelaku pasif) sepanjang “mengetahui atau patut menduga” uang atau harta tersebut berasal dari korupsi. Begitu pula korporasi atau organisasi dapat dibekukan, jika terbukti menerima dana hasil korupsi. UU Pencucian Uang juga menerapkan “pembuktian terbalik”.
Untuk memeriksa perkara pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicat crime). Sebab tindak pidana asal dapat diketahui melalui “bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti)” tentang adanya hubungan kausalitas antara tindak pidana pencucian uang yang sedang ditangani dengan korupsi sebagai tindak pidana asal. Perbuatan tersebut termasuk “melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan”, serta ditemukan harta benda atau dana yang diduga hasil korupsi pada terdakwa yang dialirkan (ditransfer) kepada pihak lain dengan maksud disamarkan seolah-olah bukan dari hasil korupsi.
Maka itu, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap uang dan harta benda yang diduga hasil korupsi. Terdakwa harus membuktikan uang dan harta benda itu di depan sidang pengadilan, bahwa bukan diperoleh dari hasil korupsi (pembuktian terbalik). Jika terdakwa tidak mampu membuktikan kalau uang dan harta itu diperoleh secara sah atau bukan dari hasil korupsi, maka dianggap sebagai hasil korupsi melalui pencucian uang dan disita untuk negara.
Keempat, konsisten menerapkan hukuman denda dan pembayaran uang pengganti sesuai jumlah yang dikorupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Korupsi. Caranya, tidak menggunakan pidana subsider (hukuman pengganti) berupa penjara yang biasanya tidak lebih dari satu tahun. Dalam praktik, jaksa eksekutor kesulitan menyita aset terpidana karena sudah disembunyikan di luar negeri. Untuk itu, perlu dibentuk tim khusus untuk mengejar aset terpidana selain yang sudah disita dalam pencucian uang.
Penjatuhan pidana denda antara Rp50 juta sampai Rp1 miliar, serta pidana “pembayaran uang pengganti” sejumlah uang yang dikorupsi dan terbukti di sidang pengadilan, pada hakikatnya bertujuan untuk “memiskinkan koruptor”. Ini merupakan salah satu upaya progresif atau upaya luar biasa, agar koruptor merasa jera sekaligus menimbulkan rasa takut bagi calon koruptor yang antre di berbagai institusi negara untuk melakukan hal yang sama.
Hakim Agung Artidjo Alkostar (Tempo.com, 2/1/2014) menyebutkan, salah satu cara memiskinkan koruptor adalah melipatgandakan hukuman pembayaran uang pengganti. Artidjo sering menggandakan hukuman bagi koruptor, termasuk membetulkan atau meluruskan pasal-pasal UU Korupsi yang diterapkan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Sebagai contoh, ada yang memakai pasal suap pasif, padahal yang tepat pasal suap aktif.
Kita juga butuh pahlawan antikorupsi seperti pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Semua komponen bangsa harus berjiwa antikorupsi. Sebab bagi rakyat, kemerdekaan bukan hanya bebas dari kolonialisme, bebas menyampaikan pendapat, bebas beraktivitas dan berkarya. Yang penting bagi rakyat adalah peningkatan kesejahteraan hidupnya. (*)
Makassar, 2 September 2017
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Serangan Bergelombang KPK
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Makna Substantif Kerugian Keuangan Negara
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0






 Berita Pilihan
Berita Pilihan


 99
99 0
0