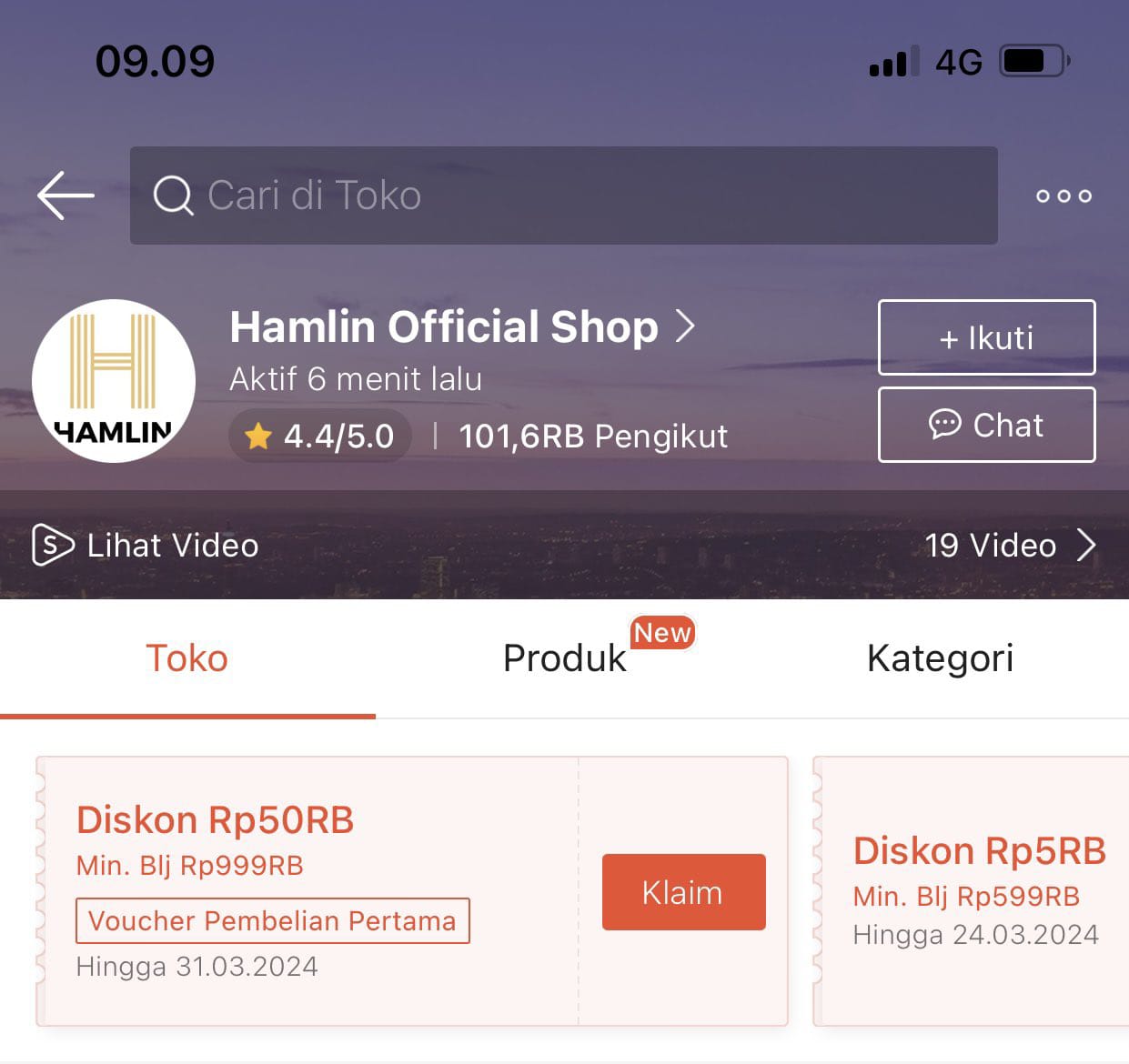Inilah ringkasan beberapa tulisan menarik yang perlu Anda simak pekan ini. Ada polemik yang cukup hangat mengenai rencana rekrutmen rektor asing. Mencuat pula usulan kalangan partai politik untuk membikin lagi GBHN seperti dalam era Orde Baru. Dua artikel ini merupakan sikap editorial Koran Tempo.
Satu tulisan lagi merupakan kolom yang tulis oleh Eko Sulistyo dari Kantor Staf Presiden. Ia menjawab pertanyaan: benarkah Jokowi mempraktekan model kekuasaan Jawa.
- Rektor Asing, Siapa Takut?
RENCANA Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mendatangkan rektor dari luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi negeri badan hukum mulai 2020 tidak perlu ditakuti dan sepatutnya didukung. Tidak tepat mengaitkan perekrutan rektor asing tersebut dengan terancamnya nilai-nilai budaya atau nasionalisme.
Kualitas mayoritas perguruan tinggi di Tanah Air yang belum membanggakan bisa menjadi alasan kenapa Indonesia membutuhkan rektor asing. Hingga saat ini, hanya ada tiga perguruan tinggi yang masuk daftar 500 top universitas dunia versi Quacquarelli Symonds World University Rankings 2019/2020. Universitas Indonesia bertengger di peringkat ke-296, Universitas Gadjah Mada di urutan ke-320, dan Institut Teknologi Bandung berada di posisi ke-331.
Daya saing kampus-kampus di Indonesia itu pun tertinggal jauh dari perguruan tinggi negara tetangga dekat, seperti Malaysia dan Singapura. Selengkapnya baca: Rektor Asing, Kenapa Tidak?
- Menolak Kembalinya GBHN
Kampanye sejumlah partai politik untuk memberlakukan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) seolah-olah dilandasi semangat nasionalisme. Namun kampanye yang bertujuan mengamendemen kembali Undang-Undang Dasar itu menyimpan kekeliruan serius.
Dilandasi semangat reformasi 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengubah aturan dasar demokrasi. Presiden pun dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat sejak 2004-tidak seperti sebelumnya yang ditentukan oleh MPR. Presiden terpilih diberi kewenangan untuk menyusun program pembangunan sesuai dengan janji kampanyenya.
Karena dipilih langsung oleh rakyat, presiden bukan lagi mandataris MPR. GBHN, yang ditetapkan oleh MPR sebagai pedoman pembangunan yang wajib dijalankan presiden, jelas menjadi tidak relevan lagi. Sebagai gantinya, disusunlah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Rencana pembangunan dibuat jangka panjang untuk periode 20 tahun, jangka menengah (lima tahun), dan tahunan. Selengkapnya baca: Tolak Kembalinya GBHN
- Jokowi dan Kekuasaan Jawa
Dalam tulisannya di harian ini (Koran Tempo), Seno Gumira Ajidarma mengkhawatirkan ungkapan Presiden Joko Widodo dalam bahasa Jawa, seperti "Lamun sira sekti, aja mateni; Lamun sira pinter, aja minteri" dan "Lamun sira banter, aja mbanteri", sebagai bentuk arogansi politik-kultural (Koran Tempo, 2 Agustus 2019).
Sayangnya, kekhawatiran itu tidak dibarengi dengan analisis yang melihat struktur politik saat ini yang sudah berubah setelah kejatuhan Soeharto oleh gerakan reformasi. Struktur politik otoriter Orde Baru memungkinkan Soeharto menjalankan model kepemimpinan dan kekuasaannya bergaya seperti raja-raja Mataram, dengan kejawaan sebagai basis legitimasi politik sekaligus kultural (Anderson, 1984; Moertono, 1985). Meski ada pemilihan umum setiap lima tahun sekali, semua itu adalah politik "seolah-olah" demokratis.
Dalam kekuasaan Jawa, seorang pemimpin atau raja perlu menjaga wibawa dan karismanya. Ia diharuskan memisahkan diri dari kehidupan masyarakat. Raja Jawa juga dipercaya sebagai titisan dewa yang suci. Rakyat yang dianggap hina harus menjauh atau dilarang menatap, apalagi berdialog dengan raja, karena akan mencemari kesuciannya. Kekuasaan dimaknai sebagai suatu kekuatan energi yang dimiliki raja-raja serta bersifat konkret, homogen, dan tetap, termasuk benda-benda yang dianggap keramat atau sakti.
Soeharto jelas mempraktikkan model kekuasaan raja-raja Jawa yang terpusat pada dirinya dan membuat rakyat takut akan kekuasaannya. Budaya Jawa dijadikan legitimasi kultural Soeharto untuk melestarikan kekuasaannya selama 32 tahun.
Hal ini berbeda dengan Jokowi. Dukungan rakyat terhadapnya bukan berasal dari rasa takut, melainkan rasa aman dan kesamaan yang dibentuk Jokowi. Popularitasnya melambung karena dinilai memahami penderitaan rakyat secara nyata. Jokowi menjadi legitimate bukan karena tindakan represi atau rasa takut akan kekuasaannya.
Penulis kolom: Eko Sulistyo (Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden)
Selengkapnya baca: Jokowi dan Kekuasaan Jawa
Ikuti tulisan menarik Indonesiana lainnya di sini.