Demokrasi Macam Apa yang Hendak Kita Wariskan?
Minggu, 1 September 2019 13:28 WIB
Kepentingan politik dan ekonomi para elite, baik yang terjun ke gelanggan politik maupun yang bermain di balik layar, telah berkontribusi dalam menyumbat lahirnya kepemimpinan nasional yang kita butuhkan dan merintangi pendewasaan demokrasi kita.
“Politikus memikirkan pemilu yang akan datang, negarawan memikirkan generasi mendatang.”
--James Freeman Clarke
Kutipan perkataan Clarke itu mewakili kecondongan kuat politikus pada kekuasaan: menang pemilu berarti berkuasa, kalah pemilu bermakna tidak dipercaya untuk berkuasa. Menjadi oposisi dianggap sebagai pilihan terakhir dan awam memandangnya sebagai kumpulan pecundang politik yang kerap membikin gaduh.
Padahal, tidak sepenuhnya demikian. Kecuali kemenangan yang telak, setiap Pilpres yang relatif fair berkemungkinan melahirkan hasil yang memadai bagi pihak-pihak yang bersaing. Jika pasangan capres-cawapres hanya dua, yang kalahpun berpotensi meraih dukungan yang jumlahnya tidak bisa diremehkan.
Dalam Pilpres lalu, Jokowi-Ma’ruf Amin meraih 85,60 juta suara atau 55,5% dari pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara, sedangkan Prabowo-Sandiaga memperoleh 68,65 juta suara atau 44,5%. Selisihnya relatif besar, tapi bukan telak, dan angka perolehan Prabowo-Sandiaga itu menunjukkan bahwa mereka memperoleh dukungan dari pemilih yang aspirasinya patut dihargai.
Cara menghargai rakyat pemilih ialah konsisten memperjuangkan gagasan yang diusung selama Pilpres. Bagi yang kalah, perjuangan ini dapat dilakukan dengan memilih jadi oposisi konstruktif atau apapun namanya. Sayangnya, kursi oposisi dianggap kurang terhormat dibandingkan kursi di kabinet, sekalipun politikus tahu bahwa oposisi itu penting dan baik bagi perkembangan demokrasi, karena di dalamnya terdapat check and balances, kritik, masukan, maupun tawaran alternatif.
Sungguh menyedihkan manakala fungsi oposisi kritis dan konstruktif itu harus menyerah kepada hasrat akan kuasa. Pikiran-pikiran pragmatis ditonjolkan dengan alasan yang dibuat seakan-akan pragmatisme itu dapat dipertanggungjawabkan—lihatlah kembali adagium ‘tidak ada yang musykil dalam politik’. Keinginan kuat dari yang kalah untuk bergabung dengan pemenang memperlihatkan bahwa kepercayaan rakyat mulai diabaikan. Para elite mulai sibuk membicarakan kepentingan mereka sendiri. Rakyat dibuat terkejut ketika tiba-tiba isu amendemen UUD dan pemindahan ibukota mencuat, padahal di masa kampanye pilpres maupun pileg, isu ini tidak pernah muncul di permukaan. Ada agenda apa?
Para elite politik mesti mengingat bahwa tugas mereka bukan sekedar menang dalam pemilu. Mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni membangun budaya politik yang sehat bagi pematangan demokrasi. Pembangunan budaya politik memerlukan waktu, tapi kurun 10-20 tahun terakhir sejak tumbangnya Orde Baru telah terlewat begitu sia-sia. Para pemain utama dunia politik kita adalah wajah-wajah yang itu-itu juga.
Situasi itu tidak lepas dari ketidakpastian di masa-masa awal reformasi. Dalam rentang waktu yang singkat, kita memiliki tiga orang presiden: B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. Pemilihan langsung menjadikan gelanggang permainan berubah. Dalam situasi perubahan yang cepat seperti ini, mereka yang lebih dahulu kuat secara ekonomi tahu benar bagaimana bersiasat agar penguasaan sumber daya mereka tidak tergerus. Sebagian mereka terjun ke politik, sebagian lainnya lebih memilih bermain di balik layar. Tujuannya sama, khas karakter oligarkis: mempertahankan dan memperbesar penguasaan sumber daya dengan memperkuat pengaruh politik.
Para penguasa sumber daya ini tahu persis bahwa politik di era baru memerlukan biaya besar. Ketika gonjang-ganjing politik berlangsung, mereka cerdik bermain. Ketika para politikus sibuk mengonsolidasikan diri, mereka menyelinap dan memainkan peran sebagai penopang logistik politik yang dibutuhkan politikus. Dan, seperti diakui Bambang Soesatyo, politikus Golkar, “Tidak ada ketua umum [parpol] yang bisa didapat dengan gratis. Mendirikan partai seperti mendirikan korporasi. Dibutuhkan biaya ratusan miliar.”
Sebagian elit mampu mengonsolidasikan kekuatan politik dan ekonomi pada dirinya. Pengalaman politik Jusuf Kalla, terutama sebagai ketua umum Golkar, serta pengalaman bisnisnya yang panjang telah menempatkan Kalla sebagai elite yang pengaruhnya tidak dapat diabaikan. Setelah dilepas SBY untuk periode kedua kepresidenannya, Kalla berhasil comeback ke Istana Wapres mendampingi Jokowi. Kalla bahkan menjadikan Sofyan Wanandi, pengusaha berjaringan luas sekaligus teman lamanya, sebagai penasihat khusus.
Surya Paloh, yang juga sukses dalam bisnis, merasa penting mendirikan NasDem. Begitu pula Hary Tanoesoedibjo; setelah sempat bergabung dengan NasDem dan Hanura, ia mendirikan partainya sendiri, Perindo. Keduanya bahkan menghimpun kekuatan ekonomi, politik, dan media di satu tangan. Keluarga Megawati sudah lama terjun dalam bisnis dan sejak dipilih sebagai Ketua Umum PDI-P, hingga 20 tahun kini posisinya belum tergantikan bahkan ia masih menjabat lagi hingga 5 tahun mendatang.
Sementara itu, berbekal kariernya di militer, Susilo Bambang Yudhoyono membentuk partai sendiri, Demokrat, yang mengantarkannya sebagai presiden. Prabowo Subianto juga membangun partai sendiri, Gerindra. Muhaimin Iskandar tergolong politikus yang cerdik, sehingga ia mampu merebut posisi ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa pada 2005 dan menguasainya hingga kini, bahkan terpilih kembali untuk periode lima tahun ke depan. Agaknya, ia bersaing dengan Megawati untuk menjadi ketua umum partai politik terlama.
Apa yang tampak menonjol dari kepemimpinan mereka ialah memusatnya pengambilan keputusan partai kepada diri mereka. Ketika para elite ini berusaha mengesankan masyarakat bahwa mereka sedang membangun alam demokrasi yang sehat, mereka malah tampak kesulitan secara internal membangun kultur organisasi politik yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Ketergantungan logistik partai kepada elite, khususnya ketua umum, sangat berperan menciptakan sentralitas itu dan menjadi persoalan yang sewatu-waktu dapat meletup.
Percaturan politik lima tahun ke depan tampaknya belum akan lepas dari nama-nama tersebut sekalipun ada tuntutan untuk regenerasi kepemimpinan, setidaknya karena alasan bahwa mereka semakin tua. Sayangnya, para elite berkepentingan menjaga kelangsungan peran keluarga masing-masing di ranah politik dan penguasaan sumber daya ekonomi. Para elite politik mempersiapkan keturunannya untuk menempati pos-pos kepemimpinan nasional. Anak-anak mereka langsung melejit ke posisi strategis partai.
Mereka yang tidak memiliki sumber daya ekonomi yang kuat harus pintar menghimpun dukungan, dan di luar sana banyak yang dengan senang hati menopang kebutuhan ini, tentu saja ‘tidak ada makan siang gratis’. Pragmatisme karena itu tidak mudah dihindari. Banyak politikus, termasuk beberapa ketua umum partai, berusaha naik jenjang dalam strata elite politik dengan mencari sumber-sumber dukungan yang membuat terjungkal dan terpaksa berurusan dengan hukum. Figur seperti Jokowi, sekalipun sudah naik jenjang dari kota ke negara, masih tampak kesulitan melepaskan diri dari pengaruh besar politik dan ekonomi di sekelilingnya.
Tampilnya kepemimpinan yang lebih kuat dan mandiri juga menghadapi tantangan presidential treshold 20% yang sengaja diciptakan sebagai rintangan. Batasan ini menyulitkan munculnya kepemimpinan nasional yang lebih luas. Siapapun yang berminat mengajukan diri sebagai presiden, ia dipaksa melakukan kompromi politik dengan para elite. Kepentingan politik dan ekonomi para elite, baik yang terjun ke gelanggan politik maupun yang bermain di balik layar, telah berkontribusi dalam menyumbat lahirnya kepemimpinan nasional yang kita butuhkan.
Apakah situasinya demikian buruk? Bukankah pemilu presiden dan legislatif telah berjalan ‘baik-baik’ saja? Peningkatan kesadaran politik rakyat harus terus dilakukan dengan pertama-tama membangkitkan kesadaran bahwa membangun demokrasi bukan sekedar menyiapkan bilik-bilik suara di hari pemilihan, tapi yang lebih mendasar ialah membangun jiwa dan kulturnya. Inilah pekerjaan besar yang tidak akan pernah selesai, bahkan hingga kelak jika demokrasi kita sudah dianggap dewasa sekalipun. >>
#74 tahun indonesia merdeka
Penulis Indonesiana
2 Pengikut

Di Balik Dugaan Manipulasi Angka Statistik ala Rezim Prabowo
Rabu, 27 Agustus 2025 18:54 WIB
Di Balik Amnesti Hasto: Prabowo dan Megawati Sepakat Mengubah Permainan
Sabtu, 2 Agustus 2025 08:59 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0





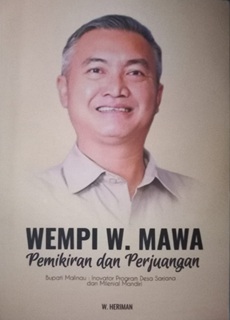

 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 97
97 0
0

















