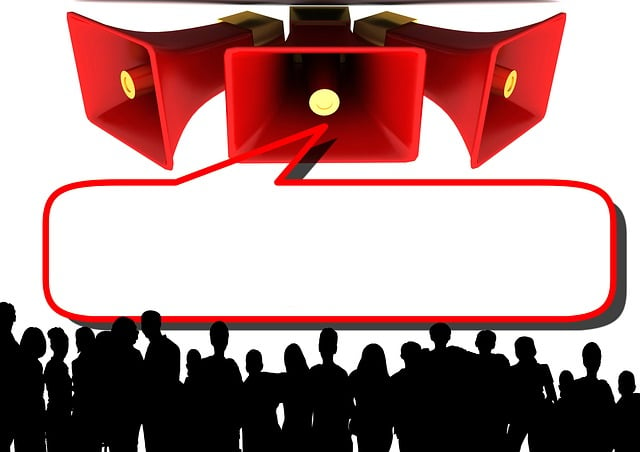“Kau punya mimpi?”
“Mimpi?”
“Seperti dokter atau arsitek?”
“Kurasa.”
“Semua orang punya mimpi, kau pasti punya juga.”
“Mimpiku? Mimpiku lulus.”
“Hanya itu?”
“Ya.”
Mimpiku adalah lulus kuliah. Bukan lulus tepat waktu atau lulus dengan nilai sempurna. Mimpiku hanyalah lulus. Mungkin orang lain menganggap mimpiku terlalu sederhana. Tapi tidak bagiku. Mimpiku begitu tinggi, dan mahal.
Angin malam semakin menggigit seiring waktu berlalu. Lampu jalan menyala dan mati. Cahaya redupnya tak lebih terang dari bulan. Aku duduk di pinggir trotoar, bersandar pada lampu jalanan di kota yang tak pernah tidur ini. Detak jantung tak pernah terasa begitu kencang sebelumnya. Detak demi detak. Detik demi detik. Rasanya seperti menunggu kematian.
Aku memang menunggu kematian. Aku yang selalu meragukan Tuhan, kini dihadapkan dengan kematian. Rasanya sangat canggung. Apa yang nanti akan kukatakan di hadapan-Nya? Mungkin Dia tidak mau repot-repot melihat makhluk remahan sepertiku.
Dapat kurasakan lengan yang melingkari pinggang kananku terasa semakin hangat. Kini penglihatanku mulai meredup seperti lampu jalanan di seberang jalan sana. Sejak bermenit-menit lalu aku tidak mengalihkan pandanganku dari depan sebuah jalan buntu. Tempat dimana kukira mimpiku tinggal selangkah, sangat mudah untuk digapai. Mimpiku yang begitu mahal.
Kuberanikan menunduk barang sesaat, melihat bajuku memerah dengan cepat.
“Kau lihat? Aku sekarat.” Ucapku kepada orang yang tergeletak di sampingku, dengan pisau menancap di dadanya. Darah segar dengan cepat menggenang mengucur dari beberapa tusukan di tubuhnya.
“Aku akan segera menyusulmu.”
“Nanti jangan sampai berkelahi lagi di depan Tuhan. Mengaku saja kalau kita sama-sama jahat.”
“Apa yang Tuhan tanyakan kepadamu? Apakah sama seperti apa yang dikatakan ustad-ustad di surau?” Tidak ada jawaban. “Kau juga jangan coba-coba mengarang cerita sebelum aku sampai kesana.”
Aku terlalu lemah, ingin sekali kunyalakan rokok terakhirku. Di saku kanan, tinggal tiga batang. Tapi meminta kisi-kisi pertanyaan Tuhan sekarang yang lebih penting.
Sial, kukira malam ini batu loncatan terakhirku. Tapi apa yang bisa kulakukan sekarang? Tidak ada. Tunggu saja malaikat mencabut nyawaku. Atau kalau Tuhan mau berbelas kasih, dia akan mengirim seseorang untuk menyelamatkanku. Tapi itu tidak mungkin, aku tidak pernah berdoa padanya kenapa dia mau repot-repot berbelas kasihan padaku.
Ternyata Tuhan sedang berbaik hati, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di seberang jalan. Kacanya turun perlahan dan aku dapat melihat seseorang menatapku keheranan. Beberapa detik herannya berubah menjadi ketakutan, lalu ia buru-buru pergi. Melihatku sepertinya membuatnya ngeri. Bagaimana tidak, aku berdarah-darah dan seseorang terbaring tak bernyawa sampingku.
“Bagaimana? Bisakah kita bertemu nanti malam?”
“Ya, tentu saja. Sesuai yang sudah kita sepakati.”
“Baiklah. Kuyakinkan kau tidak akan merugi jika bekerja sama dengan kami.”
Kututup ponselku lalu cepat-cepat kumasukkan saku. Kemudian buru-buru merogoh ponselku yang lain di saku satunya. Memasang earphone dan mendengarkan lagu, membuka media sosial, lalu bergabung dengan arus kerumunan stasiun kereta cepat seperti tidak terjadi apa-apa. Mengalir seperti sungai.
Hari-hari berjalan seperti biasa. Bangun tidur, bersiap-siap, pergi ke stasiun kereta cepat, kuliah, pulang, lalu hidup. Hidupku dimulai saat matahari tenggelam dan orang-orang pulang setelah seharian bekerja. Mereka pulang, aku berangkat. Aku bekerja di sisi gelap kota, begitu aku menyebutnya. Bukan, bukan dunia malam yang basah, tapi bisnis. Bisnis kotor lebih tepatnya.
Sorenya orang itu kembali menelpon, sekali lagi menanyakan kepastian. Kepastian tempat, jam, dan sebagainya. Tepat di stasiun yang sama seperti pagi tadi, tepat di tengah-tengah keramaian orang berlalu-lalang. Sepertinya dia gusar dan gelisah. Bukan tanpa sebab, kami membicarakan uang puluhan juta dan ini ilegal.
Hal itu pula yang menjadi sebab beberapa hari belakangan terasa cukup berbeda meski secara garis besar terasa sama saja. Dua hari lalu aku mendapat pesan yang mungkin bisa membuatku menangis terharu. Seseorang ingin berbisnis denganku dengan nominal yang sangat besar, cukup untuk biaya sampai aku lulus. Dua puluh juta katanya. Bagaimana aku bisa tidak melompat dan berteriak-teriak sendiri malam itu.
Melihat mimpiku berada tepat di hadapanku, rasanya ingin sekali aku berterima kasih kepada Tuhan meski aku tidak pernah berdoa pada-Nya.
Malam-malam yang biasa kuhabiskan dengan belajar, kini kuhabiskan dengan berkhayal akan jadi apa aku setelah lulus. Semakin malam, semakin kurasakan gairahnya. Bisa-bisa aku juga ikut gusar dan gelisah seperti orang itu yang terus saja menghubungiku. Aku ingin ini aku ingin itu, tapi semuanya tertahan.
Apa yang akan kulakukan setelah lulus? Bekerja? Tapi akan kerja apa aku, sementara selama ini aku memakan uang haram. Melanjutkan pendidikan lagi? Tapi itu artinya mimpiku bertambah mahal dan aku tidak mau melanjutkan pekerjaanku ini. Menikah? Tapi siapa yang mau? Selama ini aku tidak pernah repot-repot bersosialisasi dengan siapapun.
Kini menggapai mimpi rasanya biasa saja.
Aku tersadar kalau aku melamun ketika jam dinding menunjukkan waktu jam dua belas. Aku bisa melihat dari kamar apartemenku kalau kota masih bangun, namun manusia dan kendaraan yang berlalu lalang tidak sebanyak sebelumnya. Sebentar lagi kota akan beristirahat, tapi di sudut dan celahya masih banyak orang yang beraktivitas. Papan-papan neon mulai menyala dan kupu-kupu mulai berterbangan. Sisi gelap perkotaan mulai keluar dari balik bayangan, atau harus aku bilang, sisi menyenangkan.
Aku bangkit dari mejaku, mengambil celana panjang lalu mengenakannya. Lalu aku mengenakan hoodie, kaus kaki, dan sepatu. Aku membawa handphone lipatku, satunya kumatikan dan kugeletakkan saja. Tidak ada yang bakal mencariku. Kemudian bagian terpenting dari mimpiku, tas ransel berisi obat-obatan ilegal. Obat-obatan itu disimpan di dalam buku-buku tebal yang dilubangi tengahnya.
Memangnya apa yang anak-anak kuliahan bawa di tas mereka selain buku-buku tebal? Narkoba? Tidak mungkin.
Kota nampaknya masih terbangun saat aku berjalan pelan menyusuri trotoar. Kendaraan yang melintas masih cukup banyak. Mereka yang baru saja pulang kerja dan mereka yang baru saja berangkat kerja. Toko-toko sudah tutup namun kafe-kafe masih buka dan aku bisa melihat anak-anak muda menghabiskan waktunya di dalam. Merokok, membual tentang kopi, membicarakan cinta dan mati.
Semakin aku masuk ke dalam sisi gelap kota, semakin aku merasa akrab. Bar-bar dan tempat karaoke terbuka lebih lebar dari jam-jam sebelumnya, meski tidak seramai tadi, namun hingar bingar di dalamnya terasa sampai keluar. Aroma rokok dan alkohol yang pekat, orang-orang mabuk yang meracau dan berkelahi, wanita-wanita yang mejajakan tubuhnya. Aku sudah terbiasa dengan semua ini.
Entahlah, bagiku kehidupan datar ini tampak seperti program. Banyak sekali skenario yang bisa terjadi, namun semua itu terjadi berulang-ulang dan membosankan. Kalau tidak itu ya ini, kalau tidak ini ya itu.
Aku berjalan cukup lama sampai tiba di satu gang buntu di seberang bar. Jalannya tidak terlalu menjorok kedalam tapi jalan itu kotor, bau, gelap. Siapa juga yang mau repot-repot memasang lampu jalan. Tapi ini adalah tempat berbisnis terbaik.
Tepat di depan jalan buntu, sebelum aku masuk lebih dalam. Ada sekitar empat orang berlagak aneh yang merokok di depan bar. Mereka mencoba berbincang-bincang senatural mungkin tapi mereka amatir. Kentara sekali mereka mengawasiku. Mengawasi atau heran dengaku, aku tidak bisa membedakannya. Untuk apa seorang berpakaian tertutup malam-malam masuk ke jalan buntu menjijikkan. Tapi aku tidak ambil pusing, toh ratusan kali orang-orang mengawasiku sekaligus keheranan. Sudah biasa bagiku.
Diujung jalan nampak siluet seseorang yang sedang merokok. Dia memperhatikan gedung-gedung tinggi dan terang yang ada di balik tembok. Dia terlalu larut, sampai tak sadar aku berada di sampingnya. Cepat-cepat dia mematikan rokoknya dan membuka tudung jaketnya. Pecandu biasa, tidak ada bedanya.
“Kode.” Ucapku sepelan mungkin, takut membangunkan kota seisinya.
Orang itu memperhatikan ke balik bahuku memastikan hanya kami berdua yang ada disini. “Mata dibalas mata, maka dunia akan buta.”
“Kau ini semacam pasifis atau apa? Kodemu terdengar aneh.” Lanjutnya disertai senyuman mengejek.
“Itu peringatan.”
“Kau tak terlihat dapat membutakan mataku.”
Dasar pecandu gila. “Tolong kita percepat. Seperti kesepakatan, tidak ada wajah tidak ada nama.”
“Baiklah. Biar kulihat.”
Aku melepas ranselku dan memberikan kepadanya. Dia membukanya cepat-cepat dan terdiam begitu melihat isinya. Matanya berbinar, wajahnya tersenyum cerah, terukir senyuman tulus di mulutnya. Tidak. Mana ada pecandu seperti itu.
Orang itu mengambil satu pil lalu menelannya. Sesaat dia terlihat seperti orang yang akan diangkat ke surga. “Kau tidak berbohong ketika kau bilang kualitasnya baik. Kau mau bekerja sama denganku?”
“Saat ini aku tidak tertarik dengan kerja sama.”
“Oh ayolah. Kau akan dapat untung yang besar.”
Dia melempar tasnya. Isinya uang, aku tahu, tapi aku harus memastikan. Dua puluh juta, tunai. Transaksi online terlalu beresiko jadi kurelakan beberapa menit untuk menghitung bundelan demi bundelan sementara dia terbang melayang membelai rembulan. “Ini kurang.”
“Memang.”
“Apa-apaan? Kita sudah sepakat.”
“Tenang bos muda. Kurangnya aku ganti dengan bergabung dengan kelompokku.”
Masuk ke dalam industri kotor ini membuatku paranoid parah. Jarang sekali aku tertidur nyenyak, rasanya kapanpun polisi bisa mendobrak kamar apartemen kecilku dan menangkapku. Apalagi benar-benar menyelam, aku tidak akan bisa naik ke permukaan lalu aku akan tenggelam.
Kulakukan bisnis kotor ini hanya untuk lulus, untuk menggapai mimpiku. Sedangkan aku tak pernah menggunakan uang haram ini untuk berfoya-foya atau untuk sekedar menuruti gengsi. Aku menggunakan apa yang kuperlukan.
“Aku tidak tertarik. Berikan sisanya!”
Dia melirik ke balik bahuku lalu tersenyum tipis. Ketika kubalikkan badan, empat orang sudah berada tepat di belakangku. Masing-masing membawa senjata, entah pisau atau pentungan bisbol, siap menghajarku.
Dasar amatir. Kode mata dibalas mata maka dunia akan buta kugunakan bukan tanpa alasan. Sejak di depan aku tahu ada yang tidak beres.
“Dengarkan dulu, aku punya jaringan distribusi yang luas.”
“Dengan kualitas barangmu yang sangat baik, kita bisa meraup untung lebih banyak.”
“Aku bisa mendapatkan keuntungan tiga kali lipat jika aku menjual kembali obat ini.”
“Kau juga tidak terlihat seperti anggota geng atau apapun. Kau terlihat seperti anak kuliahan. Kalau benar, kau bisa membuat jaringan di dalam universitasmu, bukankah itu terdengar keren?”
“Atau kau bisa menjadi informan atau distributor? Tampilanmu tidak begitu mencolok. Kau akan bekerja dengan baik.”
Mencari masalah dengan para pecandu adalah ide buruk. Mereka tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Tapi aku bisa rugi banyak, jumlah uang di tasnya bahkan tidak sampai tiga perempat dari kesepakatan. Aku bisa saja menghajarnya atau bahkan membunuh mereka, tapi bagaimana aku bisa meraih mimpiku di dalam penjara. Setelah beberapa saat aku mempertimbangkan, “aku akan mengambil uangnya. Terima kasih sudah berbisnis denganku.”
“Baiklah, bos muda. Semoga bisnismu lancar.”
Tapi apa yang bisa diharapkan dari pecandu seperti mereka? Empat orang mengelilingiku, sekarang lima. Masing-masing membawa senjata tajam untuk menghajarku. Aku tahu sejak aku melakukan pekerjaan haram ini suatu saat aku akan menghadapi situasi seperti ini minimal lebih dari sekali. Aku menganggapnya sebagai resiko pekerjaan, tidak lebih.
“Seharusnya kau terima saja tawaran kami bos muda. Kau tahu? Kau benar-benar menyakiti hatiku.” Ucap pecandu di belakangku. “Karena pelayanan yang buruk, aku ingin uangku kembali.”
Mereka semua terlihat ganas, bersemangat sekali untuk menghabisiku. Aku memperingatkan, “mata di balas mata dan dunia menjadi buta.”
“Woah, mengerikan sekali. Aku takut.” Ucap salah seorang dari mereka dan semua temannya ikut tertawa.
Tanpa aba-aba satu orang maju menerjang, kemudian semuanya mengalir seperti sungai. Dan disinilah aku. Duduk sendirian dengan darah terus mengalir karena luka sayatan yang sangat lebar. Ditemani pecandu gila yang berani-beraninya menyerang duluan.
“Bodoh, seharusnya kalian tidak menyerang duluan. Lihat sekarang kalian mati dan aku sekarat.”
“Kuakui kalian semua punya nyali. Tapi aku juga bukan amatiran.”
Kualihkan pandanganku ke jalan buntu di seberang. Sekarang darah mereka sudah melebar sampai trotoar. Di balik bayangan gelap itu, empat mayat tergeletak. Gampang sekali menghabisi pecandu muda yang gegabah, meski aku mendapat luka yang begitu lebar ini. Yang satu ini, melihat teman-temannya terbantai membuat nyalinya ciut lalu berusaha kabur. Namun aku tidak bisa membiarkannya begitu saja.
Dan disinilah aku duduk sendirian menunggu kematian. Tuhan mengirimkan bantuan melalui orang-orang yang berhenti sebentar kemudian lari terbirit-birit. Terima kasih Tuhan, bantuan-Mu sangat berguna. Lebih baik aku menghadap-Mu daripada harus repot-repot berurusan dengan polisi dan masyarakat.
Mimpiku redup seperti lampu jalanan di seberang jalan. Semakin lama semakin mustahil mimpi itu untuk diraih. Aku hanya ingin lulus, kenapa susah sekali.
Terlintas bayangan bapak dan ibu barang sekejap. Raut wajah mereka kecewa, tentu saja. Meski aku bukan pecandu, aku tidak lebih baik dari mereka. Entah apa yang akan kukatakan pada bapak dan ibu setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Rasanya jadi tambah canggung. Tapi mana mungkin aku bisa bicara dengan mereka, Tuhan tidak akan membiarkanku melihat surga barang sekilas.
Perlahan bayangan hitam merambat dari sisi penglihatanku. Inilah saatnya istirahat, selamanya.
Mimpiku… Begitu tinggi dan mahal.
Seperti pungguk merindukan bulan. Tidak, pungguk tak pernah merindukan bulan, mengenalnya saja ia tak pernah. Kenapa harus repot-repot rindu.
Ikuti tulisan menarik Alvito Faza lainnya di sini.