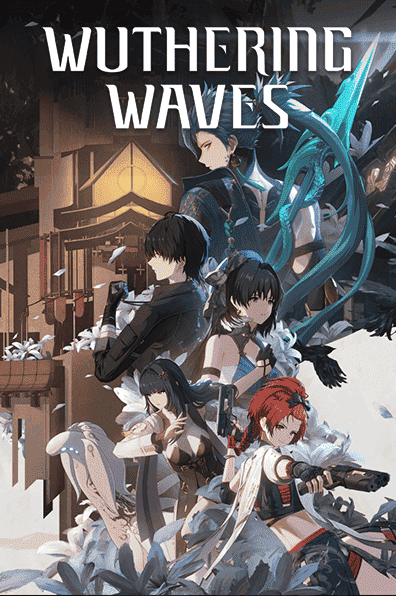Lonceng Kematian
Rabu, 17 November 2021 15:48 WIB
Kisah mengharukan perjuangan sepasang kekasih beda ras dan kultur yang harus terpisahkan oleh tirani kekuasaan dan politik hingga lonceng kematian memisahkan cinta mereka untuk selama-lamanya.
Dengan nafas terengah-engah dan bermandikan keringat dingin membasahi tubuhnya, Kho Bing Ong, sang kapitan Tionghoa terbangun dari tidurnya. Pelupuk matanya mengerjap-ngerjap. Sudut-sudut matanya masih digerayangi sisa mimpi semalam. Dia mengambil napas panjang. Ditatapnya langit-langit penjara yang rendah, bau lembab, yang sudah setahun lamanya dia tempati. Kho Bing Ong ditangkap karena dituduh menjadi dalang pemberontakan para tauke dan kelompok pemuda keturunan Tionghoa terhadap pemerintah VOC yang saat itu berkuasa di Batavia hingga berujung pada tragedi Kali Angke pada tahun 1740 yang menewaskan puluhan ribu warga keturunan Tionghoa di Batavia.
Pemuda keturunan Tionghoa tersebut melangkah berat menuju lubang pintu besi penjara bawah tanah. Di luar sana, ekor matanya hinggap pada lalu lalang pasukan kompeni yang sibuk mengepulkan asap rokok. Sesekali menggerombol, berbincang-bincang, tertawa-tawa, lantas menyebar ke bilik-bilik, menatap para napi dengan wajah garang dan tak bersahabat.
Sementara dari dalam bilik sel, siang dan malam, Kho Bing Ong bisa mendengar suara dinding yang dikikis perlahan. Sebenarnya mereka sadar bahwa mustahil dan sia-sia belaka untuk melubangi tembok penjara yang kokoh dan tebal itu, namun mereka tetap saja berusaha mengikisnya. Bahkan cara itu sudah seperti ritual keagamaan bagi mereka, cara untuk meyakini bahwa masih ada kehidupan yang indah di luar sana. Sementara itu beberapa pasukan kompeni yang berjaga hanya mondar-mandir di sepanjang lorong, menyeret langkah mereka seperti bayi kurus.
Dari jauh, sayup-sayup terdengar suara langkah kaki, decit sepatu, berpasang-pasang, tetapi teratur. Semakin lama semakin keras, semakin dekat, menggema di segenap tembok lorong penjara. Memecah kesunyian pagi yang meruang. Menyadarkan jiwa para pesakitan yang masih terlelap. Berpasang-pasang mata dari balik jeruji besi memandangi mereka dengan penuh tanda tanya, siapa lagi pagi ini yang akan menemui takdirnya untuk memenuhi panggilan sang lonceng kematian. Soli Deo Gloria, begitulah orang-orang Belanda biasa menyebut lonceng itu.
Entah kapan waktu mereka tiba, yang pasti hal itu pasti akan terjadi. Semua suara sepatu itu berhenti tepat di depan pintu bilik penjara Kho Bing Ong.
“Selamat pagi Kho Bing Ong!” sapa seorang berkulit putih dengan baju pendetanya. “Selamat pagi!” jawab Kho Bing Ong seraya bangkit dari pembaringannya.
“Perkenalkan namaku Albert. Aku seorang pendeta. Aku ditugaskan oleh gubernur Andriaan Valckenier untuk memberikan pencerahan kepadamu sebelum pelaksanaan eksekusi mati. Bing Ong, aku banyak mendengar cerita tentangmu dan aku turut bersimpati kepadamu. Aku hanyalah seorang pendeta, meskipun aku seorang Belanda tetapi aku adalah orang yang menentang kesewenang-wenangan,” kata Albert.
“Aku mengerti pendeta, pastilah engkau adalah orang yang baik,” ucap Kho Bing Ong.
“Bing Ong apakah kamu takut?” tanya Albert.
“Pendeta, nyawa ini hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemiliknya, kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Bukankah kematian itu adalah sebuah takdir. Jadi mengapa aku harus takut?” jawab Kho Bing Ong.
“Pendeta, maukah kamu memenuhi permintaan terakhirku?” tanya Kho Bing Ong lirih dengan tatapan mata penuh makna kepada Albert.
“Oh, tentu, katakanlah!” balas Albert.
“Tolong sampaikan suratku ini untuk Maria?” jawab Kho Bing Ong.
“Pendeta, sungguh kerinduanku pada Maria semakin dalam mengeruk cintaku padanya. Meski kami berbeda dunia, namun cinta kami tak akan sirna. Tatapan mata birunya terus mengikutiku, membuatku luluh karena desiran jiwa ini tak mungkin bisa kuingkari,” lanjutnya.
“Baik. Akan kusampaikan suratmu ini,” sahut Albert.
“Terimakasih,” balas Kho Bing Ong.
Sesaat kemudian, dari bilik penjara, sayup-sayup terdengar suara lonceng berbunyi. Suara lonceng besar terdengar dari atap menara Stadhuis, Batavia. Suaranya sungguh akan membuat bulukuduk berdiri bagi siapapun yang mendengarnya. Bunyi lonceng itu seolah merupakan panggilan kematian, pertanda ada tawanan Belanda yang akan dieksekusi mati. Sudah tak terhitung lagi berapa orang tawanan Belanda yang sudah menjemput ajal di tiang gantungan.
Soli Deo Gloria, begitulah mereka menyebut nama lonceng itu. Bunyi lonceng ini merupakan pertanda warga akan menyaksikan “malaikat maut” menggantung sang pesakitan. Lonceng itu akan dibunyikan untuk memanggil semua warga di dalam maupun di luar tembok Batavia untuk menyaksikan pelaksanaan eksekusi mati.
“Bing Ong, lonceng besar telah dibunyikan, berarti eksekusi siap dilaksanakan,” kata pendeta Albert.
“Aku sudah siap pendeta.” sahutnya.
“Bing Ong, sekali lagi apa ada permintaan terakhir yang ingin kamu sampaikan kepadaku?” tanya Albert.
“Pendeta, tolong sampaikan juga pada Maria bahwa suatu yang terbaik adalah percaya pada hati nurani,” ucap Kho Bing Ong.
“Baik nanti akan kusampaikan pesanmu ini pada Maria,” ucap Albert.
“Terimakasih pendeta, semoga Tuhan membalas kebaikanmu,” sahut Kho Bing Ong.
Kini kedua tangan Kho Bing Ong sudah terikat dengan borgol, dengan kepala tertutup kain hitam, dia pergi meninggalkan bilik penjara menuju lapangan eksekusi. Yang ada hanya kegelapan, hitam pekat, hanya desiran angin yang terdengar di telinganya. Hembusan angin sepoi, lembut, seolah hendak menyapanya, membisikkan suatu pesan dari surga. Sunyi, senyap, mengiringi suasana hatinya yang pasrah. Sesaat lagi eksekusi mati siap dilaksanakan. Sebagian warga Batavia yang sudah berkumpul di lokasi eksekusi pun terdiam seribu bahasa, mereka menanti saat-saat sang tali menggantung leher Kho Bing Ong.
Sementara itu di lain tempat, di dalam kamar, nampak seorang wanita dengan wajah dan perawakan Belanda mondar-mandir, sambil sesekali pandangannya mengarah ke luar. Dengan sepasang mata birunya, dari balik jendela kamarnya, dia memperhatikan suasana keramaian di lapangan Stadhuis. Suara riuh rendah dari kerumunan warga yang bergerombol di sekeliling arena panggung eksekusi.
Dalam kegalauannya, gadis itu terduduk lemas, bersimpuh di samping ranjang, menghadap tembok kamarnya. Nampak sebuah salib terpajang di sisi tembok warna putih. Dengan kepasrahan, menurut keyakinannya sebagai penganut Kristen, dia mulai khusyuk mengucapkan bait-bait doa dan harapan kepada Tuhannya. Jemari kedua tangannya disatukan dan sementara sepasang mata birunya yang berbingkai kelopak mata dengan bulu rambut mata yang lentik, tak lepas dari salib yang terpasang di tembok kamarnya. Nampak butiran bening bagaikan kilauan embun diterpa cahaya pagi memenuhi kelopak matanya.
“Atas nama Bapa di surga, Tuhan salahkah jika aku mencintainya. Apakah semua perbedaan ini harus memisahkan kami, setelah Engkau menghadirkan cinta di hati kami? Mengapa cinta kami harus berakhir di ujung kematian? Di manakah keadilan untukku. Bapa, kini kekasihku sedang menjemput kematiannya, namun bukan atas kemauannya. Kumohon selamatkan dia, berikanlah kesempatan kepadanya untuk memenuhi takdir hidupnya,“ tangisnya dalam doa.
Sementara itu Kho Bing Ong sudah memasuki lapangan eksekusi di lapangan Stadhuis dengan dikawal pasukan bersenjata lengkap. Dengan tangan terikat, sebagai seorang pesakitan, dia memasuki lapangan eksekusi. Langkah demi langkah semakin dekat menuju tiang gantungan. Suasana yang penuh sesak dengan lautan manusia yang ingin menyaksikan jalannya eksekusi tersebut, bisik-bisik, kasak-kusuk membuat nyali sang pesakitan semakin ciut.
Dengan iringan suara langkah berpasang-pasang sepatu pasukan kompeni yang berbaris di belakangnya, menimbulkan irama yang teratur bak musik pengiring kematian. Belum sampai langkahnya sampai di panggung eksekusi, tiba-tiba terlihat kilatan-kilatan petir yang menembus langit mendung dengan awan hitam bagaikan cakar sang maut yang ingin mencengkeram nyawa siapa pun, yang disusul dengan suara gemuruh halilintar yang menggelegar, memekakkan telinga, membuat suasana semakin mencekam. Sesaat kemudian awan hitam pun tak kuasa untuk menahan beban, hujan pun turun dengan deras mengguyur lapangan Stadhuis. Tetapi itu semua tidak membuat orang-orang beranjak dari tempatnya, mereka ingin menyaksikan detik-detik pelaksanaan eksekusi sang kapitan.
Langkah kakinya terhenti di pinggir panggung. Dengan dikawal dua orang yang bertugas sebagai eksekutor, Kho Bing Ong segera menaiki panggung eksekusi. Sekarang nampak di hadapannya sebuah tiang gantungan yang kokoh tegak berdiri bagaikan malaikat pencabut nyawa. Tali yang kuat menggelantung di tiang gantungan seolah siap menyambutnya.
Sejenak kemudian, setelah ada perintah dari sang pimpinan eksekutor, Kho Bing Ong naik ke atas kayu penopang kaki. Dengan cekatan seorang memasang tali gantungan ke leher Kho Bing Ong. Dengan hati berdebar dan jantung berdegub kencang, dia berpasrah kepada Sang Maha Pencipta. Belum sampai aba-aba kedua, tiba-tiba terjadi kegaduhan dari dalam salah satu ruangan Stadhuis. Terlihat beberapa pasukan memegang tangan seorang gadis Belanda yang berontak ingin keluar menuju lapangan. Dia berteriak-teriak memanggil nama Kho Bing Ong.
Tetapi karena tenaga gadis itu kalah kuat dari tenaga para prajurit yang menahannya untuk tidak keluar, dia hanya terduduk lunglai sambil menangis tersedu-sedu, sesekali dia menyebut nama Kho Bing Ong dengan lirih. Lirih dari hati yang paling dalam. Semua yang hadir di situ, menahan nafas, sejenak terdiam seribu bahasa, entah apa yang ada di benak mereka dan apa yang mereka rasakan. Seketika suasana mendadak menjadi hening. Sang eksekutor segera mengambil kayu penopang kaki Kho Bing Ong. Seketika itu juga tubuhnya menggelantung dengan tali yang mengikat di leher dengan sangat erat. Sesaat setelah tubuhnya menggeliat-geliat karena nafas tertahan tali gantungan, tubuhnya diam tak bergerak, hanya angin yang cukup kencang menggoyang tubuhnya. Nampak raut kesedihan di wajah orang-orang yang sejak tadi mengikuti jalannya eksekusi. Banyak yang meneteskan air mata kesedihan. Air hujan mengiringi eksekusi tersebut sepertinya langit pun turut bersedih.
Tiba-tiba wanita Belanda tersebut lolos dan kembali berlari keluar menuju lapangan sambil memanggil nama Kho Bing Ong, memecah keheningan suasana. Gaun terusan berenda khas Belanda warna putih basah kuyup oleh guyuran air hujan. Rambut pirangnya dia biarkan terurai oleh air hujan. Seolah tak memperdulikan berpasang-pasang mata yang menatapnya, perempuan itu terus saja berlari menembus kelebatan hujan.
Gadis itu terus berlari tak menghiraukan dengan kejaran pasukan yang mencoba untuk menghalanginya, menuju panggung eksekusi, menubruk, memeluk tubuh Kho Bing Ong pada sebatas paha. Kemudian dia terduduk lunglai, bersimpuh sambil meratap. Di tengah-tengah guyuran hujan, ratapan gadis itu semakin membuat pilu hati orang-orang yang menyaksikan tragedi tersebut. Tragedi cinta yang memilukan.
“Jangan kamu tinggalkan aku. Aku tidak bermaksud mencelakaimu. Aku telah dibohongi, aku dijebak (menangis), aku mencintaimu. Maafkan aku... ” tangis dan ratap pilu Maria.
“Kalian cepat lepaskan dia, lepaskan ikatan tali di lehernya!” teriak kembali Maria pada sang eksekutor. Tetapi sang eksekutor hanya diam mematung saja, tak menggubris kata-katanya.
Untuk sesaat isak tangisnya mereda dan terdiam, hanya rongga dadanya yang naik turun sambil mengatur nafasnya dengan perlahan. Tiba-tiba saja Maria merebut belati dari pinggang sang eksekutor, mencabutnya dan menghujamkan ke jantungnya. Maria pun sontak meregang nyawa. Dalam sisa tenaganya, dia memandang tubuh sang kekasih yang tergantung dengan tatapan mata nanar, berurai air mata dan selanjutnya terpejam.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Lonceng Kematian
Rabu, 17 November 2021 15:48 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0








 97
97 0
0