Kehilangan
Selasa, 23 November 2021 05:40 WIB
Kehilangan selalu mengajarkan banyak hal
Pada sebuah kardus berdebu, menyembul sebuah buku berwarna biru yang perlahan kehilangan warnanya, memudar seiring berjalannya waktu. Buku itu memiliki motif seperti bunga atau entah apa, sudah tidak terbentuk lagi. Buku itu kira-kira memiliki ketebalan sebesar tiga inchi dan berhasil membuatku terbatuk ketika pertama kali aku membukanya.
Pada lembar pertama buku ini menampakkan wajah dua sosok yang paling aku cintai di dunia setelah Allah dan RasulNya, Ibu dan Ayahku. Ibuku mengenakan gaun putih panjang menyapu lantai. Riasan matanya memberi efek mata tampak lebih besar dan tajam. Ibu tersenyum bahagia dengan rona merah pada pipi dan bibirnya. Ayah juga tampak gagah dengan setelan jas hitamnya. Sepatu pantofel yang dikenakannya membuat Ayah terlihat tampak lebih tinggi. Peci hitam yang Ayah kenakan juga menambah nilai elegan penampilannya. Itulah awal kisah cinta orang tuaku, tanpa pacaran hanya ada ikatan pernikahan.
Pada lembar kedua dari buku berwarna biru itu tamapklah wajahku. Anak pertama sekaligus terakhir mereka. Ibuku tidak pernah Allah berikan kesempatan mengandung lagi, hanya akulah harapan mereka, kebanggaan mereka, dan amal jariyah mereka.
Lembaran-lembaran selanjutnya dari buku berwarna biru itu menampakkan betapa bahagianya masa kecilku.
Ayah selalu mengajak kami berkeliling kota dengan menunggangi sebuah becak. Memang becak memakan waktu cukup lama karena hanya mengandalkan kekuatan kaki mamang becak, tapi tidak pernah membuatku bosan. Aku menyukai terpaan angin menyapa wajahku, diiringi dengan suasana kota di malam hari dengan kilauan lampu berbagai warna yang terpantul dari rumah-rumah, pertokoan, atau sekadar kendaraan bermotor yang melintas.
Ayah memiliki banyak tukang becak langganan bahkan sampai sekarang tukang-tukang becak itu masih hapal pada kami. Tidak sedikit juga tukang becak yang mengeluhkan berbagai macam alat transportasi online mematahkan usahakan mereka, tapi bukankah Allah sudah menjamin rezeki semua hambanya? Aku yakin Allah tidak akan sia-siakan usaha mereka.
Ayah juga suka wisata kuliner. Kami rela berjalan kaki menyusuri pedagang kaki lima menuju pedagang kaki lima lainnya. Rasanya hampir tidak ada satu pun pedagang yang terlewat. Semua pedagang memanggil Ayah “Pak Haji” hanya karena Ayah selalu menggunakan peci. Memang Ayah sempat pergi haji bersama Nenek sebelum menikah dengan Ibu, tapi Ayah belum pernah pergi haji lagi bersama kami. Kata Ayah semoga kami bisa ke sana lagi nanti karena selalu ada rasa rindu tertinggal di sana, selalu ada cerita dan hikmah terbaik di antara Mekkah dan Madinah.
Setiap akhir pekan aku selalu meminta Ayah untuk menemaniku ke pusat perbelanjaan. Bukan, bukan untuk selalu membeli sesuatu tapi hanya sebagai penebus waktu yang Ayah tidak lewatkan bersamaku ketika Ayah sibuk bekerja. Saat perjalanan pulang dari pusat perbelanjaan seringnya aku tertidur di pangkuan Ayah di atas sebuah angkutan kota. Betapa menyusahkannya diriku kala itu, tapi Ayah hanya tersenyum.
Lembar-lembar selanjutnya dari buku berwarna biru ini menampilkan aku yang sudah tumbuh remaja dalam sebuah acara, aku masih ingat sangat jelas detail acara itu karena acara itu selalu aku bayangkan sebagai acara untuk diriku sendiri.
Pagi-pagi sekali keadaan rumah kami sudah ramai dikunjungi beberapa pesulap yang akan merubah penampilan wajah kami dengan riasan sederhana tanpa bulu mata palsu dan cukur alis. Pakaian yang kami kenakan semua senada, biru langit secerah warna langit pagi ini. Bagian roknya menjuntai panjang menyapu lantai sampai rasanya sepatu kesayaganku pun terlahap olehnya. Berkali-kali aku mematut-matutkan diriku pada cermin bulat yang berada di sudut kiri kamarku. Kupandangi diriku dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku tampak berbeda dari aku yang biasanya. Bolehkah aku memuji diriku sendiri?
Ayahku juga tampak tak biasa dengan setelan jasnya. Terlihat lebih muda dari usia asalnya. Sepatu pantofel yang Ayah kenakan membuatnya tampak terlihat lebih tinggi. Peci kesayangannya tidak pernah luput darinya, melengkapi penampilannya hari itu.
Ayahku duduk di sana, di kursi yang menyita seluruh perhatian para keluarga dan tamu. Menjabat erat tangan seorang lelaki yang hampir penuh dengan peluh karena sangat cemas dengan apa yang akan keluar dari lisannya dapat menghancurkan momen yang dia harapkan hanya terjadi sekali seumur hidupnya.
Saat akhirnya kata “SAH!” itu mengudara dari seluruh saksi, ayah dan laki-laki itu tersenyum untuk alasan yang berbeda. Ayah tersenyum bangga pada laki-laki itu dan menaruh harap besar laki-laki itu akan bertanggung jawab sebagaimana mestinya seorang lelaki sejati. Sedangkan lelaki itu tersenyum lega pada Ayah, lega bahwa perjalanan pertama menapaki kehidupan yang baru telah terlewati dengan sangat baik. Tangis haru para keluarga dan tamu mengiringi perjalanan sepupuku menuju laki-laki itu. Ucapan selamat dan doa tidak pernah terlepas dari lisan-lisan kami. Ya, sudah semestinya sepupuku itu bahagia dan menemukan sosok pengganti Ayahnya yang meninggal 3 tahun silam.
Ketika Ayah sudah kembali duduk bersama aku dan Ibu, tak henti-hentinya aku berkata bahwa aku juga menginginkan pernikahan syar’i seperti ini. Tirai menjulang tinggi nan panjang sebagai pemisah tamu laki-laki dan perempuan, layar proyektor lebar menayangkan nasihat pernikahan dan adab makan diiringi latar belakang suara gemricik air dan cuitan burung sebagai pengganti musik, lalu buku dzikir pagi petang beserta buku-buku saku lainnya bersampul namaku dan nama suamiku kelak sebagai tanda terima kasih pada para tamu yang telah hadir. Anganku sudah jauh ke sana padahal laki-laki yang akan menikahiku pun belum tampak, tapi Ayah mendukung dengan sangat bahkan seolah memberi kode pada pemilik Wedding Organizer yang kami sewa hari itu untuk dapat bekerja sama lagi nanti.
Lembar selanjutnya pada buku berwana biru ini tampak beberapa foto yang berbeda. Foto-foto tersebut memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari foto-foto sebelumnya. Foto-foto ini diambil dari telepon pintar pertama yang Ayah beli. Ayah yang sebelumnya tidak pernah tertarik dengan telepon pintar, tiba-tiba membeli telepon pintar hanya karena saat itu aku akan menuntut ilmu di Ibu Kota. Ayah ingin selalu memastikan aku menunaikan kewajiban ibadahku walau aku berada puluhan kilometer jauhnya. Ribuan pesan singkat dan rekaman suara bernada sama, “Jangan lupa shalat, Tan” tak pernah luput dari hari-hariku.
Sedikit cerita tentang bagaimana aku dapat menuntut ilmu di Ibu Kota.
Aku sudah mengikuti sebuah bimbingan belajar sejak aku duduk di kelas sebelas. Harapanku besar untuk dapat berkuliah di perguruan tinggi negeri ternama di Jakarta dan Bandung.
Saat hari pengumuman tes tersebut, aku berhasil lolos di pilihan keduaku yaitu Bandung. Haru meliputi diriku ditambah lagi raut wajah bangga orang tuaku padaku. Seluruh drama perkuliahan melambung tinggi dalam benakku.
Sayangnya segala khayalanku saat itu harus pupus karena situs kampus down setiap kali aku mengaksesnya. Mungkin karena banyaknya mahasiswa baru yang mengakses kala itu dan bodohnya aku santai saja, tidak terus menerus mencoba masuk sampai berhasil. Selang dua hari berlalu setelah pengumuman, aku berhasil membuka situs kampus dan aku baru mengetahui bahwa hari itu adalah hari terakhir daftar ulang sedang hari itu sudah cukup sore dan jarak antara rumahku dan Bandung itu cukup jauh. Jika aku sampai sana pun hari itu, bagian administrasi telah tutup. Apa yang harus aku lakukan?
Kampus itu agak unik. Setiap mahasiswa yang dinyatakan lolos sebagai mahasiswa baru walau belum daftar ulang dihimpun dalam sebuah grup chat, termasuk aku. Katanya grup chat ini berfungsi untuk memberi informasi terkait kampus dan menjalin ukhuwah antar mahasiswa baru dan panitia ospek. Namun, pertanyaannya mengapa grup chat ini baru ada sekarang? Di saat informasi sepenting daftar ulang telah tutup?
Dengan harapan yang masih tersisa dalam diriku, aku dengan cerobohnya langsung mempercayai seseorang yang mengaku mahasiswa di sana dan berkata akan membantuku melakukan registrasi ulang. Tugasku harus transfer sejumlah uang padanya yang akan dia serahkan pada admin kampus. Ya, seperti yang kau duga … aku tertipu dengan indahnya dan aku gagal menjadi mahasiswa kampus negeri ternama di Bandung itu.
Sampai akhirnya aku mencoba lagi mendaftarkan diriku pada universitas negeri lain di Jakarta, tapi lagi-lagi uang. Seorang oknum menjanjikanku untuk membayar sejumlah uang agar aku menjadi mahasiswa resmi, tapi aku menolak. Aku ingin cara yang bersih. Aku percaya penuh akan kemampuanku.
Aku mengganti haluan, aku memutuskan untuk daftar universitas swasta. Alhamdulillah segalanya terasa lancar sampai aku resmi menjadi mahasiswa.
Sampai tiba akhirnya aku bertemu seorang teman yang cukup membuatku iba dengan kisah hidupnya. Ibunya telah meninggal dan ayahnya telah menikah lagi. Dia hanya tinggal dengan adiknya. Untuk menghidupi dia dan adiknya, dia kerja apa saja yang dia mampu sampai nilai kuliahnya pun berantakan dan beasiswanya terancam dicabut.
Tidak hanya itu, laptop lamanya yang biasa dia gunakan untuk menunjang kuliahnya pun rusak. Dia semakin kesulitan mengerjakan tugas-tugas kampus. Aku berinisiatif meminjamkannya laptopku. Dalam sehari pinjam, laptopku masih kembali ke tanganku lagi. Namun, di hari berikutnya … raib.
Di saat yang bersamaan, di kota asalku.
Ayah dituduh di tempat kerjanya yang terpaksa merenggut seluruh harta, kekuasaan, dan jabatan yang Ayah bangun dari nol. Namun, ayah tidak menyerah. Itu yang membuat hatiku hancur berkali-kali lipat jauh lebih sakit karena aku tahu perjuangan Ayah.
Ayah selalu mengusahakan segala hal yang terbaik untuk kami. Bekerja diterpa debu jalanan di bawah terik matahari dan kadang hujan badai. Sepatunya menganga, kakinya menebal menandai lelahnya menopang tubuhnya. Tubuhnya pun semakin lama semakin kurus seiring bertambahnya usia.
Di tambah lagi penyakit ganas yang kami kira sudah punah dari tubuhnya, kembali menggerogotinya. Kesadarannya menurun, Ayah bahkan sempat melupakan aku, satu-satunya putrinya. Ingatan masa lalu dan masa sekarangnya menyaru, Ayah sudah tidak mampu lagi membedakan mana masa lalu dan mana masa sekarangnya. Lisannya banyak meracaukan hal-hal yang selama ini Ayah pendam. Ayah juga sering berkata seperti ada duri yang menusuk-nusuk kakinya sehingga sulit untuk membuatnya berdiri. Ya, jangankan untuk berjalan, untuk berdiri pun Ayah butuh banyak hal untuk menopangnya.
Sampai akhirnya momen itu tiba. Momen-momen yang mengakhiri buku berwarna biruku bersama Ayah.
Kubendung air mataku. Aku katakan berkali-kali pada diriku sendiri bahwa aku kuat. Aku sanggup melewati ini. Sampai jasad Ayahku telah hilang tertimbun tanah, hanya segelintir air mataku yang jatuh. Kata-kata ‘aku kuat’ tetap aku rapalkan kencang-kencangnya dalam benakku.
Ayahku tidak meninggalkan warisan apa pun. Tidak dengan sebidang tanah atau juga emas yang berlimpah. Bahkan kekuasaan Ayahku pun langsung lenyap. Seolah tidak ada yang pernah mengenal Ayahku setelah kematiannya, padahal Ayahku satu dari dua orang paling berjasa di tempat kerjanya. Sekejap itu mereka melupakannya. Teriakanku di depan muka mereka bahwa aku ini adalah anaknya pun sudah tak menghasilkan apa-apa.
Selang beberapa hari kematian ayahku, aku masih harus disibukkan dengan segala dokumen kematian Ayahku. Satu, surat kematian berwarna kuning cerah … ah rasanya aku sudah tidak akan melewatkan hari secerah warna kuning surat ini lagi dalam hidupku. Dua, akte kematian … ah rasanya baru kemarin Ayahku yang mengurus akte kelahiranku dengan perasaan haru karena terlampau bahagia menyandang status baru sebagai seorang Ayah. Sekarang aku yang mengurus akte kematiannya dengan perasaan haru yang sama untuk alasan yang berbeda, haru karena terlampau sedih menyandang status baru sebagai seorang anak yatim. Tiga, kartu keluarga … rasanya semakin sepi saja kartu keluargaku. Dulu ada tiga nama di sana, nama Ayahku, Ibuku, dan aku. Sekarang hanya ada nama Ibuku dan aku saja, sungguh janggal rasanya melihat nama Ibuku menjadi kepala keluarga. Aku pun mengurus Kartu Tanda Penduduk Ibuku yang sekarang berstatus sebagai cerai mati. Tidak hanya itu, aku pun mengurus uang duka dan uang-uang yang harus menjadi hak Ayahku pasca kematiannya. Namun sungguh, aku bagaikan pengemis. Segala hal terasa sulit. Uangku sudah habis duluan untuk transportasi ke kantor sana dan sini sebelum aku sempat dapat uang Ayahku.
Aku pun berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Sampai akhirnya panggilan untuk wawancara dari sebuah sekolah sunnah itu muncul.
Ternyata selain wawancara, ada sebuah tes keagamaan yang alhamdulillah dapat aku lewati dengan kadar keilmuan agamaku yang masih seadanya. Tanpa disangka, jawaban-jawaban itu tetap mampu mengantarkanku resmi menjadi salah satu pengajar di sana.
Pikirku, di sini aku akan baik-baik saja karena segalanya akan diatur dengan norma agama. Ternyata tidak, ada banyak ketidakadilan di sini. Mereka memperlakukanku seolah aku ini paling hina karena aku bukan orang dari lulusan pondok pesantren ternama, aku juga bukan seorang donatur atau anak dari donatur yang paling berpengaruh untuk kelangsungan pembangunan sekolah. Apakah sikap membeda-bedakan ini pantas untuk sebuah sekolah sunnah? Sedangkan yang kita tahu, Allah tidak pernah membeda-bedakan hambanya kecuali atas kadar ketakwaannya. Apakah latar belakang pendidikan dan isi dompet memengaruhi ketakwaan seseorang? Sebenarnya Tuhan siapa yang mereka sembah?
Sekalinya mereka seolah berbuat baik padaku, mereka mencoba menjodohkanku dengan seorang lelaki. Lucunya ketika kutanya lebih dalam tentang laki-laki itu, mereka pun tidak begitu mengenal laki-laki tersebut. Bagaimana bisa aku membiarkan sisa hidupku di tangan seorang laki-laki asing yang tidak aku ketahui sama sekali. Jangankan laki-laki itu dapat mengantarkanku ke surgaNya, untuk selamat di dunia saja aku ragu.
Lain soal lagi jika mereka mencarikan jodoh untuk salah seorang anak kerabat yayasan dan memiliki hafalan Al-quran yang baik. Mereka langsung mencarikan seorang laki-laki lulusan Unversitas Islam Madinah. Bukankah di sini juga aku sedang mempelajari Al-quran? Aku tahu, aku masih belum ada apa-apanya. Aku masih belum sebanding dengan mereka, tapi aku berproses selangkah demi langkah menjadi aku yang lebih baik setiap harinya.
Betapa beratnya dunia yang aku lalui tanpamu, Ayah. Bukan sekali dua kali aku berharap mati, tapi aku harus sadar mati pun tidak akan menyelesaikan masalah. Aku pun harus sadar, ada Dzat yang jauh lebih mampu menjagaku lebih dari Ayahku. Dialah penciptaku. Satu-satunya Tuhanku. Tugasku hanya perlu untuk bertakwa padaNya di mana pun berada dan dalam kondisi apa pun, lalu Allah yang akan beri jalan keluar dari arah yang tidak terduga.
“ … Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya” (Surat Ath Thalaq ayat 2)
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Satu Kalimat
Minggu, 28 November 2021 16:31 WIB
Ironi
Rabu, 24 November 2021 19:19 WIBArtikel Terpopuler

 0
0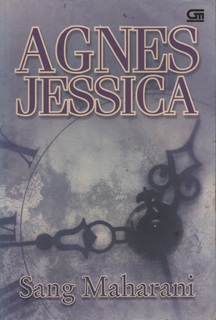
 Berita Pilihan
Berita Pilihan








 99
99 0
0


















