Lomba Esai Zaman Kiwari: Niat Hati Berinovasi, tapi Malah Membikin Jeri
Sabtu, 20 Agustus 2022 06:23 WIB
Atas nama inovasi, kebanyakan lomba esai di kalangan mahasiswa dewasa ini bisa dibilang salah parkir. Membikin jeri.
Kebanyakan pihak penyelenggara bakal “mempersyaratkan” esai-esai yang memuat produk atau aplikasi teranyar—yang biasanya dipadu-padankan menjadi sebuah akronim—sebagai output-nya. Gaya penulisan yang lurus plus judul yang panjang, merupakan ciri khas dari tulisan-tulisan yang diikutkan dalam perlombaan bergenre samacam ini.
Adapun perihal tema, biasanya, kekinian: soal Revolusi industri 4.0 lah, Society, 5.0, SDGs, atau Indonesia Emas 2045. Kata “menyongsong”, “peran”, atau “implementasi”, adalah beberapa diksi yang lazimnya terselip dalam tema perlombaan.
Soal ketentuan penulisan esai, pihak panitia (dalam buku panduan lomba atau guidebook) bakal menyuruh para peserta untuk membaginya menjadi tiga bagian—pendahuluan, isi, penutup. Bahkan, tak sedikit juga pihak panitia yang meminta untuk menyertakan lampiran dalam esai yang akan dilombakan.
Entah hal apa dan siapa yang memulai, serta menjadi musababnya. Namun yang jelas, dengan mempersyaratkan esai yang demikian, malah menimbulkan suatu pertanyaan sekaligus prasangka: apa benar yang dilakukan oleh para penyelenggara tersebut merupakan sebuah lomba esai?
Pasalnya jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, katanya, esai itu yang prosa lalu sepintas dan personal sifatnya. Adapun menurut mbah-nya esai, Michel de Montaigne (1533-1592), esai adalah percobaan—yang bukan sekedar coba-coba. Menurutnya, esai merupakan sebuah cerminan, meditasi, serta pengungkapan gagasan, yang diekspresikan secara licin dengan bahasa yang luwes [1].
Edward Hoagland, penulis asal Amerika, menjelaskan bahwa esai adalah tentang bagaimana kita berbicara dengan yang lain melalui sebuah teks (print) [2]. Sedikit berbeda menurut sastrawan-cum-cendikiawan, Ignas Kleden, yang menyatakan bahwa esai bakal membikin kita teringat pada “..gerak-gerik, mimik dan gestikulasi, demikianpun kegembiraan dan rasa jengkel akan muncul dalam kalimat-kalimatnya” [3]. Dengan kata lain, ada seni bertutur di dalam tulisan berjenis ini.
Dan esai, “..tidak diperkenankan untuk hadir tanpa rasa poetika,” kata Emha Ainun Nadjib, dalam bukunya Muhidin M. Dahlan, “Inilah Esai” [4]. Maksudnya, esai tidak hanya menyampaikan yang konkrit, tapi juga yang abstrak.
Produk ataupun konsep mengenai aplikasi teranyar, seperti yang dipersyaratkan oleh kebanyakan pihak penyelenggara lomba, adalah suatu yang kongkrit. Dan tentunya, bukanlah suatu yang abstrak.
Perihal produk atau aplikasi yang kerap dipersyaratkan pihak penyelenggara, jika ditanggalkan seluruh aksidensi yang melekat padanya, kedua hal tersebut merupakan semacam respons terhadap “problematika” yang menyalang. Dengan kata lain, sebuah jawaban—bahkan bila pembuatnya cukup ngotot, bisa berarti sebuah kepastian atau ketetapan.
Lantas, apakah esai mengutamakan yang demikian? Goenawan Mohamad, penulis Catatan Pinggir, menyatakan bahwa esai-esainya tak pernah berpretensi untuk memberikan jawaban. Sebab menurutnya, esai itu tak melulu bicara mengenai konsep, tetapi yang lebih dalam dari itu, yakni soal metafora[5].
Sehingga jika mengacu pada pernyataan para esais yang bukan kaleng-kaleng, yang sudah saya sebutkan di atas, bakal mengusik satu pertanyaan paling fundamen terhadap lomba “bergenre” semacam itu: apakah itu sebuah lomba esai?
Apabila disebut sebagai kompetisi karya tulis ilmiah, lomba makalah, (atau mungkin) business case dan semacamnya, saya rasa adalah hal yang tepat. Pasalnya, gaya penulisan dalam lomba bergenre semacam ini terbilang “lurus”; tak licin dan tak luwes, sehingga mengenyampingkan seni bertutur. Pun soal konten yang dimuat dalam tulisan: nihil abstraksi.
Namun jika bersiteguh mendompleng kata “esai” atas perlombaan yang diselenggarakannya itu, jujur saja, sungguh sulit untuk dicari pembenarannya. Ini yang dibilang salah parkir. Sebab, ada ketidaktepatan antara nama yang digunakan dengan apa yang "dilakukan".
Tentu bukan bermaksud meremeh-temehkan berbagai ide dan inovasi yang ada di dalam perlombaan bergenre semacam itu, apalagi berniat untuk memadamkan gelora menulis Kaum Muda. Tidak. Namun pertanyaannya, apakah inovasi yang “wah” bakal muncul dari gelanggang yang masih saja keliru dalam memilih sebuah nama?
Sehingga, kendati perlombaan semacam itu ditujukan untuk menyerap berbagai buah pikiran—dengan harapan menghasilkan suatu inovasi—dari segala penjuru, hal itu malah membikin jeri. Para peserta lomba akan tertuntut dengan sendirinya untuk memenuhi kesalahparkiran pihak penyelenggara. Dan lama-kelamaan, kesalahparkiran itu bakal dianggap sebagai hal yang lumrah—dan benar.
Memiliki generasi penerus yang bersemangat dalam mengaktualisasikan penalarannya, namun seolah tak tahu akan konteks dan untuk hal apa atas seluruh usahanya tersebut, tentu bukanlah suatu hal yang patut dilestarikan.
Bibliografi:
[1] dalam Philippe Desan, ‘Montaigne’, in Montaigne (Princeton University Press, 2017).
[2] Edward Hoagland and Robert Atwan, The Best American Essays 1999 (Mariner Books, 1999).
[3] Ignas Kleden, Sastra Indonesia Dalam Enam Pertanyaan: Esai-Esai Sastra Dan Budaya (Pustaka Utama Grafiti, 2004).
[4] Dahlan, Muhidin. M., Inilah Esai. Tangkas Menulis Bersama Pesohor (Yogyakarta: I:BOEKOE, 2016) p. 12.
[5] ‘Goenawan Mohamad Tentang Esai Dan Puisi’, DW.Com, 5 Mei, 2015.
Orang biasa, lulusan psikologi. Serius bisa, becanda oke; dua-duanya juga sanggup.
0 Pengikut

Lomba Esai Zaman Kiwari: Niat Hati Berinovasi, tapi Malah Membikin Jeri
Sabtu, 20 Agustus 2022 06:23 WIB
Benarkah Mafia Minyak Goreng Sudah Dibongkar?
Kamis, 28 April 2022 16:45 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0



 Berita Pilihan
Berita Pilihan



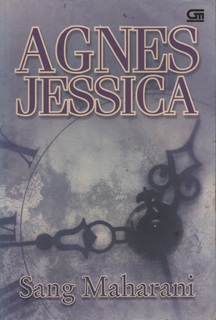

 99
99 0
0
















