Riwayat Tentang Kakek
Selasa, 2 Mei 2023 07:39 WIB
Aku tak tahu mengapa ketika bertanya pada nenek tentang keberadaan kakek, ia selalu membuang muka. Paling sederhana mengalihkan pembicaraan dan yang paling parah aku disentaknya jika terus bertanya.
Kalau boleh jujur, aku hanya ingin tahu mengapa sejak kecil sampai kini usiaku hampir kepala tiga, aku tiada pernah mengetahui riwayat suami dari nenekku itu. Bahkan, sebatas foto yang menggambarkan sosoknya pun tidak ada yang terpajang di dinding maupun tersimpan di laci-laci almari rumah kami. Dan, yang membuat tidak habis pikir, ibu, ayah, berikut paman seolah mengamini ketaksukaan nenek bila aku bertanya tentang kakek.
***
Ketika usiaku genap terbilang tujuh, aku merasa ada hal yang ganjil dalam silsilah keluarga kami. Seperti ada sesuatu kurang, ada sesuatu yang hilang. Tapi, sudah barang tentu aku tidak serta merta tahu apa bagian yang hilang itu. Setelah mulai sering bermain dengan teman-teman sebaya, menghabiskan banyak waktu di rumah mereka, lalu bertemu dengan anggota keluarga kawan-kawan mainku itu, baru kuperoleh kesadaran bahwa ternyata aku tidak memiliki seorang kakek.
Masih lekat di ingatan, usai menyadari kealpaan sosok kakek di rumah kami, aku bertanya kepada ibu perihal keberadaan kakek. Barangkali karena usiaku saat itu masih terlampau hijau, sambil mengulum senyum ibu menjawab sekenanya, “Kakekmu ada di tempat yang sangat jauh dari kita, Ndhuk.”. Lalu ketika kelas lima sekolah dasar, aku mengulang pertanyaan yang sama. Jawaban ibu lebih diplomatis kala itu, ia katakan bahwa kakek sudah tiada sebelum aku terlahir dari rahimnya. Namun anehnya, baik ibu maupun nenek, sekalipun tak pernah mengajakku berziarah ke makam kakek. Hal yang lebih ganjil menurutku, di pemakaman yang berada sepelemparan batu dari komplek perumahan tempat kami tinggal, aku sama sekali tidak menjumpai pusara kakek.
Seiring bertambahnya usiaku, semakin menyeruak rasa penasaranku pada sosok kakek. Saban waktu aku bertambah yakin, jika ada sesuatu yang disimpan rapat-rapat oleh nenek, ibu, ayah, dan paman. Karena mereka selalu memberikan jawaban mengambang setiap kutanya, aku pun berlagak menjadi detektif dadakan. Ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama, kucoba mencari informasi dengan bertanya pada tetangga perumahan. Kupikir mereka yang usianya tidak terpaut jauh dengan nenek pasti tahu. Ternyata dugaanku keliru, sebab ketika kutanya, tetangga-tetanggaku hanya menjawab dengan gelengan kepala dan bahu yang terangkat.
***
Setelah sekian tahun hidup dengan teka-teki, untuk pertama kali di petang yang gamang ini nenek bersedia membuka tabir misteri tentang kakek. Aku sama sekali tidak memaksanya. Ia tiba-tiba saja menyambangi kamar tidurku dan mengatakan jika sudah waktunya aku mengetahui riwayat tentang suaminya. Aku tercengang, mengingat kemarin malam nenek bersikap nganeh-anehi.
Malam kemarin, ketika aku larut dalam tulisan di layar laptop yang akan kukirimkan ke dewan redaksi, nenek menemuiku. Ia memintaku memasukkan benang pada jarum yang akan digunakannya untuk menjahit taplak meja. Baru saja akan mulai mengerjakan apa yang dimintanya, nenek mengambil salah satu buku yang terserak di meja kerjaku. Ia memicingkan mata, mengamati buku hasil investigasi salah satu media nasional tentang kesaksian para algojo tahun 1965 itu. Kuamati, seketika air mukanya berubah. Ia lemparkan buku itu dengan kasar, lalu buru-buru meninggalkanku tanpa sepatah kata.
Dan, tiba-tiba petang ini nenek sudah berubah seratus delapan puluh derajat.
“Aku ingin mengubur sedalam-dalamnya masa lalu. Tidak ingin cucu-cucuku tahu tentang kakek mereka. Tapi sepertinya Gusti Allah punya kehendak lain,” tukas nenek begitu ia duduk di sudut kasur tidurku.
“Maksud Nenek?”
“Bukumu kemarin, Ndhuk.”
Garis keningku bertaut, apa coba hubungan buku itu dengan kakek? Tapi, sepersekian detik kemudian aku terlonjak dengan asumsi yang kubuat sendiri, “Kakek seorang anggota partai komunis, Nek?!”
***
Awal Oktober 1965, suasana petang di Lirboyo selalu terasa tintrim. Ketika matahari beringsut pergi, rumah-rumah tertutup rapat, jendela pintu serta merta terkunci. Lampu-lampu teplok serentak dipadamkan. Sepekan terakhir, selepas terdengar selentingan kabar tentang serangan masa kader PKI ke Pesantren Lirboyo, perkampungan serasa mati setiap kali malam tiba.
Petang itu, setelah mengunci semua pintu, nenek membenamkan diri di kasur bersama ibu dan paman yang masih belia. Sementara, kakek yang masih berusia tiga puluhan, selepas isya hanya tepekur di ruang tengah. Lama ia tidak beranjak dari sana. Tengah malam, setelah berjam-jam duduk mematung di ruang tengah akhirnya kakek beringsut ke kamar tidur. Nenek yang masih terjaga mendapati kakek mendekat ke arah lemari pakaian, tangannya kemudian menggapai sesuatu dari atas sana. Usai tahu apa yang baru saja diambil oleh kakek, nenek gelisah. Ia membatin, mengapa suaminya tiba-tiba mengambil setelan serba hitam yang hampir belasan tahun telah ditanggalkan dari tubuh pemakainya. Setelan hitam serupa jelaga itu sesungguhnya pernah melegitimasi kakek sebagai pendekar silat yang gaungnya terdengar di seluruh penjuru Kediri. Akan tetapi, sudah lama kakek tidak mengenakan seragam hitam itu. Sebab, semenjak menikah dan memiliki bayi di rumahnya, kakek tak pernah lagi bertanding silat dengan siapa pun. Hanya sekali waktu berlatih di belakang rumah agar tangan dan kakinya tidak kaku.
Kakek membawa satu set pakaian itu ke ruang depan. Lama ia mengamati seragamnya, terlihat menimbang-nimbang, sebelum kemudian mengenakannya. Mungkin agak berlebihan, tetapi kata nenek ada sebuah sinar kebiruan yang memancar dari tubuh kakek kala mengenakan seragam itu lengkap dengan iket kepalanya.
“Ke mana, Pak?” agak ragu nenek bertanya.
“Malam ini dapat tugas dari Gus Maksum, Bu. Kunci rapat semua pintu. Aku mungkin kembali besok pagi.”
Nenek hanya mengangguk, ia tahu betul apa arti “tugas dari Gus Maksum”. Tanpa banyak bicara nenek membukakan pintu. Ia melepas kepergian kakek di depan rumah hingga punggung kakek menghilang di telan kegelapan. Derik jangkrik mengiring kepergian kakek di malam yang pekat itu. Ketika akan menutup pintu, mata nenek terantuk pada setandan pisang yang tergeletak di teras rumah. Siang tadi, kedua orangtua nenek datang berkunjung menengok cucunya. Mereka membawa serta setandan pisang kepok dan dan beberapa ikat ketela pohon sebagai buah tangan. Namun, kunjungan itu hanya berlangsung sebentar, baik nenek maupun kedua orang tuanya sama-sama tahu bahwa ketegangan antara PKI dan para santri di Lirboyo masih berlangsung. Maka, mereka tak mau ambil risiko. Nenek memejamkan mata, ia sadar betul bahwa Bapak dan Emaknya adalah segelintir petani yang tertarik masuk dalam partai yang belakangan gencar dibasmi. Akan tetapi, ia tidak bisa berbuat banyak. Hanya bisa mendoa untuk keselamatan kedua orang yang teramat dikasihinya.
Malam makin pekat ketika derum truk dan derap lars sepatu menghentak telinga warga desa yang masih terjaga. Nenek mengintip dari jendela depan, hatinya mencelus, dalam gelap ia samar-samar melihat rumah limasan di seberang rumahnya digedor paksa oleh sejumlah orang berseragam tentara. Tidak berapa lama kemudian, sang pemilik keluar disertai todongan moncong senapan dari orang asing berseragam itu. Nenek bergidik, ditutupnya kembali tirai yang sempat sedikit ia sibak.
Selepas azan subuh, pintu rumah diketuk beberapa kali. Nenek membuka pintu dengan teramat hati-hati, dilihatnya kakek berdiri di depan pintu dengan muka yang pucat pasi. Tercium bau anyir dari baju yang dikenakan kakek ketika itu. Kakek meminta nenek untuk berkemas, ia berkata bahwa mereka harus meninggalkan Lirboyo sebelum matahari terbit. Nenek bergegas untuk mengemasi barang bawaan, sedangkan kakek berganti pakaian.
***
Aku terhanyut mendengar cerita nenek. Sekarang baru aku mengerti bahwa sebenarnya kami bukan warga asli di perumahan yang kami tinggali saat ini. Wajar saja bila para tetangga tidak mengetahui riwayat keluarga kami. Namun, masih belum terjawab pertanyaanku mengapa nenek seolah tak mau mengingat kakek. Apakah setelah sampai di tempat pelarian mereka mengalami masalah keluarga lalu bercerai?
“Waktu itu, kakek, nenek, ibu dan paman pergi kemana?” aku bertanya untuk kesekian kali.
“Dini hari itu, kami berempat meninggalkan Lirboyo. Kami menuju terminal. Sepanjang perjalanan kami tak banyak berkata-kata.”
“Tapi kenapa nenek tidak ingin mengingat kakek? Bukankah kalian pergi bersama?”
Nenek menggeleng perlahan. “Tidak. Kami tidak pergi bersama. Setelah sampai terminal aku disuruhnya menaiki bus jurusan Surabaya untuk menemui seorang rekannya. Waktu itu nenek begitu takut dan panik, sehingga menurut perkataan kakek demi keselamatan kami semua. Tapi, sebelum pergi kakekmu kemudian berbisik kepadaku, ‘Aku telah membunuh ayah dan ibumu. Maafkan aku’. Semenjak itu, nenek tidak lagi mengenal kakekmu.”
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Menelisik Permainan Simbol dalam Lubang Dari Separuh Langit Karya Afrizal Malna
Selasa, 22 Agustus 2023 12:00 WIB
Riwayat Tentang Kakek
Selasa, 2 Mei 2023 07:39 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
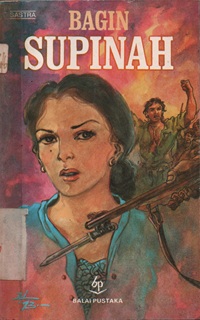






 99
99 0
0




 Berita Pilihan
Berita Pilihan










