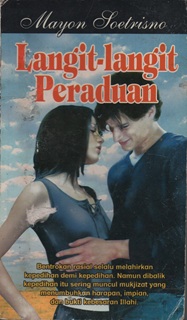Tilik the Series: Menilik Kenyataan dari Dekat Sekali
Sabtu, 3 Juni 2023 07:57 WIB
Artikel ini mengulas film Tilik the Series yang memuat kritik sosial, seperti budaya patriarki, lokalitas, perasaan personal seorang anak, dan beban ganda seorang perempuan. Padahal kenyataan seperti itu sangat dekat dengan manusia, namun kerap diabaikan begitu saja.
Mudah saja bagi manusia untuk menggali kuburnya sendiri. Cukup dengan mengartikan bahwa kesetaraan adalah jumlah yang sama. Kehidupan yang diidealkan berdasarkan kuantitas, bukan kualitas. Dengan begitu, Alexander Berkman merasa jengah dan menuliskan dalam bukunya yang berjudul “Cultural Theory” (1990) bahwa kesetaraan bukanlah jumlah yang sama, melainkan kesempatan yang sama.
Penggugatan atas kesetaraan sebagai kesempatan yang sama akan kita temukan dalam Tilik the Series besutan sutradara Wahyu Agung Prasetyo yang diproduksi oleh MD Entertainment dan Ravacana Films. Series ini mencoba menampakkan lokalitas secara telanjang. Tentu kita masih belum bisa move on dari film pendek Tilik (2018) dengan lakon utamanya Bu Tejo (Siti Fauziah), Yu Ning (Brilliana Desy Arfia), Bu Tri (Putri Manjo), dan ibu-ibu lainnya yang merepresentasikan ibu-ibu di desa serta lokalitasnya yang hangat dan natural.
Dalam series ini, lakon-lakon itu bermunculan lagi dengan tambahan Pak Tejo (Ibnu Widodo), Pak Hartono (Setheng Sadja), Kotrek (Jamaludin Latif), Nopek (Aryudha Fasha), dan pemeran-pemeran lain. Tak jauh beda dengan versi film pendek 2018, series ini juga sangat related dengan judulnya: Tilik.
Jika pada film pendek menceritakan serombongan ibu-ibu yang ingin menilik (membesuk, menjenguk) Bu Lurah yang sedang sakit. Maka pada series delapan episode ini mengajak penonton untuk menilik kehidupan sekumpulan masyarakat yang hanyut dalam gegap-gempita pemilihan lurah baru.
Menariknya, Tilik the Series ini tak hanya menampilkan intrik politik masing-masing calon lurah. Banyak hal-hal subtil—yang jika dibaca secara mendalam—menampilkan keadaan kultur masyarakat kita hari ini. Oleh karena itu, tilik di sini bukan sekadar membesuk atau menjenguk an sich, melainkan menilik, membesuk, atau menjenguk apa-apa yang dirasakan seseorang ketika politik dan kultur yang patriarki menjadi tuan atas hidup bersama.
Menilik Budaya Patriarki dari Akar Rumput
Selama ini pembahasan tentang patriarki selalu ramai dalam ruang-ruang diskusi di kafe-kafe, di ruang seminar, maupun di tumpukan buku-buku atau penelitian-penelitian. Singkatnya, wacana tentang budaya patriarki acapkali masih terendapkan begitu saja di menara gading. Teramat banyak informasi yang mengatakan apa, bagaimana, dan kapan budaya patriarki itu.
Namun dalam Tilik the Series, kita akan disuguhkan bahwa itulah budaya patriarki. Tanpa definisi yang ndakik-ndakik. Tanpa perdebatan yang bertungkus lumus. Dalam series tersebut kita akan memahami perlahan demi perlahan bahwa budaya patriarki yang bercokol di desa sangat berdampak pada banyak aspek.
Plot awal series ini menyajikan persaingan calon lurah antara Pak Tejo melawan Pak Hartono. Peran Bu Tejo, sebagai istri dari Pak Tejo pun sangat krusial. Awalnya ia menjadi tim sukses dari suaminya. Namun di pertengahan jalan cerita jadi lain sama sekali. Alih-alih persaingan antara Pak Tejo dan Pak Hartono, persaingan justru terjadi antara Bu Tejo yang menjadi calon lurah menggantikan suaminya karena saran dari Bu Lurah (lurah terdahulu) melawan Pak Hartono.
Pertanyaannya, apakah dengan bergantinya calon lurah dari pihak Pak Tejo dan Bu Tejo itu keadaan baik-baik saja? Tentu tidak. Saat itulah budaya patriarki menampakkan wajahnya yang bengis. Saat Pak Tejo merasa gagal menjadi calon lurah, lalu istrinya maju menggantikan suaminya, di situlah Pak Tejo (sebagai laki-laki) merasa harga dirinya babak belur.
Pak Tejo pergi begitu saja dari rumah, jarang pulang, dan enggan membicarakan masalahnya dengan keluarganya.
“Angger ono masalah ora malah dirampungke tapi malah mlayu. Sesok yen ono lomba lari dari masalah, Bapak juara siji!” (Setiap ada masalah bukannya diselesaikan, tapi malah lari. Nanti kalau ada lomba lari dari masalah, Bapak juara satu!)—Bu Tejo.
Dalam hal ini, Pak Tejo merasa malu karena jika istrinya yang menjadi calon lurah, bahkan jika sampai menang dan menjadi lurah, maka kedudukan sosialnya berada di bawah istrinya. Sudah tentu di kampung orang akan lebih menghormati Bu Tejo, sebagai lurah, daripada suaminya yang hanya sebagai pemborong.
Keadaan demikian yang membuat Pak Tejo tak pernah pulang dan lambat laun berpihak pada Pak Hartono. Keberpihakan Pak Tejo pada Pak Hartono bukanlah sesuatu yang tak beralasan. Pak Tejo menjadi loyalis Pak Hartono karena dengan cara itulah ia bisa menjegal Bu Tejo agar tak menjadi lurah dan ia kembali memiliki kuasa atas rumah tangganya.
Apa yang terjadi pada Pak Tejo dan Bu Tejo itu persis dengan apa yang disampaikan oleh Frederic Angels dalam bukunya “The Origin of the Family, Private Property and the State” (1884). Angels menyebut bahwa budaya patriarki sebagai sistem dominasi paling awal dan tercatat pada sejarah dunia mengenai kekalahan jenis kelamin perempuan.
Ya. Pak Tejo terus berupaya agar istrinya bisa berada di bawahnya, disubordinasi. Namun—seperti yang saya sampaikan di atas—bahwa Tilik the Series ini adalah upaya menggugat kesetaraan. Bu Tejo tetap maju dalam pencalonan dan mengupayakan kesempatan yang sama, bahwa sebagai perempuan ia bisa memimpin desanya dan menampik wajah bengis patriarki yang akan dilanggengkan oleh lawannya, Pak Hartono. Namun perjalanan untuk mencapai hal tersebut tak mudah, berdarah-darah sejak dalam pikiran.
Beban Ganda Perempuan dan Anak yang Merana
Akibat sikap Pak Tejo yang merasa harga dirinya sudah diludahi oleh istrinya sendiri hingga ia jarang pulang ke rumah, dampak yang terpotret jelas sekaligus menggetirkan terjadi pada Arka, anak dari Pak Tejo dan Bu Tejo. Padahal secara telanjang tak ada yang salah jika Bu Tejo mencalonkan diri menjadi lurah. Kultur patriarki-lah yang membuat seolah-olah laki-laki terlihat tak pantas jika posisi sosialnya di bawah perempuan.
Dalam series itu, Arka menjadi anak yang pada mulanya kesepian, karena ibunya sibuk mengurus kampanye pencalonan lurah dan ayahnya tak kunjung pulang ke rumah setelah gagal mencalonkan diri menjadi lurah. Arka pun bersentuhan dengan gawai, lupa waktu, dan menanam api kemarahan dalam dirinya sendiri.
Tak salah jika Indonesia masuk kategori fatherless country, yaitu negara yang ditandai dengan keadaan masyarakatnya yang kekurangan atau bahkan ketidakterlibatan peran ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari seorang anak di rumah.
Keterlibatan seorang ayah rupanya dipotret secara jelas dalam konflik batin Arka dan Bu Tejo. Arka menjadi anak yang gemar membantah orang tuanya dan kerap mencari pelarian di luar rumah, seperti main kartu remi dengan bapak-bapak di pos ronda, main game tanpa mengindahkan sekitar, atau pergi bermain hingga lupa waktu. Padahal sebelumnya Arka merupakan anak yang tak segegabah itu dan bisa dibilang cerdas.
Perubahan yang terjadi pada Arka merupakan dampak nyata dari fatherless yang antara lain: rendahnya penghargaan atas diri sendiri, merasa minder dan tak percaya diri, merasa cemas, berpotensi melakukan kejahatan, dan lain sebagainya.
Bahkan Arka secara gamblang mengatakan bahwa ia malu dengan teman-temannya saat ibunya mencalonkan diri menjadi lurah dan ayahnya yang entah ke mana. Realita tersebut yang kerap terjadi di akar rumput namun jarang disadari. Perlu diketahui, bahwa fatherless ini juga anak kandung dari budaya patriarki yang meyakini bahwa laki-laki bertanggung jawab dalam urusan finansial, sedangkan perempuan hanya mengurusi domestik dan mengurus anak
Persoalan ini juga menjadi beban ganda seorang perempuan. Bu Tejo yang harus melakukan kampanye dan mempersiapkan pemilihan lurah, disibukkan pula untuk merawat anak-anaknya tanpa kehadiran seorang suami. Dalam series itu nampak bahwa Bu Tejo kerap menangis dan merasa kelelahan ketika menghadapi Arka yang demikian.
Bahkan dalam episode terakhir, Bu Tejo mengatakan pada Pak Tejo bahwa di rumah setiap hari selalu ramai, namun sebagai keluarga ia tetap sendirian dalam mengurus anak dan rumah tangga. Bagaimanapun juga anak-anak selalu membutuhkan peran ayah dalam rumah tangga.
Meskipun akhir cerita dari series ini happy ending, tapi tidak menafikan bahwa perebutan kuasa, budaya patriarki, beban ganda perempuan, serta dampak psikologis yang terjadi pada anak adalah hal yang perlu direnungkan ulang.
Series itu menurut saya berhasil memotret banyak hal selain budaya patriarki, di antaranya dinamika masyarakat, politik uang, budaya jilat-menjilat, feodalisme, hipokrit, dan apapun itu—yang dalam orde baru terkenal—dengan istilah ABS (Asal Bapak Senang).
Sebagai pungkasan, saya ingin mengajukan pertanyaan: butuh berapa generasi lagi yang harus berdarah-darah sejak dalam pikiran karena dihisap habis oleh budaya toxic yang bengis itu? Mari buka mata, kebengisan patriarki sangat dekat. Sangat erat. Sangat rapat dengan kita.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Tilik the Series: Menilik Kenyataan dari Dekat Sekali
Sabtu, 3 Juni 2023 07:57 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 98
98 0
0