Aktif dalam menulis cerita fiksi dan opini.
Neraka di Desa Nirawangi—Part 5: Perpisahan.
Sabtu, 5 April 2025 16:54 WIB
Rio bilang ada jalan keluar dari Desa Nirawangi. Tapi jalan apa? Dan bisakah Jaya membawa kedua orang tuanya keluar?
Kami terus menghitung—hitung—hitung—hitung—hitung hari; sampai kami tidak tahu sudah berapa lama terkurung dalam neraka ini. Tiga puluh lima hari? Tiga puluh tujuh? Tiga puluh sembilan? Empat puluh hari? Sial! Kami bahkan sudah lupa!
Persediaan makanan hampir habis—tersisa beberapa keping biskuit; berapa bungkus batang cokelat sisa yang mencair; setoples kerupuk udang; serta beberapa botol air mineral. Makanan-makanan segar—seperti daging dan sayur—sudah habis; walau sebagian besarnya membusuk. Menurunnya persediaan makan, juga diikuti dengan kesehatan jasmani maupun rohani.
Walau kami selamat dari serangan para entitas pemakan daging di luar sana, tapi kemerosotan mental maupun raga mulai merambat bagai sel kanker yang mematikan. Pelan-pelan pikiran kami mulai kacau dan semakin kelam; berpikir bahwa pertolongan tidak akan pernah datang; mujizat ataupun harapan itu tidak nyata; tidak ada yang peduli dengan nasib kami di Desa Nirawangi!
Kini Ibu terbaring lemah di atas sofa. Wajahnya memucat, bibirnya kering dan pecah-pecah. Nafasnya pendek dan berat. Tubuhnya tak lagi sanggup bergerak banyak. Sedangkan Ayah hanya duduk diam di pojok ruangan, menundukkan kepala yang dihiasi raut wajah melankolis; sementara aku hanya bisa menggenggam tangan Ibu yang terasa semakin dingin. Perutku mulai perih karena lapar, tapi Ibu lebih mengkhawatirkan—sebab dia harus makan sesuatu!
Tiba-tiba Ayah berdiri perlahan, membenahi kemeja lusuhnya, lalu meraih jaket yang tergantung di kursi. Melihat gelagat Ayah yang mencurigakan, aku langsung beranjak dan menghampirinya.
"Ayah mau ke mana?" tanyaku.
Ayah menatapku dengan sorot mata yang tenang, tapi di baliknya aku bisa melihat keputusasaan.
"Kita butuh makanan." jawabnya singkat.
"Jangan keluar, Yah! Itu sama saja bunuh diri!" teriakku sambil berusaha menghalangi.
Ayah hanya menghela napas dan berkata;
"Aku ini ayahmu, Nak. Aku bertanggung jawab atas kalian. Seharusnya aku mendengarkanmu dan pergi dari sini lebih awal; tanpa harus mempedulikan sentimental rumah maupun tokoh warisan leluhur kita. Tetapi sekarang, kita berada di kondisi amat kritis! Kita tidak punya pilihan. Ibumu butuh makan!"
"Ibu lebih butuh kita bertahan hidup! Kalau Ayah keluar, Ayah tidak akan kembali!" suaraku meninggi, tanganku mencengkeram lengannya dengan erat.
Ayah tersenyum kecil, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lain—keputusannya sudah bulat.
"Aku harus mencoba!" katanya lirih, "Aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu keajaiban."
Aku terus memohon, menahan, dan memaksanya tetap tinggal. Tetapi Ayah terus melangkah ke pintu belakang rumah, membuka kayu-kayu yang menyegelnya, dan mengintip lingkungan sekitar—memastikan keadaan aman. Lalu dia menoleh ke belakang, menatapku dan Ibu yang masih terbaring lemah.
"Aku akan kembali." katanya, "Jika terjadi apa-apa denganku, tolong jaga Ibu baik-baik dan bawa dia ke lantai atas!"
Itulah kata-kata terakhir Ayah yang dia tinggalkan; sebelum dia memutar kunci secara perlahan, lalu melompat keluar dan menghilang ke dalam kegelapan di luar. Di waktu yang bersamaan, suara-suara makhluk itu mulai terdengar secara serentak dan mengejar Ayah. Aku segera menutup pintu, memasang kembali kayu-kayu penyegel, lalu terpaku di depan pintu dengan dada sesak—firasat buruk telah mencengkeram erat batinku.
****
Jam demi jam berlalu. Jam berganti hari. Satu—dua—tiga—empat hari telah berlalu, dan akan terus berlalu—tapi Ayah tidak kunjung pulang. Aku tidak pernah melihat tanda-tanda kehadirannya selama mengintip dan mengawasi keadaan luar rumah dari balik jendela.
Sedangkan kondisi ibu kian kritis. Tubuhnya semakin kurus dan pucat, bahkan tulang-tulang sendinya mulai menyembul dari balik kulitnya. Matanya tampak tidak fokus, meski masih ada sedikit kesadaran untuk berkomunikasi denganku. Hal yang bisa kulakukan saat ini hanyalah memprioritaskan Ibu dengan memberinya lebih banyak makanan yang tersisa di rumah—meski dia berusaha menolak.
Dalam kesempatan yang ada, aku menghubungi teman dekatku, Satrio Kuncara, untuk bertukar informasi sekaligus menjaga kestabilan mental. Kami sudah berhari-hari tidak berkomunikasi, karena upaya penghematan daya WiFi portabel yang kian kritis. Di momen inilah, air mataku sempat mengalir keluar akibat rasa rindu bersosialisasi dengan teman dekat sekaligus satu-satunya hiburan dalam kegilaan ini.
Rio tampak senang karena aku masih hidup, dan berusaha menghiburku semampunya. Dia menghiburku dengan memberi tahu bahwa dia telah berhasil menghubungi salah satu pekerja konstruksi jalan tol di Desa Nirawangi. Menurutnya, pekerja itu memiliki peta konstruksi—terdapat denah saluran air yang tersembunyi. Dulunya itu adalah sungai utama desa yang mengalir menuju Kota Mandalawening; namun terkubur di bawah fondasi beton dan baja selama pembangunan jalan tol, sehingga kini tampak seperti gorong besar yang gelap dan menakutkan. Saluran air itu mengarah ke pintu air besar yang terletak di ujungnya, dan aku harus membukanya. Namun, ada konsekuensi dari tindakan tersebut.
Pintu air itu menahan aliran sungai yang selama ini terhambat oleh pembangunan jalan tol. Jika dibuka, air yang tertahan dengan jumlah yang besar akan langsung mengalir deras—menciptakan arus liar yang bisa menyapu siapa aja di dalamnya. Bisa saja aku berhasil selamat jika mengantisipasi dan memiliki perhitungan yang matang; tapi jika tidak beruntung, maka aku akan tenggelam ke dalam arus. Namun secara perhitungan ilmiah, hanya kecil peluangnya untuk selamat—kecuali ada bantuan langsung dari tangan Tuhan.
Meski berbahaya, itu satu-satunya jalan keluar dari Desa Nirawangi. Tidak ada jalan keluar lain! Semua akses keluar desa telah ditutup dan dijaga ketat oleh aparat bersenjata, tapi saluran air ini luput dari perhatian mereka—karena mereka berpikir tidak ada yang tahu atau berani memakai saluran air ini sebagai rute pelarian. Kemudian Rio mengatakan bahwa dia selalu mendoakan yang terbaik untuk aku dan kedua orang tuaku, lalu percakapan usai dengan habisnya daya WiFi portable.
Aku menghela napas panjang, menatap Ibu yang semakin lemah. Batinku penuh kebimbangan. Di satu sisi aku memiliki satu-satunya peluang untuk membawa Ibu pergi dari desa, tapi peluang itu juga sangat berisiko. Di sisi lainnya, aku masih mengharapkan kepulangan Ayah, agar kami bisa pergi bersama-sama.
Tiba-tiba, terdengar suara ketukan—ketuk—ketuk—ketuk—ketuk di pintu belakang rumah. Ketukan itu pelan dan teratur—tampak tenang dan dingin. Aku tersentak, dan buru-buru meraih Ibu yang duduk lemas di sofa pojok ruangan. Seketika telingaku menangkap sebuah suara yang tidak asing.
"Jaya... ini Ayah... bukain pintunya."
Itu suara Ayah! Awalnya aku ragu dan tidak yakin; tapi suaranya terdengar sangat mirip dengan Ayah! Sontak, api keceriaan mulai memercik di batinku, dan aku segera beranjak ke pintu itu.
"Ayah? Ayah akhirnya pulang!" teriakku penuh kegirangan.
Tiba-tiba tangan Ibu langsung meraih tanganku dan menahannya. Dia menatapku dengan tatapan cemas, seolah menyadari sesuatu hal ganjil yang belum kusadari.
"Jaya... ayok... bukain pintunya... Nak."
Di saat itulah, ketika jeda di antara kalimatnya, seolah Ayah tampak berusaha memilih kata-kata yang tepat. Nada bicaranya juga sedikit... datar. Anomali tersebut membuat jantungku berdegup lebih kencang, dan tubuhku membeku sambil menatap ke arah pintu belakang rumah.
Suara ketuk—ketuk—ketuk—ketuk—ketukan di pintu kembali terdengar dan lebih keras. Bahkan aku juga mendengar suara cakar—cakar—cakar—cakar—cakaran yang samar.
"Jaya... buka pintunya..."
Kali ini, suara Ayah terdengar lebih berat; lebih dalam, seperti gema dari rongga kosong. Aku perlahan mundur dan memeluk Ibu dengan ketakutan. Telingaku menangkap sesuatu yang tidak biasa—intonasinya yang datar berubah jadi serak, seolah suara itu keluar dari tenggorokan yang tidak lagi manusiawi.
"Jaya... ini Ayah..."
Sekarang, ada sesuatu yang lain—sesuatu yang mengerikan—di balik suara itu. Seperti desisan samar di antara kata-katanya yang tidak utuh—suara dari sesuatu yang basah dan berlendir. Tidak! Itu bukan suara Ayah! Itu… Itu adalah sesuatu yang mengerikan… bengis… dan mampu meniru suara Ayah! Sesuatu yang berusaha memancing; menjebak; mempermainkanku!
Lalu, suasana senyap seketika. Tetapi aku merasa tidak mampu bernafas, dan jantungku terasa berdegup kencang. Tanganku terus memegang erat kedua tangan Ibu dengan penuh gelisah. Mata—mataku terus menatap pintu—dengan penuh waskita— tubuhku menggeligis.
Tiba-tiba, suara ketuk—ketuk—ketuk—ketuk—ketukan kembali terdengar, tapi hampir di semua sisi rumah. Jumlahnya banyak—sangat banyak! Tidak hanya berasal dari pintu utama rumah… ada dari jendela… dinding-dinding luar ruangan. Di luar jendela, secara samar-samar, tampak serangkaian bayangan hitam berdiri—tubuh mereka kurus dan membungkuk; jari-jari panjang dengan kuku tajam mengetuk kaca jendela dengan irama yang tidak beraturan. Mata mereka... hitam pekat, dalam, dan kosong seperti lubang tanpa dasar. Mereka menyeringai—menyeringai lebar secara tak wajar seperti bulan sabit—menyeringai sambil mempertontonkan gigi-gigi panjang dan runcing yang tidak manusiawi.
Akan tetapi, ada satu makhluk di antara mereka yang membuat dadaku terhentak keras. Sosok itu adalah… Ayah!
Iya! Wajahnya sangat mirip dengan Ayah! Tetapi dia lebih cekung, kulitnya pucat kebiruan seperti mayat yang membusuk. Tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali kulihat, jari-jarinya lebih panjang, dan kuku-kukunya tajam seperti cakar. Matanya... itu bukan mata Ayah! Itu mata hitam menyeramkan yang memantulkan kehampaan.
Dia terus mengetuk—ketuk—ketuk—ketuk—ketuk—ketuk jendela dengan gerakan yang lambat namun pasti. Kepalanya sedikit dimiringkan, seolah mengamati setiap gerakan kami di dalam rumah. Mulutnya menyeringai lebar—terlalu lebar daripada biasanya.
"Jaya..." suaranya serak dan dalam, hampir seperti gumaman yang berasal dari tenggorokan yang tidak lagi normal, "Buka... pintunya... biarkan kami masuk..."
Tubuhku gemetar. Ibu mulai terisak pelan.
Cobalah—coba—coba—coba—coba lakukan sesuatu! Ya Tuhan, jauhkan kami dari kegilaan ini! Apa—apa—apa—apa—apa yang harus kulakukan?
Ah iya! Aku—aku ingat pesan—pesan dari Ayah! Pesan terakhirnya—sebelum dia pergi—meninggalkan kami!
Aku lantas melawan rasa takut; membopong Ibu dan bergegas membawanya ke kamarku di lantai dua. Di waktu yang bersamaan, ketukan—ketukan—ketukan—ketukan para makhluk di luar semakin keras dan liar. Secara perlahan, ketukan itu mulai berubah menjadi dobrak yang gila.
Lalu, suara Ayah kembali terdengar. Tetapi kali ini terdengar lebih mendesak dan semakin terdistorsi.
"Jaya... kami lapar..."
Kemudian, suara kaca pecah mulai terdengar secara serentak, dibarengi dengan suara kayu yang dipatahkan secara beringas.
Aku segera mempercepat langkahku—tanpa memedulikan rasa takut dan fisik yang melemah. Sesampainya di dalam kamar, aku baringkan Ibu di atas kasur. Lalu kukunci pintu dan menutupnya dengan apa saja yang ada; meja belajar dan lemari baju—berharap itu bisa menahan mereka, setidaknya untuk beberapa saat.
Arkian, aku segera menatap jendela kamar—menilai bahwa ini satu-satunya jalan keluar. Selama para makhluk itu sibuk mencari kami di lantai bawah, kesempatan ini tidak boleh kusia-siakan. Jika aku bisa keluar dan membawa Ibu keluar ke pintu air, kami masih punya harapan!
"Ibu, kita harus pergi sekarang!" ujarku sambil menggenggam erat tangannya, "Jendela ini menghadap ke atap rumah belakang. Kita bisa lompat ke sana dan menyelinap keluar. Aku tahu jalan keluar alternatif dari desa ini!"
Ibu menatapku dengan mata yang lelah. Bibirnya bergetar—tapi bukan karena takut—dia berusaha mengucapkan kata demi kata.
"Jaya... kamu yang harus pergi, Nak."
Aku terkejut mendengarnya. Lantas aku menggeleng cepat.
"Tidak! Aku tidak akan meninggalkan Ibu di sini!"
Ibu tersenyum, tangannya meraih pipiku dan mengelusnya dengan lembut—seperti dirinya mengelus pipiku sewaktu aku masih kecil.
"Aku sudah terlalu lemah. Aku hanya akan memperlambatmu." ujar Ibu dengan suara yang tenang—sangat kontras dengan suara-suara di luar kamar yang semakin liar dan beringas, "Aku bisa menahan mereka cukup lama. Pergilah, Nak. Kamu harus keluar dari sini."
Dada dan tenggorokanku terasa sesak. Batinku mengalami konflik. Aku tahu Ibu berusaha mengorbankan diri. Tetapi aku... aku tidak bisa... aku tidak bisa meninggalkannya seperti ini!
Tiba-tiba pintu kamar bergetar keras. Kayu-kayu berderak, suara geraman mengerikan dan bising menggema dari baliknya. Lantas Ibu menggenggam bahuku dengan erat dan menatapku dalam-dalam, "Jaya, ini bukan pilihan! Ini keharusan! Ibu tidak ingin melihatmu dimakan oleh mereka! Jika kamu tidak bisa melakukan untuk dirimu, lakukanlah untuk Ibu!"
Seketika air mataku mengalir keluar, tapi aku tahu—waktu semakin tipis—tidak ada ruang untuk berdebat. Aku menggigit bibir, menahan isak yang hampir pecah. Tanganku mencengkeram bingkai jendela dengan erat, tubuhku gemetar saat melangkahkan satu kaki ke luar.
"Ibu... aku..." ucapku, tapi suaraku tertahan.
Ibu membalas dengan senyum lembut, "Jangan lihat ke belakang, Nak!"
Aku mengangguk, lalu dengan satu gerakan cepat, aku melompat keluar jendela dan mendarat di atap rumah belakang. Kakiku sedikit goyah, tapi aku berhasil menyeimbangkan diri. Di waktu yang bersamaan, di belakangku, terdengar suara pintu kamar yang berhasil didobrak paksa dan hancur berkeping-keping.
Aku menahan napas, mencengkeram tepian genting saat suara-suara dari makhluk terkutuk itu mulai memenuhi ruangan tempat Ibu berada. Ada suara benda jatuh, kayu patah, dan langkah kaki yang menyerbu.
Tetapi Ibu... ia sama sekali tidak berteriak. Aku tidak mendengar suaranya, selain helaan napas panjang yang terdengar begitu berani dan tenang; sampai tenggelam oleh raungan liar, suara daging dirobek, dan bunyi kunyahan brutal.
Aku hanya bisa mendengarnya dari luar jendela sambil mengepalkan tangan, menggigit bibirku hingga berdarah. Aku ingin menoleh! Aku ingin berbalik! Tetapi aku tahu, Ibu tidak menginginkannya!
Jadi, aku berlari.
Selamat tinggal Ibu... Ayah...
****
Penulis Indonesiana
0 Pengikut
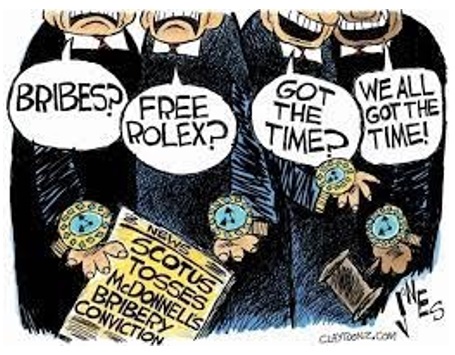
Tidak Hanya Pemerintah, Rakyat Juga Perlu Diperbaiki
Minggu, 7 September 2025 09:42 WIB
Perlawanan Rakyat dalam Brave Pink Hero Green Resistance Blue
Jumat, 5 September 2025 14:41 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 98
98 0
0


















