Penulis lepas, seringnya berpuisi tapi juga suka bercerita. Memiliki koleksi delapan buku ber-ISBN, salah-satunya mendapatkan penghargaan dari Kemendikbudristekdikti. Sekarang masih menulis dan akan selalu begitu.
Jakarta Sehabis Hujan: Genangan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial
Kamis, 19 Juni 2025 21:22 WIB
Aku menyebut Jakarta kebanjiran, bukan karena air. Tapi karena banjir ekspektasi, ambisi serta ego yang melimpah tinggi.
***
Malam itu, selepas hujan mengguyur Jakarta dengan deras yang nyaris seperti kemurkaan, aku menyalakan motor tuaku dan memutuskan untuk tidak melalui jalan-jalan utama yang penuh oleh klakson, ego, dan asap. Aku memilih jalur sempit, membelah pasar-pasar yang mulai redup, melewati jalanan becek yang menyimpan sisa-sisa transaksi hari itu: plastik robek, ikan membusuk, sayur layu, dan manusia-manusia yang tak punya tempat lain untuk pulang.
Di sinilah aku melihat kenyataan yang telanjang. Di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit yang mencuat seperti lambang supremasi, justru hidup yang paling hina mengendap. Jakarta berdiri megah seperti raksasa yang tuli—memamerkan cahayanya, menjual citranya, tetapi gagal melihat luka-luka di kakinya sendiri.
Di bawah jalan layang, keluarga-keluarga kecil berselimutkan terpal robek, tidur dalam deru knalpot dan kelembaban aspal yang belum kering. Di antara tiang-tiang penyangga gedung elit yang katanya milik negara atau perusahaan besar, anak-anak berguling di atas genangan lumpur, menyebutnya permainan karena tak tahu definisi kenyamanan. Tubuh mereka kurus, penuh gigitan nyamuk dan masa depan yang tak pernah ditulis dalam rencana pembangunan.
Mereka hidup dari sisa. Sisa makanan. Sisa tempat. Sisa perhatian. Sisa harapan. Dan lebih dari itu—mereka hidup di sisi lain dari narasi kemajuan. Mereka adalah cacat yang tak disebut dalam presentasi pemerintah. Mereka adalah statistik yang disisipkan di catatan kaki laporan ekonomi. Mereka tak punya suara, hanya tubuh yang menjadi bukti bahwa Jakarta bukan hanya tentang mall, MRT, atau gelar kota global.
Di sinilah letak paradoks yang nyata. Satu sisi kota menjual mimpi dengan harga apartemen, sedangkan sisi lainnya menukar mimpi dengan sekadar bertahan. Ini bukan sekadar ketimpangan. Ini adalah bentuk perbudakan modern—di mana satu kelas hidup dengan menjunjung gengsi, dan kelas lainnya bertahan dengan menjinjing penderitaan. Kemiskinan bukan lagi sebuah masalah yang hendak dipecahkan, melainkan aib yang ingin disembunyikan di balik pagar seng dan baliho “selamat datang di kota metropolitan.”
Jakarta tidak benar-benar hidup. Ia hanya berdetak karena orang-orang miskin masih bekerja di bawahnya, menyapu, mengangkat, melayani, dan kemudian dibuang kembali ke kolong. Mereka bukan warga, mereka adalah pelengkap narasi indah yang disusun oleh elite yang tak pernah menginjak jalan becek selepas hujan.
Dan aku, hanya bisa mengamati dalam diam. Tak ada yang bisa kulakukan malam itu, selain menatap anak kecil yang memeluk kardusnya erat, mungkin berharap bahwa dunia bisa selembut ibu yang tak pernah ia kenal.
Rama Kurnia Santosa
3 Pengikut

Panggung Kebodohan Penuh Kepalsuan
5 hari lalu
Sejarah Hanya Berganti Wajah
Jumat, 5 September 2025 09:40 WIBArtikel Terpopuler

 0
0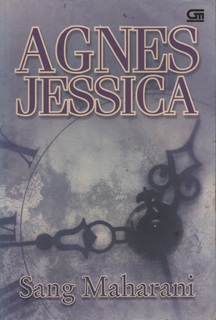
 Berita Pilihan
Berita Pilihan








 96
96 0
0



















