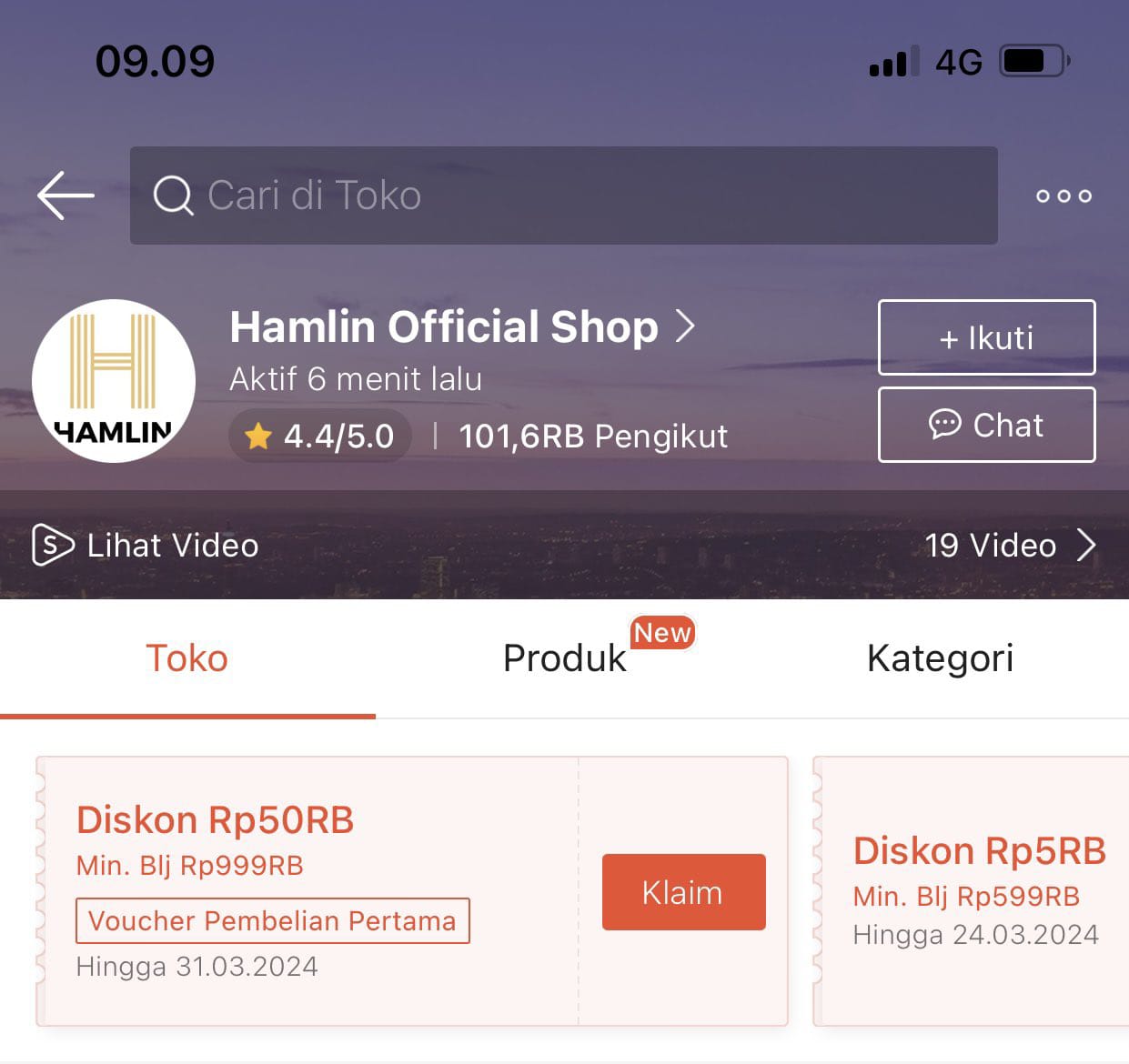Presiden Central Connecticut State University di Amerika Serikat, John W. Miller, merilis studi perihal peringkat budaya baca di 61 negara di dunia. Studinya menunjukkan temuan menarik terkait negara yang mendapuk peringkat pertama hingga negara terbuncit dalam tingkat rata-rata budaya baca warganya. Peringkat pertama ternyata diduduki Finlandia lalu hingga urutan kelima diikuti empat negara Skandinavia lainnya (Norwegia, Islandia, Denmark, dan Swedia). Lalu siapa yang terbuncit? Untuk tiga peringkat terakhir ternyata diduduki Thailand (59), Indonesia (60), dan Botswana (61).
Terkait studinya itu, Miller menjelaskan bahwa indikator kesejahteraan ekonomi sebuah bangsa, tak bisa dilepaskan dari tingkat pengetahuanwarganya yang berelasi dengan kualitas budaya melek baca. Setidaknya studi ini bisa menjadi cermin bagi Indonesia yang menduduki peringkat kedua terakhir. Sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia, jelas ini permasalahan yang tak bisa dibiarkan apalagi dianggap sepele.
Membaca dan Spirit Kemanusiaan
Ketika membaca studi Miller itu,spontan saya teringat dengan tulisan Sindhunata “Belajar Bersama Kuncung dan Bawuk”(Basis, No. 01 – 02, 2008). Dengan menggunakan pendekatan pedagogi pembebasan à la Paulo Freire, Sindhunata menekankan bahwa dalam fase literasi yang paling penting bukanlahsekadar membebaskan buta aksara; tapi lebih pada bagaimana manusia dapat mengenal realitas kehidupan dari kata-kata yang dibentuk melalui aksara. Tahapan awal yang dikehendaki Freire adalah pemanfaatan media visual/gambar sebagai sarana membayangkan berbagai realitasagar dapat mudah ditangkap, dicerna, dan dimaknai oleh anak-anak ketika mereka belajar membaca.
Jika menyimak saksama metode freirean itu, saya menjadi tersadar dengan buku-buku pelajaran membaca terbitan J.B. Wolters pada masa awal kemerdekaan Indonesia yang dibahas Sindhunata. Buku-buku terbitan penerbit itu sungguh terasa dapat menggugah anak-anak Indonesia saat itu untuk bukan sekedar mengenal aksara, tapi juga mengasah imajinasinya agar dapat menangkap realitas di sekelilingnya lalu secara bertahap dirangkai melalui aksara. Aksara memang jalan menuju cakrawala pengetahuan. Tapi, tanpa disertai imajinasi yang terasah, maka aktivitas membaca akhirnya hanyalah sebatas membaca teks; adapun pesan dan makna di baliknya tidak: ditangkap, dicerna apalagi dimaknai.
Sejak usia dini, substansi dari aktivitas membaca idealnya menumbuhkan kesadaran seorang anak terhadap nilai-nilai dasariah kehidupan. Misalnya, berkesadaran melestarikan alam, menyayangi makhluk ciptaan Tuhan, menghormati orangtua, toleran menyikapi perbedaan, cinta tanah air dan bangsa, serta jujur dan disiplin dalam berbagai aspek kehidupan.
Pada masa awal abad ke-20 hingga awal kemerdekaan, buku-buku pelajaran membaca dirancang sebagai bahan belajar bagi anak-anak menyerap nilai-nilai dasariah itu. Hal itu bisa disimak dari buku-buku seperti Batjoet Sapeuë: Kitab Beuët keu Aneu’ Miët(sejumput dari segala hal: bacaan anak, 1911) karya Mohamad Djam, Soetan Pamènan, dan Nja’ Tjoet untuk siswa-siswa di Aceh;Rusdi jeung Misnem (Rusdi dan Misnem, 1913)karya A.C. Deenik dan Rd. Djajadiredja untuk siswa-siswa berbahasa ibu Sunda; dan Siti koro Slamet (Siti dan Slamet, 1948) karya M. Samoed Sastrowardojo untuk siswa-siswa berbahasa ibu Jawa.
Misi yang dituju oleh para penulis buku itu kiranya cukup sama, yaitu ingin membentuk mental anak-anak menjadi pribadi beradab dan berperikemanusiaan di lingkungan keluarga, sosial, dan alam.Inilah pelajaran paling hakiki –lebih dari sekadar belajar mengenal aksara–sebagai bekal mental bagi anak-anak untuk meniti kehidupannya di masa depan.Mari coba untuk menyadari kembali, bagaimana generasi paruh pertama abad ke-20 sepertiSukarno, Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka bisa membayangkan sebuah bangsa yang merdeka dari penjajahan. Ternyata, hal itu bisa terwujud berkat habitus membaca mereka yang kemudian membentuk ide-ide genial dalam mewujudkan kemerdekaan hidup bagi rakyat Indonesia.
Dimulai dari Keluarga
Habitus membaca memang harus terus hidup, tapi juga bisa mati jika tak dijaga spiritnya. Memang, sekolah menjadi ruang untuk mengenalkan dan mengembangkan budaya literasi. Tapi juga harus disadari, sekolah hanyalah perpanjangan dari pendidikan dalam keluarga. Keluargalah yang sebenarnya merupakan ruang penting untuk menjaga kebiasaan membaca terus hidup sejak masa kanak hingga tua. Menjadi bermasalah jika baik orangtua maupun guru tidak gemar membaca buku dan tidak mengetahui manfaat dari budaya membaca. Hasilnya bisa dipastikan, mental mereka yang demikian itu akan mewaris ke anak-anak.
Jika saat ini dunia perbukuan –seperti halnya nasib media massa cetak– mengalami kelesuan, penyebabnya bukan semata karena kian beralihnya manusia ke gawai-gawai canggih. Namun, ini lebih disebabkan kian lemahnya habitus membaca di kalangan keluarga Indonesia. Jangan heran jika anak-anak sulit dibendung untuk terbiasa memilih “belajar”menggunakan gawai ketimbang buku.Sekali lagi letak kesalahan bukanlah pada gawainya, melainkan pada bagaimana individu memanfaatkannya secara bijak dan cerdas tanpa harus kehilangan status kemanusiaannya karena takluk oleh teknologi bikinan manusia. Ketika takluk, maka proses belajar menjadi ingin serba mudah, instan, dan kian berjarak jauh dari lingkungan alam, sosial, dan budaya. Artinya, kekhawatiran yang mesti dikhawatirkan saat ini adalah makin lemahnya kepekaan, nalar, dan refleksi manusia dalam menghadapi dan menyikapi berbagai persoalan, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga bangsa dan negara.
Tampaknya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perlu mensosialisasikan pentingnya budaya membaca bukan hanya dimulai dari lingkungan sekolah, tapi dari ruang lingkup keluarga. Keluargalah yang paling diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga habitus membaca di kalangan anak-anak. Peran penting keluarga dalam menumbuhkan budaya literasi ini misalnya dipikirkan begitu serius dalam program “Families and Literacy... Where Learning Grows” yang digarap lembaga The Connecticut Family Literacy Initiative & the Study Circles Resources Center (2001). Program ini mencoba mendorong terbentuknya “lingkungan rumah yang melek baca” (literate home environment)dan “keluarga adalah pusat pembelajaran” (family is the center of learning).
Tampaknya, program seperti itulah yang saat ini absen di lingkungan keluarga Indonesia. Dengan menciptakan lingkungan rumah yang melek bacadan menekankan keluarga sebagai pusat pembelajaran, tentu ini menjadi langkah sangat penting untuk menanam dan menumbuhkan (kembali) nilai-nilai kemanusiaan pada diri setiap anak Indonesia.
Ikuti tulisan menarik Fadly Rahman lainnya di sini.