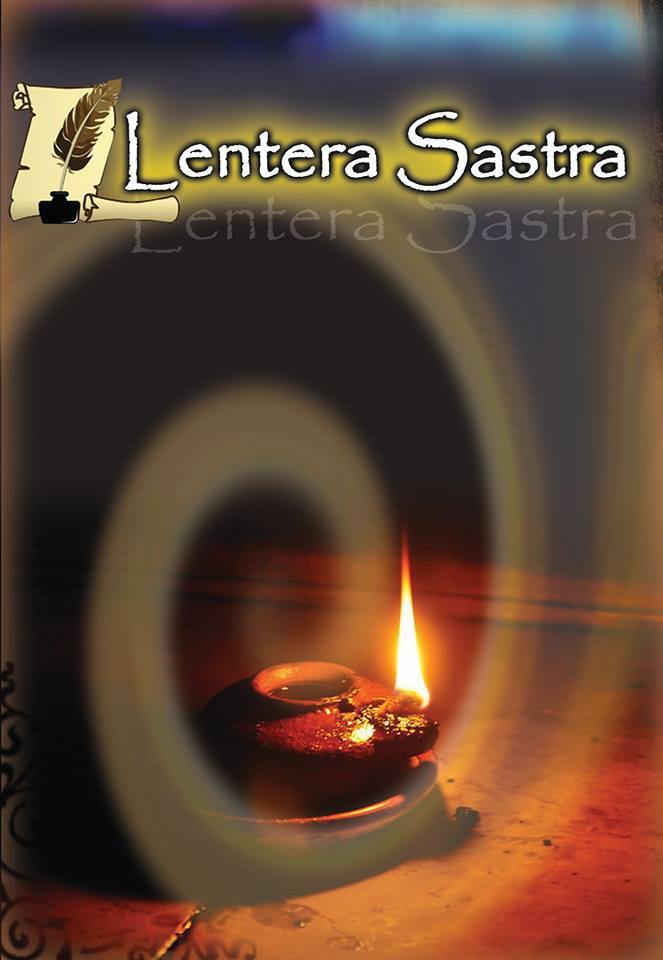Supendi atau yang lebih dikenal di kalangan dengan nama Spenk Afenk merupakan penyair Banten yang memiliki ciri khas yang cukup kuat, setidaknya itu tercermin dari puisi-puisi pendeknya dalam Menuju Kota Pagi. Ia mampu mengatur komposisi judul dan isi dengan baik. Ia tidak terjebak dalam pengulangan judul di dalam tubuh puisi. Adapun beberapa pengulangan pada tubuh puisi, misalnya pada puisi “Aku”, cukup berhasil karena mampu memperluas dan mempertajam kebermaknaan. Selain itu Spenk cukup bijak dengan menghadirkan puisi yang prismatic: tidak gelap segelap gelapnya tidak juga terang benderang. Sehingga pembaca dapat leluasa membangun imajinasi dalam proses penghayatannya. Puisi-puisi prismatic memang memungkinkan beberapa kalangan pembaca, yang jarang atau awam sastra, kesulitan menembus ruang-ruang maknanya, lantaran menghadapi simbol-simbol, baik simbol personal maupun universal, yang ketat. Tetapi kesulitan itu dapat ditangani jika pembaca bersedia melakukan pendalaman yang lebih. Misalkan ketika membaca puisi ini.
TAUBAT
malamku
menyusu di ketiak ibu
2016
Kebanyakan puisi pertaubatan hubungannya selalu langsung antara hamba dan Tuhan. Karena tobat secara lazim memiliki pengertian yang diarahkan pada permohonan ampun kepada Tuhan, sedangkan permohonan ampun kepada manusia, lebih sering menggunakan kata “maaf”, bukan “taubat”. Tetapi dalam puisi ini Spenk menghubungkan taubat dengan satu di antara sekian simbol kehidupan di alam semesta ini, yakni ibu. Wal hasil kalimat sederhana yang membangun tubuh puisi ini cukup absurd. Meski demikian puisi ini bukan sama sekali tidak menyediakan kunci bagi pembaca. Banyak kunci yang dapat ditemukan, misalkan memosisikan “menyusu” dan “ketiak ibu” sebagai kias yang mengarah pada konsep dasar judul. Kemudian “ibu” sebagai symbol ruang katarsis, dimana seseorang dapat bertafakur merenungi perjalanan hidupnya. Adapun “ketiak” yang dipilih (bukan hal lain) merupakan upaya untuk menunjukkan kebutuhan, ketidakberdayaan, dan keinginan untuk berlindung.
Barangkali begitulah puisi, meski dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan para pembacanya, puisi tetaplah puisi yang, dari segi bentuk, sangat padat. Kepadatan kerap membuat puisi, mau tidak mau dan suka tidak suka, menyimpan begitu banyak misteri. Pesan-pesan yang ingin disampaikan penyair kepada para penghayatnya (pembaca) terkadang melampaui teks puisi itu sendiri. Karena puisi tidak saja terdiri dari unsur ekstrinsik—yang kaitannya dengan teks itu–melainkan ada unsur intrinsic, berupa pengalaman empiris, pengetahuan, pemahaman, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kepadatan puisi berikut kepadatan makna dan luasnya ruang pemaknaannya merupa konsekuensi sederhana yang lazim adanya, bahkan tetap dapat dinilai lazim pada teks puisi yang tampak tidak lazim seperti puisi ini.
AKU
aku mencipta tuhan
Tuhan mencipta aku
aku adalah tuhan
Tuhan dalam aku
kubunuh
bunuh aku, Tuhan
2013
Jika dibaca sekilas, puisi “Aku”, seiras dengan konsep-konsep Manunggaling Gusti, Ana Al-Haq, dan sejenisnya. Di Indonesia, konsep tersebut diejawantahkan dalam puisi oleh banyak penyair. Di antaranya, yang cukup dikenal, “Tuhan, Kau Begitu Dekat” karya Abdul Hadi WM, selain puisi-puisi Syaikhuna Hamzah Fansuri yang tersohor itu. Tetapi “Aku” tidak berangkat dari pemahaman penyatuan atau peleburan seorang hamba dengan Tuhannya. Ianya menunjukkan adanya pertarungan sengit di antara hamba dan Tuhan. Di mana tuhan (huruf kecil) diciptakan oleh “aku”, sedangkan aku yang diciptakan “Tuhan” (huruf kapital) mengaku dirinya sebagai “tuhan” ketika “Tuhan” di dalam dirinya dibunuh.
Pembunuhan Tuhan di dalam diri manusia (dalam diri sendiri) dapat dimaknai sebagai puncak kesadaran seorang hamba sebagaimana pandangan Ibn Athaillah dalam Al-Hikam, “Allah ada, dan tiada sesuatu pun di samping-Nya, dan kini Dia sebagaimana ada-Nya semula”. Keberadaan Allah itu mutlak. Tidak akan dipengaruhi oleh makhluk maupun realitas-realitas yang ada. Dengan kata lain, puisi ini mengakui akan ketidakberdayaan makhluk. Di sini, ada yang perlu dicermati dengan hati-hati, terutama larik terakhir di bait penutup “bunuh aku, Tuhan”. Kemungkinannya ada dua: meminta dibunuh dalam pengertian dimatikan jasadnya atau dimatikan penyakit-penyakit jiwa yang membuat manusia meniadakan Tuhan dari imannya. Pada saya, melihat dari keseluruhan teks dan memperhatikan konteksnya, maksud “aku lirik” (tokoh aku di dalam puisi) adalah memohon agar jiwanya yang menuhankan selain Tuhan dibunuh.
Tidak jauh berbeda dengan “Taubat” dan “Aku”, puisi “Dalam Gigil” terbilang berhasil menghadirkan ruang terbuka bagi pemaknaan.
Top of DALAM GIGIL
langit menangis
seekor katak memanggil Tuhan
2013
“Katak” kerap sekali dikaitkan dengan hujan. Karena di saat hujan, di saat itu pula katak-katak berbunyi lebih nyaring dari biasanya. Dalam tradisi masyarakat, suara katak saat hujan menandakan rasa syukur katak kepada Tuhan. Dari kacamata ilmiah, alasan katak bersuara lebih nyaring saat hujan karena sistem pernapasan katak terganggu saat kelembaban tubuh terlalu tinggi, sehingga katak—yang bernapas tidak hanya dengan paru-paru, melainkan dengan kulit—harus menggelembungkan dan mengempiskan lehernya untuk bernapas. Itulah yang menimbulkan bunyi keras ketika hujan. Apa kaitannya dengan puisi ini? Simbol katak di sini merupakan gambaran tentang suara makhluk yang memanggil-manggil Khaliknya dalam keadaan duka lara. Pemaknaan ini didukung oleh larik pertama yang menyatakan langit menangis. “Langit menangis” dapat dimaknai sebagai penderitaan, kesedihan, atau keadaan batin lainnya yang menunjukkan kemuraman.
Pertanyaan krusialnya, mengapa dan untuk apa katak memanggil Tuhan? Di dalam puisi ini tidak ada jalan untuk menemukan kejadian setelah katak memanggil Tuhan atau tujuan-tujuannya. Yang dapat dijejak hanya bagaimana dan dengan cara apa, sedangkan pertanyaan mengapa dan untuk apa, penyair yang juga seorang pendidik ini rupanya sengaja membiarkan pembaca membuat kemungkinan-kemungkinan sendiri. Dalam persoalan ini, penyair memiliki hak memilih tidak membuka jalur pemaknaan yang, mungkin, bagi sebagian pembaca dianggap penting. Bolehkah demikian? Boleh.
Sebenarnya Menuju Kota Pagi tidak saja memuat puisi-puisi pendek. Ada beberapa puisi panjang, paling tidak lebih panjang dari puisi-puisi yang diketengahkan di dalam tulisan ini, tapi karena keterbatasan ruang, tidak dapat dihadirkan di sini. Barangkali akan ada pembaca yang menganggap puisi-puisi pendek adalah puisi yang ditulis oleh penyair malas atau penyair bersumbu pendek yang tidak mampu lagi mengurai puisinya menjadi lebih panjang. Tanggapan semacam itu kerap saya temukan ketika menjadi juri lomba menulis puisi. Anggapan semacam itu boleh jadi benar pada keadaan tertentu, tapi salah besar jika digeneralkan. Karena keberhasilan puisi tidak diukur dari panjang pendeknya. Akan jadi lucu dan rancu jika seseorang menilai puisi dari jumlah kata, larik, dan baitnya. Oleh sebab itu, jika ada yang mempertanyakan, mana yang lebih indah, puisi pendek atau puisi panjang, saya selalu menjawab: sama saja.
Bahkan pada sudut pandang tertentu menulis puisi pendek memiliki tantangan yang lebih sulit ketimbang menulis puisi panjang. Ketika menulis puisi panjang, penyair tinggal menuangkan dalam puisi dengan alur yang jelas, sedangkan puisi pendek nyaris tidak memiliki alur. Untuk menggambarkan tingkat kesulitan menulis puisi pendek, saya kerap menganalogikan dengan sebuah skenario pembunuhan. Jika puisi panjang melakukan pembunuhan melalui proses yang cukup lama, maka puisi pendek melakukannya dengan cara yang sangat cepat. Jika puisi panjang membuat pembaca terbius sehingga terus menelusuri setiap kata di dalamnya, puisi pendek harus mampu membuat pembaca menghentikan pikirannya sejenak, sebelum akhirnya pikiran dan jiwa pembaca penuh dengan pertanyaan dalam imajinasi yang liar.
Demikian yang dapat saya ketengahkan sebagai pengantar buku ini. Semoga Spenk Afenk—yang saya kenal rendah hati dan tidak lelah belajar ini—terhindar dari penyakit yang menjerat sebagian penyair, yakni penyakit mudah puas dan merasa besar. Penyair tidak boleh gampang puas dan menjadi “besar” bukan tujuan seorang penyair.
Banten, 2016
*( Muhammad Rois Rinaldi, pendiri Rumah Baca Bintang Al-Ikhlas Banten dan Presiden Lentera Internasional.
Ikuti tulisan menarik Lentera Sastra lainnya di sini.