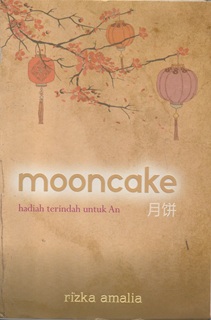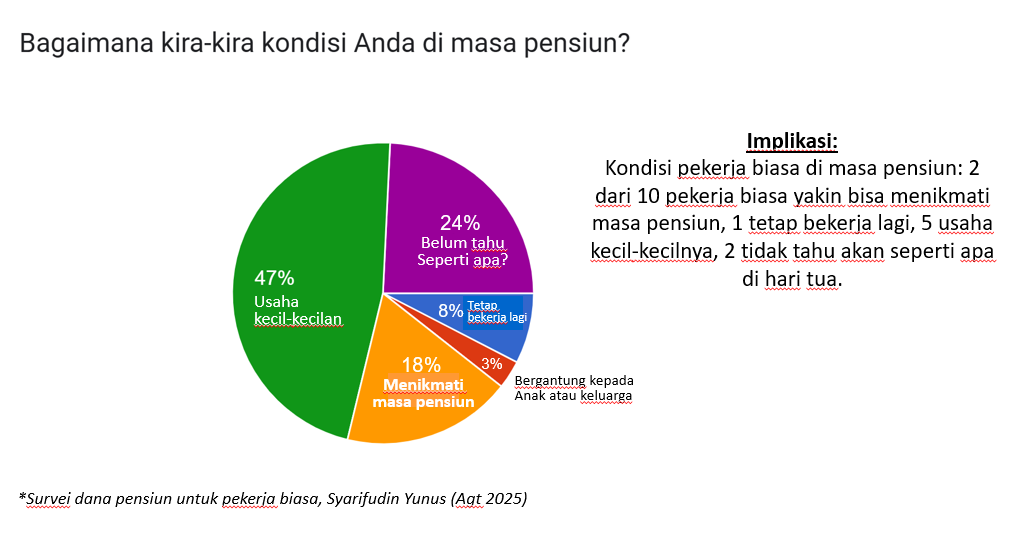Banalitas Demo
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Iklan
Agama, dengan demikian, telah menjadi “komoditas bisnis”. Begitu pula dengan 4/11/16.
Demonstrasi 4/11/16 berlangsung lancar, tertib, dan berakhir dramatis. Massa aksi yang bejibun, tak terhitung pasti jumlahnya, koalisi umat muslim dari seluruh penjuru negeri, berhasil mengepung istana dari empat sudut mata angin; sebuah pemandangan “unik”, karena di antara mereka ada kelompok yang selama ini anti-demokrasi tetapi justru menuntut keadilan hukum di alam demokrasi. Paradoks.
Dramatisasi terjadi, yang jika saja benar-benar tertib sampai peserta bubar hingga batas waktu aturan pemerintah, jam 18.00 WIB, demo itu akan mendulang pujian nomor wahid seantero dunia sebagai aksi massa terbanyak, islami, dan damai. Namun sayangnya, aksi ini terus berlanjut hingga larut malam dan menimbulkan setidaknya dua noda: melanggar aturan dan terjadi insiden anarkistis.
Bagi pendemo, noda itu dikatakan sebagai kewajaran, karena sangat sulit membubarkan massa yang jumlahnya konon mencapat 1 juta atau bahkan lebih; dan insiden itu ditepis sebagai tindakan yang dilakukan oleh oknum provokator. Sepintas alasan ini benar dan masuk akal, tetapi justru meninggalkan jejak keculasan: melanggar aturan dan melakukan penyerangan serta pembakaran mobil dianggap sebagai “bumbu” yang lazim dalam demo, terlebih membawa bendera agama tertentu, Islam.
Ketika tindakan-tindakan barbar dan kriminalitas dilakukan—apalagi dengan sengaja—sebagai sebuah kelaziman, maka seketika itulah menjadi apa yang oleh Hannah Arendt dalam Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963) disebut “banal”. Banalitas kejahatan, menurut Arendt, adalah situasi yang oleh pandangan umum dianggap melanggar norma, tetapi oleh pelakunya ditanggapi biasa-biasa saja, normal, dan wajar.
Dalam arti yang lebih luas, banalitas dalam konteks demo 4/11/16 tersebut menjalar ke semua lini yang mengitarinya. Pertama, persepsi masyarakat tentang demo, yang bukan lagi sebagai suatu aktivitas menakutkan dan perlu dihindari, tetapi justru menjadi sebuah tontonan, hiburan yang bisa disaksikan secara live di media televisi. Peserta aksi kala itu, terutama oleh media elektronik, diperlakukan bak suporter bola, mengundang pembicara sebagai komentator, mewawancarai peserta tentang bagaimana pesan dan kesan ikut aksi, dan lain sebagainya.
Banalitas demo 4/11/16, yang semula mestinya bernuansa “sakral”, karena aspirasi yang diusung menyangkut persoalan agama, kemudian bergeser ke wilayah “profan”, bercampur dengan kepentingan-kepentingan politik-duniawi. Sampai hari ini, tuntutan pendemo terhadap (dugaan) penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok semakin tidak menemukan titik terang, tapi justru blunder melebar, bahkan dicurigai tidak murni semata-mata persoalan penistaan agama, tapi lewat kasus ini, menargetkan agar ada cagub DKI gugur di tengah jalan sebelum pemungutan suara.
Kedua, peristiwa demo 4/11/16 juga menguntungkan pelaku bisnis, terutama media televisi yang saat acara berlangsung, pernak-pernik berita bisa sehari penuh menyiarkannya. Pemirsa di rumah tentu gayung bersambut, tidak mau meninggalkan layar kaca, sehingga perusahaan televisi pun juga meraup untung melimpah, rating naik.
Korelasi positif antara pendemo, isu agama, religiusitas, dan bisnis tersebut mengingatkan kita pada apa yang diamati oleh Greg Fealy ketika menuangkan hasil risetnya berjudul Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia (2008). Greg mengemukan fakta ril keberagamaan umat Islam di Indonesia, yang semakin semarak dengan cara melakukan komodifikasi terhadap Islam dalam banyak aspek, seperti fashion, pariwisata, hingga sarana dakwah via SMS atau ringtone religi.
Agama, dengan demikian, telah menjadi “komoditas bisnis”. Begitu pula dengan 4/11/16. Perhatikan hubungan simbiosis-mutualistis itu membingkai peristiwa demo dan menjadi berita hot dan aktual sampai hari ini atas jasa media. Termasuk pula, kontroversi dan polemik terhadap kasus Ahok dan demo 4/11/16, jika semata-mata ditinjau dari kebutuhan pelaku bisnis, jelas merupakan momentum yang tepat agar situasi ini terus berlangsung.
Akibat demo 4/11/16 justru kini umat Islam terpolarisasi ke dalam varian-varian sempit. Kalau saya, misalnya menyatakan tidak setuju dengan demo 4/11/16, langsung dijustifikasi pro-Ahok, padahal tidak selalu begitu. Ini juga yang dialami oleh Buya Syafii Maarif, yang memiliki pandangan berbeda dengan mainstrem umum umat muslim, langsung di-bully oleh tidak hanya masyarakat luas tetapi di jantung komunitasnnya sendiri.
Selain itu, di alam bawah sadar sebagian kalangan umat muslim, kesediaan untuk ikut demo dihubungkan dengan kualitas iman seorang mukmin. Seolah-olah orang muslim yang ikut berdemo pada 4/11/16 menunjukkan kualitas iman yang tinggi karena secara nyata peduli kepada persoalan agama, sedangkan bagi mereka yang tidak ikut, kualitas imannya rendah. Jelas persepsi ini tidak benar, dan semakin menunjukkan terjadinya banalitas itu.
Oleh: Ali Usman
Ali Usman, aktivis sosial di Yogyakarta
Baca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0







 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 99
99 0
0