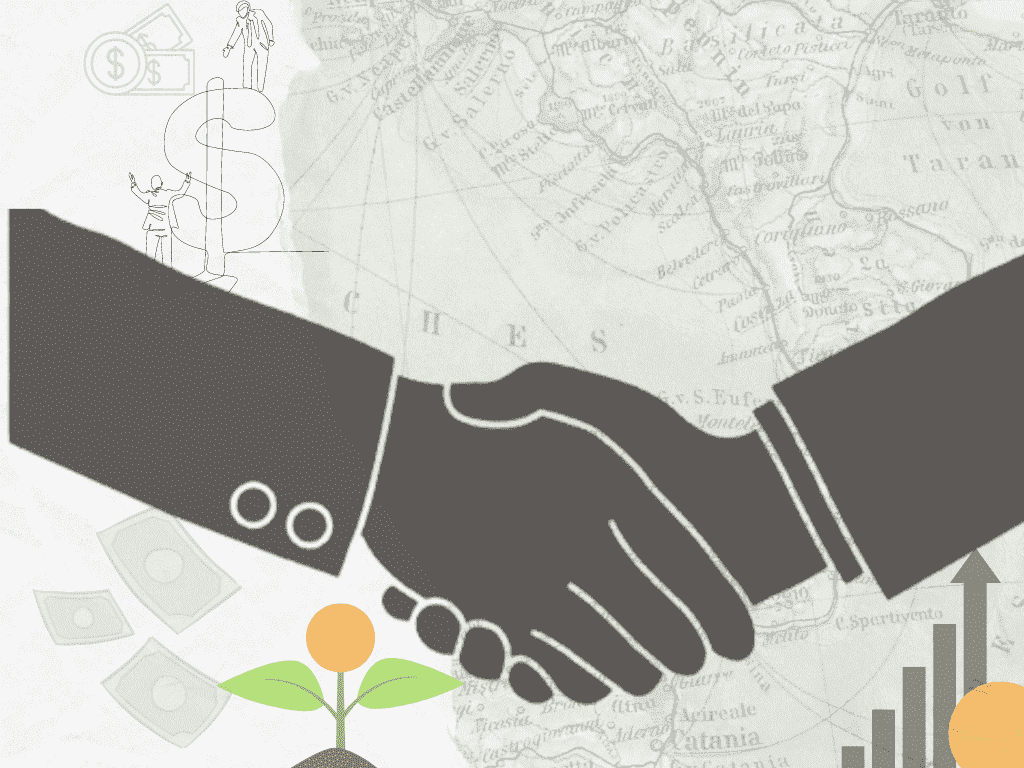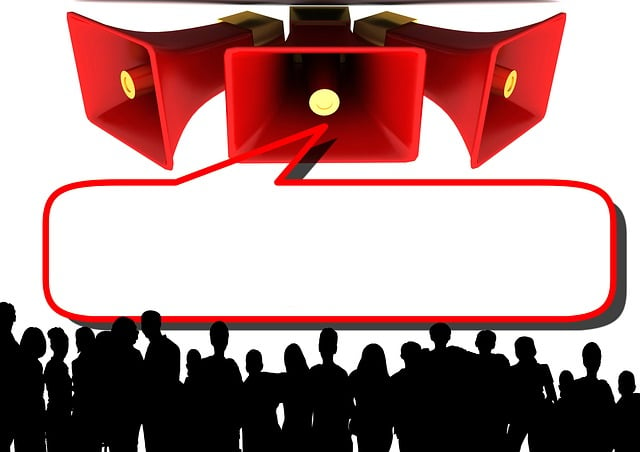Nobody can choose, in which family, they were born. Yup. Tak ada manusia yang bisa memilih lahir dari rahim siapa, ibu yang bagaimana, berjenis kelamin apa, dari suku apa, sebagai warga negara apa, bagaimana rupanya, atau bahkan dilahirkan di mana. Tak ada yang bisa memilih. Itu murni, urusan yang Maha di luar sana, bukan urusan si bayi yang mau lahir.
Sama halnya dengan saya. Saya mana ngerti kalau dilahirkan di keluarga campuran. Almarhum papah saya ‘masih’ Chinesse. Sementara, mamah saya ‘konon katanya' Jawa Banyumasan totok mblekok--lahir di lereng Gunung Slamet, di kota Purwokerto. Saya? Ya sama...lahir di Purwokerto, tempat kedua orang tua tinggal. Bukan di negara China, meskipun papah saya orang Cina.
Almarhum papah bernama Tjioe Kho Tjwan. Dia lahir dari rahim emak saya yang bernama Thio Hap Nio, gegara engkong saya yang bernama Tjioe Sioe Khong. Mamah saya bernama Narsiti, lahir dari mbah putri saya yang bernama Nawijah karena ulah kakung saya yang bernama Wirdjosuwito, seorang mantri tentara di zaman penjajahan. Lalu, apa saya pernah mimpi dilahirkan di keluarga ini? Boro-boro dah.
Tulisan ini saya buat sebenarnya karena gelo--sedih sekaligus kesal--dengan segambreng-gambreng tulisan tentang etnis Cina di medsos yang di-broadcast ke mana-mana.
“Hati-hati, jangan sampai negara ini dikuasai oleh China. Perekonomian sudah mereka kuasai. Semua taipan di negeri ini dipegang oleh orang Cina. Tinggal nunggu waktu negara ini dijajah China.”
Yassalam…
Sebagai manusia setengah Cina, jujur saya gemas. Apalagi sekarang broadcast kayak gitu tersebar cepetnya minta ampun. Selama ini yang mereka lihat cuma segelintir mata sipit yang, ndilalah, rejekinya moncer. Mereka mungkin tak pernah tahu kalau itu mereka capai dengan usaha yang tak sebentar plus tak gampang pula untuk bisa terus bertahan di posisi empuk perekonomian. Saya juga tak bisa bilang apakah mereka semua memakai mars yang merdu, agak slendro, atau slendro banget untuk mempertahankan kelanggengan bisnis mereka. Lha wong namanya bisnis, ya pasti punya trik dan politik sendiri-sendiri. Perkara apa dan bagaimana, setiap pengusaha punya cara sendiri yang tak mungkin dibagikan pada khayalak.
Tapi, mbok tolong...plis...jangan terus gebyah uyah, menyamaratakan keturunan Cina yang hidup di sini itu semua hidup enak, tinggal bersin ae jadi duit, tinggal lirik ae semua urusan cincai. Keturunan Cina yang--lahir, besar, dan--sudah sah sebagai warga negara Indonesia tak semuanya hidup mewah. Haiyaaaaaa...
Pernah tidak terpikirkan oleh Anda, mengapa sedikit sekali mata sipit yang duduk di pemerintahan, entah sebagai PNS, Angkatan Bersenjata, atau juga Kepolisian? Mungkin juga Anda mafhum rerata mata sipit, kalau tak berbisnis ya paling pol sekolah lalu sekolah terus sekolah dan sekolah lagi. Melenceng sedikit, mereka berkesenian. Itupun mereka memilih cabang yang kurang populer, piano misalnya. Baru akhir-akhir ini saja ada tukang lawak matanya sipit.
Edmund Burke pernah mewanti-wanti, ”People crushed by laws, have no hope to evade power. If the laws are their enemies, they will be enemies to the law. And those who have most to hope and nothing to lose will always be dangerous.” Intinya, orang bisa menjadi berbahaya kalau selalu dimarjinalkan. Namun, pemerintah Indonesia tak belajar dari hal tersebut saat mengadopsi hukum warisan penjajah tentang keberadaan orang Cina di Indonesia.
Selepas tahun 1945 dan segala pergolakannya, pemerintah baru membuat UU tentang kewarganegaraan. Mungkin jarang yang tahu, bahwa yang menyangkut warga keturunan baru dibuat terperinci pada 1958, yaitu UU no. 62 Tahun 1958. Undang-undang ini mengatur warga keturunan yang tinggal di Indonesia untuk mengurus surat-surat sebagai WNI. Yang jadi korban keruwetan implementasi UU tersebut terutama adalah warga keturunan Cina. Padahal, jauh sebelum negara ini berdiri keturunan Cina yang tinggal di Nusantara sudah banyak.
Nah, di sini mulai timbul masalah. Negara saat itu masih mengadopsi administrasi kependudukan warisan Belanda, yang pengaturannya didasarkan pembedaan entitas etnis dan agama: Staatsblad 1849-25 untuk golongan Eropa, Staatsblad 1917-130 jo 1919-81 untuk golongan Timur Asing (Chinesse), Staatsblad 1920-751 jo 1927-564 untuk golongan Bumiputera Non-Kristen, dan Staatsblad 1933-75 jo 1936-607 untuk golongan Bumiputra Kristen.
Karena peliknya proses adopsi ketentuan soal catatan sipil, alhasil, keturunan China yang sudah sah menjadi WNI dan warga negara Republik Rakyat China (RRC) dipandang berkedudukan hukum yang sama di hadapan Staatsblad 1917. Apalagi, sebelum keluarnya Inpeskab no 31/U/IN/12/1966, akta-akta yang diterbitkan oleh catatan sipil hanya berisi keterangan golongan etnis, tanpa menyebutkan status kewarganegaraan pemiliknya.
Hasilnya, meskipun sudah sah menjadi WNI, tetap saja etnis China diperlakukan sebagai WNA. Pun UU no. 62 tahun 1958 "hanya" mengukuhkan etnis China yang lahir dan besar di Nusantara ini sebagai warga keturunan asing. Berpijak dari sana, dimulailah pemberian "stempel khusus" lewat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI).
Sekarang, Anda punya gambaran kan kalau kami-kami ini ternyata sudah distempel sebagai alien dari zaman baheula hahahaha
Belum lagi kalau bicara soal keputusan Menteri P dan K no. 015/1968 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Sekolah Nasional Proyek Khusus. Peraturan ini mengatur jumlah siswa di sekolah khusus, dengan proporsi WNI 60%, WNA 40%. Pada prakteknya, siswa WNI keturunan Cina selalu dikategorikan dalam WNA yang 40%. Hasilnya bisa dilihat sampai sekarang, jarang sekali mata sipit yang belajar di sekolah-sekolah negeri. Dan wajar jika pada akhirnya mereka lalu berkumpul, membuat yayasan guna bisa mendirikan sekolah demi mendidik anak-anaknya. Bukankah pendidikan adalah hak segala bangsa?
Belum cukup? Masih ada cerita pasca Gerakan 30 September 1965. Karena negara RRC yang menganut paham komunis, dalam perkembangannya masyarakat tak jarang mengaitkan PKI dengan etnis Cina.
Dari ribetnya kenyataan yang saya paparkan di atas, Anda dapat membayangkan bagaimana sulitnya seorang mata sipit bisa untuk masuk ke jalur pemerintahan. Kami pun manusia yang butuh makan dan bertahan hidup. Lalu solusinya apa? Ya wes, larinya ke jalur bisnis, perdagangan, dan jalur swasta lainnya. Masuk akal, bukan?
Begitulah kurang lebih jalan hidup yang harus dihadapi etnis Cina di negara tercinta ini. Sedikit beronak, banyak liku-likunya. Sudah seperti itu kok ya masih saja entitas etnis kami 'dipakai' untuk mengangkat yang isu tak jelas sampai sekarang, yang tujuan pun tak jelas. Haruskah kami membuktikan bahwa di belantara Nusantara ini banyak juga Cina yang hidupnya kurang mujur?
Kalau Anda memang ingin membuktikan, mari berkunjung ke tempat saya. Saya juga Cina kere kok. Atau nanti saya ajak ke daerah Pecinan di dekat Kota Lama Semarang. Mau cari tukang parkir yang sipit, tukang bubur ayam, atau tukang tambal ban? Banyak.
Atau, Anda pernah dengar cerita tentang kawin kontrak antara perempuan Cina Indonesia dengan warga negara China, yang sistem pernikahannya lebih mirip jual beli manusia? Kalau belum, mungkin sesekali Anda perlu sowan ke kawasan Cina Benteng di Tangerang sana.
Ayolah, tak semua etnis Cina yang hidup di Indonesia bisa tanpa susah bermewah-mewah seperti anak-anak pemilik Salim Grup. Dan repot pula kalau karena segelintir Cina kaya yang menguasai perekonomian Indonesia, Anda lantas menganggap kami semua yang bermata sipit itu dompetnya tebal amit-amit, kartu kreditnya tanpa limit. Ah, sungguh pahit hahahaha
Sejujurnya, banyak dari kami yang merasa sedih dengan banyaknya broadcast miring tentang Cina. Tapi, kami sama sekali tak ingin berkonflik. Kami hanya ingin menikmati menjadi warga negara Indonesia yang kedudukannya sama dengan yang lain. We love to live in peace, tak lebih dan tak kurang.
Kami sadar bahwa kami tumbuh besar karena makan dari beras yang disediakan ibu pertiwi. Pun, kami masih hidup dan mencari makan di sini. Dan dengan bangga pula, kami mencintai Merah Putih dan Garuda kami, bukan bendera merah lima bintang. May God give us more time to live, that we can see our grandchildren grow up in peace and harmony.
Itu saja.
Ikuti tulisan menarik margaretha diana lainnya di sini.