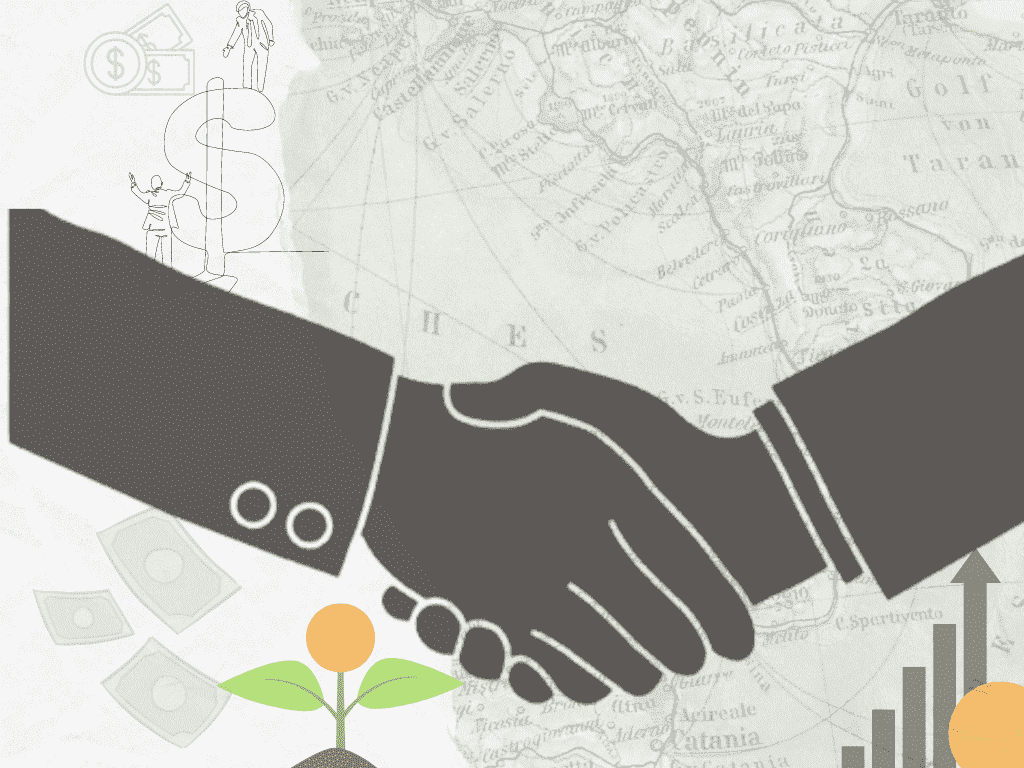Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah menuai kontroversi. Penolakan muncul dari masyarakat, organisasi guru bahkan ormas Islam seperti NU. Bahkan Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin pun turut memberikan pernyataan terkait penolakannya atas kebijakan baru ini, yang di media lazim dikenal dengan sebutan full day school.
Jika merujuk pada Permendikbud di atas, pastinya tidak ada satupun penggunaan istilah full day school di dalamnya. Secara umum peraturan yang berisi 11 Pasal ini memaparkan tentang waktu bersekolah yang ditentukan pemerintah, serta konsekuensinya bagi pendidik (guru) dan tenaga kependidikan. Selama ini waktu bersekolah yang terjadi di sekolah-sekolah Indonesia, baik di bawah Kemdikbud (seperti SD-SMA/SMK) maupun di bawah Kemenag (seperti Madrasah Ibtidaiyah-Madrasah Aliyah) adalah mulai hari Senin sampai Sabtu alias 6 hari.
Walaupun di banyak kota besar, sudah lama bermunculan sekolah (SMA) yang waktu belajarnya hanya 5 hari (Senin-Jumat), di Jakarta contohnya. Bahkan di sekolah seperti SMA Labschool Jakarta, sekolah lima hari sudah diterapkan semenjak tahun 1995, semasa tokoh pendidikan Prof. Dr. Arief Rachman masih aktif sebagai kepala sekolah. Dengan waktu belajar selama 8 jam dalam sehari dan 40 jam dalam seminggu. Permendikbud ini mengatur seperti demikian. Agar waktu siswa/i tersebut secara penuh digunakan 5 hari belajar dalam sistem pendidikan formal (sekolah) dan 2 hari berikutnya diisi oleh pendidikan keluarga.
Waktu 8 jam belajar tersebut, menurut Permendikbud tadi tidak hanya diisi dengan belajar dalam artian klasik (tatap muka belajar di dalam kelas), tetapi waktu belajar digunakan juga dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas sosial di sekitar sekolah. Misalkan pukul 07.00-13.00 siswa belajar di sekolah (kegiatan intrakurikuler). 2 jam berikutnya siswa melakukan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Jadi siswa bisa belajar di sanggar-sanggar seni, kunjungan ke taman kota, panti-panti sosial, vihara, masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya (secara prinsip termuat dalam Pasal 6). Nah, penggunaan waktu esktra inilah yang diharapkan mampu membentuk karakter siswa, yang oleh Kemdikbud disebut sebagai “Penguatan Pendidikan Karakter” (PPK). Demikian penjelasan tim Kemdikbud yang santer di publik. Bahwa kebijakan lima hari sekolah ini dalam rangka penguatan pendidikan karakter.
Kemudian agar tidak keliru dalam memahami penggunaan istilah yang berkembang di media, ada pentingnya kita memahami peristilahan tersebut secara utuh. Pertama, istilah full day school, jika diterjemahkan menjadi “sekolah sehari penuh”, yang bermakna siswa akan berada seharian di sekolah. Istilah ini memang tidak akan ditemukan dalam Permendikbud. Kedua, adalah istilah “8 jam di sekolah” (lima hari di sekolah), jika kita baca teliti memang juga tidak ada dalam peraturan tersebut. 8 jam di sekolah bermakna siswa akan belajar tatap muka di ruang kelas (sekolah) secara penuh selama 8 jam. Ketiga, adalah yang mirip dengan kedua tadi, yaitu “8 jam sekolah” (lima hari sekolah/LHS). Selama 8 jam siswa belajar, tetapi tidak full berada di sekolah, seperti yang peraturan ini kehendaki dan diutarakan di atas.
Kenapa Lima Hari Sekolah Ditolak?
Ketika PBNU dan beberapa organisasi guru menolak aturan ini, seperti Persatuan Guru NU (Pergunu), LP Ma’arif NU, Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), bukan tanpa alasan. Jika disimpulkan secara umum, setidaknya ada lima (5) alasan utama penolakan kebijakan lima hari sekolah (LHS) ini oleh publik.
Pertama, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa “penetapan hari sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan pada tahun pelajaran 2017/2018”. Pemerintah terkesan “memaksakan” aturan ini, yang baru disahkan pada 12 Juni 2017 lalu. Sedangkan awal tahun ajaran baru yaitu Juli 2017, hanya berjarak 1 bulan. Peraturan ini sangat terasa “dadakan” perencanaan dan pelaksanaannya. Padahal pepatah lama mengatakan, segala sesuatu yang tergesa-gesa, akan tidak baik hasilnya.
Dalam proses pembuatan aturan ini sekolah-sekolah di bahwa Kemenag tidak dilibatkan, bahkan Kemenag itu sendiri. Padahal pengelolaan pendidikan dan persekolahan di tanah air ini, berada di bawah 2 kementerian tersebut. Ketergesa-gesaan ini akan makin terasa jika membaca semua pasalnya yang “hanya” berjumlah 11 Pasal. Sangat tidak mendetil uraiannya. Padahal yang akan diatur oleh Permendikbud ini adalah lebih kurang 60 juta siswa dan hampir 300 ribu sekolah (data dari www.databoks.katadata.co.id, 2016), belum termasuk Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah/Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Padahal peraturan selevel Peraturan Menteri ini harus mengatur hal yang bersifat khusus, mendetil dan bersifat teknis, (berbeda dari UU atau Peraturan Pemerintah).
Lebih aneh lagi (jika tidak dikatakan “ngaco”), dalam konfrenesi pers yang dilakukan Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin dan berdiri di belakangnya Mendikbud Muhadjir Effendi pada 19 Juni 2017 di Istana Presiden. Justru kebijakan full day school ini ditangguhkan oleh presiden, bahkan pemerintah akan mengganti Permendikbud No. 23 Tahun 2017 menjadi setingkat Perpres. Jadi otomatis Permendikbud ini sudah batal secara “politis”. Tetapi anehnya justru sekarang Mendikbud tetap mempertahankan dan memaksakan kebijakan ini secara nasional, mulai tahun ajaran baru 2017/2018 yang dimulai beberapa hari ke depan.
Pemaksaan waktu pelaksanaan LHS di awal tahun ajaran baru justru akan berdampak tidak baik dan menjadi alasan kedua, yaitu tidak semua sekolah secara nasional memiliki prasyarat fasilitas-fasilitas sosial/umum seperti disebutkan di atas. Posisi (lokasi) sekolah di Indonesia, khususnya yang di daerah masih jauh dari kata strategis, atau dekat dengan fasilitas sosial-keagamaan. Bahkan akses menuju sekolahpun jauh dari kata laik dan pantas, bahkan tidak manusiawi.
Para siswa dan guru harus berjuang mati-matian, lewat jembatan lapuk di atas sungai beraliran deras. Akses jalan ke sekolah yang sangat buruk, bahkan harus menempuh 2-4 jam agar sampai sekolah. Kendaraan yang tidak memadai. Potret suasana sekolah dan akses pendidikan di SD Muhammadiyah Gantong, Belitung seperti dalam film “Laskar Pelangi” (2008), yang menggambarkan pendidikan di tahun 70-an itu, ternyata masih banyak bertahan secara “istiqomah” di sekolah-sekolah daerah pelosok Indonesia hingga kini. Tentu inilah yang sifatnya “fardu ‘ain” bagi pemerintah untuk dipenuhi terlebih dulu. Agar keadilan dan pemeretaan kesempatan pendidikan benar-benar terasa di seluruh pelosok negeri.
Makanya tidak heran jika dikatakan LHS ini sangat ramah terhadap sekolah dan siswa di perkotaan, tapi tidak bagi daerah pedalaman. Padahal semua mereka itu, baik yang di kota besar maupun di daerah pelosok negeri adalah anak-anak Indonesia juga, yang berhak menjadi cerdas dan berkarakter!
Alasan ketiga, waktu belajar 8 jam sehari itu sangat tidak mengakomodir kearifan lokal (local wisdom) yang sudah terjadi puluhan tahun di masyarakat daerah. Maksudnya yaitu, secara demografis masyarakat Indonesia bertempat tinggal di kawasan pertanian, sehingga pekerjaannya mayoritas petani, peternak, berkebun dan nelayan. Selama ini, jam belajar siswa rata-rata pukul 07.00-13.00, selepas pulang sekolah para siswa di kawasan pertanian misalnya membantu orang tua mereka ke sawah dan ladang, berternak bahkan berjualan.
Sudah menjadi kewajiban bagi anak-anak petani membantu orang tua ke ladang, demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Atau berjualan makanan dan es keliling desa (seperti yang penulis pernah rasakan semasa kecil di Sumatera Barat). Justru inilah sesungguhnya pendidikan karakter yang sudah ada lama hidup dalam bumi nusantara. Tanpa lahirnya Program PPK di atas, yang dikait-kaitkan dengan lima hari sekolah, karakter pejuang, ketangguhan, kemandirian, percaya diri, kepatuhan, disiplin, kerja keras dan lainnya itu sudah terbentuk dalam masyarakat agraris dan nelayan. Bagaimana anak akan bisa membantu orang tuanya ke sawah ladang, jika waktu belajarnya masih terpakai sampai sore hari?
Lima Hari Sekolah dan Pendidikan Karakter, Kok Bisa?
Inilah kemudian yang menjadi alasan keempat penulis. Para birokrat di Kemdikbud termasuk konsultan yang dikaryakan di sana mengatakan di berbagai forum, bawah keberadaan Permedikbud tentang Hari Sekolah ini justru dalam rangka memperkuat program yang dinamakan “Penguatan Pendidikan Karakter” yang lazim dikenal dengan sebutan PPK. Kami bertanya-tanya, apa hubungan antara 8 jam belajar itu dengan pendidikan karakter? Apakah dengan 8 jam sekolah itu karakter siswa akan makin mudah terbentuk? Makin lama anak belajar formal, maka makin terbentuk pula karakternya.
Jika demikian halnya, tentu konsep “Boarding School” dan “Pesantren” akan nyata-nyata lebih unggul dalam pendidikan karakter, sebab jam belajar mereka justru 24 jam sehari di sekolah/pesantrennya masing-masing! Menghubung-hubungkan jam belajar dengan pembentukan karakter, logika ini bagi penulis tidak berbasis kajian ilmiah atau penelitian yang kuat. Di sinilah letak kerancuan cara berpikirnya.
Bukan berarti penulis menolak konsepsi pendidikan karakter dan PPK ini, tetapi mencoba mengaitkan PPK dengan Permendikbud tentang Hari Sekolah ini adalah sangat mengada-ada dan khayal belaka. Sebab pasal demi pasal dalam aturan pendek ini, tidak satupun yang menuliskan dan memuat istilah karakter atau penguatan pendidikan karakter di dalamnya, tidak satupun! Padahal Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Budi Pekerti (yang berisi pendidikan karakter) sudah pernah dibuat di era Anies Baswedan. Lantas, peraturan pendidikan karakter apa yang mesti dipatuhi dalam Permedikbud tentang Hari Sekolah ini, jika dalam Permendikbud ini tidak satupun mengatur tentang pendidikan karakter.
Alasan kelima yang juga krusial disampaikan di sini adalah, agaknya adagium lama yang mengatakan “ganti menteri ganti kebijakan”, ini masih berlaku di Kemdikbud. Semestinya Mendikbud fokus saja kepada kelanjutan program-program Kemdikbud sebelumnya. Fokus pada penguatan dan keseriusan dalam pembenahan program yang masih compang-camping tersebut. Seperti masalah Kurikulum 2013 (yang sampai sekarang belum semua sekolah melaksanakan secara nasional) yang masih bermasalah dalam implementasi. Guru-guru masih banyak belum dilatih dalam implementasi Kurikulum 2013.
Kemudian persoalan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) seperti yang dijanjikan dalam Kampanye Jokowi-JK dulu. Pemeretaan akses dan keadilan dalam pendidikan kepada seluruh anak Indonesia. KIP sangat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan kualitas anak Indonesia, apalagi yang berada di pelosok-pelosok daerah. Kemudian persoalan pembenahan sebaran dan kualitas guru yang timpang antara perkotaan dan daerah. Yang bagi MA pemerintah dianggap lalai dalam peningkatan kualitas guru tersebut. Juga pembenahan perguruan tinggi yang mencetak calon-calon guru (eks IKIP) tentunya.
Hal tersebut terkait dengan konsistensi pemerintah dalam melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung (2009) tentang UN. MA memutuskan agar pemerintah melakukan pembangunan sarana-prasarana pendidikan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, akses dan informasi pendidikan yang terbuka dan peningkatan kualitas guru. Yang kesemua itu masih jauh dari kata tercapai. Justru masalah-masalah seperti di ataslah yang mesti sesegara mungkin dipenuhi dan dibenahi, karena akan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia Indonesia, seperti yang diharapkan dalam Pembukaan UUD 1945. Inilah masalah sesungguhnya pendidikan nasional kita yang mesti dituntaskan, bukan dengan lima hari sekolah jawabannya!
*Satriwan Salim adalah Pengurus SEGI Jakarta, Peneliti PUSPOL Indonesia dan saat ini mengajar di SMA Labschool Jakarta
Ikuti tulisan menarik Satriwan Salim lainnya di sini.