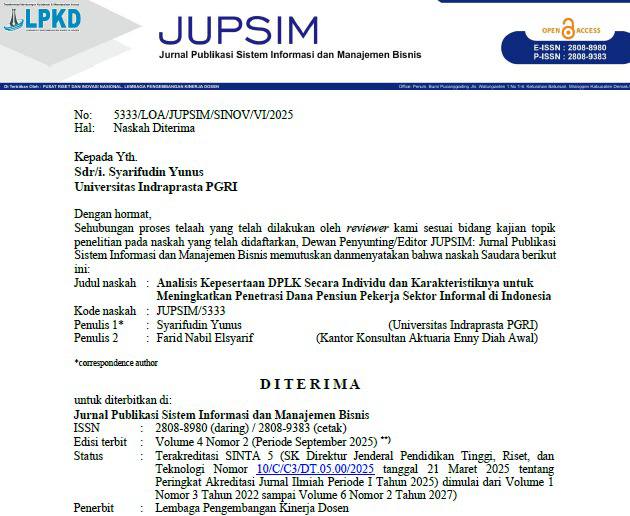Defisit Empati
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Apakah masyarakat kita tengah mengalami defisit rasa empati?
Pernahkah kamu mencoba memakai sepatu orang lain? Apa yang kamu rasakan, ketidaknyamanan? Barangkali, kamu merasa ibu jarimu tertekuk, bagian tumitnya longgar sehingga ketika dipakai untuk berjalan terasa mau lepas, atau ujung mata kakimu lecet karena iritasi.
Pepatah ‘cobalah pakai sepatu orang lain’ adalah nasihat agar kita berempati kepada orang lain. Pepatah ini mengajak kita untuk memandang sebuah persoalan dari sudut pandang orang lain, merasakan pengalaman yang dirasakan orang lain. Apa yang kita lihat dari jauh begitu menyenangkan, mungkin akan jadi menyakitkan ketika kita berada di posisi orang itu. Kita mungkin jadi mengerti mengapa ia bersikap seperti itu (mengerti tidak mesti berarti menyetujui atau menyepakati).
Empati, kata para arif, membuat kita mampu memerlakukan orang lain dengan lebih hormat dan lebih peduli. “Saya ikut berduka,” adalah ucapan yang melukiskan perasaan ikut kehilangan seseorang yang disayangi—ayah, ibu, saudara. Sebagian ahli menyebut perihal ‘empati emosional’—kita merasakan pengalaman yang dirasakan orang lain namun dalam kadar yang lebih rendah.
Menarik bahwa mereka yang empati emosionalnya kuat akan merasakan kesakitan di area yang sama pada otaknya dengan orang yang benar-benar merasakan kesakitan itu. Ketika menyaksikan seseorang terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit, orang tertentu dapat menyerap pengalaman yang tengah dirasakan pasien itu. Dalam kondisi seperti ini, kata-kata ‘aku dapat merasakan penderitaanmu’ bukan lagi sekedar metafor, apa lagi basa-basi, melainkan bermakna literal secara neurologis. Seseorang mungkin ikut merasakan nyeri ketika melihat lutut orang lain membentur pintu.
Ada pula yang disebut ‘empati kognitif’ yang terkait dengan kemampuan kita untuk memahami apa yang sedang dipikirkan orang lain, apa yang sedang bergolak dalam benak orang lain. Berbeda dengan empati emosional yang mentautkan rasa, empati kognitif lebih berbicara tentang ‘pemahaman’—“Saya dapat memahami mengapa ia berbuat seperti itu. Peristiwa ini bukan hal yang mudah baginya.” Dalam relasi antarmanusia, empati kognitif tak kalah penting dibandingkan empati emosional. Empati kognitif memungkinkan kita bersikap lebih sabar dalam menghadapi konflik dan tidak merasa diri kita yang paling benar.
Para ahli juga menyebut istilah compassion—yang dicirikan oleh perasaan kehangatan, kepedulian, dan dorongan untuk memperhatikan orang lain, ada sejenis motivasi untuk membantu dan menolong orang lain bangkit dari keadaannya yang kurang baik: kesulitan hidup, musibah, petaka. Compassion bukan sekedar kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain, bukan hanya kapasitas untuk memahami apa yang dipikirkan orang lain dan alasan mengapa orang lain melakukan tindakan tertentu, tapi—lebih dari itu—mempedulikan, membantu, dan menolong orang lain yang kesulitan.
Lantas apa pentingnya semua itu: empati emosional, empati kognitif, maupun compassion? Jika kita tergerak untuk merefleksikan ketiganya ke tengah masyarakat kita, tidakkah kita berpikir bahwa “Apakah masyarakat kita tengah mengalami defisit empati?” Lihatlah sekeliling pada kata-kata yang bertebaran di ruang-ruang virtual di jalur internet, tampakkah tanda-tanda defisit itu? **
Penulis Indonesiana
2 Pengikut

Di Balik Dugaan Manipulasi Angka Statistik ala Rezim Prabowo
Rabu, 27 Agustus 2025 18:54 WIB
Di Balik Amnesti Hasto: Prabowo dan Megawati Sepakat Mengubah Permainan
Sabtu, 2 Agustus 2025 08:59 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0




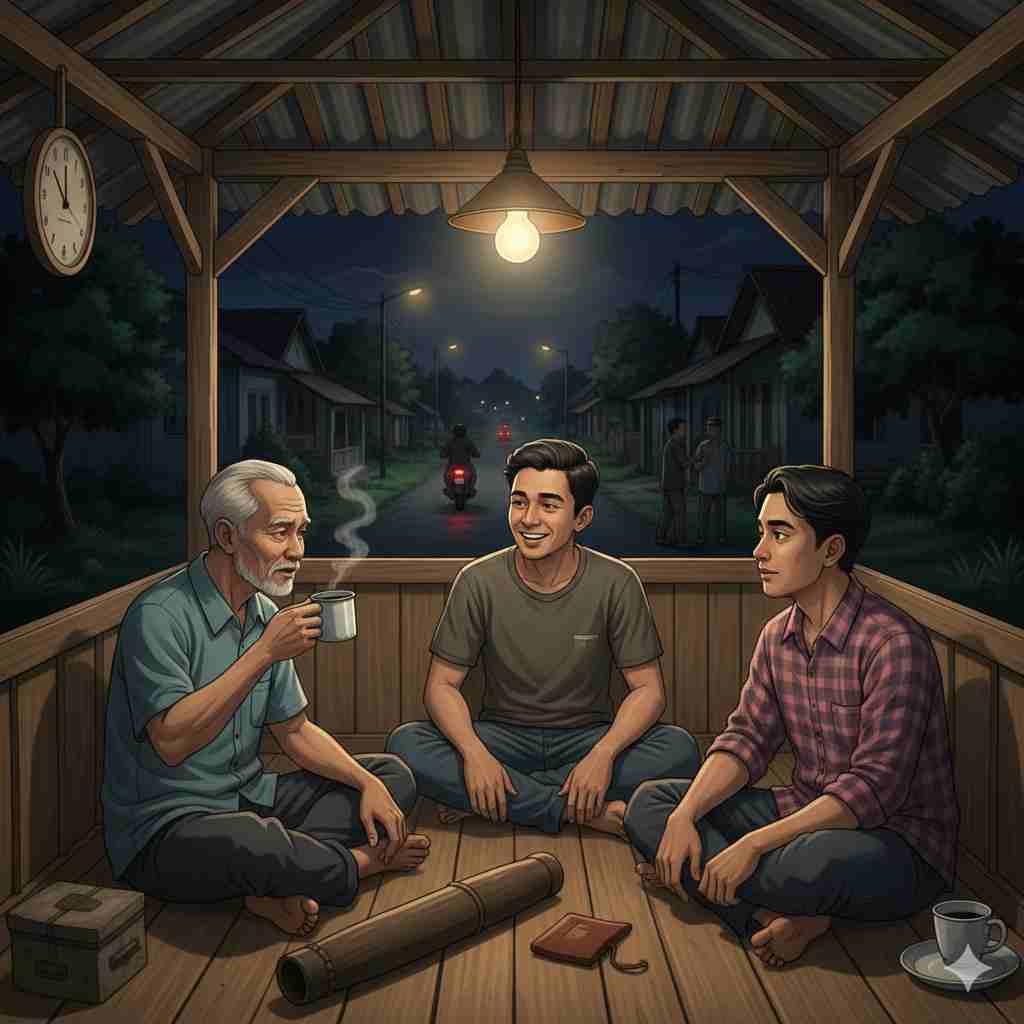

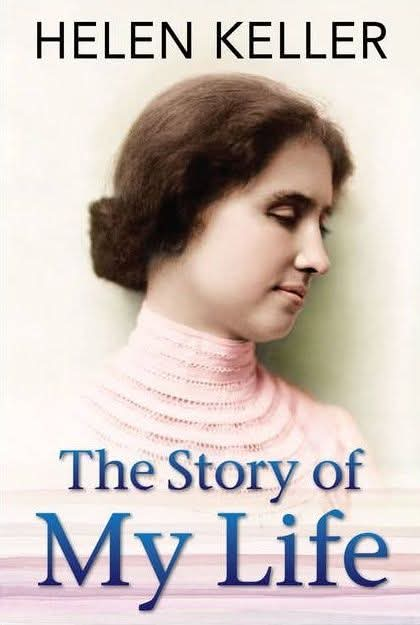
 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 96
96 0
0