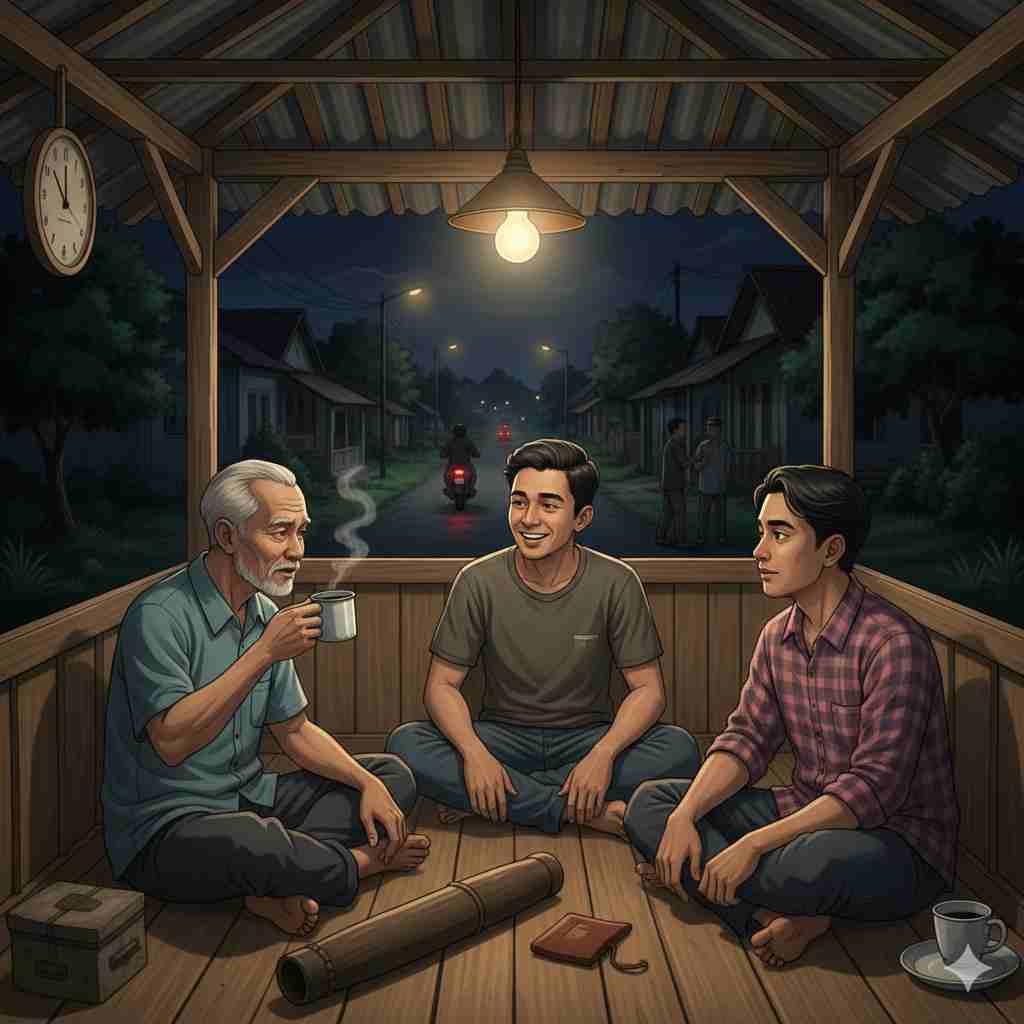Merenungi (Kembali) Pasca G-30 S
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Tulisan Pasca G-30 S terjadi.
Tahun lalu ketika peringatan G-30 S, Panglima TNI yang kala itu masih dijabat oleh Gatot Nurmantyo menginstruksikan untuk menonton bareng film Pengkhianatan G-30 S PKI secara serentak pada tanggal 30 September 2017. Suatu upaya kristalisasi memori kolektif bangsa tentang peristiwa sejarah yang dilihat dari perspektif pemerintah. Kiranya sah-sah saja bila ada tafsiran baru mengenai peristiwa itu. Terutama pasca peristiwa itu terjadi.
Dalam buku Sarwo Edhie dan Misteri 1965 (2012) diceritakan ketika pagi hari 1 Oktober pasca penculikan keenam jenderal dan satu perwira tinggi tersebut, Letnan Kolonel Sarwo Edhie yang pada saat itu menjabat kepala RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) dipanggil menemui Panglima Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat), Mayjen Soeharto. Setelah menyerobot masuk ke ruang Panglima Kostrad karena tak jua mendapat perintah, akhirnya Soeharto memerintahkan Sarwo untuk menstabilkan keadaan.
Setelah mengumpulkan anak buahnya dan mengoordinirnya, tepat pada 2 Oktober pukul 06.00 pagi pasukan taktis RPKAD bergerak ke Lapangan Udara Halim Perdanakusumah. Tak sampai setengah jam, Halim telah dikuasai tanpa perlawanan berarti. Selain menstabilkan kondisi ibu kota, satu tugas Sarwo yang terpenting adalah menemukan keberadaan keenam jenderal dan satu perwira yang hilang.
Lubang Buaya, 3 Oktober. Sukitman, seorang anggota kepolisian yang diculik oleh kerumunan masa PKI namun berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di bawah sebuah truk hingga tertidur dibangunkan oleh beberapa anggota RPKAD dan dibawa menghadap atasannya, Sarwo Edhie. Setelah diyakinkan Sarwo bahwa pasukan khusus bergantung pada informasi yang dimilikinya, Sukitman baru buka mulut tentang lokasi markas PKI di Lubang Buaya.
Akhirnya sumur tua yang dijadikan tempat dikuburnya para jenderal dan perwira itu ditemukan. Namun, pengangkatan jenazah mereka ditunda karena Soeharto selaku Pangkostrad akan menyaksikan keesokan harinya. Sarwo Edhie pulang ke rumah setelah memberikan instruksi penundaan itu. Di rumah dia memandangi foto Jenderal Ahmad Yani yang menjadi salah satu korban. Dia menangis di hadapan foto sahabatnya. Hubungan mereka sudah seperti kakak-adik karena sebelum masuk ABRI, mereka pernah digembleng bersama-sama dalam PETA. Soeharto mengetahui kedekatan mereka berdua. Hal inilah yang dimanfaatkannya dalam menumpas Gerakan 30 September.
Pasca G-30 S
Masyarakat Indonesia pada umumnya selama ini hanya mengetahui satu versi tentang peristiwa G-30 S. Terutama siapa pelakunya. Sampai saat ini ada lima tesis tentang siapa pelaku utamanya. 1) PKI, 2) klik Angkatan Darat, 3) Soeharto, 4) CIA, dan 4) Soekarno sendiri. Sayangnya, hasil penelitian para ahli Barat tersebut kurang dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini tidak terlepas dari “militerisasi” dan “orbaisasi” sejarah yang terjadi ketika Soeharto berkuasa.
Asvi Warman Adam dalam buku Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia (2004) menuliskan pasca peristiwa G-30 S terjadi, di rentang tahun 1965-1966 terjadi pembantaian besar-besaran terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan PKI. Bahkan, lebih tragis mereka yang tidak berafiliasi sama sekali dengan PKI menjadi korban. Selama ini angka korban yang disodorkan berkisar antara 78.000 hingga 3.000.000. Namun, Asvi mengutip Robert Cribb yang mengumpulkan 39 artikel yang memuat angka korban yang berkisar antara 78.000 hingga 2.000.000. Setelah semuanya dijumlah dan dibagi 39, didapatkan angka rata-rata 430.590 orang. Suatu angka yang cukup moderat. Kebanyakan korban berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Asvi melanjutkan, ada faktor pendukung mengapa pembantaian itu terjadi. Pertama, konflik di daerah-daerah antara golongan komunis dan non-komunis terutama para kiai sudah mulai tampak pra-1965. Kedua, militer berperan dan membiarkan massa bergerak sewenang-wenang. Ketiga, provokasi media massa yang menyebabkan masyarakat geram. Keempat, budaya “amuk” dan “tawuran”, yang dipercaya sebagai unsur penopang kekerasan.
Orbaisasi sejarah ini pada akhirnya seakan-akan menutupi kesalahan rezim Orde Baru yang berkaitan pasca G-30 S. Pembuangan orang-orang ke Pulau Buru di rentang 1969-1979. Bahkan setelah keluar dari sana, dalam kartu tanda penduduk mereka disematkan tanda “ET”, Eks-Tapol. Diskriminasi ini berlanjut hingga ke masalah mengisi perut. Para ET ini tidak boleh menjadi PNS. Sampai ke anak-cucunya pun ada istilah PKI “biologis”. Kalau orang tuanya PKI, otomatis keturunannya pun akan menjadi PKI.
Selanjutnya pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Orde Baru bisa dirunut mulai dari Pembantaian 1965-1966, Pembuangan Politik ke Pulau Buru 1969-1979, Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, Petrus (Pembunuhan Misterius) 1980-1985, Peristiwa Talangsari 1989, Kudatuli 1996 (Kudeta 27 Juli 1996) sampai Kerusuhan Mei 1998. Warna hitam dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang tidak boleh dilupakan.
Ribka Tjiptaning Proletariyati dalam bukunya Aku Bangga Jadi Anak PKI (2002) membeberkan kisah hidupnya pasca peristiwa 1965 terjadi. Ayahnya, Raden Mas Soeripno Tjondro Saputro merupakan salah satu aktivis PKI yang bergerak di Kota Solo. Ibunya, Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati masih keturunan Kesultanan Yogyakarta. Meskipun terlahir dalam keluarga ningrat dan ayahnya pun seorang borjuis pemilik 5 pabrik besar di Karanganyar, Semarang, dan Solo, namun kedua orang tuanya mengajarkan kesederhanaan hidup pada Ribka. Suatu hal yang kelak berguna pasca keluarganya harus pindah dari Solo ke Jakarta.
Di Jakarta, Ribka sekeluarga mengalami getirnya kehidupan. Karena ayahnya diburu, maka mereka harus berpisah. Ibunya melakukan “bunuh diri” kelas. Dari seorang ningrat menjadi pedagang laksa, ikan pindang, singkong, tape, semangka, kelapa, dan abon. Bahkan mereka sempat tinggal di pinggiran kali. Lebih dari itu, kucing dan tikus rumah pernah menjadi lauk-pauk mereka ketika bersantap. Belum lagi mereka sekeluarga harus berpindah-pindah rumah menghindari kejaran aparat.
Dalam ranah pendidikan pun Ribka kesulitan untuk memasuki sekolah formal. Beberapa sekolah sempat menolaknya untuk menjadi murid karena mengetahui latar belakang keluarganya. Selain itu dia tidak pernah membeli buku pelajaran di sekolah. Ribka selalu menyalin dengan cara menuliskannya kembali dari buku pelajaran milik temannya. Untuk memenuhi kebutuhan uang jajan, dia pun sering memberikan les untuk adik kelasnya.
Diskriminasi semacam yang dialami Ribka merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kasus yang terjadi pada masa Orde Baru berkuasa. Cap anak PKI, tidak Bertuhan, hingga musuh Ulama disematkan kepada para lawan politiknya. Terutama di tingkat akar rumput. Mulai dari urusan perut hingga hak pendidikan semuanya dipersulit. Kejahatan rezim yang pada akhirnya membawanya ke liang lahat sendiri pada 1998.
Hari ini ketika tahun politik semakin mendekat, berbagai ujaran kebencian maupun fitnah kembali berseliweran. Terutama di dunia maya. Merenungi pasca G-30 S semoga sedikit menyadarkan kita bahwa bangsa ini belum berdamai dengan masa lalunya. Tidak perlu saling klaim siapa pelaku utamanya. Yang harus dipikirkan sekarang ialah bagaimana beban sejarah ini bisa diselesaikan bersama dengan kepala dingin. “Barangsiapa yang tidak belajar dari masa lalunya, maka dia dikutuk untuk mengulanginya”, ujar George Santayana.
Penulis, Mahasiswa Ilmu Sejarah FIB Universitas Padjadjaran
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Biografi KH. Mukhyiddin (Mama Pagelaran ) Pendiri Pesantren Pagelaran Sumedang
Senin, 1 Agustus 2022 18:00 WIB
Sang Utusan Perdamaian
Minggu, 21 Juni 2020 14:46 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
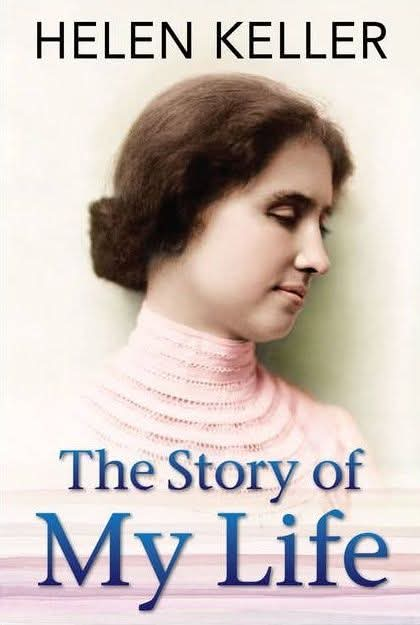
 Berita Pilihan
Berita Pilihan





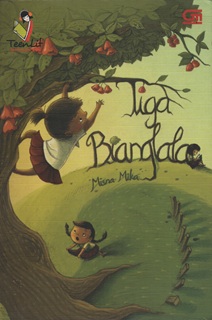

 99
99 0
0