Demokrasi Nan Bising di Usia 74
Sabtu, 24 Agustus 2019 15:15 WIB
Kebisingan di ruang-ruang publik adalah cerminan dari kebisingan di ruang-ruang politik, pemerintahan dan kanal-kanal penegakan hukum di negeri ini. Inilah wajah demokrasi di negeri kita yang telah berusia 74 tahun ini. Demokrasi nan bising.
Kurang lebih 4 bulan setelah Pemilu berakhir, kebisingan di negeri ini tak juga berakhir. Perdebatan antara kaum “kampret” dan kaum “cebong” memang tak lagi merecoki ruang-ruang publik. Tapi sinisme di media-media sosial tetap berlanjut dengan topik-topik baru.
Kita seperti tak pernah kehabisan bahan untuk diperdebatkan, dipergunjingkan dan diributkan. Sebagian besar keributan itu bermula dari kejadian biasa; diperbincangkan satu dua netizen di media sosial, kemudian ditanggapi figur publik baik kaum selebriti, aktivis, maupun politisi. Karena telah melibatkan figur publik, media massa memamfaatkannya sebagai “click bait”. Maka jadilah viral dan mengundang reaksi masyarakat luas.
Kebisingan di ruang-ruang publik adalah cerminan dari kebisingan di ruang-ruang politik, pemerintahan dan kanal-kanal penegakan hukum di negeri ini. Inilah wajah demokrasi di negeri kita yang telah berusia 74 tahun ini. Demokrasi nan bising.
Demokrasi Prosedural
Di bidang politik, demokrasi yang kita praktekkan hanyalah prosedur perebutan kekuasaan di antara para elit dengan memperebutkan suara dan dukungan publik. Belum tampak secara signifikan hubungan antara prosedur-prosedur demokrasi seperti Pemilu yang kita jalankan dengan penguatan nilai-nilai demokrasi dalam sistem politik kita seperti penguatan mekanisme “check and balance” antara eksekutif dan legislatif, pelembagaan parpol dan sejumlah indikator penting lainnya.
Kita masih juah dari ideal sebuah sistem demokrasi yang menempatkan pemenang kontestasi politik sebagai pemimpin pemerintahan (eksekutif) dan pihak yang kalah otomatis sebagai kekuatan kontrol (oposisi). Format ideal seperti ini akan memberi ruang lebih luas dan energi lebih besar bagi pemenang untuk mempersiapkan diri menjalankan roda pemerintahan begitu kontestasi politik berakhir. Demikian juga untuk kelompok yang kalah, semestinya memusatkan energi untuk melakukan konsolidasi kekuatan kontrol terhadap pemerintah.
Pada kenyataannya, setelah kontestasi berakhir, pemenang sibuk bertengkar, memicu berbagai kebisingan dan kegaduhan dalam rangka “bagi-bagi kursi”. Kelompok yang kalah terus menerus memobilisasi “kenyinyiran” publik sambil berharap mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan pihak pemenang demi mendapatkan jatah kursi atau minimal diberi konsesi kekuasaan.
Kalau kita perhatikan dengan seksama, berbagai kegaduhan publik tersebut selalu berakhir dengan cibiran pada penguasa (pemerintah) atau mendiskreditkan elit-elit politik yang berada di luar kekuasaan. Sindir-menyindir di tengah masyarakat seakan menjadi alternatif dari pertarungan antara kelompok elit penguasa dengan kelompok elit di luar kekuasaan, atau alternatif terhadap pertarungan antara pemerintah dengan kelompok oposisi.
Tambal Sulam Komposisi Oligarki
Seruan untuk golput yang sempat berdegung keras di media sosial menjelang Pilpres 2019 sebagian besar dilatarbelakangi semakin tidak jelasnya di mata publik perbedaan antara elit baru dan elit lama. Elit baru seperti Jokowi semakin sering menunjukkan preferensi kompromistis termasuk dengan lawan politiknya. Dalam politik, semakin banyak kompromi maka semakin banyak fulus dibutuhkan, baik berupa jabatan, konsesi bisnis, perlakuan khusus di hadapan hukum atau bentuk fulus lain. Praktek berkompromi dengan menarik sebanyak mungkin kekuatan ke dalam koalisi pendukungnya dipandang sebagai cara-cara lama yang lazim dilakukan oleh oligarki. Maka populerlah ungkapan “siapapun yang anda pilih dalam Pilpres, pemenangnya adalah oligarki”.
Dalam studi sosial-politik, kemunculan elit baru dari tengah masyarakat seperti Jokowi lazim disebut “sirkulasi antar elit dan massa”. Sirkulasi elit seperti ini dipandang ideal, di mana elit yang lama diganti kelompok yang baru dengan kemampuan lebih baik. Mereka diharapkan lebih mampu merespon kepentingan masyarakat yang lebih beragam dan selalu berubah sesuai gerak zaman.
Akan tetapi, publik segera menyadari bahwa politik dengan sistem apapun (termasuk sistem demokrasi) tidak pernah seindah uraian buku teori. Elit lama, kendati tidak memiliki jabatan politik secara defenitif, dengan berbagai upaya tetap dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan dan keputusan hukum secara langsung maupun tidak langsung. Ada banyak contoh yang dapat kita rujuk untuk membuktikan ini dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi.
Singkatnya, elit lama tidak pernah benar-benar digantikan. Mereka hanya memudar dari pantuan publik seraya terus melakukan perpanjangan tangan melalui elit-elit baru. Karena itu, kemunculan elit baru dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini lebih tepat disebut sebagai bagian dari “tambal sulam komposisi oligarki” daripada “sirkulasi elit” yang sering digunakan dalam buku teori sosial politik.
Peningkatan presidential threshold yang menutup kemungkinan munculnya poros kekuatan baru dalam Pilpres dapat kita jadikan salah satu contoh kesuksesan oligarki lama memempertahankan dominasi mereka menggunakan tangan elit-elit baru. Konsekuensinya, dua kali kita mesti menghadapi pertarungan politik yang benar-benar menguras energi di tengah kondisi masyarakat yang terbelah dua akibat perbedaan pilihan politik. Dengan hanya dua calon (Pilpres 2014 dan 2019) masyarakat hanya memiliki 2 pilihan: mendukung kubu nomor 1 atau nomor 2, tidak ada alternatif lain. Hanya ada “kita” atau “mereka”. Maka Pilpres 2014 dan 2019 layak dijuluki sebagai Pilpres paling bising sepanjang sejarah Indonesia dan jejak-jejaknya masih terasa hingga sekarang yakni kebisingan yang tak kunjung mereda di ruang-ruang publik kita.
Kembali pada teori sirkulasi elit yang disinggung sebelumnya, menarik untuk menyertakan perumpamaan sinis dari Vilfredo Pareto dalam artikel ini sebagai “warning” bagi kita untuk terus kritis mengawasi perilaku para elit melalui saluran-saluran demokrasi yang tersedia. Teoritikus politik berkebangsaan Italia tersebut menggambarkan elit lama seumpama serigala yang serakah, egois, cerdik dan sekaligus licik untuk bertipu muslihat. Sementara itu, elit baru dilukiskan sebagaimana halnya dengan sekawanan singa yang gagah, tangguh dan mempunyai cita-cita mulia. Akan tetapi, begitu tercapai keinginannya untuk menduduki tampuk kekuasaan, singa itu akan menjelma menjadi serigala. Pareto menyatakan bahwa nasib semua serigala adalah dijatuhkan oleh singa, tetapi nasib semua singa adalah menjadi serigala.
JPM Group Reporter
0 Pengikut

Ambulan Musolla All-Falah untuk Semua Masyarakat dari Semua Agama
Rabu, 30 Maret 2022 19:10 WIB
Cengkeraman PT TPL Membuat Masyarakat Tak Berdaya (Bagian 1)
Selasa, 22 Februari 2022 07:37 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0





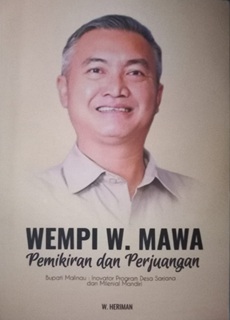

 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 97
97 0
0

















