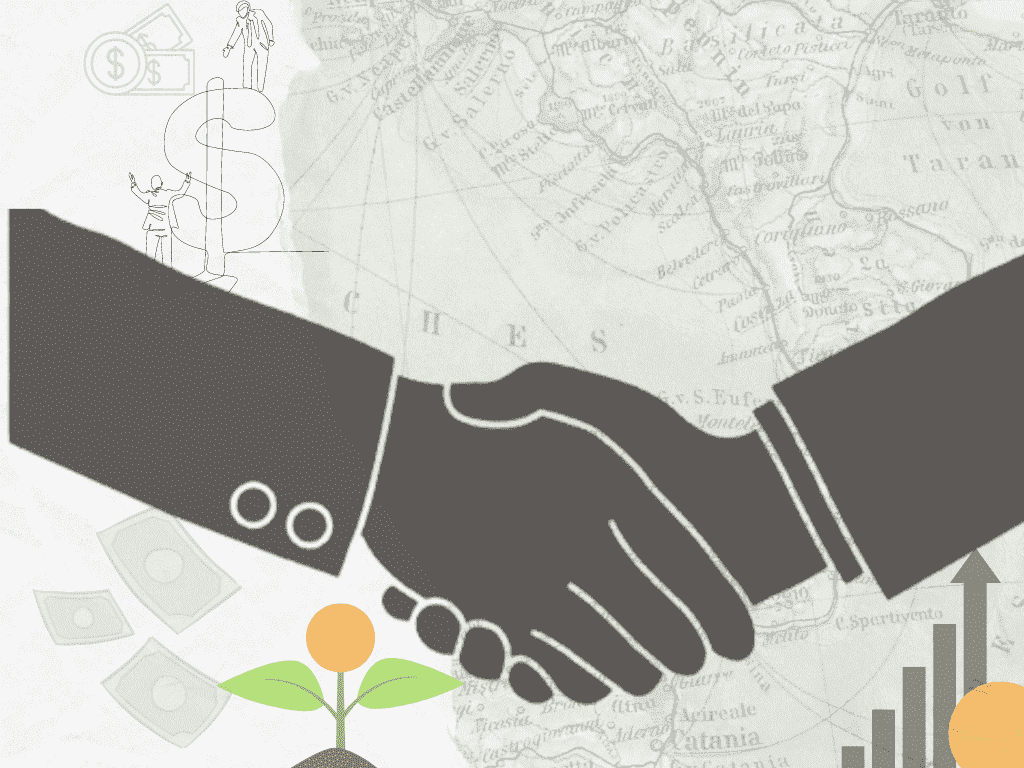“Politikus memikirkan pemilu mendatang, negarawan memikirkan generasi mendatang.”
--James Freeman Clarke (1810-1888)
Di hadapan pengadilan kolonial Belanda di Bandung, 1930, Bung Karno—saat itu berusia 29 tahun—menyampaikan pembelaannya, Indonesia Menggugat. (Judul pembelaan ini kemudian menjadi nama gedung tempat Bung Karno diadili, yang hingga kini masih tegak berdiri di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 5 Bandung). Apapun pembelaan yang ia sampaikan, Bung Karno dan kawan-kawan (Maskoen, Gatot Mangkoepradja, Soepriadinata, Sastromoeljono, dan Sartono) tahu bahwa mereka tetap akan masuk penjara. Namun, dengan membacakan pledoi yang mereka susun sendiri, dunia akan tahu sikap bangsa ini terhadap kolonialisme Belanda.
Bung Karno melihat bahwa kolonialisme membawa serta kapitalisme. Oleh sebab itu, dengan lantang Bung Karno melontarkan kritik lewat pledoinya: “Kapitalisme adalah suatu pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi.” Bung Karno memberi tekanan: “Kapitalisme mengarah kepada pemiskinan.” Dari masa sekarang, menyaksikan praktik ekonomi yang sedang berlangsung, bagaimana kita becermin kepada kritik Bung Karno waktu itu?
Dalam pikiran Bung Karno, kolonialisme dan kapitalisme menyengsarakan kehidupan rakyat banyak. Dalam ikhtiarnya menemukan gagasan yang tepat bagi manusia Indonesia, Soekarno muda memelajari gagasan-gagasan besar dunia—cara belajar yang umum dilakukan anak-anak muda masa itu yang kelak memimpin proses kemerdekaan. Tidak heran bila ia begitu fasih mengutip Ernest Renan, Karl Marx, Adam Smith, hingga Jamaluddin al-Afghani. Hingga kemudian, Bung Karno muda mengonstruksi gagasannya sendiri yang ia anggap cocok untuk manusia Indonesia, dari sosok Marhaen yang ia anggap mewakili manusia Indonesia.
Sekitar dua tahun lebih awal dibandingkan pengadilan Bung Karno di Bandung itu, Bung Hatta—ketika itu berumur 26 tahun—mengajukan pembelaan di hadapan pengadilan kolonial di Den Haag, Belanda. Dalam pledoi yang diberi judul Indonesia Merdeka, Bung Hatta mengritik keras kolonialisme dan imperialisme. “Lebih suka kami melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi daripada suatu negara asing,” kata Bung Hatta. Begitu radikal Bung Hatta di mata kolonial.
Bung Hatta melakukan pula pengembaraan intelektual dan berkenalan dengan banyak pikiran dunia di masa itu maupun masa-masa sebelumnya. Perkenalannya dengan pemikir Yunani, yang kemudian ia tuangkan dalam buku Alam Pikiran Yunani, turut membentuk cara berpikir Bung Hatta. Tapi perjumpaannya dengan gagasan Karl Marx dan Adam Smith—dua ekonom yang pemikirannya niscaya ia pelajari sebagai mahasiswa ekonomi di Belanda—membuat Bung Hatta mengerti benar bagaimana kapitalisme bekerja. Bagi anak muda yang melek politik masa itu, seperti Soekarno, Hatta, maupun Sjahrir, membaca Das Kapital dan Wealth of Nations adalah keharusan sebagai ikhtiar untuk memahami bagaimana dunia bekerja. Tentu saja, membaca kritis, bukan menelan bulat-bulat.
Sikap radikal Bung Hatta, seperti juga Bung Karno dan Sutan Sjahrir—yang berusia 8 tahun lebih muda dibanding Bung Karno, sudah terlihat sejak usia muda. Bung Hatta, pada usia 21 tahun, telah menulis Indonesia di Tengah-tengah Revolusi Asia. Revolusi yang berlangsung di Indonesia, kata Bung Hatta, tidak bisa dilepaskan dari pergolakan bangsa-bangsa Asia yang sedang berusaha membebaskan diri dari kolonialisme. Datangnya kesadaran untuk menjadi manusia merdeka tidak dapat dibendung. Di usia 18 tahun, Sjahrir bersama kawan-kawan menggagas pembentukan himpunan pemuda nasionalis, Jong Indonesie—lalu berganti nama Pemuda Indonesia, yang pada tahun berikutnya menjadi motor Kongres Pemuda 1928.
Zaman memang telah berubah, tapi kita tak bisa melupakan pertautan historis dengan mereka yang merintis jalan dan menegakkan Republik ini. Di usia muda, sosok-sosok perintis dan pendiri Republik ini telah memperlihatkan kejelasan tujuan perjuangan mereka, pendirian mereka, dan keteguhan integritas mereka. Sutan Sjahrir selalu mengumandangkan ide-ide tentang demokrasi yang bermartabat—ide yang seharusnya dikembangkan saat ini: bukan demokrasi asal unggul mayoritas tapi mengabaikan etika. Meskipun beberapa kali masuk dan keluar penjara kolonial—bahkan juga dibui di masa Orde Lama yang dipimpin Soekarno [kawan sepenjara Sjahrir di masa kolonial], namun keyakinan Sjahrir kepada demokrasi tidak luntur sebagaimana ia tuangkan dalam Pikiran dan Perjuangan maupun Renungan Indonesia--yang ia tulis di penjara Cipinang dan pengasingan Bouven Digul dan Banda Neira.
Tan Malaka, yang beberapa tahun lebih tua dari mereka bertiga, mengenal dekat beragam pemikiran yang juga dibaca anak-anak muda itu. Sembari menjalani perjuangan bawah tanah, Tan Malaka menyempatkan diri menuangkan pikirannya ke dalam tulisan. Lahirlah Massa Actie, Gerilya Politik dan Ekonomi, Madilog, hingga catatan hariannya, Dari Penjara ke Penjara. Di mata kolonial Belanda, Tan bagaikan hantu karena berpindah-pindah tempat demi menghindari tangkapan reserse kolonial.
Dalam Massa Actie, Tan Malaka berbicara tentang dua tombak Revolusi Indonesia: mengusir imperialisme Barat dan mengikis sisa-sisa feodalisme. Yang satu datang dari luar dan yang satu lagi berasal dari dalam diri sendiri. Revolusi ini, kata Tan Malaka, bila berhasil dilaksanakan akan mendatangkan perubahan yang menyeluruh dalam politik, ekonomi, sosial, dan bahkan mental—ya, Tan Malaka sudah berbicara perihal revolusi mental puluhan tahun yang lampau. Bagi Tan, mengikis sisa-sisa feodalisme merupakan perjuangan yang belum akan berhenti sekalipun Indonesia sudah merdeka dari kolonialisme.
Dalam usia 27 tahun, pada 1924, Tan Malaka menerbitkan risalah Menuju Republik Indonesia yang memuat konsep negara Indonesia yang tengah diperjuangkan. Karya ini mendahului pledoi Bung Hatta di Den Haag maupun pembelaan Bung Karno di Bandung. Karya-karya mereka, bersama buah pikir H.O.S. Tjokroaminoto, Tirto Adhi Soerjo—yang menerbitkan beberapa suratkabar dan mendirikan Sarikat Dagang Islam, Moh. Yamin, dan banyak lagi, telah memberi warna pada fondasi Indonesia merdeka.
Zaman terus bergerak dan berubah, namun tautan historis ini tak bisa dihapus. Mereka menetapkan tujuan perjuangan yang jelas dan berjuang dengan integritas yang mereka jaga sekuat mungkin. Setiap Oktober adalah saat untuk mengingat kembali perjuangan anak-anak muda, sebagaimana setiap Agustus adalah momen untuk becermin kepada sejarah. Di sanalah kita akan mendapati sejumlah perbedaan sepak terjang perintis kemerdekaan dengan elite politik masa sekarang. Setidaknya ada empat perbedaan yang dapat disebutkan:
Pertama, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, Tan Malaka, dan lain-lain terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menempuh risiko penjara dan pengasingan kolonial. Mereka bukan hanya memikirkan gambaran Indonesia Merdeka yang dicita-citakan, tapi sekaligus berjuang mewujudkannya. Mereka, anak-anak muda itu, adalah manusia gagasan sekaligus manusia aksi. Adakah politikus masa kini yang punya gagasan jelas tentang Indonesia masa depan—setengah abad mendatang?
Kedua, gagasan dan sikap pilihan mereka dituangkan dalam tulisan, sehingga siapapun dapat membaca dan memahaminya. Mereka menulis karena mengerti benar apa yang mereka pikirkan dan bagaimana harus mengungkapkannya. Mereka punya cita-cita untuk beberapa generasi Indonesia mendatang dan berusaha menyiapkan landasannya, bahkan memperjuangkannya. Sekali lagi, mereka manusia gagasan sekaligus manusia aksi. Mereka bertindak dengan pemahaman.
Ketiga, mereka tidak berusaha mengambil keuntungan ekonomis saat berjuang maupun saat berkuasa setelah kemerdekaan. Tan Malaka terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Bung Hatta dan Bung Sjahrir hidup pas-pasan, bahkan Bung Hatta pensiun dalam keterbatasan ekonomi dan menolak jabatan komisaris perusahaan. Bandingkan dengan elite politik sekarang yang berlomba-lomba menguasai ekonomi atau bersekutu dengan oligark, bahkan mereka menyatukan kekuatan politik dan ekonomi dalam satu genggaman.
Keempat, mereka teguh pendirian serta menjaga integritas dan nilai-nilai. Mereka tidak akan menggoyahkan integritas sendiri untuk dipertukarkan dengan jabatan maupun kue bisnis. Hingga kematian menjemput, mereka memegang teguh ide dan integritas serta membebaskan diri dari godaan kekuasaan. Memang, di masa tua, tak semua anak muda itu sanggup bertahan dari godaan kekuasaan dan terlena dibuatnya.
Betapapun demikian, para perintis dan pendiri Republik itu bukanlah politikus seperti yang digambarkan James Freeman Clarke: “Politikus memikirkan pemilu yang akan datang, negarawan memikirkan generasi yang akan datang.” **
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.