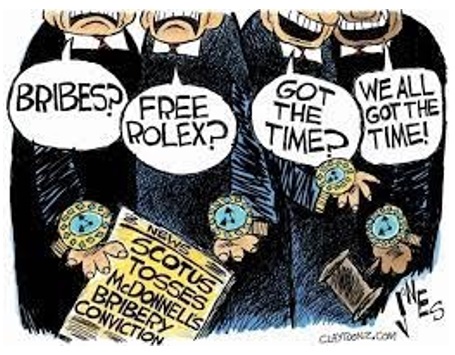Sisa-sisa Perahu
Jumat, 12 November 2021 16:50 WIB
Perahu itu hanya sisa-sisa dari keserakahan nenek moyang. Di karamkan, dan dihancurkan lebih baik untuk menghilangkan kenangan.
Harusnya juga kau jaga baik-baik peninggalan 10 turunan ini. Benar-benar kau tak tau untung dan tak tahu berterima kasih, membalas budi kepada benda-benda yang telah memberimu jalan penghidupan dari jaman susah sampai tetap saja susah. Tapi setidaknya perahu itu telah memberi mu umur, dimana usia mu sudah berjalan diatasnya sebagai jembatan setelah apa yang kau raih dan dapatkan selama ini. Dan sekali lagi kau harus banyak-banyak belajar pada nenek moyang mu yang katanya seorang pelaut, seorang yang arif kepada laut.
Achilles mendengkur menghadap gundukan pasir pantai, kedua telapak tangannya tak kuasa menahan amarah dengan mengusap-usap wajah hingga kepalannya. Laut dan ombak begitu santai menatap tubuhnya yang begitu berani, kekar, tak lekang tersentuh matahari begitu tidak mampu dirinya membuang ucapan-ucapan pamannya dalam kepala. Kenangan dalam keluarganya menjelma karang yang kuat dengan ditumbuhi berbagai tumbuhan laut. Dan ia begitu tak kuasa menghancurkan karang-karang itu, kecuali hidup dalam kehidupannya.
Malam itu hujan begitu deras di pesisir pantai. Angin dan ombak saling berhubungan menjelma nada-nada tinggi yang mengerikan. Daun-daun kelapa menyapu keras udara. Bunyi kentongan penjaga termakan hujan. Warga pesisir hanya menyisakan doa-doa agar perahunya tak karam dan badai cepat berlalu. Dan ditengah perhelatan badai yang menggentarkan, ibumu merintih kesakitan tentang perutnya yang mengandung kau. Lalu kaulah yang keluar dengan diiringi redanya badai dan kecamuk angin, tapi kau tak seharusnya ditakdirkan untuk menjadi manusia yang mandiri sejak lahir, angin dan badai telah membawa ibumu. Begitulah sang paman selalu bercerita menganyam kenangan.
Tubuhnya yang tumbuh begitu cepat dengan garis-garis otot yang menonjol pada kulitnya, ia mengenal dunia begitu tangkas dengan matanya yang tajam menatap lautan. Bukan bangku sekolah yang ia kenal, apalagi guru-guru yang mengajarinya parade di tengah halaman. Ia dirawat dan dibesarkan oleh laut. Tanah pesisir telah menjadi buku yang ia cintai sejak pertama kali bisa berjalan dengan paman sebagai gurunya.
"Paman kau tak takut, berlayar kelaut yang tak bertepi" tanyanya sambil menunjuk tengah laut.
"Apa yang ditakuti?"
"Laut itu memang tak punya mulut yang bisa melahap paman, tapi ia telah memakan bapak ku"
"Sudahlah. Laut ini sudah menjadi negeri kita. Kalau tak mati di laut ya di darat"
Achilles terdiam, mengikat dukanya pada air laut.
"Esok bila kau sudah berumur lima belas tahun akan ku ajak melaut. Kau bisa membawakan dongeng atau lukisan-lukisan mu pada bapak kau. Ah sudahlah sana kau balik, jaga baik-baik bibi. Saya pasti pulang tapi tidak juga membawa bapak mu pulang"
Sejak saat itu ia mulai suka membaca laut, mengeja garis-garis pantai dan melukis nasib dengan pasir. Berkali-kali ia mencoba menggambar wajah bapaknya pada air laut tapi selalu gagal dan marah. Bila mengenang bapaknya yang entah kemana, sedang bercumbu dengan laut mana. Bapak telah meninggalkan ibu setelah mengandung delapan bulan, dua belas rombongan nelayan telah karam dan bangkainya tak ditemukan. Bibi yang selalu bercerita dan berceloteh sabar.
Matahari telah berulang kali terbit dan bercermin pada tubuh laut. Dan usia Achilles semakin beranjak menginjak ke lima belas tahun, berkat petuah kakeknya ia begitu mencintai laut dan tanah halamannya. Sudah sering ia diajak melaut, sekaligus menaburkan doa-doa ke laut untuk bapaknya. Ceramah pamannya pun, tak pernah ia absen mendengarkan. Pamannya yang selalu bercerita tentang negeri laut. Begitu menghormati pada nenek moyangnya seorang pelaut. Bahwa laut adalah negeri yang tak pantas mendapati kata serakah, perusak, ia telah memberi mu kenangan. Berkali-kali ia memintal nasehat dan memasukkannya ke dalam saku celana.
Begitu waktu berjalan, ia menghabiskan masa pujangga dihamparan laut. Usianya yang genap ke dua puluh tahun, ia melepas diri untuk tidak bekerja pada pamannya. Dan tinggal seorang diri di gubuk pojok pantai.
"Paman saya hendak berlayar sendiri"
"Memangnya kau sudah ada perahu?"
"Belum. Saya hendak membeli dengan tabungan"
"Saya baru ingat. Kau ambil saja perahu yang satu itu, yang dekat perahu paman. Perahu peninggalan bapak kau. Itu negeri mu dan jaga baik-baik, perahu itu turun temurun dijaga dan dirawat, meski sudah tua masih mampu kau gunakan tenaganya untuk mengenang bapak kau"
"Besok saya akan berlayar paman"
Tidak akan ada kenangan lagi yang menghantuinya. Sekali perahu retak, karamkan saja dari pada selalu menambal kenangan, pikirnya. Jika negeriku saya tenggelamkan, tak akan ada lagi generasi yang tumbuh dengan akar-akar serakah, pikirnya kembali.
Matahari belum keluar, tubuh molek laut belum kelihatan. Ia keluar untuk menghancurkan karang-karang kenangan. Ia menyalakan mesin perahu dan berlayar sedikit menengah. Ia hancurkan lantai-lantai perahu. Perlahan perahu karam.
"Kau makan juga peninggalan bapak ku, negeriku bukan peninggalan. Kenangan telah mengutukku" ia memaki-maki pada laut. Mengenakan pelampung lalu berenang ke tepian. Matahari muncul, perahu telah karam. Paman muncul dengan wajah garam. Dan ia siap dengan beribu-ribu tamparan.
"Apa maksudmu?" Tamparan begitu keras mengenai wajahnya
"Mengapa paman tak menceritakan semuanya"
"Cerita apa?"
"Paman seolah-olah cinta pada laut, bertekuk lutut pada nenek moyang" telunjuknya menunjuk pada wajah pamannya "Bapak ku mati bukan dimakan laut tapi dimakan keserakahan, ia terlalu serakah pada negerinya. Dan kau paman begitu arif menyuruhku mencintai laut. Kau sendiri pelancong. Mungkin kali ini paman masih hidup, entah suatu saat laut tak akan sudi dengan paman yang masih hidup"
Pamannya mengutuk dengan kata-kata dan amarah.
Sementara Ia berlari meninggalkan pantai, memunggungi kenangan, membelakangi kata-kata pamannya. Mengucapkan selamat tinggal kepada pasir tubuh laut. Dan ia mendengkur di halaman rumahnya membaca huruf-huruf kenangan.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Sisa-sisa Perahu
Jumat, 12 November 2021 16:50 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 999
999 0
0