Impian Arimbi
Jumat, 19 November 2021 06:25 WIB
Cerpen ini mengisahkan bagaimana sastra masih mampu bersuara, meski kerap dianggap sebagai fiksi
Pada mata kuliah Kajian Budaya, Arimbi selalu memberi tugas pada para mahasiswa untuk berkunjung ke beberapa tempat bersejarah di Yogyakarta. Kali ini ke Monumen Jogja Kembali atau sering disebut dengan Monjali. Kuliah pada semester Agustus hingga Desember ini, menandai awal dari perkuliahan mahasiswa-mahasiswa baru. “Silakan diamati, dengan cara menguping misalnya, obrolan para pengunjung di sana,” katanya.
Meski sudah bergelar sarjana, para mahasiswa tampak bingung dengan tugas yang baru saja diberikan. Tugas yang terkesan hanya seperti piknik itu justru membuat mereka terhenyak dan enggan untuk bertanya lebih jauh lagi. Beginilah, pikirnya, tugas dari seorang cendekiawan bukan sekadar memberi jawaban yang terbaik. Namun, justru bagaimana membuat pertanyaan yang tajam dan akurat. Bagaimanapun juga, mereka bukan lagi mahasiwa yang perlu ditiupkan seruling agar dapat menari. Tetapi, sebaliknya, dididik dengan cambuk dan kursi seperti pawang singa melatih raja hutan untuk dapat beratraksi dengan dahsyat dan memikat di tengah para penonton sirkus.
Memang bukan kali ini saja Arimbi menugasi para mahasiswa di kelasnya untuk mengunjungi Monjali. Bahkan sesama kolega dan pengajarnya di tempat kuliahnya dulu kerap dibawa ke sana. Terakhir, salah seorang pengajar seniornya, diajak ke sana dan tampak sangat puas. Untuk apa Monjali dibangun, pikir Arimbi, apakah monumen itu adalah bagian dari masa lalu? Masa lalu siapa? Ia pun teringat dengan salah seorang guru besar di kampusnya yang menulis tentang monumen dan kartun sebagai wahana komunikasi politik di era Orde Baru. Boleh jadi memang benar bahwa museum yang dibangun oleh keluarga besar dari bapak pembangunan nasional itu adalah warisan dari politik ingatan masa lalu. Jadi, museum itu mirip dengan album foto yang digunakan untuk menyimpan kenang-kenangan belaka. Dengan kata lain, tak ada peringatan yang berdaya dering untuk mewaspadai dengan jeli bahwa ada yang penting dan mendesak untuk dikerjakan.
Kini saatnya presentasi. Arimbi mempersilakan setiap kelompok melaporkan hasil kunjungan mereka dan dilanjutkan dengan diskusi bersama.
Kelompok pertama mempresentasikan laporannya dengan sebuah kisah. Kisahnya bermula dari sebuah diorama yang menggambarkan para pejuang RI bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta sedang berkumpul di lapangan dan memberi hormat pada bendera merah putih. Tiba-tiba salah seorang pengunjung berkomentar, “Lho kok Bung Karno dan Bung Hatta tidak menghormat ke bendera merah putih ya?” Pengunjung lain menimpali, “Mungkin karena tidak memakai topi, kali?” Pengunjung yang pertama berkomentar berujar, “Ah, bisa aja kamu. Dengan atau tanpa topi, hormat pada bendera merah putih berlaku untuk semua dong.”
“Dari kisah itu tampak bahwa upacara bendera yang sampai saat ini masih dilakukan selalu berorientasi pada militer. Artinya, segala hal yang berkait dengan upacara itu tidak bisa tidak menampilkan atribut, bahkan aroma, militer,” demikian pemaparan dari salah seorang perwakilan kelompok.
“Lalu, apa pelajaran yang bisa diambil dari sana?” Arimbi menyela dengan pertanyaan singkat.
“Paling tidak penting untuk dicatat bahwa perjuangan merebut kemerdekaan di republik ini bukan semata-mata didominasi oleh aksi angkat senjata. Tetapi juga didukung dengan diplomasi yang tepat dan cermat, serta yang tak kalah pentingnya adalah dukungan dari nasionalisme,” jawab sang wakil kelompok.
“Apa itu nasionalisme?” Arimbi tampak penasaran.
“Kalau dalam konteks ini, nasionalisme adalah semangat untuk rela berkorban demi orang lain, daripada sekadar mengorbankan yang lain,” tukas sang wakil kelompok.
Sesudah semua kelompok melaporkan hasil kunjungan lapangannya itu, kelas pun diakhiri. Arimbi pun tampak cukup puas dengan apa yang dilaporkan oleh para mahasiswanya. Paling tidak dari apa yang dilaporkan itu ada pelajaran, khususnya yang berkait dengan sejarah, yang diperoleh di luar kelas.
“Selamat pagi,” sapa Arimbi pada awal kelasnya.
“Hari ini kita akan melanjutkan perbincangan tentang sejarah dengan membaca dan mengupas salah satu cerpen dari Seno. Nama lengkapnya Seno Gumira Ajidharma. Dan judul cerpennya, “Pelajaran Sejarah”. Ada yang sudah pernah baca?” tanya Arimbi.
Sepertinya tidak ada reaksi yang cukup antusias dari para mahasiswanya yang hadir di kelas pagi itu.
“Tentang Timtim ya?” celetuk salah seorang mahasiswa yang duduk agak di pojok kelas.
“Ya, ada yang mau disampaikan?” selidik Arimbi pada sang penceletuk itu.
“Bukan tentang cerpennya sih. Tapi dulu ada bapak dari teman saya yang dibunuh di sana. Sama Fretilin, katanya. Diserbu dan dihabisi semuanya,” cerita sang penceletuk.
“Tapi justru karena itu, teman saya dan adiknya bisa masuk Akabri, tanpa seleksi. Katanya sih, sebagai balas jasa atas pengorbanan bapaknya. Begitu,” tambah sang penceletuk.
“Ada lagi yang mau menambahkan?” tanya Arimbi pada mahasiswa lain yang ada di kelas pagi itu.
“Cerpen ini memang bercerita tentang Timor-Timor atau Timtim. Sekarang sudah menjadi Timor Leste. Ketika menjadi Timtim, itu adalah provinsi ke-27 dari Republik Indonesia. Namun, sejak awal dianeksasi menjadi bagian dari NKRI, Timtim serupa dengan Aceh dan Irian Jaya atau Papua saat ini. Sama-sama menjadi daerah operasi militer, atau disingkat DOM.” Arimbi memaparkan dengan singkat.
“Jika ingin tahu lebih jauh tentang cerpen ini, cobalah untuk mencari tentang apa dan bagaimana Timtim di era Orde Baru. Khususnya berkait dengan peristiwa di Santa Cruz, tahun 1991. Di tanah makam atau pekuburan itulah, cerpen ini mendapatkan saat dan tempat yang tepat untuk dijadikan pelajaran sejarah tanpa kelas,” tutur Arimbi untuk mengakhiri kelasnya di pagi itu.
“Cerpen ini memang langka.” kata Arimbi pada rekan sejawatnya.
“Maksudnya?” tanya rekannya.
“Bukan karena tidak ada yang mampu menulis. Namun untuk menuliskannya butuh imagined communities atau komunitas-komunitas terbayang,” jawab Arimbi dengan tangkas.
“Oh, ya, seperti yang ditulis Ben Anderson bahwa novel dan suratkabar adalah wahana pertama yang berkembang bagi kelahiran komunitas-komunitas terbayang?” timpal rekannya.
“Betul. Dari kedua wahana itulah gagasan tentang suatu bangsa terbentuk dalam keserempakan. Atau, dalam istilahnya Walter Benjamin, disebut “waktu mesianis”, “waktu yang homogen dan hampa”, di mana “masa silam serempak mengada dengan masa depan dalam masa kini yang bersifat instan,”” balas Arimbi dengan penuh keyakinan.
“Wah, menakjubkan sekali,” tutur rekannya.
Tentu, bukan sekali ini saja Arimbi kerap terlibat dalam perbincangan seperti di atas. Bahkan buku yang disebut di sana pun sudah sering dibacanya berkali-kali dan dikutip beberapa pernyataan yang ada di dalamnya. Buku yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa itu memang memberi pelajaran penting bahwa nasionalisme bukan sekadar dilahirkan, tetapi juga perlu untuk dihadirkan. Artinya, semangat rela berkorban demi sesama adalah pengalaman yang sejak semula dihadirkan berkat jasa kapitalisme cetak.
“Sejak mesin cetak ditemukan, maka segala sesuatu yang dirahasiakan lambat-laun mulai disingkapkan,” Arimbi berkata dengan wibawa
“Contohnya apa?”, tanya rekannya ingin tahu.
‘Yang paling populer adalah Kitab Suci,” jawab Arimbi.
“Maksudnya?” selidik rekannya.
“Kitab Suci yang dipandang sebagai satu-satunya sumber paling otentik dan hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan agamawan belaka, kini justru menjadi bahan bakar untuk merevolusikan paham kebangsaan di kalangan orang biasa. Itulah mengapa penemuan mesin cetak, khususnya dengan pencetakan bibel pertama kali di tahun 1455, menjadi terobosan teknologi tinggi yang sebelumnya tak pernah terbayangkan,” jelas Arimbi sekali lagi.
Syukurlah, dengan tetap mempraktikkan belajar tanpa kelas, Arimbi dapat menemukan yang hilang dari apa yang selama ini lebih didominasi oleh kepentingan politik sesaat dan sepihak semata daripada kebersesamaan yang mampu menghadirkan kebersamaan. Melalui berbagam pengalaman itu pula, bukan saja nasib banyak orang hilang yang dipertaruhkan, tetapi sekaligus imajinasi untuk menjadi nasionalis tanpa perlu melenyapkan nyawa orang lain, bahkan menyerahkan nyawanya sendiri demi pembayangan yang serba terbatas. Meski Arimbi hanya seorang pengajar di kampusnya, namun ia selalu ingin bercerita dan bercita-cita membangun republik ini melalui para pemudanya. Karena sejarah telah mencatat bahwa merekalah yang mengobarkan semangat untuk menjadi nasionalis. Nasionalisme memang tidak lahir dari kata-kata, melainkan justru dari tindakan yang nyata melalui pengorbanan. Seperti pernah dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidatonya yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila, bahwa nasionalisme itu sesungguhnya adalah perikemanusiaan.
Alarm di telepon genggamnya berbunyi. Arimbi tersadar. Perlahan dia bergumam, “Ah, hanya mimpi, ternyata.”
“Tak apalah. Daripada tak bisa bermimpi di tengah pandemi,” tukas Arimbi sembari bangkit dari tempat tidurnya.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Yang Tidak Biasa
Selasa, 9 Agustus 2022 15:56 WIB
Impian Arimbi
Jumat, 19 November 2021 06:25 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0





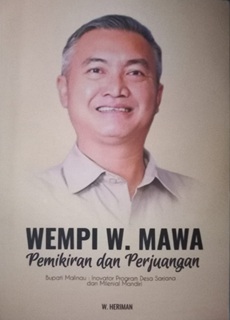

 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 99
99 0
0

















