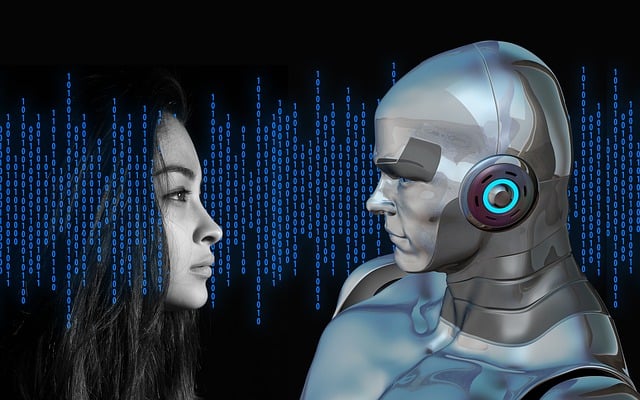Untuk sahabatku Azi Pratama
Malam ini adalah petualangan terakhir seorang lelaki tua yang pulang ke kampung halamannya. Dalam tas berat yang dipikulnya tak ada kerinduan dalam bentuk oleh-oleh atau setumpuk kisah untuk dibagikan di rumah sahabat lamanya. Dia hanya ingin pergi ke sana, setelah apa yang namanya ‘rumah’ tak tertebus lagi di masa lalunya dan tidak ditemukan di mana-mana.
Setibanya di sana, si tuan rumah baru saja menyelesaikan upacara pemakaman istrinya. Ketukan si Tamu disambut derit engsel pintu. Hal pertama yang dilihat oleh si tuan rumah adalah syal yang melilit leher tamunya. Dia kenal betul tangan siapa yang merajut kain itu. Kalau dilukiskan, maka silaturahmi ini akan tampak seperti karangan bunga tanda duka cita – masih ada warna cerah di situ, tetapi kering dan selamanya layu.
Keduanya saling memandang. Waktu seperti halnya cicak yang merayap perlahan ke arah bohlam yang terang-redup, di mana ngengat berputar-putar. Biar pun cicak berhasil menyantap ngengat itu, masih saja tak ada sepatah kata pun di antara dua sahabat lama itu. Sampai akhirnya, entah dari kilauan mata siapa, keduanya sepakat untuk berjalan bersama menempuh kesunyian malam yang membentang dari perumahan, kebun warga, hingga hutan di kaki gunung.
Jangan tanya ke mana mereka akan pergi, yang jelas keduanya melangkah beriringan menapaki jalan berbatu-batu yang mereka kenal. Dan seperti halnya jalan itu, selain penuaan tidak ada kekhasan yang berubah di antara mereka berdua. Si Petualang memiliki langkah-langkah yang mantap hingga permukaan batu yang tak karuan pun tidak menggoyahkannya. Bahkan umur tidak menghentikannya kebiasaannya yang menendang-nendang kerikil yang sama sampai ke tempat tujuan. Sedang sahabatnya terlihat canggung, dia agak tertunduk demi menghindari cuatan batu-batu kerikil yang menguji keseimbangannya.
Dua orang tua itu sempat melewati tempat peristirahatan istri salah seorangnya. Jangkrik telah menggantikan kekhusyuan doa dan isakan tangis. Si Duda sempat terdiam di depan gerbang makam, mengusap keringat dengan sapu tangan buatan istrinya, dan memperhatikan sahabatnya barang sejenak. Masih saja si Petualang lebih tertarik pada batu yang ditendangnya. Jika diibaratkan, wataknya mirip angin yang membawa serta keharuman bunga, alih-alih terbuai dan hinggap di sekitar bunga tadi seperti halnya seekor lebah.
Tak berapa lama, mereka tiba di pinggir sungai yang merendam kaki gunung. Si Petualang segera menendang batunya ke sungai, tetapi mereka tidak berhenti di sini. Mereka malah melintasi jembatan dan menerobos pagar kawat pembatas hutan seperti waktu kanak-kanak dulu. Sebelum melangkah lebih dalam, si Petualang memberikan salah satu senter untuk sahabatnya.
Di dalam hutan, degup jantung dan nafas mereka berkolaborasi dengan simfoni malam: siulan burung hincuing, burung hantu, dan sesuatu yang terusik oleh sorotan cahaya mereka. Entah apa yang menunggu mereka di antara kepungan pohon-pohon dengan dahan-dahan merunduk nyaris seperti tangan-tangan tua mereka yang meraba-raba di kegelapan.
Kian jauh ke dalam hutan, mata dan telinga mereka kian awas. Bunyi ranting patah adalah bunyi yang paling meneror di antara keliaran yang saling bersahutan di sekitar sini. Siapa pembuatnya? Babi hutan, macan kumbang, singa gunung, pemburu, penebang liar, atau malah polisi hutan? Si Petualang selalu siap untuk semua kemungkinan itu, sebaliknya si Duda memilih tersandung akar pohon dan berharap dikira bangkai. Namun, untuk beberapa saat pertanyaan tentang ‘siapa’ atau ‘apa’ menjadi tidak terlalu penting. Bunyi di belakang mereka kian mengintai. Ketika mereka sama-sama diam, bunyi itu pun berhenti, dan kembali mengendap-endap di antara bunyi langkah mereka.
Si Petualang menoleh ke arah suara itu dan menyorotkan senternya. Sesekali memadamkan dan menyalakan kembali senternya dalam hitungan tertentu. Sementara si Duda lebih tertarik mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk berjaga-jaga. Batu-batu mau pun dahan pohon yang bisa digunakannya sebagai tongkat jalan. Setiap kali dia hendak memungut batu, sahabatnya segera menendangnya, namun dia terlihat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Demikian, ketika dia menemukan tongkat yang dikiranya cocok, sahabatnya sempat menendangnya ke udara, menangkapya, kemudian melemparnya seperti tombak tanpa sasaran yang pasti.
Macan lapar dalam batin menampakan diri pada wajah si Duda, memandang tampang rusa yang tercitra di wajah si Petualang. Baginya rusa itu sedang mengunyah daun-daunan dengan tenang sekaligus dungu. Tetapi begitu matanya berbalik ke arah si pengintai misterius, si Duda memalingkan wajahnya, dan tak peduli dengan langkah-langkah ringkihnya yang kian goyah. Sejenak, dia merobohkan diri dengan lutut yang mencium tanah.
Barulah dia bangkit setelah si Petualang memapahnya. Dia bahkan memberikan sebuah tongkat dari dahan pinus. Ketika itu mereka masih diikuti sesuatu, namun pikiran mereka kini tertuju pada suara pekikan sumbang yang sayup-sayup di kedalaman hutan. Mereka bertukar pandangan, pada air muka masing-masing terbaca rasa terkejut. Keduanya hendak mengatakan sesuatu, tetapi batal, si Petualang memalingkan wajahnya, sedang si Duda menunduk. Tiba-tiba, perjalanan mereka diiringi oleh kunang-kunang yang menghambur dari semak-semak.
Dua orang tua itu mematikan senternya. Terpana. Bintang-bintang seperti turun ke bumi. Pohon, dahan, batang mati, serangga, dan tumbuhan merambat tampak bermunculan sekilas, lalu mengundurkan diri ke dalam keremangan. Barang sejenak mereka saling memandang, sementara kunang-kunang mengitari mereka hingga membentuk pusaran. Dari situ, bara api yang hidup itu berterbangan, seakan-akan terpanggil suara asing-tapi-familiar tadi.
Mereka terpancing untuk mengikuti terbangnya kunang-kunang. Tanpa penerangan senter. Si Petualangan mengambil jalan menanjak melewati bangku-bangku peristirahatan yang kini ditiduri tanaman rambat. Sedangkan si Duda mengambil jalan mendatar, semakin menanjak begitu dia mengelilingi lereng ini. Di sini dia menemukan barang-barang yang seharusnya ada di gudang, mulai dari gergaji, palu, kapak, dan pahat. Sampai akhirnya, mereka sama-sama menemukan sebuah lentera tua yang terikat tambang lapuk di sebuah batang pohon. Mereka mengambil lentera itu dengan padangan menerawang. Di dalamnya masih terdapat minyak dengan bau yang tajam. Selama perhatian mereka terserap kepada sosok lentera yang berkarat itu, kunang-kunang telah menghilang.
Mereka mencoba menyalakan senter masing-masing. Namun, sia-sia saja. Kegelapan pun mengepung keduanya.
Bau minyak tanah yang menyengat membawa sinar harapan. Mereka segera mengeluarkan korek atau pemantik api masing-masing. Beruntunglah si Petualang yang masih bisa menyalakan lentera itu, meskipun cahaya yang menerangi sekelilingnya hanya seluas kubangan air. Sahabatnya kurang beruntung, sumbu lentera itu sudah habis walau masih cukup minyak di dalamnya. Dia mencoba menggantinya dengan tambang semula tetapi tak bisa ditemukannya. Akhirnya, dia mencoba membuat obor dengan menggunakan tongkatnya dan sarung tangan buatan sang istri.
Dari kegelapan, si Pengintai misterius itu kembali menghadirkan dirinya dalam bunyi semak-semak terusik dan patahan ranting. Diikuti suara binatang yang berlari menjauh, entah itu rubah, kijang, atau lainnya. Si Petualang menengok ke arah langit yang terbingkai dahan pohon-pohon pinus, dia mencari bintang utara. Dari tempatnya berdiri, suara itu kian jelas teruma ketika angin bertiup. Seperti halnya angin yang bertiup kepada lonceng angin, si Petualang berjalan sambil bersiul. Mula-mula dalam irama tak beraturan, hingga dengan sendirinya terdengar seperti nyanyian yang sudah lama tak didengarnya lagi.
Di sudut lain, si Duda berjalan merunduk dengan tubuh gemetaran. Bisa dipastikan si Pengintai ada beberapa langkah di belakangnya. Mencicipi jejak ketakutan dari tetesan keringatnya. Dia harus cepat-cepat mencari tempat aman. Dari mulutnya yang terkatup, dia berusaha menahan teriakan yang sedari tadi bergema di dalam dirinya.
Seandainya dia lima tahun lebih muda, mungkin dia akan mencoba memanjat pohon dan menunggu pagi. Tetapi sekarang, dia harus mencoba bangkit, menenangkan dirinya dengan menggumamkan sebuah lagu. Mula-mula lagu kesukaan istrinya, namun lama-lama seiring dengan jelasnya suara yang bertepuk-tepuk dan agak memekik itu, lagunya berganti menjadi nyanyian dari masa mudanya.
Tak berapa lama kemudian suasana mencekam mendatanginya lagi. Si Duda tak sanggup bergumam lantaran suaranya sendiri membikin bulu kuduknya merinding. Rasa lelah pun menyergap bersama nafas pendek-pendeknya dan linu yang menggerogoti persendiannya. Kehadiran si Pengintai terasa lebih kentara dalam kesunyian yang tiba-tiba membungkam segala bunyi-bunyian hutan. Dalam keadaan ini, pohon-pohon dalam kegelapan tidak jauh bedanya dengan mayat-mayat yang tergantung.
Si Duda memasrahkan diri di bawah pohon hingga nyala obornya kian menyusut. Dia menoleh ke arah makam istrinya tanpa disadari. Dengan padamnya api, hutan terasa bernafas kembali. Dari kejauhan dia mendengar kedatangan sesuatu. Setitik cahaya yang kian membesar dan menyeruakan dirinya dari balik rerimbunan semak belukar. Dia terperangah dan melompat kala menyaksikan kedatangan sahabatnya. Untuk pertama kalinya, dalam naungan sinar yang buram mereka menyadari kalau keduanya menyimpan wajah masing-masing.
Malam hampir berlalu. Langit kian memekarkan kebiru-biruannya. Akhirnya, mereka tiba di tempat yang jadi sumber panggilan itu. Di hadapan keduanya berdiri sebuah kincir angin. Udara dingin di sini menyegarkan kenangan yang tertanam bersama batu-batu kali fondasi monumen itu. Kincir yang dibangun mereka berdua jauh sebelum perpisahan di hari pernikahan.
Si Petualang mendekat, mengambil sebuah batu berpermukaan datar yang tampak simetris. Cukup bagus untuk membuat sebuah prasasti kecil. Dia menyerahkan batu itu pada sahabatnya yang dibalas anggukan setelah ditatapnya dengan haru. Matahari pun terbit. Untuk menutup kisah ini, orang-orangan sawah berlengan baling-baling memberi lambaian.
[1] Aletheia merupakan kata dari bahasa Yunani Kuno yang berarti ‘ketidaktersembunyian’, kata ini digunakan oleh filsuf Jerman Martin Heidegger untuk mengungkapkan konsep kebenaran yang berkorespondensi dengan hakikat ‘Dasein’ (Ada di sana). Ada yang secara ontologis berlainan dengan ‘adaan’ (Seinde) karena Dasein dapat memikirkan tentang ‘Ada’-nya. Dengan konsep kebenaran tersebut, Heidegger hendak menjelaskan bahwa eksistensi Dasein adalah berada di dalam kebenaran itu sendiri, saking dekatnya hampir tidak bisa dikenali kembali bahkan dilupakan. Karenanya diselidiki melalui pendekatan hermeutika yang menunjukan bahwa keberadaan dalam kebenaran merupakan suatu jalinan relasional antara Dasein dengan Ada lainnya, adaan, dan secara keseluruhan menunjukan totalitas dunia yang dihuninya (welt).
Ikuti tulisan menarik Fadzul Haka lainnya di sini.