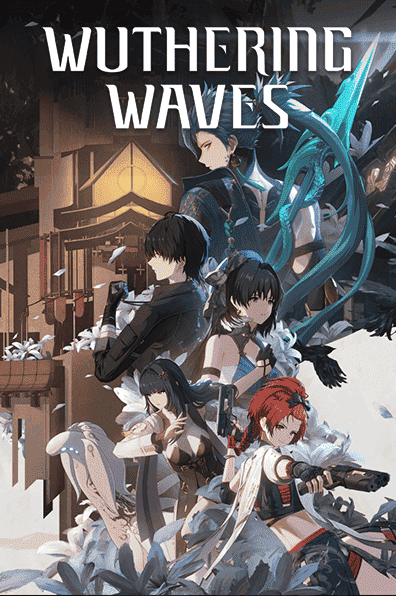Kisah Putri Duyung
Senin, 6 Desember 2021 12:31 WIB
Lihatlah lelaki itu, begitu bahagia menggandeng tangan wanita yang mulai hari ini sah menjadi istrinya. Semakin erat jemarinya terjalin di antara jemari lentik wanita itu, menegaskan kepada setiap tamu yang datang bahwa wanita itu adalah miliknya—wanitanya—dan seumur hidup tidak akan sekali pun dia berpaling. Berat untuk kuakui bahwa wanita itu punya segala hal yang menjadikannya wanita idaman—paras yang cantik, hati yang jernih, pemikiran yang cemerlang, dengan sedikit sifat manja dan posesif yang menggemaskan dan pada satu titik bisa berubah memuakkan. Lebih dari itu, dia punya satu hal penting yang dulu sempat menjadi milikku—hati lelaki itu—dan satu hal yang dulu lelaki itu janjikan akan menjadi milikku—posisi berdiri bersamanya di pelaminan.
Sudah hampir tujuh tahun berlalu sejak benang merah yang sempat menghubungkan aku dan lelaki itu terputus dan aku mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Sebuah hadiah atas kesabaranku meredam rindu yang sempat tumpah ruah, begitu kupikir awalnya. Salah, salah besar. Belum lima menit aku menikmati hadiahku, aku sudah kehilangan akal.
Garis semu yang membedakan putih dan hitam memudar. Garis tipis yang memisahkan rasa dan logika jebol. Betapa tidak adil, ingatanku tentang dia menjadi yang tidak pernah terlupakan sementara ingatannya tentangku sirna hanya dalam hitungan tahun. Betapa tidak adil, aku menjadi satu-satunya yang menepati janji sementara dia mengumbar janji yang sama kepada orang lain. Betapa ironi, aku selalu mendoakan kebahagiaannya dan kini aku begitu hampa menyaksikan dia berbahagia, sebab aku tidak bersamanya, sebab bukan aku sumber kebahagiaannya.
Aku teringat pada suatu kisah yang sering kudengar saat masih kecil, kisah putri duyung cantik jelita pewaris tahta kerajaan bawah laut merelakan segala yang dia miliki demi sang kekasih. Kurasakan jiwa putri duyung malang itu bersemayam dengan nyaman dalam diriku. Betapa bahagianya aku mendapati semesta mendukung konspirasi yang begitu saja tercipta dalam pikiranku yang kalut dengan menghadirkan sosok pahlawan untuk membantu merebut segala yang seharusnya menjadi hakku—hatinya, bukti dari janji-janjinya, posisi untuk bersanding dengannya di pelaminan.
Begitulah jadinya orang yang telah hilang akal. Ingat menjadi lupa. Salah menjadi benar.
Begitulah jadinya orang yang telah hilang akal, lupa dengan jati dirinya sendiri, sebab nurani di hati telah padam. Dan akhir dari semua ini, siapa pun bisa menebak dengan mudah—akhir kisah paling cliche sekaligus menjadi yang paling tidak terhindarkan.
**
Aku ingat kayu-kayu ini, kayu mahoni mejelma pilar-pilar kokoh dan teguh yang telah puluhan tahun menopang atap megah aula di sisi timur kawasan kampus. Pada salah satu pilar kayu itu, aku pernah mengukir namaku dan namanya dengan pensil di tengah pertunjukan teater perdana setelah dia resmi diterima sebagai anggota baru klub teater pada tahun pertama kuliah.
Tidak sampai satu minggu sejak aku tertangkap basah menyaksikan penampilan perdananya, dia mengajakku pergi ke toko buku. Masih bisa kurasakan dengan jelas debaran jantungku yang menggila mengetahui selama ini dia diam-diam mempelajariku—kesukaanku, keluargaku, jadwal kuliah, termasuk fakta bahwa aku bergabung dengan klub sastra dan perlu mencari bacaan baru untuk bahan diskusi mingguan—dari salah satu teman baikku yang ternyata satu SMA dengannya. Sejak kencan pertama kami, tidak pernah sekali pun aku ketinggalan menonton penampilannya seperti dia yang tidak pernah lupa mengajakku ke toko buku setiap akhir pekan. Pada acara kencan menjelang ulang tahunku yang kedelapan belas, dia memberiku buku terbaru dari penulis kesukaanku—edisi khusus berhadiah tanda tangan. Di antara lembaran buku itu, terselip selembar surat yang menjadi bukti tak terbantahkan—hitam di atas putih—bahwa sejak hari itu, hubungan kami tidak lagi sebatas teman biasa.
Aku punya kenangan yang cukup mengesankan dengan deretan kursi di barisan terdepan, tempat para mahasiswi berkerumun sebelum pertunjukan dimulai—saling mengaku sebagai pemilik salah satu kursi di deretan itu. Bukan karena mereka adalah pengamat seni atau orang-orang congkak yang selalu merasa layak mendapatkan yang terbaik dibandingkan orang lain, melainkan semata-mata karena mereka sama sepertiku—remaja labil yang terkena pengaruh pesona pria pemain teater yang menurut pengalamanku merupakan sekumpulan manusia paling romantis dan penuh kejutan. Mereka mampu membuat para wanita terbius oleh setiap bahasa tubuh dan ucapan yang tidak lebih dari sekadar kata-kata manis berselimut bumbu dramatisasi. Oleh mereka, kami—kaum hawa yang terjebak di tengah kehidupan yang terlalu lurus dan datar—dengan begitu mudahnya dibuat mabuk kepayang. Demi mereka, kami rela duduk nyaris dua jam dekat sorot lampu ribuan watt yang tidak hanya menyilaukan mata, tetapi juga menguarkan panas tiada tara seolah aula tanpa pendingin ruangan itu menjelma sauna atau pemanggang berukuran raksasa.
Pada kali pertama aku melibatkan diri dalam pertarungan yang selalu sukses menarik perhatian penonton itu, tidak sampai lima menit berlalu, kuputuskan untuk menyerah. Kedatangan rombongan para pemain yang bermaksud melerai pertikaian membuatku sontak melarikan diri kemudian bersembunyi, seperti pelaku kriminal yang tega meninggalkan rekannya saat tertangkap basah oleh pihak berwajib. Pilar kayu di sisi barat itulah tempat persembunyianku, tempatku menorehkan dosa—vandalisme—dengan hati berbunga-bunga. Dari situlah kusaksikan dia beraksi untuk pertama kali di atas panggung teater, memainkan peran pemuda tangguh berhati mulia yang dengan kekuatannya berhasil mengusir roh-roh jahat dari desa.
Di akhir pertunjukan, para penonton bersorak. Pecinta dan pengamat seni teater bersorak sebagai bentuk apresiasi sebesar-besarnya atas pertunjukan yang bisa dibilang cukup luar biasa untuk sekelas pertunjukan mahasiswa tahun pertama yang sebagian besar pemainnya baru pernah tampil di hadapan ratusan penonton sehingga penyakit demam panggung begitu mudah menular seperti penyakit kudis. Beberapa penonton bersorak untuk membahagiakan hati teman-teman mereka yang pada malam itu akhirnya debut sebagai pemain teater profesional cabang kampus. Beberapa penonton lain bersorak untuk merayakan kemenangan si tokoh utama. Sementara itu, para penonton barisan terdepan bersorak seperti kawanan cacing kepanasan, sebab tidak kuasa menahan diri untuk meluapkan rasa kagum sekaligus bermaksud menarik perhatian para pemain yang justru sibuk menyeka keringat dengan asal-asalan. Riasan wajah yang mulai luntur semakin terlihat tak keruan, tetapi tidak sampai mengaburkan pesona mereka yang menjadi-jadi di bawah sorot lampu.
Mudah saja aku menghindari kerumunan dengan meliuk-liukkan tubuh sebab sahutan ‘permisi’ bernada sopan tidak pernah mempan melawan kerumunan yang semakin ramai menjelang dimulainya pertunjukan teater dan kata-kata sumpah serapah kasar hanya akan menyulutkan pertikaian yang tidak perlu. Aku datang kemari untuk menonton lagi pertunjukan teater ‘Keong Mas’, pertunjukan teater yang selama ini kuingat sebagai pertunjukan teaternya yang terakhir. Tidak lagi, sebab setelah pertunjukan berakhir, aku tidak akan buru-buru meninggalkan aula sekali pun Bapak berkali-kali meneleponku, memintaku segera pulang karena sudah lewat jam sembilan malam—jam malam yang diberlakukan di rumah sekaligus batas toleransi Bapak membiarkan anak gadisnya berkeliaran di luar rumah. Sebab setelah pertunjukan berakhir, aku akan menunggunya menepati janji mengantarku pulang dengan motor bebek usang berknalpot bising kebanggaannya. Sebab setelah pertunjukan ini berakhir, aku ingin menyaksikan pertunjukan teaternya yang lain.
Di situlah kursi kebangsaanku, kursi di barisan tengah, kursi ketiga belas dari kanan maupun kiri—tempat paling strategis, sebab dari situ aku bisa melihat seluruh bagian dirinya. Lengkap, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bukan karena itu saja. Dia bilang, jika aku duduk di situ, dia bisa dengan mudah menemukanku dari atas panggung. Melihatku duduk di tengah lautan manusia seperti melihat sekuntum bunga di tengah gurun pasir, katanya. Apa kubilang. Dramatisasi adalah salah satu hal yang lekat pada pemain teater. Terlebih saat mereka sedang dimabuk cinta.
Dengan cekatan aku bangkit dan menepi ketika wanita bertubuh jangkung seenak jidat mendaratkan tubuhnya di atas singgahsanaku. Sulit dipercaya bahwa selain buta, wanita-tidak-tahu-sopan-santun itu juga tuli. Ucapanku yang berkali-kali memintanya pergi dari situ ibarat suara berfrekuensi tinggi yang hanya bisa didengar makhluk malam dan makhluk laut. Tidak ingin suasana hati berubah kacau pada malam yang indah ini, aku memilih berdiri setengah bersandar pada pilar kayu yang menjadi saksi bisu kenakalanku dulu. Dalam diam, kusaksikan pertikaian hebat di deretan kursi paling depan perlahan terurai dengan sendirinya seiring asap mulai mengepul memenuhi bagian depan panggung.
Pandanganku sesaat melihat jauh keluar jendela. Langit malam begitu cerah, tetapi bulan purnama tidak tampak. Ya, bulan purnama, salah satu hal yang kuingat dari kejadian malam itu. Barangkali dia bermukim di sisi lain langit nan luas ini, begitu pikirku yang tidak ingin pusing memikirkan hal yang tidak perlu.
Lampu padam serentak. Seorang pria berambut panjang telah berdiri tegak di tengah panggung saat lampu sorot menyala dan sukses menjadikannya pusat perhatian. Pria itu mengenakan celana hitam dengan sebilah senjata tersemat di pinggang kiri. Dadanya terumbar bebas tanpa sehelai pun benang menutupinya. Para mahasiswi di deretan depan sukses dibuatnya menjerit histeris seperti kesurupan arwah penasaran. Matanya tidak secerah dulu, sebab matahari telah hilang dari sana dan yang tersisa hanyalah awan kelabu. Dia menatap lurus ke tengah lautan manusia kemudian tertunduk sejenak.
Perasaan aneh ini, aku pusing tujuh keliling dibuatnya. Belum pernah sekali pun aku mempertanyakan kebenaran ingatanku tentang dia, termasuk segala hal tentang aksinya di atas penggung. Melihat penampilannya saat ini, dengan kumis tebal tidak terawat menghiasi wajahnya yang dipenuhi raut kesedihan, aku bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana bisa aku merasa asing dengan kejadian yang pernah kualami? Bagaimana bisa aku merasa asing dengan ingatanku sendiri?
Cukup lama dia menatap lurus ke tengah deretan penonton. Dia pasti mencariku. Dia selalu melakukannya, tetapi tidak pernah dengan sorot mata semenyedihkan itu. Aku memang sudah benar-benar hilang akal. Secepat kilat aku berlari membelah kerumunan penonton dan berdiri tepat di hadapan wanita yang merebut singgahsanaku—menghalangi pandangannya. Sejak detik itu, aku disadarkan oleh kenyataan bahwa wanita buta dan tuli itu adalah bentuk peringatan keras dari Tuhan untukku yang sudah dengan lancang ikut campur dalam urusan yang mutlak menjadi kekuasaan-Nya.
**
Bagaimana bisa aku lupa bahwa aslinya, kisah putri duyung memiliki akhir yang tragis?
Itulah akibatnya jika meminta tolong makhluk tercela yang lancang menantang Tuhan. Putri duyung ditakdirkan di laut, bukan di darat. Seperti aku yang ditakdirkan sebagai tamu tak diundang, bukan pendampingnya di pelaminan.
Dulu, aku bersimpati pada si putri duyung yang merana seorang diri, sementara sang pujaan hati sibuk merajut kebahagiaan dengan wanita lain. Setelah semua kejadian ini, setelah kusaksikan akibat kebodohanku yang tiada tanding, andai kubisa, aku rela bernasib sama seperti dirinya.
Seorang wanita berpakaian serba putih bersama rombongan pria kekar berpakaian warna senada mendekati pintu kamar di ujung lorong yang mengurung pria muda malang selama bertahun-tahun.
“Waktunya minum obat.”
Wanita pendek itu terlalu sering berbohong. Nyatanya, tidak satu pun obat masuk ke dalam mulut pria itu. Dia memilih cara lain yang lebih mudah—cara yang menyakitkan.
Benar-benar pria yang malang. Dia harus bergelut dengan empat pria kekar tanpa sedikit pun rasa kasih dan sayang terlukis di wajah mereka. Sampai kapan pun, mustahil dia bisa menang.
“Waktunya istirahat.”
Salah satu obat yang dengan paksa disuntikkan ke dalam tubuh pria itu mulai bekerja. Kontras dengan matanya yang terlihat akan segera terpejam dalam hitungan detik, mulutnya tak gentar mengoceh. Di antara ocehannya, selalu terselip satu nama. Namaku. Hanya namaku. Satu kata itu dia ucapkan berulang-ulang dengan lemah sambil telunjuknya menunjuk ke sembarang arah seolah aku berada di setiap sudut ruang yang nyatanya hanya dihuni dirinya saja. Jika bukan karena pengaruh obat, pria itu tidak akan berhenti mengoceh seolah aku nyata berdiri di hadapannya, balik menatapnya, menyahut setiap ucapannya.
Salah. Bukan pintu besi, dinding putih, atau keluarga yang tertekan menanggung malu—bukan mereka yang mengurung pria malang itu. Aku, keegoisanku, dan masa lalu bahagia yang tak sudi kulepas sebagai kenangan—kamilah pelakunya.
Pemandangan ini meruntuhkan dinding egoku sekaligus menamparku dengan kenyataan bahwa ada yang lebih menyakitkan dari melihat sang kekasih berbahagia dengan orang lain, yaitu menjadi alasan sengsara yang tak berujung.
Dan di sinilah aku, duduk memeluk lutut di depan pintu kamarnya—menangis tersedu-sedu.
**
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Aku Positif
Senin, 6 Desember 2021 12:37 WIB
La Ville Natale de Darla (Kampung Halaman Darla)
Senin, 6 Desember 2021 12:36 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0








 97
97 0
0