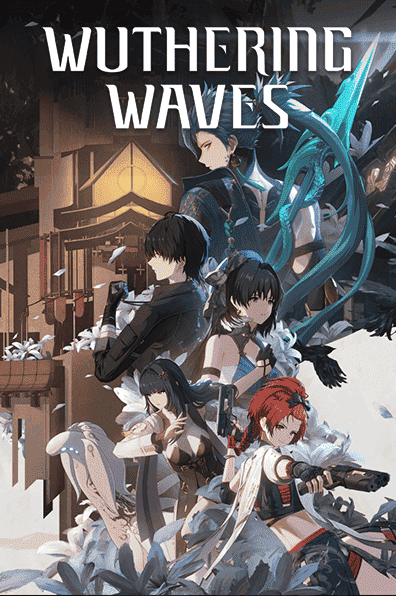Aku Positif
Senin, 6 Desember 2021 12:37 WIB
Hidupku benar-benar sempurna, sebab aku memiliki semua yang kubutuhkan untuk hidup bahagia. Hingga suatu hari, dia mengatakan, "Mas, aku positif."
12022021—12 Februari 2021—kombinasi angka cantik, tanggal cantik, tetapi tidak secantik kekasihku dalam balutan gaun sederhana serba putih lengkap dengan jilbab panjang terurai melindungi mahkotanya dan tampak serasi dengan riasan wajah nuansa merah muda. Salah satu hal yang paling kukhawatirkan sepertinya tidak akan terjadi pada hari istimewa ini, sebab langit begitu biru, cerah dengan sedikit semburat awan, tetapi tidak secerah wajah ibuku yang akhirnya mendapat kesempatan menyaksikan putra bungsunya berjabat tangan dengan calon besan di hadapan penghulu dan para saksi. Suara para saksi dan hadirin kompak menyerukan satu kata—sah!—bagaikan lambaian tangan menepuk ribuan gendang dalam hatiku. Merdu suaranya, indah iramanya.
Haru, bahagia, masih dengan sedikit rasa gugup bercampur jadi satu. Tanganku gemetar menyambut tangan sang ayah mertua, cinta pertama kekasihku. Betapa aku bersyukur mendapat kepercayaan darinya untuk membahagiakan putri kesayangannya—dunianya, segala-galanya. Lembut tangan ibunda mertua membelai kepalaku, petuah demi petuah terucap di antara isak tangis bahagia. Bendungan air mata ibuku jebol begitu saja saat mata kami bertemu. Ibu hanya mengucapkan satu kalimat: bapak pasti bangga melihatmu hari ini.
Sambil menunggu waktu salat Jumat, kuhabiskan waktu berdua saja dengan istriku. Sepupu-sepupu istriku dan ketiga kakakku kompak tidak menyia-nyiakan kesempatan menggoda kami. Bergantian, mereka melempar ledekan—terkadang siulan—dari depan pintu kamar ganti, sebab aku tidak kunjung membiarkan istriku berganti pakaian dan menyusul teman-temannya. Senyum indah istriku tepat sebelum mengakhiri panggilan video membuatku sudah merindukannya, padahal lima detik yang lalu wajahnya masih menghiasi layar ponsel. Aku tahu betul kalau setelah panggilan video selama hampir dua jam itu, aku perlu menunggu berhari-hari untuk sekadar mendengar suaranya yang merdu memanggilku—Sayang.
Hari demi hari berlalu seperti pusaran waktu tanpa ujung. Kesibukan mengurus kerjaan kantor di rumah orang tuaku yang hangat cukup membantu mengusir sepi, menumbuhkan sedikit demi sedikit rasa ikhlas sebab tidak bisa menjalani kehidupan berumah tangga yang manis nan romantis sebagaimana pasangan suami-istri pada umumnya, tetapi tetap saja tidak cukup untuk mengusir rindu yang tidak bisa diajak kompromi—semakin dilawan, semakin tak tertahankan. Teknologi tercanggih saat ini—panggilan video—tidak ada gunanya, sebab yang di seberang sana, nun jauh di salah satu tempat paling berbahaya di ibukota, tidak punya waktu untuk sekadar mengangkat panggilan telepon.
Apakah istriku sudah makan? Apakah istriku tidur dengan nyenyak? Bagaimana kalau dia tambah kurus? Ah.... pertanyaan-pertanyaan ini sungguh menyiksa.
Seperti hujan deras yang datang setelah kemarau panjang, ponselku menyerukan nada dering berbeda—nada dering khusus panggilan masuk dari istriku—setelah hampir dua minggu tidak kunjung kudengar kabar darinya. Rasanya seperti mimpi melihat tulisan ‘Istriku’ muncul di layar ponsel pada tengah hari—waktu puncak kesibukan istriku bertugas atas nama kemanusiaan.
Seperti sambaran kilat dan petir di tengah lengkung cahaya pelangi, bunga-bunga di hatiku hangus begitu mendengar istriku berucap lirih setelah jeda hening yang cukup panjang, “Mas, aku positif.”
**
Positif.
Satu kata itu layaknya seorang penipu. Serigala berbulu domba. Pembohong besar. Satu kata yang menduduki kasta tertinggi kedua setelah kata ‘Tuhan’ kini tercuri identitas dirinya, tercoreng harga dirinya, dipaksa lengser dari kedudukannya. Dia tidak lagi erat dengan hal-hal baik, indah—segala yang diharapkan. Sebaliknya, orang tidak ingin mendengar kata itu lagi dan berharap dia lenyap untuk selamanya.
Pria sepertiku—menikah di usia kepala tiga dengan seorang wanita hebat berpendirian teguh yang tidak takut kehilangan nyawa asalkan bisa menyelamatkan nyawa orang lain—pada masa seperti ini menjadi terlampau traumatis pada kata yang satu itu. Mendengarnya melesat dari mulut sang istri rasanya seperti mendengar deklarasi bahwa kematian akan datang secepatnya dan merenggut raga seseorang yang paling kami cintai, seseorang yang ingin kami bahagiakan, seseorang yang kami harap ada di sisi kami sekarang dan selamanya.
Aku tidak ingin memikirkan soal kematian, tetapi segala hal yang berkaitan dengan kematian terus saja menghantui. Mulai dari kabar duka diumumkan lewat toa masjid kompleks perumahan, berita pemakaman tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit di kota besar di Indonesia disiarkan tiada henti di televisi, sirine ambulans sahut-sahutan dari segala penjuru jalan, isak tangis mereka yang berduka mendengar kabar kematian mereka yang telah terjemput—orang tua, kekasih, saudara, teman—sampai tiba giliranku menjadi yang terisak tak berdaya menghadapi kenyataan bahwa aku tidak akan pernah lagi mendengar ibu memanggilku—Anakku.
Hampa, hanya itu yang kurasakan. Tidak ada artinya mendapat pekerjaan berpenghasilan di atas UMR dengan jaminan pensiunan. Tidak ada artinya renovasi rumah sebagai hadiah ulang tahun. Tidak ada yang berarti, sebab aku telah benar-benar gagal sebagai seorang anak—memberi ibu kesempatan melihat rupa cucu yang telah diidam-idamkan sejak hari dunia menyambut kedatanganku.
Tiada yang lebih menyedihkan dari tidak bisa berada di sisi orang yang dicintai untuk terakhir kali—melihat wajahnya, menggenggam tangannya, mengantarnya ke tempat peristirahatan terakhir, menemaninya hingga jejak air mata sepenuhnya mengering. Segala hal yang tadinya menjadi kebiasaan—seperti telapak tangan yang diposisikan terbalik—berubah menjadi larangan. Haram hukumnya, kecuali untuk mereka yang senang berurusan dengan hukum dan sukarela menjadi bahan hujatan publik.
Berita kesembuhan istriku menjadi semacam pelipur lara sekaligus pengingat bahwa sudah saatnya untukku bangkit dari duka yang beberapa hari terakhir menghadirkan mendung di rumah yang kini hanya dihuni aku seorang, sebab aku masih punya berjuta alasan untuk terus berjuang merajut masa depan. Alasan pertama dan yang utama: aku belum menepati janjiku pada sang ayah mertua.
“Sebentar lagi, masyarakat umum bisa daftar vaksin. Pastikan untuk daftar secepatnya. Lebih cepat lebih baik. Jangan ditunda.”
Ketika seisi dunia tertidur, pada saat itulah aku benar-benar terjaga. Dunia serasa hanya milik berdua—aku dan istriku. Cerita pengalaman istriku merawat orang-orang agar tidak sampai terjun ke dalam jurang kematian sebelum waktunya selalu sukses melenyapkan rasa kantuk—lebih mujarab dari segelas kafein.
“Akhir-akhir ini, aku sering memikirkan ibu,” ucapnya pada kencan malam minggu virtual kami.
Hening pun datang, tetapi bukan hening yang menyenangkan. Bukan juga hening yang menenangkan. Lebih seperti terjebak dalam hitung mundur dan sebelum waktu habis, aku sudah harus menyadari kesalahan yang kulakukan secara tidak sengaja dan dengan begitu mudahnya kulupakan atau bom waktu yang akan menjawabnya.
“Ketika mendengar kabar Ibu meninggal, kamu berharap akulah yang merawat Ibu. Kamu pikir, dengan begitu, Ibu mungkin bisa bertahan sampai sekarang.”
Istriku menghela napas panjang.
“Setiap kali mendengar kabar pasien sembuh dan bisa kembali ke keluarganya, aku merasa bersalah karena tidak bisa menemani ibu—berada di sisinya untuk merawatnya. Akan tetapi, setiap kali kehilangan pasien, aku selalu bertanya. Apakah aku kurang baik? Apakah aku melakukan kesalahan? Mungkinkah dia meninggal karena aku? Mungkinkah dia masih hidup seandainya dia dirawat orang lain, seseorang yang lebih baik—lebih kompeten—dibandingkan aku? Mungkinkah keluarganya berharap dia dirawat oleh orang lain?”
“Dik.... “
“Awalnya, kupikir, seiring dengan berjalannya waktu aku akan terbiasa dan berhenti bertanya. Ternyata tidak.”
Dari seberang sana, terdengar samar-samar suara wanita memanggil nama istriku. Perlahan terdengar semakin jelas sampai akhirnya tenggelam oleh gemuruh suara roda bergulir di atas lantai. Kontras dengan kesunyian yang menyelimuti setiap bagian rumah orang tuaku, sungguh mencekam setiap detik yang dilalui oleh istriku di tempat kerja bahkan pada waktu menjelang dini hari sampai-sampai tidak sempat menyampaikan salam perpisahan sebelum menutup panggilan telepon.
Butuh waktu berhari-hari untukku bisa perlahan-lahan menghapus kesedihan atas kepergian ibu. Tidak terbayang dan tidak akan pernah bisa aku membayangkan betapa berat rasanya menyaksikan orang-orang yang ditemui setiap hari satu per satu pergi menjemput ajal—hingga berakhir mempertanyakan kelayakan diri. Selepas sembahyang, tidak pernah aku lupa berdialog dengan Tuhan, bertanya kapan kiranya Dia akan mempersatukan aku dan istriku di bawah atap yang sama. Di tempat yang berbeda, pikiran istriku penuh dengan status pasien, keluh kesah pasien, segala hal tentang pasien sampai tidak ada cukup ruang untuk dia memikirkan diri sendiri.
Bagaimana kalau kita harus hidup seperti ini sampai beberapa tahun ke depan?
Pesan singkat pertama setelah panggilan telepon yang terpaksa diakhiri beberapa hari yang lalu itu menyulutkan firasat buruk. Seperti pertanyaan menjebak dalam ujian masuk perguruan tinggi, jawaban apa pun terasa salah, sampai di titik aku berharap punya kemampuan menghapus ingatan dan lupa pernah membaca pesan singkat itu.
Pada hari pertama perkenalan kami, aku tahu bahwa bagi istriku, karir adalah segalanya. Emas, berlian, istana, bahkan seluruh uang di dunia—dia tidak akan pernah mau meninggalkan pekerjaannya demi semua itu. Jangan tanyakan kepada kedua orang tuanya, sebab mereka telah lama menyerah dan memilih pasrah menerima kenyataan bahwa putri semata wayang kesayangan mereka tumbuh menjadi wanita yang keras kepala bukan main.
“Bagaimana kalau nanti, karena pekerjaanku, kita harus hidup terpisah cukup lama?” tanyanya waktu itu.
Tanpa ragu—tanpa berpikir panjang—aku memberi jawaban seperti yang dia harapkan dan bukan semata-mata agar perkenalan kami bisa dilanjutkan. Aku bersungguh-sungguh menerimanya berserta segala konsekuensi yang berkaitan dengan pekerjaannya.
Tiga bulan setelah pertemuan pertama kami, istriku menanyakan hal yang sama. Dia memberiku waktu tiga hari untuk memikirkan ulang kelanjutan hubungan kami dan dia akan menghormati apa pun keputusanku. Keadaannya telah berbeda, sebab hari itu dia bertanya lewat pesan singkat. Dia tidak bisa menemuiku. Dia bahkan tidak bisa lagi pulang ke rumah orang tuanya. Dengan ketidaktahuanku soal apa pun terkait situasi pandemi yang membuat seisi dunia dilanda panik didukung kata-kata persuasif dan pemikiran optimis ibu, aku bertahan dengan keputusanku memperjuangkan hubungan kami.
Karena keteguhan hatiku saat itu, kini aku terjebak dengan pertanyaan yang sama untuk ketiga kalinya. Begitu banyak hal telah berubah. Sebagian besar orang percaya kalau kondisi tidak akan semerta-merta membaik dalam hitungan hari. Beberapa orang cerdas di televisi bahkan meyakini bahwa keadaan tidak akan pernah pulih sepenuhnya, tidak akan bisa kembali seperti sedia kala.
Kalau situasinya terbalik, bagaimana? balasku.
Balasan darinya datang setengah jam kemudian.
Maksudnya?
“Seandainya Mas yang ada di sana,” ucapku begitu panggilan telepon tersambung, “tidak bisa pulang bertahun-tahun dan menanyakan hal yang sama kepadamu, jawabanmu bagaimana, Dik?”
Istriku mengerang kesal.
“Mas curang!” balasnya dengan nada kesal diakhiri tawa renyah yang sangat kurindukan. “Berbeda dong, Mas....”
Istriku menjelaskan panjang lebar soal kenapa dia kembali mengungkit pertanyaan maut itu dan aku hanya bisa terdiam—kagum sekaligus terharu oleh betapa dia sangat memikirkan perasaanku terlepas dari beban fisik dan pikiran yang tiada henti menerjangnya di tempat kerja.
“Sejatinya, hidup dan mati seseorang itu ada di tangan Tuhan, Dik,” ucapku. “Bagaimana pun akhirnya, Mas yakin kamu pasti selalu melakukan yang terbaik selama merawat pasien-pasienmu. Bayangkanlah, akan ada banyak nyawa yang bisa diselamatkan jika kamu tetap di sana.”
Bom waktu yang kukhawatirkan akhirnya meledak—meluncurkan kembang api yang begitu indah.
Suara halaman depan map saling bergesekan selagi aku menata dokumen pekerjaan ke dalam tas menambah ramai suasana bincang-bincang kami malam itu. Pikiranku terbagi antara menanggapi curhatan istriku sambil mencoba memahami pesan singkat baru dari rekan kerja di kantor. Pria yang merupakan seorang ayah dari dua putri kembar itu seminggu yang lalu pindah ke ruang kerja yang sama denganku. Dia menjelaskan soal kondisi keluarganya dengan bahasa yang sulit dimengerti. Belum lagi dia mengetik pesan dengan kombinasi huruf kecil dan kapital yang diletakkan tidak pada tempatnya ditambah tanda baca porsi berlebihan hampir di setiap akhir kalimat. Di antara deretan kata yang tertulis di sana, terselip kata keramat itu—tertulis dengan huruf kapital dan diakhiri barisan tanda baca seru.
Malam itu, aku terjaga hingga pagi. Daripada mempersiapkan diri menerima kenyataan bahwa kemungkinan besar aku telah beberapa langkah lebih maju dengan kematian, aku justru tenggelam memikirkan cara mengabari istriku: Dik, Mas positif.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Aku Positif
Senin, 6 Desember 2021 12:37 WIB
La Ville Natale de Darla (Kampung Halaman Darla)
Senin, 6 Desember 2021 12:36 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0








 98
98 0
0