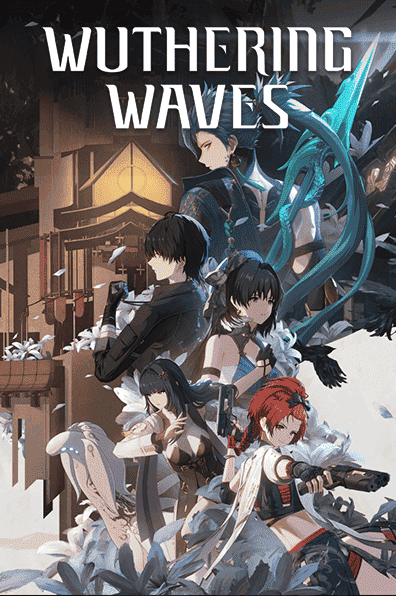La Ville Natale de Darla (Kampung Halaman Darla)
Senin, 6 Desember 2021 12:36 WIB
Paris adalah kota impian. Di sana aku punya kesempatan mengubah mimpi menjadi kenyataan. Akan tetapi, ada satu hal yang mustahil untuk kulakukan di sana: memecahkan misteri tentang siapa aku sebenarnya. Hanya ada satu tempat di mana aku bisa mendapatkan jawabannya: kampung halaman.
Semakin erat aku memeluk tubuh yang kebanjiran keringat dingin. Mataku perih setelah dipaksa terjaga semalaman oleh rasa mual karena beragam aroma menguar dari deretan kursi bis yang terguncang dengan brutal—memberi sensasi layaknya wahana roller coaster. Aku tidak punya pilihan lain. Bis menjadi satu-satunya transportasi umum yang bisa menjangkau daerah terpencil.
‘Village de Fleur et Pluie’ ditulis elok menggunakan cat merah menyala kontras dengan latar papan kayu putih mulai tampak dari kejauhan. Perjalanan beratus-ratus mil melintasi jalan berliku yang diapit hamparan perkebunan dan hutan—tanjakan, turunan, tikungan curam tidak terhitung jumlahnya—akan segera berakhir. Rasa mual perlahan surut begitu teringat dengan kenangan masa kecil di sebuah desa yang dikenal karena keindahan lembah dan bukit oleh hamparan bunga pada musim semi.
Aku beranjak dari kursi lalu dengan sedikit kepayahan menyeret koper ke arah pintu. Pria muda bertubuh kekar yang duduk di kursi seberang melirik sesaat ke arahku—tidak berniat memberi pertolongan. Sebaliknya, pria tua berpakaian lusuh dengan cekatan beranjak kemudian lekas menahan koperku agar tidak jatuh saat bis terguncang melewati turunan curam setelah tanjakan yang menukik. Akan tetapi, apa daya. Pria malang itu lekas kembali ke kursinya lalu sekuat tenaga menumpahkan sisa isi perut ke dalam kantong.
Dengan barang bawaan sebanyak ini, orang-orang mungkin mengira aku kabur dari rumah. Tidak, sama sekali tidak. Aku mendapat restu penuh dari orang tua untuk meninggalkan kota Paris dan segala yang kumiliki di sana—teman, nama besar, pekerjaan, dan seorang sahabat yang sering salah dikira sebagai kekasihku—untuk kembali ke suatu tempat yang dianggap oleh sebagian orang Prancis sebagai negeri dongeng—fiksi belaka.
“Bienvenue au village, Madame,” ucap si supir bus berwajah jenaka dengan ramah. “Passe une bonne journée.”
“Au revoir, Monsieur, merci. Bonne journée à vous aussi.”
Udara sejuk di awal musim semi dengan semerbak aroma bunga, embun pagi, dan tanah basah sisa hujan semalam—aku merindukan semuanya. Desa yang dihuni kurang dari seribu penduduk ini memiliki semua yang tidak bisa kutemukan di kota Paris. Itulah salah satu alasan aku kembali selain fakta bahwa kepingan diriku terjebak di desa ini—enggan ikut denganku bertolak ke ibukota sepuluh tahun yang lalu—dan aku ingin merangkainya kembali.
Gapura atau yang lebih dikenal dengan sebutan ‘Gerbang Selamat Datang’ tampak sama seperti saat terakhir kali aku melihatnya—salah satu tiang penyangganya sedikit miring dengan bunga rambat menghiasinya seperti benalu menolak berpisah dengan inangnya. Di ujung jalan setapak menurun di muka gapura, jembatan batu berdiri kokoh melintasi sungai terbesar di desa—Sungai Sans Nom. Nenek moyang kami membangun jembatan itu untuk menyatukan wilayah desa dengan jalan besar. Pada musim panas, ketika air sungai surut, peternak akan menggiring hewan ternaknya menyusuri jalanan lebar yang membelah aliran Sungai Sans Nom. Orang-orang tua di desa mengatakan bahwa Sungai Sans Nom mengalir hingga ke kota Paris. Entah memang benar begitu atau hanya mitos yang dibesar-besarkan agar anak-anak desa terdorong menuntut ilmu sampai ke kota Paris untuk membuktikan kebenarannya.
Dari ujung jembatan, berdiri deretan rumah sederhana berdinding batu bata dengan hamparan bunga menghiasi pelataran rumah. Pagar kayu rendah bercat putih menjadi pembatas pelataran rumah dengan jalan beraspal. Bersih dan asri, namun terasa sedikit sesak karena beberapa rumah baru berdiri di atas tanah yang dulunya merupakan tanah kosong tempat digelarnya pasar malam.
Aster si Sulung mencetuskan ide mengunjungi pasar malam tiap Sabtu. Bukan untuk bermain permainan arkade, naik wahana, atau wisata kuliner. Bukan juga untuk membantu menjual kerajinan tangan karya Madame Martin—seperti yang dijanjikan—melainkan untuk berkenalan dengan murid-murid akademi khusus putra. Aster lebih tua tiga tahun dariku. Jadi, aku baru berusia sepuluh tahun saat Aster pertama kali mengajakku berkenalan dengan teman-temannya. Saat itu, tidak ada hal lain terlintas di pikiranku selain kecurigaan makanan di kafetaria sekolah mereka diracuni sehingga sebelah mata mereka sering sekali berkedip, nyaris seperti latah. Semuanya berubah sejak malam ulang tahunku yang kedua belas. Aster memberiku hadiah dan surat titipan dari salah satu temannya—pria sederhana berkemeja kotak-kotak yang pada pertemuan pertama kami membuka pembicaraan dengan membanggakan pekerjaan ayahnya sebagai tukang kebun yang pernah diberi kepercayaan oleh kepala desa untuk merapikan taman alun-alun desa.
Pada suatu hari, Ebony si lugu yang ternyata punya bakat berkhianat melaporkan kenakalan kami pada Madame Martin. Dahlia dan Fern—mereka lahir di tahun yang sama dengan Aster, tetapi telat masuk sekolah—membela Aster habis-habisan. Pipi Dahlia yang tembam memerah ketika marah dan Fern kelepasan mengucapkan kata kasar sehingga Madame Martin menghukumnya membersihkan kamar mandi. Sebagai hukuman, kami—kecuali Ebony—diwajibkan belajar merajut dan dilarang pergi ke mana pun selain sekolah dan pasar, itu pun dengan ditemani Madame Martin. Aku memberikan syal rajutan buatanku kepada Madame Martin sebagai hadiah ulang tahun. Dia mengharu biru menerimanya dan sepanjang musim dingin tahun itu tidak pernah mengenakan syal lain selain syal pemberianku. Saat tahu salah seorang pria muda di desa kami memiliki syal rajutan yang sama persis dengan yang kuberikan padanya, Madame Martin marah besar. Kami saling diam selama hampir seminggu penuh. Pada musim dingin tahun-tahun berikutnya, Madame Martin tidak pernah mengenakan syal pemberianku lagi.
Begitu lulus sekolah menengah, Aster, Dahlia, dan Fern dikirim oleh Madame Martin ke akademi perawat di suatu kota nun jauh di daerah barat. Entah dari mana Madame Martin mendapat uang sebanyak itu sampai bisa menyekolahkan tiga gadis desa di sebuah akademi bergengsi di kota, padahal saat itu donatur yayasan panti yang sebagian besar anggota parlemen daerah berhenti mengirimkan uang. Mereka merasa menjadi donatur yayasan panti tua di sebuah desa terpencil bukan lagi strategi kampanye yang menjanjikan. Satu hal yang kuingat, sejak keberangkatan Aster, Dahlia, dan Fern, Madame Martin melarang aku dan teman-temanku bermain di rumah pohon di kebun samping rumah kami. Selang satu minggu, rumah pohon dan pohon eboni tua itu dirubuhkan. Tidak lama setelahnya, pagar tinggi dipasang mengelilingi kebun tempat kami membangun kerajaan kami. Ya, Madame Martin telah menjualnya untuk biaya sekolah ketiga kakak kami.
Sementara itu, lulus dari sekolah menengah, Madame Martin menyekolahkan kami ke sekolah khusus putri yang berada agak jauh dari rumah. Kami harus naik bis pagi-pagi sekali kalau tidak ingin terlambat. Karena masalah finansial, kami tidak punya kesempatan merantau seperti ketiga kakak kami. Di sekolah itu, sebagian muridnya datang dari kota. Beberapa dari mereka terlalu sombong dan suka pura-pura bodoh dengan menanyakan kenapa marga keluarga kami sama, padahal lahir di tahun yang sama—hanya berbeda tanggal dan bulan—dan tidak satu pun fitur fisik kami menjelaskan bahwa kami merupakan saudara kembar.
Aku, Ebony, Olive, dan River bernasib sama—tidak seorang pun menginginkan kami selain Madame Martin. Wanita tua itu mengizinkan kami menggunakan namanya untuk keperluan administrasi sekolah. Kami berbeda dengan Ellen Granger, Gwen D’aureville, dan Vivienne Barbeau. Mereka bertiga juga dibuang, tetapi mereka tidak sudi disamakan dengan kami. Mereka merasa lebih tinggi, sebab menyandang nama orang tua kandung mereka. Mereka berdalih, suatu saat nanti, ketika sudah dewasa, mereka akan menjelajahi seisi negara Prancis—atau bahkan seisi dunia, kalau perlu—untuk mencari tahu keberadaan keluarga mereka.
Belum lama ini kudengar Gwen bertemu dengan ayahnya di Toulouse. Rupanya dia korban penculikan anak oleh kelompok buronan yang dibayar oleh saingan bisnis ayahnya. Ya, Gwen rupanya anak konglomerat.
“Aku yakin, sebenarnya aku terlahir sebagai orang terhormat.”
Aku ingat ucapannya tiap kali memamerkan liontin cantik berhiaskan ukiran namanya. Ucapan adalah doa, memang benar adanya.
Kata Gwen, keluarganya berniat membalas budi Madame Martin dengan mengirim uang, tetapi wanita itu menolak.
Setahun yang lalu aku bertemu dengan Vivienne di Paris. Dia bekerja di salah satu butik ternama dan menyesal telah berusaha mencari keluarganya. Ayah Vivienne sudah meninggal saat dia masih kecil karena sakit berat. Tidak sanggup menjadi tulang punggung keluarga, ibu Vivienne yang seorang pecandu alkohol meninggalkan anak semata wayangnya di stasiun hanya dengan bekal piyama dan selimut usang dengan bordir namanya. Vivienne yakin, Madame Martin yang kebetulan sedang bertolak ke Paris tidak sengaja menemukannya dan memutuskan membawanya ke desa.
Seperti dugaanku, Ellen menemukan keluarganya di Inggris. Aku yakin sejak awal kalau Ellen bukan orang Prancis. Setiap bagian wajahnya menegaskan bahwa dia datang dari Irlandia. Ellen memilih tinggal bersama keluarganya, bekerja sebagai penjaga toko untuk membiayai sekolah saudara-saudaranya yang masih kecil.
Langkahku terhenti di depan sebuah rumah di ujung persimpangan jalan—rumah dengan alamat yang tertera pada bagian depan surat yang kuterima tidak lama setelah aku bertolak ke Paris, dibawa pergi sepasang suami-istri yang telah lama mendambakan anak perempuan. Mendengar berita aku diadopsi keluarga kaya, semua orang di desa sepakat menilaiku sebagai anak yatim piatu paling beruntung. Mereka tidak tahu betapa berat hatiku meninggalkan kampung halaman dan seorang pria yang berjanji mengajakku pergi bersama ke pesta dansa sekolah pada musim gugur sepuluh tahun yang lalu. Tidak ada yang peduli, kecuali satu orang.
“Maaf, aku tidak membalas suratmu,” Eloise kembali dari dapur dengan segelas minuman hangat. “Bagaimana Paris, Darla?”
“Tidak apa-apa, El. Sudah kukatakan, aku tidak ingin membebanimu,” Aku mengesap sedikit minuman beraroma rempah racikan Eloise. “Paris.... c’est incroyable! La tour Eiffel est belle.”
Eloise terdiam memandang lantai. Sesekali dia kedapatan menatapku penuh arti.
“Ada apa, El?” tanyaku. “Sesuatu terjadi saat aku pergi?”
“Kudengar.... Jesper pergi ke Paris tidak lama setelah menemui Madame Martin. Dia pasti mencarimu.” Eloise menduga-duga.
“Jesper menemui Madame Martin?” Aku hampir saja tersedak. “Kapan?”
“Beberapa hari sebelum pesta musim gugur sekolah.... mungkin dua hari setelah kau pergi?” Eloise mencoba mengingat-ingat. “Aku tahu dari ibuku. Kebetulan dia sedang mengunjungi Madame Martin.”
Garis wajah Eloise berubah. Aku buru-buru menjemput tangannya.
“Aku turut berduka, El. Madame Lavigne tidak perlu lagi menahan rasa sakit.”
Madame Thea Lavigne mendedikasikan hidupnya sebagai juru melahirkan andalan di desa kami. Madame Lavigne bertemu Madame Martin di akademi kesehatan. Sejak saat itu, mereka tumbuh dewasa bersama sebagai sahabat dekat. Sulit dipercaya, Madam Lavigne memilih mengingkari janji pada sang sahabat menjelang waktu kepergiannya demi aku.
Eloise buru-buru menyeka air mata di pipi kemudian menepuk punggung bayi mungilnya yang mulai menangis.
“Tentang Jesper....” Eloise mengalihkan topik pembicaraan. “Kau tidak bertemu dengannya?”
Aku menggeleng.
“Paris kota yang besar, El. Dan mungkin dia pergi ke Paris bukan untukku.”
“Tidak mungkin,” sanggah Eloise. “Dia tergila-gila padamu. Kalau tidak, mana mungkin dia berani mengirimi Madame Martin surat, memintanya tidak menghukumu karena berkirim surat dengannya?”
“Bagaimana kau tahu soal....”
“Monsieur Bodin, si kepala pos sekaligus biang gosip desa ini.” Eloise menghela napas. “Mungkin kau sudah lupa, Darla. Di desa ini, semua orang tahu tentang semua orang.”
Senyumku lepas begitu saja. Di dunia ini, hanya sebagian kecil kisah cinta pertama yang berakhir bahagia. Paris menjadi saksi bahwa kisahku dan Jesper bukan salah satunya.
“Sampaikan salamku pada Noel.”
“Tentu saja. Hei, tentang Sungai Sans Nom,” Eloise tersenyum iseng, “apakah benar bermuara sampai ke Paris?”
Aku berdecak kesal. “Maaf, El. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan soal sungai.”
Dari rumah Eloise, aku melanjutkan perjalanan ke utara, menyusuri jalan lurus sampai tiba di perempatan. Dari sana aku berbelok ke kanan. Di ujung jalan itu berdiri rumah tua dikelilingi bangunan baru—megah nan agung, menggantikan kerajaan kecil yang kubangun dulu.
Madame Martin susah payah mengangkat ujung selang yang diarahkan ke deretan pot bunga nan indah yang menghiasi pelataran rumah—ada mawar, petunia, lili, dahlia, dan aster. Dia menuangkan sedikit air pada pot yang menggantung—pot bunga anggrek—lalu menyibukkan diri memangkas rumput liar. Melingkar di lehernya syal pemberianku.
Ketika mata kami tidak sengaja bertemu, tangisnya pecah seketika.
“Darla....”
Begitu yang kubaca dari gerak bibirnya yang bergetar.
Madame Martin menatap nanar surat yang Madame Lavigne kirimkan padaku. Marah, menyesal, sedih, malu, semuanya melebur jadi satu, terbaca jelas dari sorot kedua matanya yang layu karena usia.
“Aku melakukan kesalahan. Aku minta maaf.”
“Tidak apa-apa, ma mère,” ucapku pelan. “Kau merahasiakan soal keluarga Leroy dan mengirimku pergi ke Paris, semua itu kau lakukan demi aku.”
Aku mengusap punggung tangan Madame Martin.
“Sekarang giliranku. Aku kembali ke desa ini untukmu, ma mère.”
Madame Martin buru-buru menarik tangannya lalu melangkah dengan tergesa-gesa ke dalam rumah. Dia kembali dengan wajah basah oleh air mata dan selembar kertas yang terlihat menyedihkan: kusut dan dipenuhi perekat.
“Aku takut kau.... jadi.... maafkan aku....”
Aku sudah lebih dulu memeluk Madame Martin sebelum dia selesai menjelaskan.
“Tidak apa-apa,” ujarku berkali-kali dengan lirih sambil sebelah tanganku meremas kuat surat dari Jesper: dia mengajakku bertemu di Jembatan Alexander Lii untuk yang terakhir kali sebelum bertolak ke Inggris untuk memulai hidup baru.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Aku Positif
Senin, 6 Desember 2021 12:37 WIB
La Ville Natale de Darla (Kampung Halaman Darla)
Senin, 6 Desember 2021 12:36 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0








 99
99 0
0