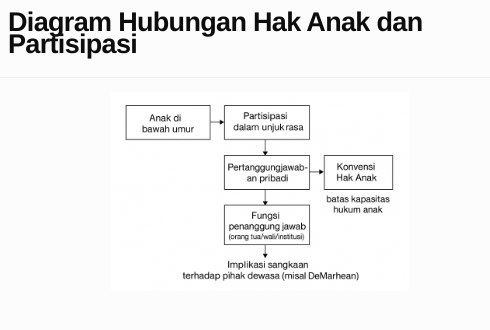Prasangka
Selasa, 7 Desember 2021 08:14 WIB
cerpen Prasangka berkisah tentang seorang gadis yang merasa iri dengan teman sekelasnya. Ia merasa hidupnya tidak seberuntung temannya itu. Namun, kenyataannya hidupnya jauh lebih beruntung.
Di sekolah, saat yang lain berjalan ke kelas masing-masing sambil bergandengan tangan dengan temannya, aku adalah murid yang selalu terlihat murung, beradaptasi sangat baik di bawah bayangan sampai-sampai orang lain suka tak sadar bahwa aku ada di sana. Aku menyatu dengan bayangan.
Tepat di seberang lorong tempatku berdiri, di dekat banyak loker yang ditempeli stiker warna-warni, berdirilah seorang gadis dengan senyum paling memikat yang pernah kulihat, bahkan paling menawan di sekolah ini.
Namanya Alora, ia sekelas denganku. Setiap hari, banyak orang mengerumuninya. Dia terlihat seperti putri yang sedang dikagumi oleh para pelayannya. Dia selalu bersinar, tak peduli dia berada dimana atau bersama siapa. Sangat sempurna, ia terlihat seperti malaikat.
Diam-diam aku mengaguminya. Meskipun aku sangat mengaguminya, rasa benciku terhadapnya juga tak kalah besar. Dia selalu tersenyum, selalu ramah kepada orang lain yang ditemuinya. Seolah-olah dia tidak pernah merasakan hampa, merasakan hidupku. Aku iri. Kadang aku berpikir mengapa dunia bisa begitu tidak adil, mengapa ada orang seperti dirinya, mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada aku. Aku menjadi muak setiap melihat hal itu.
Bel sekolah sudah berdering, waktunya jam pelajaran dimulai. Seperti biasa, aku melesat secepat kilat menuju kelas, buru-buru duduk di kursi belakang agar tak ada yang bisa mengambilnya. Berjalannya waktu, kelasku sudah mulai penuh dengan murid-murid, membuat ruang kelas menjadi semakin ramai. Beberapa menit kemudian, Alora muncul bersama para ‘penggemar’-nya. Sungguh mencengangkan betapa banyaknya murid yang menawarkan kursi mereka pada Alora, bagaimana mereka bersikap sebaik mungkin untuk mendapatkan perhatiannya.
Pelajaran hari ini adalah Bahasa Indonesia, pelajaran yang menurutku menyenangkan jika topiknya tepat. Kami membahas tentang rasa syukur. Topik ini sungguh tidak menyenangkan bagiku. Alasannya karena kami harus mengerjakannya secara berpasangan.
Coba tebak aku dipasangkan dengan siapa? Alora Miller, sang putri.
Saat tahu aku dan dia berpasangan, Alora menolehkan kepalanya ke arahku, tersenyum kecil. Aku tak tahu maksud dari senyumannya itu, tetapi aku membalasnya.
Aku belum pernah berbicara dengannya, sebagian besar karena aku berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Aku tak bisa membayangkan diriku berdiri bersebelahan dengan Alora, tidak saat lingkungan kami berbeda jauh.
Saat bel pulang sekolah, terdengar orang yang meneriakkan namaku dari ujung koridor.
“Reina! Tunggu!” Alora meneriakkan namaku sambil berlari menghampiriku. Anehnya, setelah dia berhenti berlari, deru napasnya jadi sungguh tak karuan. Padahal dia hanya berlari beberapa meter ke arahku. Dia seperti habis lari marathon.
“Hai, Alora! Ada apa?” tanyaku, agak kaget karena dia ternyata mengenalku.
“Kapan kau ada waktu mengerjakan tugas Bahasa Indonesia?” tanyanya ramah segera setelah napasnya stabil.
“Aku tak pernah sibuk selain sekolah, jadi kapan saja di luar jam sekolah mungkin?”
“Bagaimana kalau aku ke rumahmu Sabtu ini?” matanya berbinar menunjukkan semangat.
“Tapi kau tidak tahu letak rumahku” aku mengingatkan.
“Aku punya data semua alamat teman-teman sekelas kita. Aku bisa mencari alamatmu di sana.” Suaranya yang selembut lantunan lagu ninabobo entah mengapa membuatku merasa tenang. Aku mengangguk pelan sambil mengacungkan satu ibu jari. Alora tersenyum lebar sambil menunjukkan gigi-giginya.
“Baiklah kalau begitu. Sampai jumpa besok!” Dia pergi melewati pintu sekolah, menghilang ditelan kerumunan murid-murid.
Besok? Astaga, aku lupa hari ini hari Jumat. Berarti besok merupakan pertemuanku dengannya, si itik buruk rupa dengan si angsa, aku tak bisa membayangkannya.
Tetapi toh hari itu datang juga.
Sekitar jam 10 pagi, terdengar suara Alora di depan pintu rumahku. Aku berlari cepat menuju pintu, takut membuatnya menunggu terlalu lama meski hanya beberapa detik.
“Hai, Reina!” Alora melambaikan tangannya antusias.
“Hai,” aku langsung menyuruhnya masuk dengan nada kikuk yang terdengar aneh di telingaku.
Ayah dan ibuku sedang ke kantor, mereka tidak biasanya pergi kerja hari Sabtu, tetapi kata mereka kerjaan kantor sedang menumpuk, jadi mau tak mau mereka berangkat kerja pagi-pagi sekali. Aku jadi sendirian di rumah.
“Aku suka rumahmu, warnanya cantik” kata Alora saat ia duduk di sofa.
“Benarkah? Aku rasa rumahku cukup berantakan,” jawabku. Ah, aku sungguh payah dalam berbincang-bincang. Tidak ada sedikit pun suara yang keluar dari mulut kami selama beberapa menit.
“Eh, Reina, menurutmu apa yang sebaiknya kita lakukan untuk tugas ini?” tanya Alora.
Aku agak tak enak hati karena sepertinya dia bersusah payah mencari topik untuk mencairkan suasana.
“Hmm, karena tugas kali ini berisi tentang rasa syukur, aku rasa kita bisa menceritakan hal-hal yang membuat kita, kau tahu, senang karena diberi kehidupan” kataku mengusulkan.
“Ide bagus. Baiklah, kita langsung mulai saja. Apa yang membuatmu senang untuk menjalani hidup?” tanya Alora benar-benar penasaran. Untuk sesaat aku diam, tak tahu harus menjawab apa.
“Bagaimana kalau kau duluan saja yang jawab? Aku sedang memikirkan kata-kataku” aku tertawa kecil, menutupi rasa canggungku.
“Oke, aku… bersyukur karena masih bisa bangun di pagi hari, dan bernapas dengan baik setiap paginya. Kurasa itu masuk daftar hal-hal yang selalu aku syukuri,” ucap Alora.
Aku terkejut saat dia menjawab seperti itu. Aku tidak menyangka dia bisa begitu… merendah, bersyukur pada hal-hal kecil.
“Sekarang giliranmu!” Alora berbicara dengan nada menyemangati.
“Oh, a-aku tak terlalu memikirkan tentang rasa syukur, aku tak tahu harus menjawab apa.” Akhirnya aku mengatakan yang sejujurnya.
“Sungguh? Oh, cobalah pikirkan sebentar. Aku yakin kau punya banyak hal untuk disyukuri. Atau setidaknya hal-hal yang membuatmu tersenyum.”
“Masalahnya hidupku tak seindah itu, Alora. Hidupku tidak dipenuhi oleh orang-orang yang bersedia melakukan apa saja demi mendapatkan perhatianku. Hidupku berbeda jauh dari hidupmu!” Dari matanya yang membelalak kaget, dia sepertinya tersinggung. Ia terdiam selama beberapa saat, menatapi lantai.
“M-maafkan aku, sungguh aku tak bermaksud begitu. Aku hanya… aku iri melihatmu yang dikelilingi oleh banyak orang, aku iri melihatmu yang selalu tersenyum, seperti kau tidak memiliki kesedihan apa pun.” Mengejutkan bagaimana dengan mudahnya aku bisa berkata jujur di depannya, aku tak pernah bercerita seperti itu sebelumnya.
Tiba-tiba saja, dia tersenyum, ada kesedihan di sorot matanya.
“Hidupku tidak sebahagia itu. Sesungguhnya, ada banyak hal yang kusembunyikan dari orang-orang. Tetapi itu tidak berarti bahwa hidupku jadi lebih baik daripada kau” katanya parau.
Aku diam sebentar, mencoba mencerna perkataannya baik-baik. Aku tak tahu apakah dia sungguh bermaksud begitu atau dia hanya mencoba untuk menghiburku, tetapi itu berhasil.
“Ya, aku tahu. Mungkin aku hanya perlu mencarinya sedikit lagi, mencari alasanku untuk bersyukur,” kataku pada akhirnya. Tanpa kusadari, dia langsung menggenggam tanganku.
“Kau pasti bisa menemukannya, Reina.” Dia tersenyum manis. Sekali lagi aku terkejut dengan perkataannya, kalimatnya cukup mengubah pandanganku terhadapnya. Dia bukanlah anak populer sombong yang membanggakan keberadaannya, dia hanya ramah, baik.
“Kau tahu, anehnya aku merasa nyaman berbicara denganmu. Seharusnya kira berteman sejak dulu,” ucap Alora tertawa.
“Ya, aku tak pernah berpikiran seperti itu sebelumnya. Hei, aku harus main ke rumahmu kapan-kapan. Rumahmu ada di mana?” tanyaku antusias.
“Ah, nanti aku beritahu saat kau mau datang.”
Dari nada bicaranya, Alora seperti menghindari pertanyaanku. Kalau kulihat-lihat, wajahnya menjadi lebih pucat dari sebelumnya. “Hmm, ada yang tidak beres,” pikirku.
“Alora? Kau baik-baik saja? Wajahmu pucat,” ada nada kekhawatiran dalam suaraku.
“Ya, tentu, tentu. Mungkin karena cahaya yang kurang pas atau semacamnya” nada suaranya juga berubah. Dari gerak-geriknya, dia lemas.
“Hei, bagaimana kalau kita melanjutkan diskusi ini besok? Senin mungkin? Ada beberapa hal yang harus kuurus di rumah,” ucap Alora bangkit dari sofa, menuju pintu dengan terpanting-panting.
“Oh, baiklah. Apa kau bisa pulang sendiri? Kau yakin kau baik-baik saja?” aku membukakan pintu rumah untuknya, mataku masih menatap khawatir ke arahnya.
“Aku akan pesan ojek untuk pulang. Tak usah khawatirkan aku. Sampai ketemu Senin.” Ia melambaikan tangan dan berjalan menjauh. Saat kulihat dia menaiki ojek lewat jendela, hatiku mulai tenang.
Tetapi perasaan khawatir terus melanda pikiranku.
Hari Senin tiba, dan dia tidak ada di sekolah, membuat prasangka-ku semakin menjadi-jadi. Di sekolah, waktu terasa berjalan pelan, bahkan seperti tidak berjalan sama sekali. Mati-matian aku menunggu jam sekolah usai sambil menggigiti jariku. Saat bel sekolah berdering, aku segera berlari ke ruangan tata usaha.
“Permisi, maaf Pak, Bolehkah saya meminta data alamat siswa sekolah ini?” tanyaku pada seorang bapak pekerja bagian administrasi yang berada di sana.
“Tentu, kau mau tahu alamat siapa?”
Bapak itu tampak kaget karena suaraku terlalu keras.
“Alora Miller”
Bapak itu membuka satu buku tebal berisi seluruh alamat siswa, mencari nama Alora, dan menuliskan alamatnya pada secarik kertas. Aku mengambil kertas itu buru-buru dari tangannya, meninggalkannya setelah mengucapkan terima kasih.
Ban taksi berdecit nyaring saat pengemudinya menghentikan mobil itu secara paksa. Aku keluar dari taksi, memandang sebuah rumah dengan mata membelalak. Rumah itu besar, ukurannya mungkin tiga kali lebih besar dari rumahku, dan luar biasa megah. Di sinikah Alora tinggal? Ternyata dia jauh lebih beruntung daripada yang aku kira.
Tetapi saat aku melihat lagi alamat yang ada di kertas, ternyata bukan itu rumahnya. Aku berbalik, memunggungi rumah megah itu dan menghadap tempat yang sama sekali berbeda. Tempat itu setengah lebih kecil dari ukuran rumahku, keadaanya berantakan, seperti tidak dihuni sama sekali. Tanaman menjalar di mana-mana, catnya mengelupas karena sudah tua. Alora tidak mungkin tinggal di sinikan? Kuharap aku salah alamat.
Kenyataannya aku benar, alamat yang tertera di sana dan di kertas sama. Dengan hati berdegup kencang kuhampiri pintu rumahnya, dan mengetuknya tiga kali. Kumohon jangan dibuka, kumohon jangan Alora yang membukanya.
Jantungku membeku saat aku melihat wajahnya membuka pintu, Alora melihatku dengan syok. Tetapi bukan keberadaannya saja yang membuat jantungku berhenti, ada selang mengitari hidungnya! Seperti selang yang dipakai seseorang saat sedang kesulitan bernapas.
“Alora? Apa yang terjadi denganmu?” suaraku bergetar.
Sebelum menjawab pertanyaanku, dia membawaku masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu. Suaranya parau saat membuka mulut.
“Kejutan, aku tidak menyangka kau akan melihatku seperti ini” dia tertawa lemah.
Dengan pertanyaan-pertanyaan muncul di kepalaku, aku berkata, “Beritahu aku!”
Alora mulai bercerita.
“Kata dokter, aku terkena semacam penyakit langka, menyerang sistem pernapasanku. Aku tak bisa disembuhkan, karena tidak ada obat untuk menyembuhkanku”
“Apa? Lalu siapa yang merawatmu selama ini?” tanyaku cemas.
“Ibuku yang selama ini merawatku. Ayahku sudah meninggal sejak usiaku tiga bulan. Ibuku bekerja sebagai pembantu rumah tangga harian. Biasanya ibuku pulang malam. Kau tahu, aku mendapat ‘hak istimewa’ dari sekolah agar bisa belajar gratis karena prestasi akademisku. Sepertinya itu salah satu keuntungan dari hidupku” lagi-lagi ia tertawa.
“Bagaimana dengan orang-orang di sekolah? Kau tak memberitahu mereka? Apa teman-temanmu tahu?”
“Tidak, hanya kau dan kepala sekolah yang tahu ini, dan mungkin juga beberapa guru dan petugas sekolah,” dia berkata seolah-olah masalahnya ini sepele.
“Apa kau baik-baik saja sekarang?” tanyaku lagi.
“Belakangan ini keadaannya makin parah. Tiga tahun yang lalu, dokter bilang perkiraan hidupku hanya kurang dari enam bulan. Aku bersyukur saat ini aku masih tetap bernapas,” ia mengangkat bahu.
Aku diam sebentar dan berpikir. Sebenarnya, apa yang membuat hidupku menyedihkan? Tidak ada hal-hal menyedihkan dalam hidupku. Tetapi mengapa aku malah mengeluh sampai membuat prasangka berlebihan kepada orang yang tidak melakukan apa-apa? Keadaanku tidaklah menyedihkan, aku hanya kurang bersyukur. Mengetahui kebenaran itu, aku meneteskan air mata.
“Maaf, maafkan aku. Aku sudah keterlaluan, berprasangka padamu karena mengira hidupmu sempurna, padahal aku tak tahu apa yang benar-benar terjadi. Sungguh, maafkan aku.” Air mataku membasahi pipi.
“Oh, sudahlah. Jangan mengasihani aku begitu. Semua orang punya masalahnya masing-masing, kau tahu.” Dia mengelus pundakku pelan selagi aku bersusah payah menyeka air mata dari wajahku. Satu per satu, muncul hal-hal yang membuatku sadar betapa beruntungnya aku, betapa hidupku lebih mudah dari sebagian orang, dan itu membuatku semakin merasa bersalah. Tetapi, aku juga bersyukur karena akhirnya aku menjadi sadar.
“Terima kasih, karena sudah membuka mataku dan memberiku motivasi untuk terus bersyukur,” kataku terisak. Air mata kembali jatuh ke pipiku. Namun, itu bukan air mata kesedihan, melainkan perasaan lega dan bahagia.
“Tuh kan, sudah kubilang kau akan menemukannya suatu saat nanti” Alora tersenyum manis.
Rasanya seperti membuka lembaran baru, aku mengubah pandanganku terhadap banyak hal. Aku berjanji pada diriku bahwa tak boleh ada lagi keluhan, rasa iri, dan prasangka yang membuat hidupku terhalang dari perasaan bersyukur. Dan mulai sekarang, aku akan berteman baik dengan Alora, dan semua orang tanpa memandang mereka sebelah mata.
Baca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 99
99 0
0