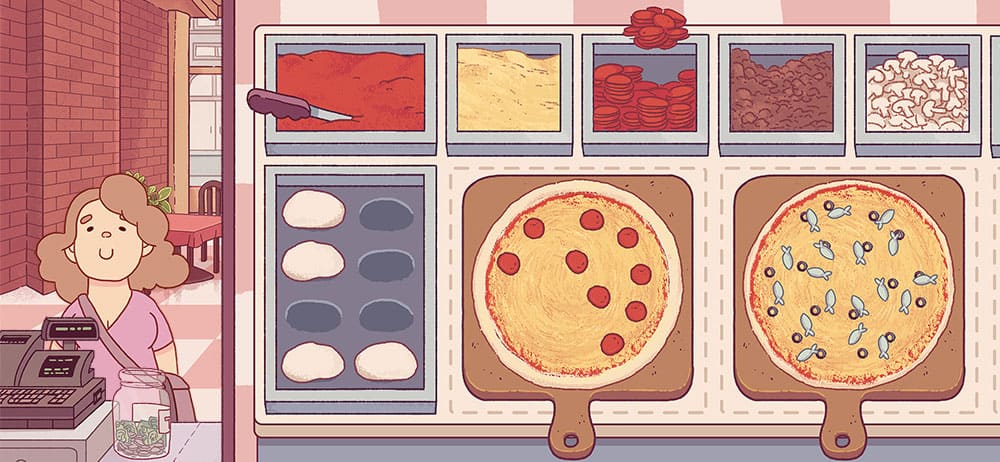Membedah Pola Pendidikan Koruptor Muda
Minggu, 30 Januari 2022 16:49 WIB
Korupsi tidak lagi memandang usia. Narasi tentang Nur Afifah Balqis mencerminkan betapa kasus korupsi juga bersifat pedofil, suka pada anak-anak muda. Generasi muda mudah diprogram dengan seperangkat ideologi yang menyenangkan untuk dinikmati sesaat tapi punya konsekuensi panjang yang berdarah-darah, termasuk harus berurusan dengan hukum. Pendidikan bagi generasi muda ternyata punya andil melahirkan barisan koruptor muda. Alih-alih mendidik pelajar, sekolah justru melahirkan pribadi yang ekonomi-sentris.
Siapa yang bisa menyangka bahwa seorang gadis bervisual agamais dan jelita serta punya prospek masa depan terang tersebut akhirnya mencatat rekor terbaru dalam rapor KPK sebagai koruptor termuda. Namanya Nur Afifah Balqis. Ia berhasil meraih sebuah prestasi yang mengenaskan. Di usianya yang ke-24, ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan ayahnya, seorang Bupati Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.
Nur memanfaatkan posisi strategisnya sebagai Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan untuk meraup uang sebanyak Rp 1 M dari proyek pembangunan. Barangkali sebagai seorang amatir dalam dunia perkorupsian, ia akhirnya terciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 13 Januari 2022.[1] Setitik tinta dosa ini tak terhindarkan merusak seluruh karir dan masa depannya.
Korupsi memang tidak lagi memandang usia. Narasi tentang prestasi Nur ini mencerminkan betapa kasus korupsi juga bersifat pedofil, suka pada anak-anak muda. Generasi muda mudah untuk ‘diprogram’ dengan seperangkat ideologi yang menyenangkan untuk dinikmati sesaat tapi punya konsekuensi panjang yang berdarah-darah, termasuk harus berurusan dengan hukum.
Prestasi naas Nur menyadarkan kita untuk melihat urgensi perbaikan pada pendidikan dasar. Pola pendidikan kita barangkali belum mampu mempersiapkan generasi muda untuk berpartisipasi dalam panggung pengabdian yang lebih besar dan lebih beresiko, khususnya politik. Mempidana Nur tidak akan bisa memutus rantai korupsi di Nusantara, sebab akar terdalam sudah dan sedang bertumbuh dalam rutinitas di ruang-ruang sekolah dan di tempat kuliah. Mari kita mengadakan kajian forensik atas tubuh pendidikan kita.
Pelajar atau Mesin Ekonomi?
Dengan kajian yang cermat, kita akan melihat betapa pendidikan kita tidak lagi berkiblat pada rumusan “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Kecerdasan, sebagaimana yang diimpikan UUD 1945, merupakan rumusan verbal yang tak punya daya. Sekolah dan lembaga pendidikan justru memproduksi tenaga-tenaga bagi mesin ekonomi kapitalis yang besar.
Neil Postman berinisiatif meneliti pergeseran paradigma ini. Menurutnya, pendidikan kini menyembah sebuah ‘tuhan’ (Bedakan dari Tuhan dengan ‘T’ besar) baru yang bernama, ‘tuhan kemanfaatan ekonomi (Utility Economic). Seluruh proses pendidikan direduksi menjadi sekedar persiapan untuk masuk lahan kerja.
Di sekolah dan perguruan tinggi tidak ada lagi pelajar. Yang mengisi ruang-ruang belajar adalah ‘unit-unit ekonomi’, calon-calon kapitalis muda. Yang dipelajari di sana hanya kelengkapan teknis untuk meraih karir secemerlang mungkin dengan iming-iming identitas “orang sukses”.
Menurut defenisi tuhan kemanfaatan ekonomi, kesuksesan pendidikan terletak pada jabatan strategis yang bisa diraih dan seberapa banyak investasi yang bisa ditanam. Sistim ini berubah menjadi sebuah ideologi akut yang meracuni pikiran generasi muda. Pendidikan yang dahulu dilihat sebagai proses ‘memanusiakan manusia’ dengan segala aspek etisnya sudah lama jadi mitos belaka, bahkan dongeng.
Ideologi ini tertanam bahkan sejak seorang manusia meraih pendidikan formal paling dasarnya. Bila seorang pelajar ditanyai tentang cita-citanya, jawaban mereka sudah bisa diprediksi; dokter, pebisnis, presiden, bupati, polisi, intinya semua jabatan yang dalam arti tertentu mendatangkan keuntungan finansial lebih. Daftarnya masih panjang. Pendidikan memang memungkinkan siapa saja meraih posisi-posisi tersebut, tapi kurang memberi perhatian pada tanggung jawab yang mesti dipikul. Pelajar disiapkan secara teknis tapi tidak humanis.
Bagi Neil, sistim seperti ini, “merendahkan peradaban dunia dan melecehkan kemanusiaan seseorang.”[2] Kemajuan peradaban hanya dilihat sebagai hasil dari mekanisme ekonomi. Manusia hanya dilihat sebagai sebuah ‘alat’ yang perlu menyesuaikan diri dalam mesin ekonomi besar supaya bisa survive. Kemanusiaan kita tidak punya cukup daya untuk mendefenisikan dan menentukan dirinya sendiri keluar dari batasan ekonomi.
Lebih lanjut, menurut kamus pemahaman Neil, sistim ekonomi-sentris dalam dunia pendidikan, “merendahkan gagasan tentang apa yang disebut dengan pelajar yang baik.”[3] Pelajar perlu dipersiapkan tidak saja untuk memenuhi lapangan pekerjaan, melainkan pula untuk berpikir tentang apa itu kebebasan, keindahan, apa yang patut dianggap benar, tanggung jawab, norma sosial, toleransi, multikulturalisme, kebijakan yang bijak serta efektifitas sebuah regulasi. Semua ini adalah modal untuk menopang kemanusiaan kita.
Bila sekolah merasa bangga karena para alumnus meraih posisi-posisi strategis dalam rimba ekonomi pasar bebas, tugas pendidikan belum selesai. Kepuasan seharusnya lahir karena seorang pelajar membuang sampah yang berserakan secara spontan dan diam-diam. Tindakan itu memang tidak punya prospek keuntungan ekonomi, tapi yang kita rayakan adalah kepedulian konkretnya untuk kebersihan lingkungan dan alam.
Arah dasar sekolah yang berorientasi pada cita-cita untuk berprestasi dalam roda perekonomian, tapi minim edukasi tentang tanggungjawab menjadi sebuah liang kondusif bagi terciptanya koruptor muda. Nur Afifah barangkali menjadi korban dari sistim warisan ini. Setelah Nur ditahan, kecemasan kita harus ditujukan bagi berjuta-juta siswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di berbagai jenjang dengan sistim pendidikan yang masih ekonomi-sentris.
Saya Memiliki Maka Saya Ada!
Tuhan kemanfaatan ekonomi yang tumbuh berjamur di tubuh pendidikan kita juga diperkuat oleh industri periklanan. Di luar jam sekolah, porsi para pelajar untuk terpapar iklan di berbagai media sosial jauh lebih tinggi dari jam pelajaran. Dengan demikian, dari segi statistic keterpaparan, iklan mungkin jauh lebih kuat mengarahkan kesadaran dan persepsi para pelajar.
Rimba iklan sebenarnya punya satu pesan tunggal kepada khalayak publik; “saya memiliki maka saya ada.” Eksistensi dan identitas diri sepenuhnya ditentukan dari kepemilikan barang atau produk terbaru. Dengan tidak memiliki, kita hanya akan terlupakan sebagai bayangan dalam pergaulan sosial.
Sekali lagi, Neil punya kosakata analogis untuk menggambarkan ideologi ini; ‘tuhan konsumerisme’. Gairah untuk memiliki merupakan sebuah patologi baru yang lahir karena sistim ekonomi kapitalis. Sistim kapitalis ini juga disuburkan melalui sistim pendidikan yang bertendensi pada kemanfaatan ekonomi. Dengan demikian, tuhan kemanfaatan ekonomi dan tuhan konsumerisme punya hubungan yang jauh lebih dekat dari sekedar hubungan darah.
Nur adalah satu dari sekian banyak generasi muda yang terpapar narasi konsumerisme. Dengan posisi strategis yang ia peroleh sebagai bendahara umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, semakin banyak yang bisa ia miliki. Bahkan uang rakyat dianggap sebagai properti pribadi.
Postman merangkum sistim demikian dalam sebuah aksioma; “kebaikan itu melekat pada orang-orang yang membeli segala sesuatu, sedangkan kejahatan itu berada pada orang-orang yang tidak bisa membelinya.”[4] Dengan demikian, benarlah adagium ‘saya memiliki maka saya ada.’ Semakin banyak dimiliki, semakin eksis.
Tuhan konsumerisme turut menyuburkan praktek korupsi bahkan sejak usia dini. Tak terhitung banyaknya generasi muda yang tenggelam dalam keinginan memiliki produk terbaru melalui situs dan media online shopping. Karakter mereka dibentuk dari seberapa banyak jemari menekan opsi produk industri terbaru di smartphone. Karakter ini pada akhirnya menjadi kekuatan yang menggagalkan pertimbangan etis-kritis. Bahkan ia membuat seseorang berbuat sesuatu tanpa berpikir. Seorang koruptor selalu mengesampingkan proses berpikir dan pertimbangan etis untuk memenuhi keinginannya.
Analisis sederhana ini tidak bermaksud untuk merubah semua praktik pendidikan yang sedang berlangsung. Paling jauh, tulisan ini hanya bermaksud memberi catatan kritis tentang arah sistim pendidikan kita. Tentu kita tidak menginginkan gedung-gedung sekolah dan perguruan tinggi menjadi tempat persemaian bibit-bibit koruptor muda. Kita tidak menghendaki Nur-Nur lain mencatat rekor di rapor kasus KPK.
Generasi muda adalah harapan masa depan sebuah bangsa. Dengan apa lagi sebuah bangsa dibangun bila generasi ini justru menjelma laskar koruptor.
Pendidikan karakter barangkali menjadi sebuah vaksin manjur untuk mencegah bertumbuhnya virus koruptor sejak dini. Sekolah perlu menyediakan tidak hanya kesempatan untuk terjun dalam angkatan kerja, melainkan pula menyediakan pemahaman yang lebih matang tentang tanggungjawab dan transparansi, tentang kerendahan hati dan kejujuran.
Mari kita mulai membenahi sekolah-sekolah dan pola pendidikan kita.
[1] Fitria Chusna Farisa, Nur Afifah Balqis, Tersangka Korupsi Usia 24 Tahun yang Pegang Uang Suap Rp. 1 Miliar Bupati PPU, Kompas.com, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/17552301/nur-afifah-balqis-tersangka-korupsi-usia-24-tahun-yang-pegang-uang-suap-rp-1?page=all., pada Sabtu, 29 Januari 2022, Pukul 21.40 WITA.
[2] Neil Postman, Matinya Pendidikan: Redefinisi Nilai-Nilai Sekolah, Terj. Siti Farida, (Yogyakarta: Immortal Publishing dan Octopus, 2019), hlm. 46.
[3] Neil Postman, loc. cit.
[4] Ibid, hlm. 49.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Mimpi Transisi Energi: antara Perlawanan Sipil Poco Leok dan Kuasa Geothermal
Selasa, 13 Mei 2025 11:51 WIB
Menantang Politik Ultra-Maskulin!
Kamis, 6 Februari 2025 15:19 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan






 98
98 0
0