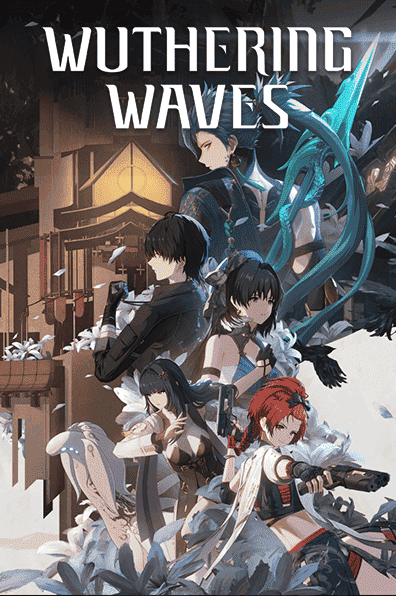Singa Padang Karautan
Senin, 2 Januari 2023 14:18 WIB
Sebuah Cerita Bersambung dengan Latar Sejarah Berdirinya Kerajaan Singhasari...sebagian tokoh dan cerita bersifat fiktif...dan cerita ini tidak bisa digunakan sebagai rujukan sejarah
BAB SATU: TUMENGGUNG RUPAYANA
PURNAMA DI PADANG KARAUTAN
Hati Tumenggung Rupayana berdesir juga ketika mulai menapak Padang Karautan. Sementara sang surya perlahan mulai meredup di ufuk barat. Pohonan di kanan kiri rombongan Tumenggung semakin jarang. Sekitar 50 tombak lagi, mereka akan sampai di Padang Karautan.
“Berhenti!” kata Tumenggung tiba-tiba.
Sais kereta menghentikan kudanya. Sepuluh prajurit berkuda yang dipimpin seorang Senopati itu juga berhenti seketika. Tumenggung melongok keluar kereta, duduk persis di samping sais. Dia memelintir kumis tipisnya, lalu sekilas memandangi sekitar. Tak lama kemudian, dia memberi isyarat kepada Senopati Panji Sumekar untuk mendekat. Senopati muda berkulit sawo matang itu bergegas mendekat.
“Hamba, Tuanku,” kata Senopati setelah turun dari kuda.
“Apakah ini yang disebut Padang Karautan?”
“Benar, Tuanku. Tidak lama lagi kita akan sampai di Padang Karautan.”
“Apakah kau sudah pernah mendengar cerita itu?” tanya Tumenggung dengan pandangan menyelidik.
“Cerita apa, Tuan?”
“Tentang Singa Padang Karautan.”
Senopati Panji Sumekar tampak sedikit berubah rona mukanya. Wajahnya sedikit kecut. Mungkin terbersit sekilas rasa takut. Namun hal itu berusaha disembunyikannya.
“Kata orang, ada suara mengaum tiap malam. Dan bukan hanya itu, setiap rombongan yang lewat sana tidak ada yang selamat. Menurut sebagian orang itu semacam singa siluman. Ada juga yang bilang itu hantu.”
“Kau percaya kalau dia itu hantu?” sergah Tumenggung.
“Tidak, Gusti Tumenggung. Saya yakin dia adalah seorang manusia. Saya dengar yang dicegat dan dibunuh adalah orang-orang kaya dan nayaka praja. Menurut saya, dia cuma seorang perampok. Hanya saja, dia memiliki ilmu kanuragan yang tinggi sehingga tak satu pun yang berhasil selamat Bahkan beberapa pendekar yang mengawal para nayaka praja juga dibunuhnya. Tak pernah ada yang selamat melewati padang itu.”
Tumenggung itu manggut-manggut dan tersenyum. Sebaliknya Panji Sumekar justru tampak kebingungan,
“Apakah tidak sebaiknya kita bergegas, Gusti? Sebelum hari keburu malam”
“Kenapa memangnya? Bukankah ini malam bulan purnama?”
“Lebih baik kita bergegas, Tuanku,” kata Senopati setengah tergagap. “Semakin cepat kita meninggalkan daerah ini, semakin baik.”
Tumenggung itu tersenyum lebar.
“Kau takut, Panji Sumekar?”
“A..ampun, Gusti Tumenggung,” Panji Sumekar terbata-bata menyembah junjungannya. “Saya dengar, beberapa tokoh pendekar sakti juga mati di padang ini.”
Tumenggung Rupayana tersenyum lebar.
“Apakah kau takut Panji Sumekar?”
Panji Sumekar menundukkan wajahnya.
“Kau ini seorang senopati pinilih kerajaan Khadiri, Panji Sumekar. Kenapa mesti takut?”
“Hamba dengar beberapa tokoh sakti dunia persilatan hilang atau mati ketika melewati daerah ini, Tuan.”
“Siapa?”
“Yang saya dengar Ki Sabda Jati, Gagak Gumilang, dan Kuda Bawana.”
“Ah, mereka itu bukan apa-apa,” kata Tumenggung kesal. “Apa kau juga meragukan kesaktianku?”
Panji Sumekar tertunduk semakin dalam.
“Kau lihat batu besar itu. Dalam sekali pukul ia akan hancur jadi pasir dan kerikil.”
“Ampun Gusti Tumenggung, hamba tidak bermaksud meremahkan kesaktian Gusti.”
“Ah Sudahlah!” Tumenggung itu mulai reda rasa kesalnya. “Bukankah ini malam Bulan nDadari alias bulan purnama, Sumekar?”
“Benar, Gusti.”
“Kalau begitu, perintahkan anak buahmu turun dari kuda. Kita berjalan menuju Padang Karautan. Aku akan turun juga. Kita akan berkemah di sana. Jangan lupa, tingkatkan kewaspadaan.”
“Baik, Gusti!”
Maka senopati muda itu melaksanakan perintah sang tumenggung. Semuanya turun dari kuda. Panji Sumekar berada di depan. Sebagian anak buahnya di belakangnya. Disusul tumenggung di tengah barisan dengan kereta dan kusir di belakangnya, dan terakhir, belakang mereka ada beberapa prajurit lagi. Para prajurit itu membabat ranting-ranting pohon, akar dan duri yang merintangi jalan. Mereka semua waspada. Namun semuanya terlihat tenang dan tak ada bahaya mengancam. Tepat ketika sang surya mulai tenggelam dan mega merah jingga bertebaran di langit, mereka sampai di sebuah padang rumput yang luas; Padang Karautan.
“Kita buat kemah di sini saja,” kata Tumenggung Rupayana setengah berteriak.
Senopati Panji Sumekar segera memerintahkan anak buahnya membangun kemah-kemah. Kemah tumenggung adalah yang paling besar dan diletakkan di tengah. Ketika mereka rampung, malam mulai turun, dan bulan mulai menyembul di ufuk barat. Beberapa prajurit menyalakan obor dengan batu titikan. Sementara kuda-kuda diikatkan pada pepohonan. Setelah semua selesai, Tumenggung Rupayana kembali memanggil Panji Sumekar.
“Bagaimana, sudah beres semua?”
“Sudah, Gusti.”
“Hmm…bagus,” sang Tumenggung menghela napas. “Dengar, aku bisa mendengar aliran air tidak jauh dari sini. Coba kau periksa, mungkin ada sungai atau danau di sekitar sini. Airnya bisa kita masak untuk wedang hangat.”
“Baik, Gusti.”
“Persediaan makanan masih cukup, kan?”
“Masih, Gusti.”
Sementara Panji Sumekar mencari air, Tumenggung Rupayana mengamati keadaan. Bulan semakin tampak jelas dan memancarkan sinarnya. Burung-burung yang berterbangan sore tadi tidak tampak lagi. Angin berhembus semilir terasa amat sejuk. Para prajurit mulai membuat perapian untuk menghangatkan badan. Suasana ini, amat tenang. Terlalu tenang bahkan. Pikiran itu tiba-tiba menyeruak dalam benaknya. Namun belum sempat sang tumenggung berpikir lebih jauh, senopati Panji Sumekar sudah kembali dengan membawa dua buah kendi besar berisi air.
“Airnya jernih sekali, Gusti. Sungai itu juga tidak jauh dari sini.”
“Bagus. Apakah keadaan aman?”
“Aman dan tenang, Gusti. Tenang sekali.”
“Terlalu tenang, bahkan,” Tumenggung Rupayana mendesah. “Jangan sampai lengah. Keadaan seperti ini justru berbahaya.”
Belum sempat Senopati Panji Sumekar menjawab, tiba-tiba terdengar suara beberapa serigala melolong. Semuanya terdiam.
“Tenang, itu hanya auman serigala,” kata Tumenggung Rupayana. “Tapi kalian harus tetap waspada.”
Tak berapa lama kemudian, mendadak turun kabut tebal perlahan. Makin lama kabut itu makan tebal menutupi sekitar perkemahan. Para prajurit menjadi kebingungan.
“Tenang! Semua tenang!” Panji Sumekar berteriak menenangkan.
“Ini bukan kabut biasa, Sumekar. Tajamkan panca inderamu!”
“Betul, Gusti.”
Panji Sumekar meloloskan pedangnya dan memusatkan konsentrasi. Dia menebarkan pandangan. Sementara Tumenggung Rupayana menajamkan pendengarannya.
“Aku mendengar desah napas. Samar sekali, “kata sang tumenggung.
Panji Sumekar berusaha menembus kabut tetapi tidak bisa. Tak berapa lama kemudian, kabut itu perlahan menipis dan menghilang.
“Kabutnya hilang, Gusti!”
“Periksa sekeliling!”
Panji Sumekar dan anak buahnya segera menyebar meneliti keadaan. Dan tiba-tiba seorang prajurit berteriak.
“Kuda putih Gusti Tumenggung hilang!”
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Singa Padang Karautan (2)
Jumat, 6 Januari 2023 06:48 WIB
Singa Padang Karautan
Senin, 2 Januari 2023 14:18 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0








 97
97 0
0