Saliman
Minggu, 2 April 2023 06:14 WIB
Aku membuka pintu saat Saliman melepas sandal di depan teras rumah. Tiga hari lagi Lebaran tiba, berarti memang betul jika hari ini laki-laki tua itu datang kemari. Dengan bertelanjang kaki Saliman menapaki lantai porselen teras rumah kami, lalu bergegas mengambil posisi duduk di kursi kayu yang berada di ambang pintu. Dari kantong celana pendeknya yang telah koyak di sana-sini, ia keluarkan sebuah buntalan kresek berwarna hitam. Tangan legam berkerut-kerutnya cekatan mengeluarkan sesuatu dari kresek hitam itu. Kulihat, lembar-lembar uang ribuan menyembul dari buntalan kresek yang telah dibukanya. Aku menebak, laki-laki kurang akal itu pasti mencari ayah.
“Nyari Pak Guru, ya?” aku bertanya memastikan.
Saliman tersenyum memperlihatkan jajaran giginya yang tidak utuh lagi. Aku mengangguk, segera masuk mengambil titipan ayah untuknya.
Laki-laki seumuran kakekku itu memang selalu datang ke rumah setiap tiga hari menjelang Lebaran. Ia akan meminta jatah pakaian kepada ayah yang selalu ia sapa dengan sebutan Pak Guru. Entah bagaimana sapaan itu dapat keluar dari mulutnya, padahal ayahku bukan seorang guru. Tapi, sepanjang yang aku tahu, semenjak memberikan koko pertamanya pada Saliman, ayahku diberi gelar Pak Guru oleh lelaki tua kurang akal itu.
Saliman masih sibuk menata lembaran uang ribuan yang ia bawa saat aku kembali menemuinya. Kurasa ia hanya menata. Tidak mungkin ia bisa menghitung jumlah kertas-kertas bernominal itu. Tidak mungkin. Terlalu sulit untuknya, menurutku.
“Pak Guru sedang pergi ke Pemda. Ini jatah dari Pak Guru, Man,” aku menyerahkan sebuah lipatan sarung dan koko putih pada Saliman.
Saliman tertawa dengan mata terpejam, “Maturnuwun Mas.” Ia terima sarung dan koko dariku. Lalu tangannya mengulur lembar-lembar uang ribuan padaku, “Ini Mas.”
Dahiku berkerut, “Uang ini untuk apa, Man?”
“Buat mengganti koko-koko Pak Guru.”
Hampir saja tawaku meledak mendengar apa yang dikatakannya barusa. Tetapi, demi menghargai lelaki berumur di depanku, aku menahannya. “Kenapa harus diganti uangnya? Kan baju koko dan sarung itu memang sudah jatah dari Pak Guru, to?”
“Saya, ndak mau terus-terusan berhutang, Mas.”
Berhutang? Sejak kapan orang kurang genep seperti Saliman bisa memikirkan hutang. Kenapa pula tiba-tiba ia merasa memiliki hutang. Cepat-cepat aku menyanggah, “Itu bukan hutang, Man. Pak Guru sengaja memberi koko-kokonya untukmu. Buat Mbok Yem aja, ya, uang itu. Kan, Mbok Yem yang merawat kamu.”
“Ha-ha-ha…Nanti saya akan kasih Simbok yang lebih banyak. Pokoknya yang ini untuk Pak Guru.”
“Wis, wis, ndak perlulah. Jangan mikir macam-macam. Aku tidak mau menerima uang itu. Pak Guru pasti tidak mau juga.”
“Tapi saya tidak mau berhutang.”
“Tenang Man, baju itu bukan hutang.”
“Weh, itu hutang, Mas. H-U-T-A-N-G. Saya pengin nyicil hutang koko-koko itu!”
Bagaimana bisa aku menerima lembaran uang ribuan dari Saliman. Ah, tapi jika terus-terusan menolak, Saliman tidak akan lekas pergi dari sini. Malas betul aku berdebat dengannya. Maka kuputuskan untuk menerima uang itu. Nanti ketika di langgar, uang Saliman akan kumasukkan ke kotak yang ada di dekat tempat wudhu, pikirku.
“Baiklah uang ini aku terima. Tapi cukup sekali ya, lain kali jangan membayar koko-koko itu lagi.”
Saliman mengangguk, tertawa, lantas berlalu pergi.
***
Aku berjalan tergesa menapaki jalan aspal menuju langgar. Sebelum adzan isya aku harus sudah tiba di sana. Sebagai orang yang ditipi amanah aku tidak boleh terlambat. Apalagi amanah yang kupegang saat ini berupa lembaran-lembaran rupiah. Jadi, harus hati-hati dan tidak boleh terlambat.
Dari ujung jalan, mataku menangkap bayangan hitam. Melihat caranya berjalan aku bisa menebak siapa sosok itu. Betul saja semakin dekat, semakin jelas jika orang itu adalah Saliman.
“Mau ke tarawih, Mas Ghozi?” Saliman lebih dulu menyapa. Seperti orang yang akan beribadah, ia juga mengenakan peci, koko, dan sarung yang ditekuk tidak simetris. Tentu saja, itu bukan pakaian yang dititipkan ayah tadi pagi untuknya.
“Heem, kamu juga, kan?
“Nggih, Mas.”
“Yo wis lah, kita bareng saja.”
“Mas? Saya mau bilang rahasia.”
“Rahasia?”
“Ssst… jangan keras-keras. Tapi jangan kasih tau orang-orang. Yang tahu cukup Mas Ghozi saja. Pak Guru juga jangan sampai tahu.”
Sebelah alisku terangkat. Agak geli mendengar Saliman mengatakan jika ia mempunyai rahasia. Lebih-lebih yang akan tahu rahasia itu hanya aku. Hanya aku. Bahkan, ayah yang sering menanggapinya di kala tetangga-tetanggaku memandang rendah dirinya juga tidak boleh tahu.
Sejenak aku berhenti, menatap sanksi Saliman. “Rahasia apa? Bilang saja.”
Saliman mendekatkan mulutnya ke telingaku “Jadi, saya tidak ingin terus-terusan ber-te-ri-ma-ka-sih.”
“Heh, maksudnya Man?”
“Ya itu, Mas. Saya tidak mau berterima kasih terus.”
“Kenapa?”
“Hahaha, embuh embuh Mas. Pokoknya tidak mau.”
“Ah, susahlah ngomong sama kamu. Selalu ndak jelas!”
“Lha saya ini ingin seperti Pak Guru. Bisa to, Mas?”
Aku tidak langsung menjawab. Apa yang diucapkan Saliman membuat otakku bekerja cukup keras. Baru kali ini aku perlu berpikir saat berbicara dengan orang kurang genep. Sebetulnya terkadang aku merasa bahwa Saliman bukanlah seperti anggapan tetangga-tetanggaku. Kurang tepat jika menyamakan ia dengan orang-orang gila yang sering berkeliaran di kampungku.
“Kok diam, Mas?
“Eh, iya. Hemm... bisa kok menurutku. Mungkin saja.”
“Carannya, Mas?”
“Eh, caranya? Gimana, ya?” Aku berpikir kembali. Tapi, belum sempat aku mendapat jawaban, tiba-tiba saja aku ingat kalau harus buru-buru ke langgar. Ah, sial kenapa aku bisa lupa begini.
“Man, jawabannya kamu cari tahu sendiri, ya. Aku mau motong jalan. Kamu terus aja lewat jalan biasa.”
Langkahku kupercepat menjauhi Saliman. Ia masih terdiam ketika kutinggalkan. Lalu, ketika aku sudah membelok ke sebuah jalan setapak sempit, Saliman di belakang memanggil-manggil. Aku terus mempercepat langkah, mengabaikan panggilannya.
***
Semua mata di langgar ini tertuju padaku. Sungguh tatapan-tatapan itu layaknya sebuah pisau. Mengkilap, tajam, siap membunuh. Aku semakin kikuk.
“Tadi aku bawa kok, iya di sini. Masa sekarang tidak ada?” tanganku terus menyibak isi stopmap kertas bermotif batik yang kubawa sejak berangkat ke langgar. Hanya ada lembaran-lembaran kertas di dalamnya.
Laki-laki jangkung yang berada di sebelahku berkata, “Coba kamu cari lagi yang benar! Yang lebih teliti.”
“Apa mungkin ketinggalan di rumah? Kamu lupa kali, Zi,” seorang bertubuh tambun di sebelah lelaki jangkung itu juga angkat bicara.
“Tidak,” sanggahku mantap. “Aku yakin sudah membawanya. Bahkan di perjalanan aku sempat mengecek amplop itu,”
“Amplop itu penting lho, Zi. Isinya uang umat. Jangan sampai hilang! Bahaya.”
Aku semakin salah tingkah, “Iya, iya, maaf. Akan kucari lagi.”
“Kamu ini gimana, sih, Zi. Jadi orang kok nggak bisa dipercaya?” Lelaki jangkung itu mencibir.
Mendengar ia bicara, kupingku mulai terasa panas. “Aku tidak sengaja. Mana tahu kalau amplop itu akan hilang?”
“Ya, semoga amplop itu benar-benar jatuh di jalan. Bukan jatuh di kantong orang yang bawa” dengan sorot mata memandang ke segala arah, laki-laki jangkung itu berkata nyiyir.
Aku mendelik, menghempaskan map, lalu spontan memegang kerah baju laki-laki jangkung di dekatku, “Kamu bilang apa, hah?! Coba bilang sekali lagi! Dengar ya, sebutuh-butuhnya, sekepepet-pepetnya, bahkan semiskin-miskinnya aku, tidak akan pernah aku berani ngambil uang itu!”
Beberapa laki-laki berusaha memegang pundakku, menyuruhku melepaskan kerah lelaki jangkung itu. Sebagian yang lain terperangah, dan sisanya berbisik-bisik dengan teman sebelah. Entah apa yang ia bicarakan. Ketika sadar, segera kulepaskan kerah lelaki jangkung di dekatku.
“Permisi, maaf menganggu rapat kalian. Ada yang mencari Ghozi,” perempuan bermata sipit dengan balutan mukena berdiri di ambang pintu langgar.
“Siapa?” aku menoleh, mencoba mengatur napas.
“Saliman”
Napasku terhela panjang, “Oh, biarkan dia masuk langgar saja”
“Saliman di luar, tidak ingin masuk. Tapi, dia nitip ini buatmu.”
Aku melangkah mendekati perempuan bermata sipit itu. Sebuah amplop putih panjang ia ulurkan. Otot-otoku yang menegang tiba-tiba saja mengendur melihat amplop yang ia ulurkan
“Alhamdulillah… amplopnya sudah ketemu!” pekikku. Tanpa memikirkan orang-orang yang mulai limbung di sekitarku, aku berlari ke arah serambi.
***
Sepi, tidak ada siapa-siapa di serambi. Ke mana perginya penyelamatku itu? Ah, ya, aku masih bisa menangkap punggungnya yang kian menjauh dari pagar langgar. Aku hanya memandangi punggung itu.
Mataku terus tertuju pada tubuh itu. Tubuh laki-laki seusia kakekku yang semakin hilang ditelan gelap malam. “Sekarang aku yakin kau bisa seperti Pak Guru. Aku sangat yakin. Te-ri-ma-ka-sih,” lirih sekali kata-kata itu kuucapkan. Hampir seperti bisikan.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Menelisik Permainan Simbol dalam Lubang Dari Separuh Langit Karya Afrizal Malna
Selasa, 22 Agustus 2023 12:00 WIB
Riwayat Tentang Kakek
Selasa, 2 Mei 2023 07:39 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
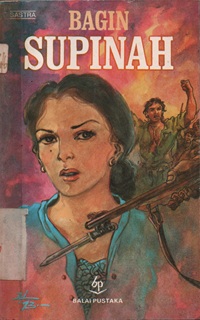






 99
99 0
0




 Berita Pilihan
Berita Pilihan










