Membeli Kucing Pemilu dalam Karung Minimnya Pendidikan Politik
Senin, 3 Juli 2023 07:10 WIB
Begitu direduksi menjadi pemilu, politik yang seharusnya berasal dari gelora hati menjadi tidak begitu menggetarkan. Politik lahir ketika dunia menginginkan perubahan. Dahulu, perubahan menuntut pengorbanan. Dan hanya dari hati yang bergelora keduanya tersedia.
Begitu direduksi menjadi pemilu, politik yang seharusnya berasal dari gelora hati menjadi tidak begitu menggetarkan. Politik lahir ketika dunia menginginkan perubahan. Dahulu, perubahan menuntut darah dan nyawa. Dan hanya dari hati yang bergelora keduanya tersedia.
Berapa banyak rakyat Indonesia yang hatinya bergelora begitu kata "politik" disebut? Hampir-hampir tidak ada. Yang ada adalah bayangan makan enak, istri cantik, rumah dan mobil mewah hasil korupsi jika disebut kata "politisi". Sesungguhnya tidaklah mengherankan karena memang begitulah fakta yang terjadi.
Tidak bergeloranya hati juga sedikit banyak disumbang oleh rendahnya pendidikan politik di Indonesia. Pendidikan politik secara serius untuk pertama kali dienyam oleh penduduk Indonesia di bangku perkuliahan. Itu pun kalau kuliah. Kuliah dan mengambil jurusan Ilmu Politik di fakultas FISIP. Pendidikan politik lulusan SMA? Jangan harap. SMP? Apalagi. Miris saya melihat kenyataan bahwa menurut data survei yang dilakukan Kemendagri tahun 2021, penduduk Indonesia paling banyak hanya tamatan SD. Meskipun tidak semua, tapi kalau cuma tamatan SD jangankan memikirkan bisa melek politik, memikirkan siapa yang mau menerima kerja saja sudah setengah mati.
Setelah pengertian politik direduksi, nasib Indonesia paling tidak selama 5 atau 10 tahun mendatang, ditentukan melalui pemilu. Pemilu untuk sekian kali direduksi lagi menjadi voting. Sekarang mari kita melihat data: Berdasarkan data BPS tahun 2022, dari 273 juta penduduk, hanya sekitar 6 persen yang mengenyam bangku kuliah. Sedangkan jumlah yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara sekitar 205 juta penduduk. Artinya, 92 persen suara diberikan oleh mereka yang tidak melek politik. Itupun dengan asumsi dari yang 6 persen itu semuanya kuliah di jurusan Ilmu Politik dan tidak ada seorang pun yang golput.
Tidak heran jika praktik money politics sering terdengar di berita-berita. Kajian KPK menyebutkan kemenangan pemilu atau pilkada di Indonesia, 95,5 persen dipengaruhi karena kekuatan uang. Karena suara mereka yang tidak melek politik stoknya banyak dan bisa dibeli —seperti prinsip ekonomi "makin tinggi penawaran, makin rendah permintaan"—dengan harga murah.
Di Indonesia sebenarnya ada satu mata pelajaran untuk pendidikan politik sejak SD, PPKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran memiliki potensi yang tinggi untuk mengajarkan politik bagi generasi muda. Karena politik, menurut Aristoteles, adalah usaha warga negara untuk bekerjasama. Politik berasal dari bahasa Belanda "politea" yang merupakan kata serapan dari bahasa Yunani "polis" yang berarti warga kota. Dalam era modern istilah kota yang semula menunjuk pada kota Athena mengalami pergeseran arti menjadi negara. Karena itu, tampak jelas bahwa politik adalah urusan kewarganegaraan.
Masalahnya, selama ini PPKN—juga mata pelajaran lainnya—semata-mata diisi dengan materi normatif dan dogmatif sehingga kemampuan para generasi muda hanya tumbuh sebelah, yaitu sisi kognitifnya saja. Kemampuan afektif yaitu kemampuan untuk merasakan mereka minim.
Mereka mungkin hebat dalam menghafal pasal dan tanggal-tanggal. Tetapi urusan merasakan, mereka jauh dari kata mampu. Seperti seorang analis yang dengan sangat canggih menampilkan data statistik tentang kemiskinan, sedangkan dia sendiri adalah orang berpunya yang barangkali belum pernah merasakan lapar dan belum pernah hidup menggelandang di pinggiran kota-kota. Padahal politik berasal dari gelora hati. Dengan kata lain: dari perasaan.
Kepekaan merasakan ini yang harusnya menjadi perhatian utama dalam pendidikan —di samping urusan pengetahuan. Kalau hanya mengembangkan kemampuan kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan itu belum dapat disebut pendidikan, namun hanya sebatas pengajaran. Pendidikan selalu berkelindan dengan perasaan yang pada akhirnya akan mendorong diri untuk melakukan suatu tindakan. Outputnya adalah gerak laku atau tindakan. Agama menyebutnya tindakan ini sebagai akhlak.
Kurikulum pendidikan berbasis karakter yang saat ini digaungkan juga —meskipun rancu— mengarah kepada keutamaan akhlak. Saya menyebutnya rancu karena dari definisi di atas, pendidikan pasti berkaitan dengan akhlak sehingga yang namanya pendidikan pasti berbasis karakter. Kalau tidak, namanya bukan pendidikan tetapi pengajaran. Di Indonesia, baru pada tahap pengajaran inilah yang namanya "pendidikan" politik berada.
Dalam urusan politik, sekolah-sekolah lebih banyak melahirkan generasi yang bertanya apa dan kapan daripada generasi yang bertanya mengapa dan bagaimana. Tidak ada momen di mana guru dan siswa membahas isu terkini mengenai permasalahan politik di Indonesia, jangankan luar negeri. Mengapa hal itu terjadi dan bagaimana solusinya.
Tidak ada satu pun diskursus dalam dunia pendidikan kita yang melahirkan pertanyaan: Mengapa dalam pemilu, seorang ulama dengan ribuan santri di Jawa Timur dan seorang pencopet sama-sama dihitung satu suara? Bagaimana logikanya? misalnya.
Penulis Indonesiana | Author of Rakunulis.com
1 Pengikut
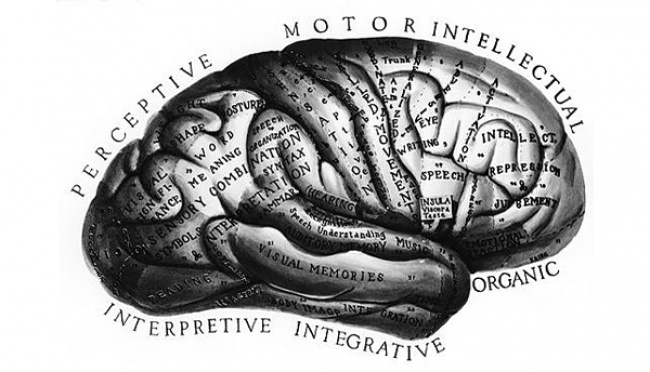
Hukum-hukum Akal dan Pertanyaan-pertanyaan Aneh yang Menyertainya
Sabtu, 7 Juni 2025 12:20 WIB
Menyoal Lampu Motor Siang Hari, Sertifikasi Halal dan PPN 12%
Selasa, 15 April 2025 21:18 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 97
97 0
0

















