Aturan Jilbab di Sekolah dan Bagaimana Memaknainya
Sabtu, 2 September 2023 10:34 WIB
Beberapa tahun terakhir pemakaian jilbab di sekolah negeri kian marak. Padahal selama ini sekolah negeri memberi keleluasaan muridnya untuk memilih apakah akan berjilbab atau tidak. Namun, di beberapa sekolah siswi muslim yang tidak berjilbab mendapat intimidasi atau kekerasan. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Baru-baru ini, timeline medsos saya diramaikan dengan berita sejumlah siswi SMP di Jawa Timur yang rambut bagian depannya dicukur botak oleh seorang guru lantaran mereka tidak mengenakan ciput (dalaman jilbab). Kasusnya memang berakhir damai melalui mediasi antara pihak sekolah dengan orangtua/wali murid. Guru yang bersangkutan juga sudah meminta maaf. Tapi, apakah minta maaf akan cukup untuk menghapus trauma yang dialami oleh belasan siswi tersebut?
Aturan berpakaian serupa yang terjadi di sekolah negeri membuat saya bertanya-tanya, sejak kapan sekolah negeri mulai diperlakukan seperti sekolah berbasis agama? Ingatan saya kembali ke masa SMP, di mana teman-teman perempuan sekelas yang muslim mengenakan jilbab saat pelajaran agama. Hanya saya, satu-satunya siswi di kelas itu yang tidak mengenakannya. Alhamdulillah, saya tidak pernah diusir dari kelas, disindir atau diperlakukan dengan tidak menyenangkan oleh guru agama yang mengajar.
Pakaian saya yang berbeda saat mata pelajaran tersebut berlangsung juga tidak mempengaruhi nilai agama saya, baik dalam tugas-tugas, ulangan maupun di rapor. Bagus ya dikasih bagus, jelak ya dikasih jelek. Tidak ada hubungannya dengan pakaian saya.
Selama ini, aturan berseragam bagi murid perempuan di sekolah negeri memang lebih longgar. Dalam artian, murid perempuan dibebaskan untuk mengenakan atau tidak mengenakan jilbab. Rok seragam pun boleh tidak panjang asalkan tidak terlalu pendek dan ketat. Intinya, selama masih dalam batas wajar dan memenuhi nilai-nilai kesopanan, seragam berjilbab atau tidak, tetap diperbolehkan.
saya tidak tahu istilah apa yang lebih tepat untuk menggambarkan kondisi sekolah negeri saat ini, di mana aturan berseragam jadi lebih “ketat”. Namun, hal ini sebetulnya bisa dilihat dari dinamika sosial-politik yang turut mempengaruhi kebijakan berjilbab di sekolah.
Salah satu pemicunya bisa dilihat dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi:
“Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah”.
Munculnya regulasi ini sebenarnya bertujuan untuk mencegah diskriminasi pelajar muslim berjilbab di sekolah negeri di daerah minoritas muslim, misalnya di Bali dan sebagainya. Sayangnya, menurut laporan Komnas Perempuan dan Human Rights Watch dalam beberapa tahun terakhir, aturan tersebut kerap dipahami oleh sekolah sebagai legitimasi untuk mewajibkan pelajar muslim yang belum berjilbab.
Faktor lainnya adalah menguatnya identitas politik Islam di ranah lokal, nasional dan global. Dalam konteks Indonesia, hal ini tak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu, terutama di masa pemerintahan Orde Baru dengan kecurigaannya pada politik Islam. Kecurigaan itu berakibat pada pelarangan jilbab di berbagai instansi, termasuk di sekolah. Apabila ada siswi yang mengenakan jilbab, ia bisa dikeluarkan dari sekolah.
Meletusnya Revolusi Iran tahun 1979 yang menyebabkan timbulnya kewajiban berjilbab bagi perempuan Iran turut menginspirasi sebagian muslimah Indonesia untuk memperjuangkan hal yang sama. Berbagai organisasi keislaman atau lembaga dakwah di kampus-kampus besar di Indonesia pun ikut andil dalam mengembangkan gerakan jilbabisasi di sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi pada tahun 1980-an.
Penggunaan jilbab yang semakin marak di tahun 1990-an terjadi seiring dengan berkembangnya peran organisasi kerohanian Islam (Rohis) di sekolah-sekolah. Baru setelah reformasi 1998, kelompok-kelompok Islam mendapat kebebasan dan ruang berekspresi yang lebih luas ketimbang di era Orde Baru, termasuk di dunia politik.
Sekarang, gerakan jilbabisasi semakin menjamur seiring dengan bermunculannya akun-akun, ustadz-ustadzah bahkan seleb-seleb hijrah yang kerap mewarnai ruang-ruang digital. Gerakan jilbabisasi yang disebut dalam satu tarikan nafas dengan fenomena hijrah, membuat jilbab tidak hanya dianggap sebagai simbol kesalehan tapi juga tren dan gaya hidup. Jilbab juga kemudian menjadi alat kontrol berlebih yang mengatur cara seorang perempuan berdandan, berpenampilan, berbicara, bekerja, berinteraksi dengan lawan jenis bahkan berpikir dan memilih sesuatu yang sifatnya personal. Anak-anak muda yang sedang mencari jati diri atau yang berada di fase quarter-life crisis adalah target potensial dari gerakan-gerakan tersebut.
Perbedaan Tafsir atas Aurat Perempuan dan Jilbab
Mayoritas muslim meyakini bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Inilah yang kemudian dijadikan dasar kewajiban berjilbab.
Sumber yang sering dikutip dan dijadikan rujukan utamanya berasal dari Al-Quran Surat An-Nur ayat 31 yang artinya “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya.”
Nadirsyah Hosein dan Ibrahim Hosein dalam buku Ngaji Fikih: Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi yang Kontekstual (2020: 428-431) menguraikan perbedaan pendapat para ulama mengenai “perhiasan” dan frasa “kecuali yang (biasa) tampak daripadanya” dalam ayat tersebut.
Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan biasa tampak adalah pakaian sehingga seluruh tubuh perempuan harus ditutup. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan biasa tampak adalah cincin dan gelang. Ada yang mengatakan maksudnya adalah make up seperti eyeliner, perona pipi atau pewarna kuku tangan dan kaki.
Ketiga mazhab (Hanafi, Maliki dan Syafi’i dalam satu qaul) mengatakan wajah dan telapak tangan bukan aurat sehingga boleh dibuka, sebagaimana yang sudah biasa terlihat secara tradisi atau adat (untuk konteks zaman itu). Dalam riwayat Imam Abu Hanifah, telapak kaki juga dianggap bukan aurat sehingga boleh terlihat.
Imam Abu Yusuf, murid senior Imam Abu Hanifah dan Ketua Mahkamah Agung zaman kekhalifahan Harun Al-Rasyid punya pendapat yang juga berbeda, yaitu lengan perempuan bukan termasuk aurat. Bahkan menoleransi untuk membuka separuh dari betis.
Perbedaan pandangan ini didasarkan pada pendekatan adat (termasuk yang berhubungan dengan konteks wilayah tempat tinggal ulama yang bersangkutan) dan hajat. Nah, bagaimana dengan konteks tradisi atau adat di Indonesia atau negara lain yang para perempuannya biasa menampakkan rambut, leher dan telinga? Bukankah simbah-simbah kita zaman dulu biasa kembenan, berkebaya dan sanggulan? Itu sebabnya, saya kerap mengerutkan kening ketika ada sebagian muslim yang nyinyir dan memaksakan pemakaian jilbab pada perempuan yang tidak berjilbab.
Jilbab Sebagai Pilihan Sadar Perempuan Muslim
Baik pelarangan maupun pemaksaan, keduanya sama-sama bentuk kekerasan dan pengekangan atas kebebasan berekspresi. Jilbab memang bisa dimaknai berbeda, tapi tubuh perempuan adalah otoritas pribadi, bukan milik publik.
Fungsi pakaian sejatinya adalah untuk melindungi tubuh dari panas, dingin dan hal-hal yang membahayakan atau melukai tubuh. Pakaian juga kerap diidentikkan dengan budaya, tradisi, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tidak cukupkah seorang perempuan berpakaian sesuai standar kesopanan dan kepantasan, meski ia membiarkan rambut, leher dan telinganya terbuka? Dalam kaitannya dengan seragam sekolah, apa tidak cukup murid perempuan berseragam rapi, sopan, tidak ketat, tidak transparan dan tidak minim?
Menutup aurat memang wajib. Namun, sampai mana batasan aurat (bagi perempuan), ulama berbeda pandangan. Oleh karena itu, saya tidak mau mempermasalahkan perempuan muslim yang tidak berjilbab, berjilbab tapi mode stylish (turban, misalnya) atau yang awalnya berjilbab kemudian melepasnya. Barangkali mereka menganut pandangan yang berbeda dengan golongan arus utama.
Berjilbab sejatinya akan lebih menentramkan jika didasarkan atas pilihan sadar dan ketetapan hati yang kuat, bukan paksaan dari luar. Sebab, kita tidak pernah tahu seperti apa pengalaman spiritual seseorang. Hanya karena kita tidak relate, bukan berarti pengalaman orang tersebut tidak valid.
Sekolah sebagai institusi pendidikan seharusnya menjadi wadah untuk menanamkan dan menumbuhkan bibit-bibit toleransi, keberagaman dan inklusivitas pada anak didik. Termasuk mendidik mereka untuk menghargai pengalaman spiritual dan pilihan orang lain untuk berjilbab atau tidak.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Aturan Jilbab di Sekolah dan Bagaimana Memaknainya
Sabtu, 2 September 2023 10:34 WIB
Menulis Sejarah Perempuan
Selasa, 8 Agustus 2023 15:53 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0






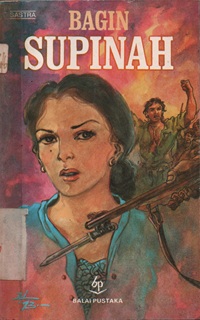

 99
99 0
0 Berita Pilihan
Berita Pilihan













