Menulis Sejarah Perempuan
Selasa, 8 Agustus 2023 15:53 WIB
Sejarah ditulis oleh pemenang. Sejarah yang selama ini lebih sering ditulis dalam perspektif maskulin membuat nama-nama perempuan terlupakan. Apa yang membuat nama dan peran tokoh perempuan dihapus dari lembar sejarah? Apa yang harus dilakukan agar perempuan dapat menulis sejarahnya sendiri?
Ketika diminta untuk menyebutkan tokoh perempuan dalam sejarah Indonesia, paling tak jauh-jauh dari sosok Kartini, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Dewi Sartika atau Fatmawati. Jangankan tokoh perempuan yang namanya terlupakan, tokoh populer seperti Kartini yang hari lahirnya kita peringati setiap tahun, sosok dan nilai dirinya saja sering direduksi jadi sebatas kebaya, sanggul, dan acara-acara yang sifatnya simbolis dan seremonial belaka.
Fenomena perempuan terlupakan dalam sejarah tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam mitologi, cerita rakyat, karya sastra dan film, perempuan lebih banyak diingat dan dipuja karena kecantikannya.
Tak heran sejarawan Amerika pemenang penghargaan Pulitzer, Laurel Thatcher Ulrich menuliskan kalimat ini dalam salah satu artikel ilmiahnya tentang khotbah pemakaman perempuan Kristen, “Well-behaved women seldom make history”. Kalimat yang populer dan sering dijadikan quote penghias kaos, mug dan berbagai benda lainnya ini kemudian dijadikan judul buku oleh Ulrich.
Apakah ini berarti perempuan tidak perlu berkelakuan baik untuk bisa menciptakan sejarah?
Faktanya, kalimat tersebut tidak sesederhana yang orang-orang pikirkan. Ulrich menjelaskan bahwa kalimat yang kemudian dijadikan judul buku itu sebetulnya ditujukan untuk mendobrak stereotip tradisional “good/bad girl” dan menyadarkan orang-orang bahwa laki-laki maupun perempuan yang mencetak sejarah memiliki latar belakang yang multidimensi dan tidak seharusnya dikotak-kotakkan secara hitam putih.
Jadi, dapat dikatakan kalau makna di balik kalimat “Well-behaved women seldom make history” tidak seharusnya direduksi untuk membenarkan perilaku problematik dan sensasional seseorang atau suatu kelompok.
Lantas, apa yang membuat perempuan terabaikan dari narasi-narasi sejarah?
Pasang Surut Gerakan Perempuan
Munculnya gerakan perempuan di ranah global sejatinya tidak dapat dilepaskan dari gelombang feminisme yang menyebar secara masif di Amerika Serikat pada tahun 1960-an dan 1970-an.
Fenomena ini sering dianggap sebagai feminisme gelombang kedua yang menuntut perubahan lebih besar, termasuk pada aspek politik, pekerjaan, keluarga dan seksualitas. Sementara feminisme gelombang pertama yang terjadi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 lebih fokus pada memperjuangkan hak pilih perempuan. Gelombang feminisme terus berlanjut hingga gelombang ketiga dan keempat yang terjadi mulai pertengahan tahun 1990-an dan awal 2010-an.
Indonesia memiliki cerita yang berbeda dengan Barat terkait perkembangan gerakan perempuan. Menurut aktivis perempuan Nursyahbani Katjasungkana, sebagaimana dirangkum oleh Magdalene, sejarah gerakan perempuan Indonesia terbagi dalam empat fase. Fase-fase tersebut adalah era Kartini hingga tahun 1945, periode pasca kemerdekaan hingga tahun 1965, era Orde Baru hingga 1998 dan tahun 1998 hingga sekarang.
Fase awal gerakan perempuan Indonesia dipelopori oleh pemikiran-pemikiran Kartini pada tahun 1900-an, terutama himbauan dari tiga bersaudara Kartini dalam koran De Locomotief.
Pemikiran-pemikiran Kartini inilah yang kemudian memicu kesadaran untuk membentuk organisasi perempuan. Atas prakarsa Boedi Oetomo tahun 1912, didirikanlah organisasi perempuan pertama di Jakarta, yaitu Poetri Mardika yang giat berkampanye mengenai pendidikan dan pengajaran.
Kemudian, organisasi-organisasi perempuan lain pun bermunculan seperti Pawiyatan Wanita di Magelang (1915), Aisyiah di Yogyakarta (1917), Wanita Susilo di Pemalang (1918) dan sebagainya. Perkembangan gerakan perempuan kian pesat, terutama pada tahun 1930-an.
Tonggak perkembangan ini dimulai dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan Pertama tahun 1928 di Yogyakarta yang menghasilkan poin-poin antara lain pelibatan perempuan dalam pembangunan bangsa, pemberantasan buta huruf dan kesetaraan dalam mendapat pendidikan, hak-hak perempuan dalam perkawinan, pelarangan perkawinan anak dan perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita.
Meski sempat surut pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, gerakan perempuan kembali menggeliat pasca kemerdekaan hingga 1965. Salah satu organisasi perempuan paling progresif kala itu, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) banyak melakukan kegiatan peningkatan kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Namun, pada kongres perempuan ketiga, Gerwani yang semula fokus pada isu feminisme, beralih menyuarakan isu sosial dan berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ironisnya, Gerwani, sebagaimana organisasi-organisasi sayap kiri lainnya, dilibas habis oleh Orde Baru melalui kampanye dalam surat kabar militer milik pemerintah tertanggal; 10-12 Oktober 1965.
Ketika Orde Baru berkuasa, negara melakukan kontrol penuh atas tubuh, seksualitas, fungsi dan peran perempuan, baik melalui UU Perkawinan, program KB yang fokus pada perempuan dan organisasi perempuan seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK.
Fase terakhir, yaitu pasca reformasi hingga sekarang, perjuangan gerakan perempuan dihadapkan pada menguatnya konservatisme agama, seksisme dan oligarki dalam kehidupan politik dan ekonomi serta diskriminasi gender dalam masyarakat. Tingginya angka kekerasan seksual, upaya pemiskinan perempuan dan konservatisme agama yang menghambat perempuan untuk memperoleh hak-haknya masih menjadi PR besar bagi perjuangan gerakan perempuan Indonesia hari ini.
Kurangnya Representasi Perempuan dalam Sejarah
Nadya Karima Melati dalam Jurnal Perempuan menjelaskan bahwa minimnya peran perempuan dalam sejarah tak lepas dari kecenderungan sejarah itu sendiri yang bersifat maskulin.
Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history. Penekanan “his” pada history menyebabkan sejarah banyak ditulis melalui perspektif laki-laki. Yang diceritakan pun tentang kejayaan laki-laki. Dengan demikian, mereka punya kuasa lebih besar untuk menentukan arah gerak sejarah dan peradaban di muka bumi.
Ingat adagium “sejarah ditulis oleh pemenang”?
Jadi, kalau peran perempuan begitu sedikit diabadikan dalam sejarah, adagium inilah jawabannya.
Sejarah gerakan perempuan sebetulnya jelas menunjukkan bahwa perempuan punya kontribusi untuk perubahan sosial. Namun, karena kepentingan politik pihak tertentu, gerakan perempuan ikut dibungkam.
Di Indonesia, pergerakan perempuan padam dan mengalami kemunduran di masa Orde Baru.. Hingga sekarang, jejak-jejak ideologi Ibuisme Negara yang mengontrol dan mendomestikasi perempuan telah tertanam di pikiran bawah sadar masyarakat dan masih dilestarikan lewat berbagai cara.
Citra lemah lembut, penyayang, menyukai kerapihan dan keindahan yang dilekatkan pada perempuan, sekilas tampak tidak berbahaya. Namun, ini sering dijadikan pembenaran oleh masyarakat yang patriarkis untuk mengekang kebebasan dan partisipasi aktif perempuan di ruang publik.
Perubahan tidak lahir dari ruang hampa. Lalu, bagaimana perempuan mau membuat sejarah, kalau ia sendiri dibuat tidak berdaya? Tanpa pendidikan dan pengetahuan yang mumpuni, bagaimana perempuan mencapai kesadaran akan hak-haknya? Tanpa kesadaran, tidak akan ada perubahan.
Perempuan Menulis Sejarahnya Sendiri
Kalau ingin perempuan bisa menulis sejarahnya sendiri, tak ada cara lain selain memberdayakan mereka. Beri mereka akses dan kesempatan untuk memberdayakan dirinya terlebih dulu agar bisa melakukan kerja-kerja yang bermanfaat bagi banyak orang.
Perempuan yang membuat sejarah memang selalu dihadapkan pada risiko seperti penolakan, kekerasan dan nama mereka yang sengaja dihapus karena kepentingan politik dan kekuasaan. Suara mereka terlalu lantang sehingga dianggap berbahaya bagi kemapanan budaya patriarki.
Namun, jika tidak ada yang berani mengambil risiko ini, perempuan hanya akan jadi penonton. Sementara untuk bisa menulis sejarahnya, perempuan harus menjadi subjek aktif dari suatu perubahan sosial. Dan untuk mewujudkannya butuh sistem dukungan yang solid dari berbagai pihak.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Aturan Jilbab di Sekolah dan Bagaimana Memaknainya
Sabtu, 2 September 2023 10:34 WIB
Menulis Sejarah Perempuan
Selasa, 8 Agustus 2023 15:53 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0






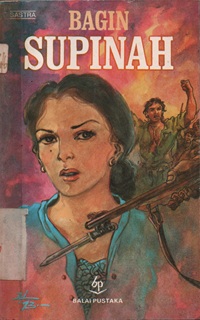

 99
99 0
0 Berita Pilihan
Berita Pilihan















