Seember Kerang dan Siput di Rumah Mama Yoram; Cerita Dari Lembata
Selasa, 26 Desember 2023 13:05 WIB
Perempuan paruh baya itu kemudian menjelaskan darimana sumber pangan harian yang biasa dia dan keluarganya konsumsi di rumah. Sebulan, dia hanya membeli paling banyak lima kilogram beras saja. Di dapur, dia sudah biasa mengolah jenis pangan lain sebagai pengganti beras seperti ubi, pisang, kacang-kacangan, dan jewawut.
Sore itu, Mama Yoram baru pulang bekarang ( aktivitas mencari ikan, kerang dan siput di pesisir laut). Rumahnya di desa Riabao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata tak jauh dari pesisir laut. Sebelum matahari terbenam, warga biasanya membawa ember dan tongkat bambu untuk bekarang.
Mama Yoram tiba di rumahnya dengan membawa seember penuh hasil laut berupa ikan, kerang dan siput. Ketika perempuan 50-an tahun itu sampai di depan pintu rumah, anak laki-lakinya yang paling kecil langsung berlari menyambut kedatangannya. Dia penasaran dengan apa yang ada di dalam ember.
Bocah empat tahun itu kemudian merengek minta diberikan kerang atau siput dari dalam ember untuk dimakan. Mama Yoram kemudian mengambil sejenis kerang (matadua), membuka cangkang, dan mengambil isinya dengan senduk. Isinya yang berlendir kuning disuapi langsung ke dalam mulut anaknya. Bocah itu tidak rewel lagi.
“Anak saya tidak suka makan mie instan. Mereka suka makan ini,” ungkap Mama Yoram sembari menunjuk kerang dan siput yang ada di dalam ember.
Saya dan Mas Yosep Budianto, peneliti dari Litbang Kompas, terkagum-kagum dengan apa yang baru saja kami saksikan.
“Bisa langsung dimakan mentah isi kerangnya, ya?” tanya Mas Yosep keheranan. Mama Yoram mengangguk sambil merekah senyum.
Seolah tak mau kalah dengan dua bocah tadi, kami pun memberanikan diri untuk memakan langsung lendir dalam kerang tersebut. Rasanya sepat di mulut, asin karena masih bercampur air laut. Lidah kami belum terbiasa saja. Tetapi makanan laut seperti ini memang bernilai gizi tinggi.
Mama Yoram adalah seorang petani sayur. Kebunnya hanya sepetak, tidah lebih dari satu hektar. Dia juga menanam tanaman lainnya seperti jagung, ubi, pisang, kacang-kacangan dan buah-buahan. Hasil kebunnya ini dia jual di pasar. Penghasilannya sebulan bisa Rp 200-300 ribu. Uang itu pun biasanya dikirim untuk anaknya yang sedang bersekolah di Lewoleba dan Kupang.
“Lalu kalau makan biasanya beli apa saja?” Mas Yosep penasaran, karena dengan pendapatan begitu Mama Yoram sekeluarga masih bisa bertahan hidup.
Perempuan paruh baya itu kemudian menjelaskan darimana sumber pangan harian yang biasa dia dan keluarganya konsumsi di rumah. Sebulan, dia hanya membeli paling banyak lima kilogram beras saja. Di dapur, dia sudah biasa mengolah jenis pangan lain sebagai pengganti beras seperti ubi, pisang, kacang-kacangan, dan jewawut. Sayur diambil langsung dari kebun sendiri. Ikan diperoleh dari hasil bekarang. Hasil olahan pangan lain dilakukan secara tradisional. Misalnya, siput mata tujuh yang difermentasi dengan garam dan cuka lontar sehingga bisa bertahan lama atau biji asam yang dikeringkan dan digoreng, dan lawar rumput laut yang juga biasa dicampur dengan siput. Ada banyak ragam pangan lokal yang biasa diolah untuk kebutuhan makan keluarga. Jadi, dia tidak bergantung sama sekali pada beras impor dan mie instan yang dijual di toko.
“Anak-anak tidak pernah sakit atau kekurangan makan,” ucapnya.
Melonjaknya Harga Beras
Pada akhir September 2023 yang lalu, Mas Yosep Budianto datang ke Lembata untuk meneliti keberagaman pangan lokal yang ada di NTT. Kabupaten Lembata jadi salah satu wilayah penelitiannya, selain di Kepulauwan Mentawai dan Sulawesi Tenggara.
Sebelum bertemu beberapa petani dan nelayan di tempat tinggal mereka, Mas Yosep menyampaikan kepada saya maksud penelitian yang akan diterbitkan secara berkala di Harian Kompas. Pada intinya, dia hendak mencari tahu sebab-sebab tersingkirnya pangan lokal yang dulu merupakan makanan pokok nenek moyang kita, “sebelum beras impor dan terigu menggantikannya di meja makan,” ucapnya.
Sebagai jurnalis, saya juga tertarik dengan riset pangan lokal tersebut. Saya teringat hasil liputan saya di Harian Pos Kupang selama hampir seminggu tentang kenaikan harga beras di pasaran. Masyarakat Lembata menjerit karena harga beras di pasaran melonjak drastis di kisaran harga Rp 14-15 ribu. Mayoritas beras yang dikonsumsi warga Lembata berasal dari Sulawesi dan Surabaya.
“Kalau gagal panen di Sulawesi atau Jawa maka kita di Lembata yang terdampak bencana kelaparan,” demikian biasanya orang berkelakar. Ya, terdengar lucu lelucon itu, tetapi kenyataannya memang demikian.
Apakah sejak dulu nenek moyang kita sudah mengkonsumsi beras dari Sulawesi atau Jawa? Kalau tidak, kenapa mereka bisa bertahan dengan pangan yang diproduksi di kebun mereka sendiri? Pertanyaan—pertanyaan ini mengganggu pikiran saya.
Mama Yoram adalah salah satu narasumber yang kami temui untuk melacak jejak pangan lokal di meja makan yang masih tersisa. Dia berdaulat atas pangannya sendiri. Tidak perlu bergantung pada mekanisme pasar.
Kampanye untuk mengembalikan pangan lokal di meja makan sebenarnya sudah lama digaungkan di Lembata. Dalam satu dekade terakhir muncul aktivis-aktivis yang mulai sadar dan peduli pada keberagaman pangan lokal di NTT, khususnya di Lembata.
Saya bisa menyebut nama Benediktus Assan, aktivis pangan lokal yang bekerja sama dengan Mama Maria Loretha (dari Adonara) untuk membudidayakan sorgum, salah satu sereal pangan yang sangat adaptif dengan iklim kering NTT. Selain itu, ada juga anak muda penggiat budaya Abdul Gafur Sarabiti yang berhasil menggerakan sekelompok anak muda untuk menghelat festival pangan lokal selama tiga hari di Kota Lewoleba. Ada juga Bernadethe Langobelen, salah satu narasumber penelitian Mas Yosep. Dia adalah seorang aktivis yang puluhan tahun mengabdi untuk pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA). Pasca badai seroja melanda Lembata pada tahun 2021, dia membeli sehektar tanah berbukit di sebelah timur Kota Lewoleba. Selain dijadikan tempat tinggal dan rumah pemberdayaan, kawasan itu juga dijadikan sumber pangan untuk kebutuhan makan setiap hari. Ubi, jagung, sorgum, kacang, sayur-sayuran ditanam di lahan perbukitan yang kering dan gersang.
“Makan apa yang kita tanam. Tanam apa yang kita makan,” adalah ungkapan yang Bernadethe utarakan untuk melukiskan upayanya mengkampanyekan pangan lokal. Setiap hari, dia dan puluhan ibu-ibu yang terhimpun dalam Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) memenuhi kebutuhan pangan harian dari apa yang ada di sekitar.
“Sekarang kita tidak lagi bicara ketahanan pangan. Kita bicara kedaulatan pangan,” dia menegaskan, seraya menunjuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar pekarangan rumahnya.
Berdaulat Pangan
Ketergantungan pada beras melemahkan ketahanan pangan NTT. Kondisi alam NTT yang tidak mendukung untuk memproduksi padi sawah secara optimal membuat provinsi ini defisit beras cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka produksi beras di NTT pada tahun 2022 hanya sebesar 442.842 ton, sementara tingkat konsumsi beras mendekati angka 1 juta ton per tahun. Situasi ini membuat NTT rentan mengalami guncangan pangan, seperti yang diberitakan Kompas.id, dalam laporannya, Inferioritas Pangan Lokal di NTT (11 Oktober 2023).
Dalam laporan yang sama disebutkan, NTT sebenarnya sangat kaya dengan beragam pangan lokal nonberas yang masih mudah dijumpai di pasar-pasar tradisional. Beragam pangan nonberas seperti jagung, singkong, dan ubi-ubian hutan, dengan mudah ditemui di pasar-pasar di Pulau Timor, Flores, Lembata dan Adonara. Sayangnya, tetap tak bisa dimungkiri ada persepsi budaya bahwa pangan lokal itu simbol kemiskinan dan ketertinggalan. Beras yang sudah dianggap sebagai pangan nasional di Indonesia dipaksakan menjadi makanan pokok.
Masyarakat tradisional memang lebih berdaulat pangan dibandingkan masyarakat modern seperti sekarang. Mereka punya banyak sekali pengetahuan lokal tentang pengolahan beragam jenis tanaman dan hasil laut untuk dihidangkan di meja makan. Perubahan pola konsumsi masyarakat tradisional akibat kebijakan pangan pemerintah yang bias beras turut memberi andil yang besar kepada proses menghilangnya tradisi menyantap pangan lokal. Keberagaman pangan musnah oleh keseragaman pangan sekaligus memusnahkan kedaulatan pangan masyarakat.
Kalau mau jujur, kita bisa melacak bagaimana pemerintah sejak era kolonial Belanda hingga Orde Baru ‘memaksa’ masyarakat untuk mengkonsumsi beras. Padahal, corak alam NTT yang kering, gersang dan minim hujan justru menyediakan beragam pangan yang adaptif. Ratusan bahkan ribuan tahun nenek moyang kita bertahan dengan keragaman pangan itu.
Dibukanya berhektar-hektar sawah irigasi di sejumlah daerah di NTT merupakan awal dari tersingkirnya pangan lokal di meja makan. Sawah irigasi yang cocok untuk tanah di Pulau Jawa atau Bali awalnya tidak dikenal di NTT yang mengandalkan sistem perladangan lahan kering ataupun sawah tadah hujan.
Pemerintah orde baru dengan program ‘Revolusi Hijau’ hendak mendongkrak produktivitas beras sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kekhasan pangan di wilayah tertentu. Sekali lagi politik pangan yang bias beras membuat warga NTT inferior dengan pangan lokal sendiri.
Masyarakat NTT lebih bangga menyajikan beras putih kepada tamu dibandingkan makanan lokal sendiri. Di Lembata, saat berkunjung ke desa-desa, saya masih sering mendengar permohonan maaf dari tuan rumah apabila mereka hanya bisa menyajikan ubi atau pisang kepada tamu daripada roti berbahan gandum atau biskuit. Padahal pemenuhan kebutuhan karbohidrat tidak hanya terbatas pada nasi.
Riset Litbang Kompas di NTT, Kepulauwan Mentawai dan Sulawesi Tenggara menampilkan setidaknya 13 jenis sumber karbohidrat selain nasi. Artinya pemenuhan asupan karbohidrat sangat mungkin dilakukan dengan mengkonsumsi pangan lokal. Wilayah NTT khususnya menyimpan setidaknya 24 jenis pangan sumber karbohidrat yang dikelompokkan menjadi delapan jenis yaitu; padi lokal, jagung, sorgum, jewawut, ubi, keladi, jelai dan labu (Beragam Jenis Pangan Lokal Menjadi Solusi Defisit Beras Nasional, Kompas.id, 20 Oktober 2023).
Beras yang harganya melambung saat ini dan mie instan kini jadi momok bagi masyarakat NTT. Anak-anak lebih suka makan mie instan daripada pangan lokal. Dan ini celaka!
Mengkonsumsi beras melebihi kebutuhan harian bahkan bisa berdampak buruk pada kesehatan. Ada hubungan erat antara konsumsi nasi putih dan risiko diabetes pada manusia.
Mengingat Mama Yoram
Mau sampai kapan kita menggantungkan kebutuhan pangan kita pada skema atau mekanisme pasar? Bagi saya, alasannya sederhana. Memilih untuk menyantap pangan lokal sama saja dengan memilih untuk tidak menggantungkan urusan perut pada mekanisme pasar. Inilah yang disebut berdaulat pangan.
Setelah seminggu di Lembata, Mas Yosep terbang ke Kepulauwan Mentawai dan lanjut ke Sulawesi Tenggara untuk melanjutkan riset yang sama. Dia pergi meninggalkan keresahan di dalam kepala saya.
Akhir Oktober lalu, saya masih mendengar percakapan ibu-ibu penjual makanan di Pelabuhan Larantuka tentang harga beras. Mereka saling bertukar informasi tentang toko mana yang masih menjual beras dengan harga lebih murah dan toko mana yang harganya sudah mahal. Obrolan mereka singkat, santai, tetapi sebenarnya meneropong isu yang sangat sensitif yakni ‘urusan perut’.
Perempuan di NTT mayoritas berperan penting mengatur kebutuhan dapur sampai di meja makan. Jika mereka resah dengan harga beras yang terus naik, maka kita semua pun juga wajib resah. Kegelisahan akan ada di mana-mana.
Siang itu, sebelum menyeberang dari Larantuka ke Lembata, saya melihat wajah ibu-ibu pekerja yang penuh harap. Tapi saya juga mengingat seember kerang dan siput di rumah mama Yoram.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Seember Kerang dan Siput di Rumah Mama Yoram; Cerita Dari Lembata
Selasa, 26 Desember 2023 13:05 WIB
Doa Ibu di Sepanjang Usia
Sabtu, 11 Maret 2023 06:28 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
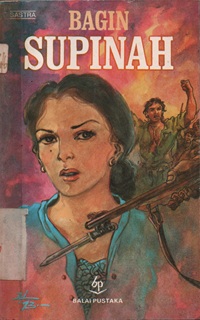






 99
99 0
0




 Berita Pilihan
Berita Pilihan











