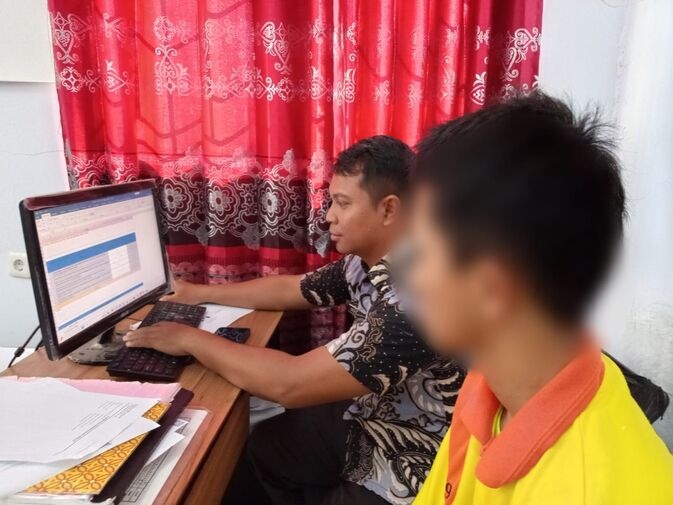Ketika Roh Meninggalkan Raga
Minggu, 25 Februari 2024 17:51 WIB
Cerita yang terinspirasi dari kisah nyata.
“Kita ngobrol pindah ke ruang keluarga saja, jangan di meja makan. Kalau di sini, Detha suka nguping dari kamar,” suara Mamaku sambil bangkit berdiri dan mengajak tiga orang adik, serta dua orang ipar, serta Papaku untuk bergeser ke ruang keluarga. Kamarku memang di samping ruang makan. Hampir setiap malam mereka berkumpul di rumah karena tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah.
Aku, tujuh tahun, menopangkan dagu di tangan, di samping Mama, tersenyum mendengar kata-kata Mama. Berjalan mendahului Mama, aku ikut duduk di karpet, menekuk lututku dan menyandarkan punggung ke lemari buku, serta terus mendengarkan pembicaraan mereka. Pembicaraan yang sering aku konfirmasi ke Mama besok paginya. Mungkin karena itu Mama berpikir aku menguping. Namun, tidak ada satu pun dari mereka mengetahui kemampuan aku mengeluarkan roh dari tubuhku.
Hampir setiap malam, sebelum tidur, aku merencanakan perjalanan sakralku. Tanpa ada yang melarang, tidak perlu usaha besar, aku bisa sampai di satu tempat dalam hitungan detik. Pernah aku pergi ke tempat saudara sepupu aku, Myrna, dan menemuinya minum dari botol susu, di umur dia yang sudah tujuh tahun.
Tempat yang paling aku suka adalah rumah Nenek dan Kakek dari Papa. Melihat mereka berdua duduk di meja makan, bermain kartu remi, yang biasa berakhir dengan Nenek marah karena dia kalah, membuat aku senyum bahagia. Mereka berdua sangat sayang pada aku.
Kehidupan berbeda, di malam hari ini, sangat aku sukai. Bangun pagi, pergi ke sekolah, mengikuti kegiatan rutin harian, sangat tidak aku sukai. Sebagai anak tengah, aku dikucilkan dan tidak dipedulikan oleh Mama, yang sangat menyayangi kakak lakiku, dan Papa, yang mencintai adik perempuanku. Pekerjaan di rumah, menyapu, mencuci, menyetrika, hingga beli bahan pangan ke toko di ujung gang, hampir selalu menjadi tugasku.
Sementara di sekolah, aku tidak mampu bersaing dengan mereka yang “berduit”. Memang sekolahku, di bilangan selatan Jakarta, tempat kumpulan kaum “borju”. Aku bisa masuk di situ karena Daniel, Paman aku, adalah Kepala Sekolah di sana. Pandangan melecehkan, cemooh hinaan, perkataan merendahkan adalah sebagian kecil dari sekian banyak kejadian yang harus aku alami setiap hari.
“Ah, bukan hal yang indah untuk aku lukiskan dalam kata-kata.”
Tetapi, keindahan itu ada saat malam hari ketika aku punya kebebasan pergi sesuka hati, bahkan sampai ke luar negeri, dan melakukan apa pun yang aku inginkan. Pada dunia berbeda itu, aku juga punya banyak teman. Mereka berhasil aku temui saat aku berada di dalam kegelapan. Tetapi, rupa mereka tidak seperti manusia, mereka bukan manusia.
******
Duduk, di bangku goyang, pada sudut kamar tidur Olivia, aku menikmati kerja yang dilakukan oleh teman-temanku. Mereka melempar boneka Barbie, menarik selimut dan kaki Olivia, menghembuskan nafas berat di telinganya, membolak-balikkan buku di samping tempat tidur. Sementara Olivia, matanya membelalak, tidak mampu berkata-kata, badannya bergetar keras, ketakutan sangat kentara di wajah putihnya. Dia, kawan satu kelasku, adalah anak yang suka menghina keberadaan aku.
“Hmmm... begitulah rasanya ketakutan yang aku rasakan setiap aku ke sekolah! Mungkin aku tidak bisa balas langsung tetapi aku sangat puas melihat kamu sekarang seperti ini, Olivia!”
Suara itu tidak keluar tetapi terngiang di kepala aku. Mataku menggambarkan kesenangan dan kebahagiaan melihat suasana yang dibuat oleh teman-temanku. Kepuasan terpancar di wajahku. Pembalasan sudah aku lakukan.
Bermain PS5, bersama “teman-teman”, terjadi dii dalam kamar Gunawan. Dia bukan kawan satu kelasku tetapi sering sekali dia mendatangi aku dan berkata, “Ngapain kamu anak tidak berada di sekolah ini. Gak malu apa sama kita-kita!” Tentu, aku hanya bisa menunduk saat dia berkata seperti itu.
Lainnya asyik menikmati tenda kecil yang ada di kamarnya dengan menyalakan dan mematikan lampu, serta riuh mengeluarkan suara yang aku tidak tahu artinya. Satu hal yang aku minta, pada si mata melotot, kepala menyala merah, dengan lidah menjulur, untuk merebahkan badannya sejajar dengan badan Gunawan dan terus memandangi wajahnya. Sesekali aku melirik untuk menikmati mata Gunawan yang melotot, tanpa kata, dengan badan tegang tidak bisa bergerak.
“Aku lelah!” seruku menghentikan semua kegiatan dan tidak lama kemudian aku terbangun di atas kasur di kamarku. Selalu ada keengganan meninggalkan dunia lainku. Tetapi aku pasti kembali ke dunia nyata karena yang lain itu hanya bisa terjadi di malam hari.
“Olivia dan Gunawan di bawah ke rumah sakit. Mereka sangat aneh, tidak bisa bergerak dan berkata-kata, serta matanya hanya bisa melotot,” suara Daniel berseru kepada Mama sesaat sebelum berangkat ke sekolah bersama kakakku dan aku. Iya, kami memang selalu ke sekolah dengan Paman.
Rumah Riana targetku berikutnya. Kebetulan malam ini, di hari Sabtu, empat temannya, bergabung di “Pinkie Girls”, menginap. “Pesta Piyama,” begitu mereka menyebutnya, sebelum keluar kelas siang tadi.
Sendiri, belum ada teman-temanku, berdiri di jendela sisi luar. Mataku memandang tajam ke dalam kamar, bercat pink, berukuran lima kali lima. Riuh rendah tawa mereka sambil meloncat-loncat pada kasur per, berukuran king. Aku memutar otak untuk menentukan siapa yang akan aku panggil dan bergerak maju menembus jendela, berdiri tepat di depan kasur.
Wanita, berbaju putih, menggebrakkan tangan pada meja belajar, di sisi kanan tempat tidur. Semua barang terlempar dan menghentikan tawa di kamar itu. Di karpet Barbie, yang memenuhi ruangan kamar, tiga teman kecilku menginjak-injak boneka-boneka mahal yang bertebaran. Di atas tempat tidur, si muka merah, dengan dua temannya, duduk berhadapan dengan kelima temanku, memandang tajam dan menjulurkan lidah. Aku, di samping jendela, merebahkan diri di sofa merah muda terang, menyeringai, menikmati pemandangan di depan mataku.
Paman memasuki rumah, wajahnya penuh cemas. Minggu itu, matahari baru saja menyembulkan wajahnya, Paman, yang terlihat lelah, memulai ceritanya, “Aneh sekali kejadian yang dialami anak-anak di Kelas Dua. Hari ini, lima anak perempuan mengalami hal yang sama seperti Olivia dan Gunawan.”
Aku terus menikmati roti mentega dan meminum susu buatan Mama, di meja makan yang tidak jauh dari ruang keluarga, tempat Paman bercerita.
“Semua ditemukan dalam kondisi ketakutan, tidak bisa bicara, dan mata mereka melotot memancarkan ketakutan yang mendalam,” Paman meneruskan cerita tentang kondisi yang ada.
Tampak Nenek, yang biasa mampir di rumah kami saat akhir pekan, merenung mendengar cerita Paman. Lalu dia melayangkan pandangannya ke kakak dan aku, yang masih menikmati sarapan pagi. Tatapan yang cukup tajam dan menusuk ke dalam dada.
“Apa yang ada di pikiran Nenek ya,” aku menundukkan kepala, kalah dengan pandangannya. Ada rasa bahwa Nenek tahu apa yang aku lakukan. Tetapi, aku rasa itu tidak mungkin.
Malam ini adalah Angga. Anak sombong tetapi bodoh dan tidak pernah belajar. Kesukaannya mengancam teman untuk membantu dalam segala tugas. Dia menganggap uang bisa berbuat semua. Untung memang sekolah kami tidak ada ujian. Semua nilai diberikan dalam bentuk tugas perorangan atau kelompok. Bisa dibayangkan kalau ada ujian, pasti dia tidak akan bisa mengerjakan.
Tidak sulit bagi aku untuk mengganggunya. Dia anak penakut, tidur pun bersama pengasuh, walaupun sudah berumur tujuh tahun. Menutup telinga si pengasuh supaya terlelap, teman-temanku mengambil ancang-ancang untuk mengusik tidur Angga. Televisi yang mati dan nyala terus menerus, ditambah suara musik menyanyikan lagu horor, mobil elektronik yang bergerak sendiri adalah sebagian dari banyak hal yang mereka lakukan.
Rencana malam ini tidak hanya Angga. Ada tiga anak laki lainnya menyatu dalam kelompok, yang mereka namakan “We Rule!” Tetapi aku tidak ikut ke semua tempat karena hanya Angga yang ingin aku kasih pelajaran paling keras. Dia, si ketua kelompok, adalah yang paling menyebalkan dan berbuat semua hal sesuka hati dia, tanpa memikirkan perasaan orang lain.
“Besok akan tambah lagi anak yang sakit, Paman,” pikiranku melayang ke Paman sambil melihat Angga yang kejang dengan perasaan bangga dan puas.
Apakah aku kasihan pada Paman dengan semua kejadian yang terjadi dalam waktu dekat ini?
Mungkin! Tetapi aku tidak akan berhenti melakukan ini! Mereka harus rasa!
Si sombong, si tukang cemooh, si tukang menghina, semua harus mendapat balasan yang setimpal. Teman-teman di sekolah aku tidak bisa “menyelesaikan” masalah seperti yang aku lakukan. Mereka tidak punya kelebihan mengeluarkan roh dari raga seperti yang aku miliki. Mereka tidak punya “teman-teman” seperti yang aku punya.
******
“Yes!” seruku saat sadar aku sudah di kasur, kembali ke kamar. Bayangan Angga masih jelas tergambar di kepala.
“Kenapa ‘Yes’, Detha,” suara Nenek di belakangku membuat aku sangat terhenyak.
Aku sama sekali tidak menyangka bahwa Nenek ada di belakangku, duduk di kursi meja belajar. Matanya tajam menatap, sama persis tatapannya saat mendengar cerita Paman tentang anak murid yang mengalami sakit aneh.
“Boleh Nenek dengar cerita apa yang Detha lakukan barusan, selain tidur,” pertanyaan yang menambah kekagetan aku.
“Apa maksud Nenek bertanya seperti itu?” suara dari kepalaku yang tidak mampu keluar karena aku masih mengatur rasa terkejut yang bertubi-tubi.
Nenek lalu bergeser dan duduk di sebelah aku. Tangannya mengangkat tubuhku, mendudukkan aku di pangkuannya, dan membelai rambutku. Nafas nenek yang halus menurunkan keteganganku. Aku tahu, Nenek tidak marah. Cerita mengalir deras dari mulutku. Semua lengkap aku sampaikan dan tidak ada satu pun yang aku tutupi. Tangan Nenek terus membelai rambutku.
Helaan nafas cukup dalam dan berat terdengar setelah semua kisah aku sampaikan ke Nenek. Matanya menerawang jauh, pikirannya melayang.
“Ternyata kamu yang meneruskan kemampuan Nenek,” akhirnya keluar kata-kata dari mulutnya. Pernyataan yang membuat aku bingung.
“Jadi Nenek seperti aku juga,” tanyaku setelah memahami apa arti ucapannya barusan.
Tidak banyak cerita lanjutan dari Nenek selain menyebutkan kemampuannya untuk mengeluarkan roh, yang sama seperti aku. Mungkin juga karena hari sudah sangat larut dan aku harus tidur karena besok adalah hari sekolah. Dia juga tahu adanya “sesuatu” yang lain di kehidupan itu. Tetapi Nenek tidak menyebut mereka “teman”.
“Detha, kita adalah orang yang beragama. Kamu tahu ajaran apa yang baik dan apa yang tidak baik. Walaupun kamu masih kecil, Nenek yakin kamu bisa membedakan itu. Berpikirlah dengan baik sebelum kamu melanjutkan semua. Ingat juga, Nenek selalu ada dan membantu kamu,” ucapan akhirnya sebelum meninggalkan kamarku.
Singkat! Tidak bertele-tele! Tapi perkataan itu membuat aku menimbang perbuatanku, “Lanjutkah aku? Atau berhenti di sini?”
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Bumi Indah melalui Kerangka 9R
Kamis, 24 Oktober 2024 17:37 WIB
Ketika Roh Meninggalkan Raga
Minggu, 25 Februari 2024 17:51 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan
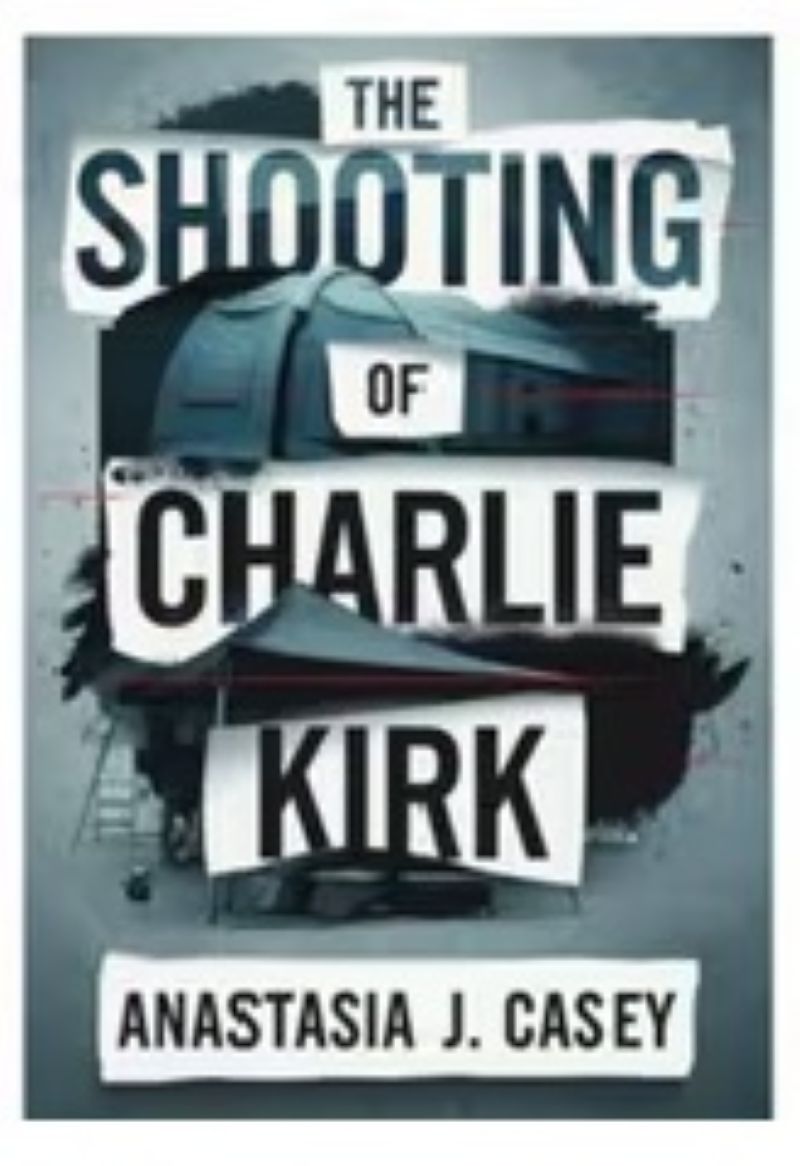



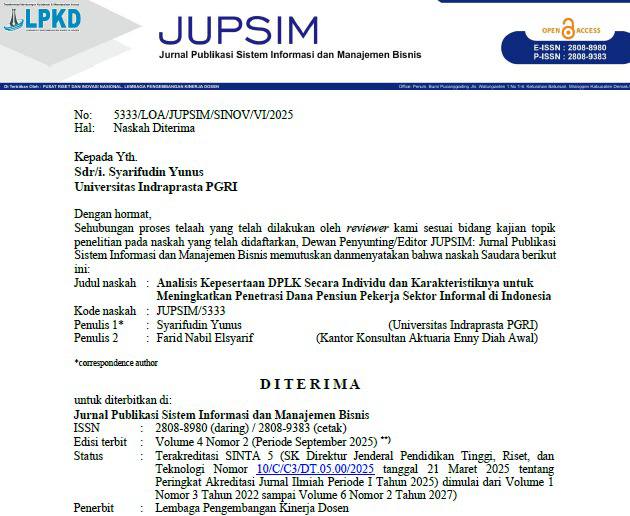


 99
99 0
0