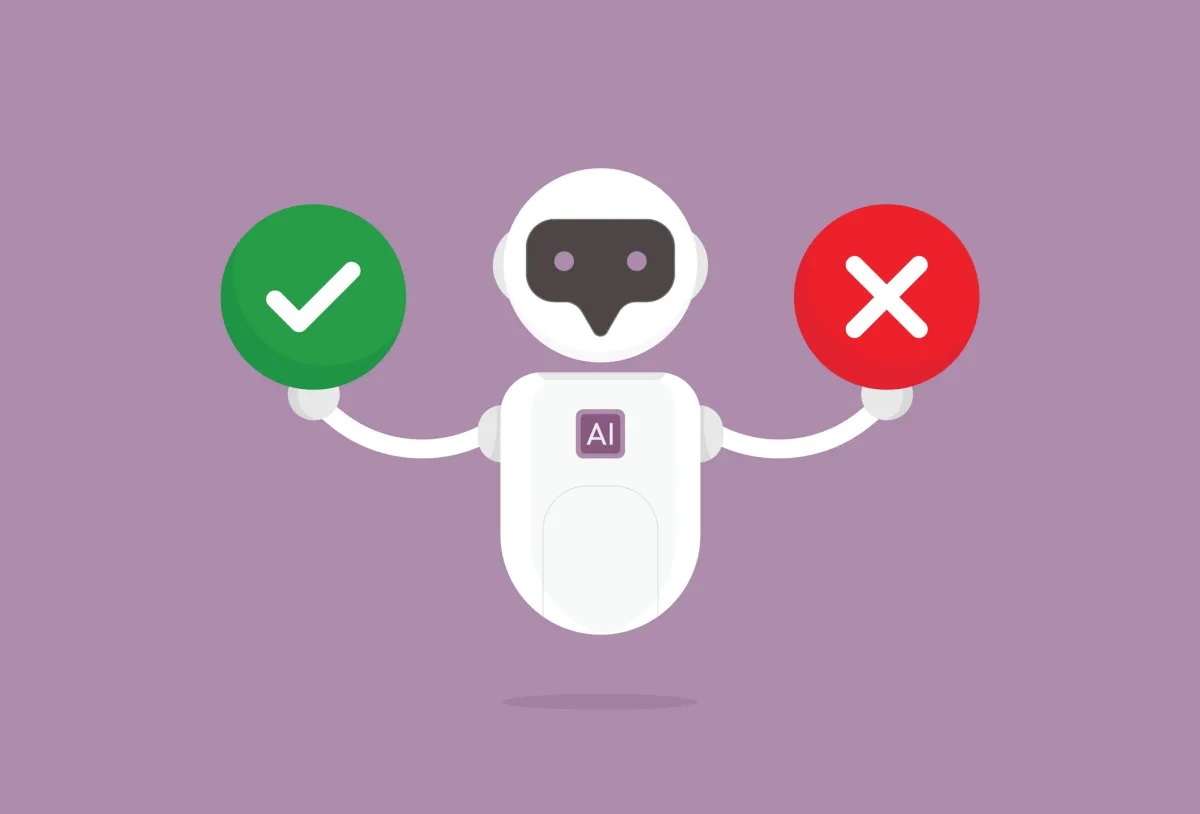Menulis Kumpulan Puisi Tanah Basah (2025), Kumpulan Cerita Anak Kejutan Manis Serabi Mbok Tonah di Pasar Pagi (2025) Antologi cerpen Klinik (2024), Puisi dan Film (2024), serta Kumpulan Puisi Biji Karet dan Bunga Sakura Musim Semi (2024).
Kenapa Indonesia Kita Terasa Makin Sempit dan Sumpek bagi Perbedaan?
Rabu, 16 April 2025 06:51 WIB
Menjadi berbeda bukanlah dosa. Kita bisa tidak sepakat, tanpa harus bermusuhan. Bahwa iman bisa menjadi jembatan, bukan jurang.
***
Suatu siang di bulan Desember, saya berada dalam forum diskusi di satu tempat di Daerah Istimewa. Hadir di sana anak-anak muda dari beragam latar belakang agama; Muslim, Katolik, Protestan, Buddha, hingga penganut kepercayaan. Kami tidak sedang merayakan hari raya agama tertentu. Kami berkumpul karena dilandasi oleh kegelisahan yang sama. Mengapa Indonesia terasa makin sempit dan "sumpek" bagi mereka yang berbeda?
Pertanyaan itu bukan datang begitu saja. Ia lahir dari pengalaman sehari-hari, dari berita tentang penolakan izin pendirian rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, komentar menyakitkan di media sosial, hingga stereotip yang terus diulang dalam percakapan kita tanpa disadari. Saya pernah tinggal di lingkungan yang nyaris seragam secara agama. Dulu saya mengira damai itu berarti semua orang sepakat. Namun, waktu dan perjumpaan mengajarkan bahwa kedamaian sejati justru terletak pada kemampuan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan tanpa rasa curiga atau takut.
Laporan Komnas HAM tahun 2023 juga menunjukkan bahwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi salah satu laporan tertinggi setiap tahunnya. Bahkan, intoleransi yang dilakukan oleh kelompok sipil meningkat drastis, terutama di kawasan perkotaan dan pinggiran kota. Fakta ini menegaskan bahwa kolaborasi lintas iman bukan lagi sebatas simbol atau kegiatan seremonial, tetapi kebutuhan mendesak untuk merespons tantangan global seperti ekstremisme berbasis agama, intoleransi digital, hingga polarisasi politik.
Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pernah berujar, “Tugas kita bukan mempersatukan perbedaan, tapi menyadari bahwa kita berbeda lalu hidup bersama.” Oleh karena itu, hemat saya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kolaborasi lintas iman bukan mimpi utopis atau basa-basi, tetapi alat yang ampuh untuk menjaga keberagaman bangsa. Namun demikian, kolaborasi ini harus melampaui ruangan seminar dan diskusi. Untuk itu perlu diwujudkan dalam tindakan nyata, bekerja bersama merespon persoalan sosial, bukan sekadar memamerkan toleransi.
Saya mengetahui sendiri di Sleman, ada sekelompok orang muda lintas iman membentuk komunitas yang peduli terhadap isu keberagaman. Di Yogyakarta, para perempuan dari berbagai latar belakang juga menjahit masker yang akan dibagikan kepada khalayak pada saat pandemi. Mereka tidak sedang membahas doktrin agama, tetapi sepakat bahwa untuk bertahan hidup, kita butuh kerja sama. Bukankah hal itu juga perwujudan iman?
Kolaborasi lintas iman menjadi semakin dibutuhkan di tengah dunia yang mudah terpecah oleh perbedaan. Ujaran kebencian menyebar lebih cepat daripada konfirmasi dan klarifikasi. Identitas agama sering ditarik-tarik dalam kontestasi politik. Bahkan di ruang pendidikan dan rumah ibadah, benih eksklusivisme kerap ditanam sejak dini.
Dalam konteks ini, teori interseksionalitas yang dikenalkan Kimberlé Crenshaw agaknya menjadi relevan. Teori yang menyadarkan kita bahwa seseorang bisa mengalami penindasan berlapis karena agama, identitas gender dan seksual, kelas sosial, atau lokasi tempat tinggal. Misalnya, seorang perempuan dari minoritas agama di pedesaan akan menghadapi tantangan yang jelas berbeda dari seorang Perempuan Muslim yang hidup di kota besar.
Saya merasa, jika kolaborasi lintas iman tidak peka terhadap konteks ini, maka yang terjadi hanyalah dialog di permukaan tanpa menyentuh akar masalah. Atau dalam istilah lain lazim disebut sebagai lazy tolerance; hidup berdampingan tanpa konflik, tapi juga tanpa kepedulian. Saling membiarkan, bukan saling memperhatikan. Karena yang satu merasa “itu urusanmu, bukan urusanku.” Padahal, kedamaian sejati bukan hanya soal tidak bertengkar, tapi juga tentang hadir saat yang lain mengalami luka.
Keberagaman Tak Cukup Dirayakan, Tapi Diperjuangkan
Kita sering mendengar kalimat, “Indonesia itu kaya akan keberagaman.” Sayangnya, kekayaan itu lebih sering menjadi slogan kosong ketimbang kenyataan. Keberagaman tak cukup dirayakan, ia harus dijaga dan diperjuangkan. Huston Smith dalam bukunya Why Religion Matters menuliskan bahwa semua agama besar pada dasarnya mengajarkan cinta kasih, keadilan, dan empati. Maka, kerja lintas iman bukan tentang menyatukan ajaran, tetapi menggali nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi akar semua keyakinan.
Tampaknya perlu untuk diingat bahwa kolaborasi lintas iman tidak boleh menjadi kedok dari tindakan dominasi. Catherine Cornille dalam bukunya The Im-possibility of Interreligious Dialogue mengingatkan pentingnya kerendahan hati dalam setiap dialog lintas iman, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok mayoritas (secara jumlah lebih banyak) atau memiliki posisi kuasa yang lebih besar. Dengan kata lain, kolaborasi lintas iman seyogianya dijalankan secara setara. Bukan ruang untuk memamerkan siapa yang paling toleran, tetapi ruang untuk saling mendengar, memahami, dan berjuang bersama. Tidak ada tempat bagi superioritas, apalagi patronase.
Urgensi kolaborasi lintas iman semakin terlihat jelas ketika kita melihat kasus terbaru. Di Jember, Jawa Timur, seorang pria berusia 55 tahun ditangkap karena menyebarkan ujaran kebencian bermuatan SARA melalui media sosial. Ia mengelola 17 akun dan secara konsisten menyebarkan konten yang menyudutkan kelompok keagamaan tertentu. Polisi menyatakan bahwa unggahannya berpotensi memecah belah masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Kasus ini menunjukkan bahwa intoleransi tidak hanya lahir dari prasangka, tetapi juga bisa dipicu oleh distribusi konten kebencian yang sistematis dan masif.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa teknologi ternyata bisa menjadi alat pemersatu atau pemecah belah-penghancur, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Maka, kerja lintas iman juga sebaiknya menjangkau ruang digital. Perlu ada inisiatif bersama antar komunitas lintas iman untuk membanjiri media sosial dengan narasi damai, memperkuat literasi digital, dan mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak pada provokasi berbasis agama.
Mulai dari Lingkaran Kecil
Saya tidak menulis ini untuk menawarkan solusi instan. Tapi saya percaya, setiap orang bisa memulainya dari lingkaran terkecil. Berteman dengan mereka yang berbeda agama. Mengucapkan selamat hari raya dengan tulus. Menghindari narasi kebencian. Bergabung dalam komunitas lintas iman di lingkungan sekitar. Jika Anda seorang guru, ajak murid berpikir kritis tentang perbedaan. Jika Anda jurnalis, tulislah narasi yang adil dan berimbang. Jika Anda aktivis, pastikan semua kelompok agama terlibat dalam advokasi. Jika Anda warga biasa seperti saya belajarlah mendengar tanpa menghakimi.
Kolaborasi lintas iman memang bukan jawaban atas semua masalah bangsa. Namun, ia menghadirkan ruang harapan, bahwa di tengah dunia yang kian terpecah, masih ada orang-orang yang memilih saling merangkul daripada mencurigai. Ia membuka jalan bagi keyakinan bahwa kita tidak perlu menjadi seragam untuk bisa berjalan bersama.
Terus terang, saya tidak tahu seperti apa wajah Indonesia dua puluh tahun ke depan. Tapi saya ingin anak-anak saya tumbuh di negeri yang tidak memandang perbedaan sebagai ancaman. Dan untuk itu, kita semua harus mulai sekarang, bukan besok, bukan nanti.
Kolaborasi lintas iman memang bukan jawaban atas semua masalah bangsa. Namun, menghadirkan ruang harapan, bahwa di tengah dunia yang tampaknya kian terpecah, masih ada orang-orang yang memilih saling merangkul daripada mencurigai. Ia membuka jalan bagi keyakinan bahwa kita tidak perlu menjadi seragam untuk bisa berjalan bersama.
Saya ingin semua orang memahami satu hal bahwa menjadi berbeda bukanlah dosa. Kita bisa tidak sepakat, tanpa harus bermusuhan. Bahwa iman bisa menjadi jembatan, bukan jurang. Dan untuk itu, kita semua punya peran untuk berbuat sesuatu sebagi bentuk kepedulian terhadap isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kita juga tidak perlu mati-matian menunggu negara, tokoh agama, atau pemimpin organisasi. Karena, perubahan bisa dimulai dari satu langkah kecil, yakni membuka hati. Dan langkah kecil itu bisa dimulai hari ini. Semoga.
penyuka kopi hitam dan jadah goreng
5 Pengikut

Kalau yang Tembak Menembak Algoritma, Lalu Kita Ini Siapa?
Selasa, 16 September 2025 17:38 WIB
Orang Muda dan Kesehatan Mental, Cukup dengan Konseling?
Selasa, 9 September 2025 11:50 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan







 96
96 0
0