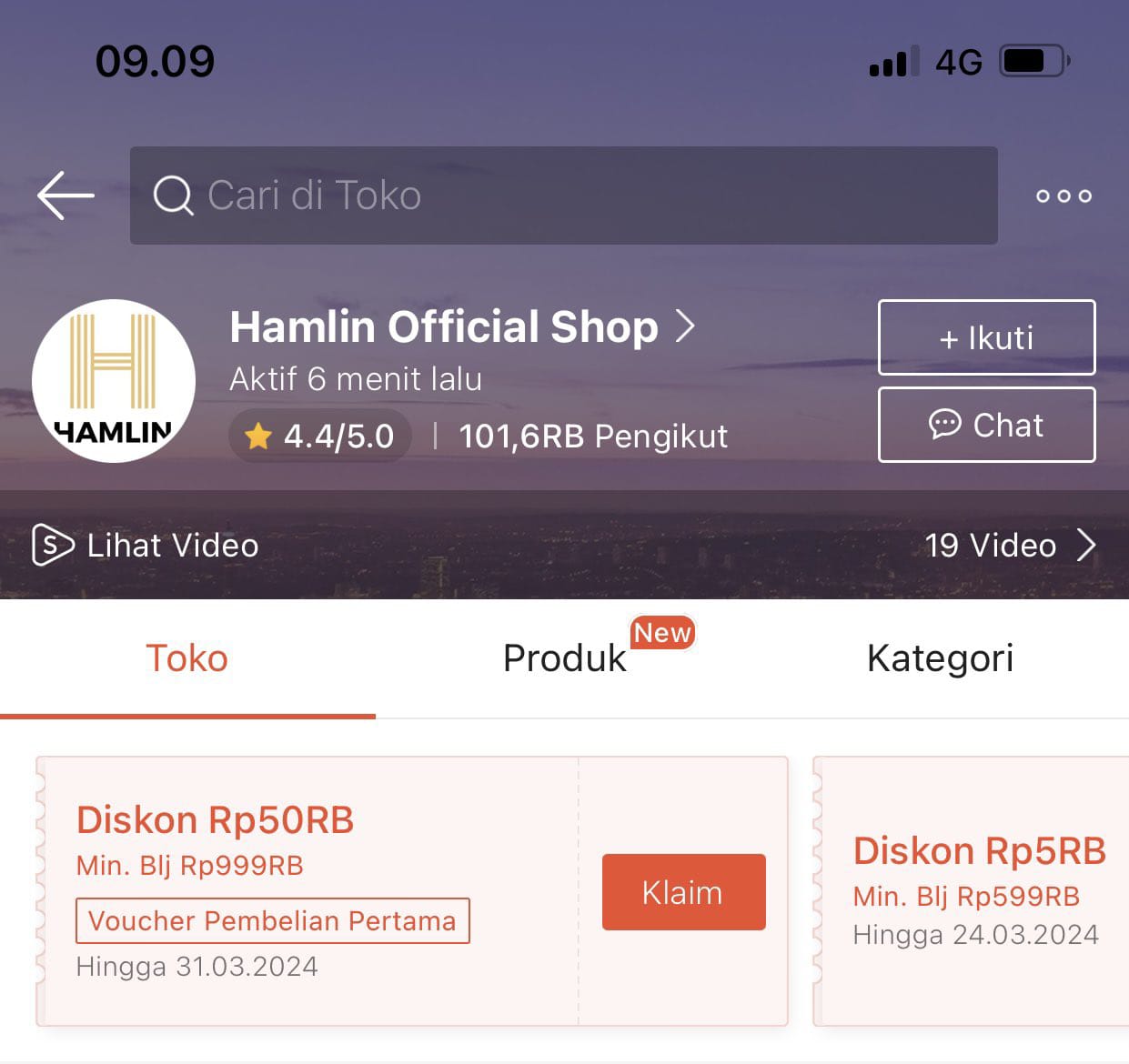Oleh: Fadly Rahman
Adalah Thomas Robert Malthus (1766 – 1843) yang dengan pesimis dalam karyanya An Essay of the Principle of Population (1798) berkata bahwa dunia akan selalu kekurangan pangan. Malthus beralasan, manusia sebagai konsumen pangan tumbuh menurut deret ukur (2, 4, 8, 16 dst); sedangkan pangan tumbuh menurut deret hitung (1, 2, 3, 4 dst). Dengan lain kata, keseimbangan di antara keduanya tidak sepadan.
Selain sebab alamiah (kematian), dan kesengsaraan (perang, sampar, dan kelaparan), Malthus lebih menyokong pengendalian moral seperti pelambatan pernikahan atau menahan nafsu seksual sebagai pengontrol jitu laju populasi. Sebagai positivis, Malthus beralasan, bahwa langkah vasektomis ini dipilih demi mencegah tanah-tanah yang sedianya ditanduri kebutuhan pangan tidak diambil alih oleh pemukiman manusia yang populasinya terus bertumbuh. Pemikiran Malthus sepintas mungkin ada benarnya. Tapi, Malthus hanya menangkap persoalan di permukaan, dengan tidak memeriksa persoalan di dasar apalagi di lokus-lokus lain yang mengandung masalah lebih kompleks.
Pandangan Malthus terlalu sederhana menangkap masalah hubungan ketahanan pangan dengan pertumbuhan populasi. Ia pun banyak dikecam oleh berbagai kalangan yang menilai teorinya begitu dangkal untuk mengatasi masalah ledakan penduduk. Meski sebenarnya ia memberi catatan kepada pihak-pihak yang telah salah menilainya, bahwa dirinya tidak sedang meramal bencana pada masa depan secara eksplisit.
Barangkali itu jugalah yang membuat sejarawan demografi semisal Peter Boomgaard dan David Henley tidak terperangkap pada cara pandang Malthusian. Boomgaard dalam studi sejarah demografinya di Jawa yang berkurun 1795 – 1880 masih memakai sekaligus mengkritik teori Malthus dalam memindai masalah lonjakan penduduk di Jawa. Tapi, Henley tidak melirik sedikitpun teori Malthus saat meneliti masalah hubungan pola cocok-tanam masyarakat peladang, iklim, ketahanan pangan, dan rendahnya populasi di Sulawesi Utara pada masa abad 19. Dengan menanggalkan cara pandang Malthus, secara leluasa ia menelisik akar masalah yang terjadi di kawasan tersebut pada masa itu.
Bahwa dikatakan Henley, kasus rendahnya pertumbuhan populasi di kalangan petani peladang tidak dapat dijelaskan hanya semata oleh faktor suplai makanan mereka, tapi juga lebih pada aspek non-ekonomi dan non-demografi. Jika misalnya berbicara faktor endemi dan epidemi penyakit serta geliat peperangan sebagai sebab masifnya mortalitas yang menguras populasi penduduk pada masa pra-abad 19, Malthus boleh ada benarnya. Tapi, pada masa yang relatif damai dan penyakit relatif sedikit mulai terjinakan oleh temuan-temuan medis, maka kasus rendahnya populasi di Sulawesi Utara adalah pengecualian dari kasus di Jawa. Maka teori Mathus pun menjadi membuntu. Ada evidensi unik yang membuat Henley menelisik apa akar masalahnya.
Sudah banyak dimafhumi bahwa subsistensi adalah pola umum dalam pertanian pada masa pra-abad 19. Namun, ketika kebijakan politik dan ekonomi kolonial merasuk masuk dalam kehidupan petani, citra subsisten secara sistemik mulai tercerabut. Berarti ini pun memengaruhi konsumsi pangan yang diasup sehari-hari. Baik di Jawa maupun di Sulawesi Utara pada periode antara 1820 - 1870, boleh dibilang punya rekam jejak yang tak jauh berbeda. Hanya kasus-kasus tertentu saja yang membedakannya.
Peneliti terdahulu seperti Scheltema(1936), mengungkap bahwa pada abad ke-19 di beberapa wilayah Jawa, produksi beras makin meningkat sebagai usaha pertanian, mengingat niaganya juga yang menguntungkan dan tingkat konsumsinya makin meningkat sebagai akibat bertambah luasnya tanah yang dijadikan pesawahan. Hanya saja keuntungan produksi beras pada paruh pertama abad ke-19 menjadi tidak sebanding dengan kesejahteraan penduduk sehubung penerapan Cultuurstelsel (1830 – 1870).
Pada masa Cultuurstelsel, kultivasi teh, kopi, indigo, dan gula menggilas produksi pangan. Tanaman kultivasi dikelola dan dihasilkan sebagai komoditas ekspor yang menguntungkan bagi perekonomian kolonial. Rakyat pribumi dari kalangan pria diharuskan bekerja di luar wilayahnya. Banyak istri dan anak-anak yang tertelantarkan dengan kondisi ini. Lahan pertanian sebagai sumber kebutuhan pangan pun menjadi beralih fungsi atau terbengkalai. Sebuah reportase pada 1847 dari pengkritik Cultuurstelsel, Baron van Hoevell, menyebutkan bahwa penduduk Jawa dilanda kemiskinan, kemelaratan, kelaparan, dan kematian akibat cara-cara Cultuurstelsel yang menghasilkan kesengsaraan bagi pribumi.
Cultuurstelsel adalah penanda mulai masuknya petani dalam sistem monetasi. Secara sistematis, pola subsisten tergusur. Tapi laporan Hoevell yang mencitrakan malapetaka agaknya tidak menyeluruh dan belum tuntas, bahkan menjadi gugur jika memakai temuan mengejutkan dari Boomgaard yang menyebutkan bahwa pertumbuhan jiwa di Jawa hingga 1880 rata-rata per tahunnya adalah 2,2 – 2,3 persen. Ini diartikan monetasi memberi efek rembesan (trickle down efect) tak terduga. Satu misalnya adalah permintaan mendadak atas tenaga kerja tidak terampil yang berusia muda sebagaimana diteorikan begitu baik oleh Coontz (1957) jadi sebab pemicu pertumbuhan populasi. Ketertarikan seksual antarpekerja muda; ditambah cukup tingginya tingkat kesuburan mereka saat menikah dalam usia dini disertai hasrat memproduksi banyak anak, menjadi alasan tingginya pertumbuhan penduduk di Jawa. Pemandulan fertilitas ala Malthus pun menjadi meleset dalam kasus demografi di Jawa yang menganut prinsip mental ”akeh anak, akeh rejeki.”
Maka, Jawa sungguh menjadi perbandingan menarik dengan studi Henley di Sulawesi Utara. Pada periode 1864 – 1866 wilayah-wilayah di Sulawesi Utara justru mengalami populasi yang rendah sebagai akibat anjloknya produksi beras sejak 1863 - 1865. Baru pada akhir dekade itu, seiring bangkitnya kembali panen beras dan jagung, populasi beringsut bangkit. Meski tidak terkena kebijakan Cultuurstelsel, akar masalah di Sulawesi Utara tak jauh beda dengan Jawa. Ketika kopi mengambil alih lahan padi, keadaan ini mengusik kehidupan masyarakat. Mungkin sekali kelaparan jadi sebab pemicu tingginya mortalitas sehingga menurunkan populasi. Tapi sebagaimana kasus di Minahasa, anomali cuaca juga dimungkinkan memengaruhi tingkat kesuburan tanah yang praktis berprengaruh pada gagalnya panen. Bahkan, sekalipun ada variasi pangan di luar beras dan jagung, hantu kematian ternyata tetap menyergap. Padahal Henley membuktikan pada masa-masa itu, epidemi penyakit cukup absen di Sulawesi Utara. Pikirnya, ada hubungan yang ketat antara anomali cuaca, produksi pangan, dan tingginya angka kematian sebagai musababnya.
Jika mencerna telaah Henley, masalah kependudukan begitu kompleks; sejejalin dengan masalah pangan yang memengaruhi hayat manusia. Henley menyadarkan, bahwa dengan tidak merusak ruang hidup, maka populasi manusia bisa terkendali. Ini kembali juga pada injeksi ekonomi makro (baca: negara) yang bertanggung-jawab menentukan naik-turunnya populasi dan ketahanan pangan.
Kenyataan ini sungguh masih didapati, hingga masa politik swasembada beras Orde Baru (Orba). Program kebanggaan Orba itu bahkan berjebah sukses hingga kawasan Papua. Meski kekuasaan Orba akhirnya berakhir, tapi program swasembada menyisakan dilema tersendiri. Itu tampak ketika beberapa tahun lalu daerah bernama Yahukimo dilanda kelaparan hebat, karena padi tak bisa lagi ditanduri di sana. Maka jelas, ’pembunuhnya’ adalah beras yang lahir dari program swasembada. Bukan karena faktor tidak ada beras. Tapi (politik) beraslah yang jadi biang tergilasnya kebiasaan konsumsi sagu di sana. Malthus bisa-bisa dibuat bingung dengan sengkarut ini. Dan masalah ini jelas harus dipahami benar oleh Pemerintahan Jokowi yang mengusung pembenahan sektor pangan sebagai resolusi tahun 2015 ini.
Ikuti tulisan menarik Fadly Rahman lainnya di sini.