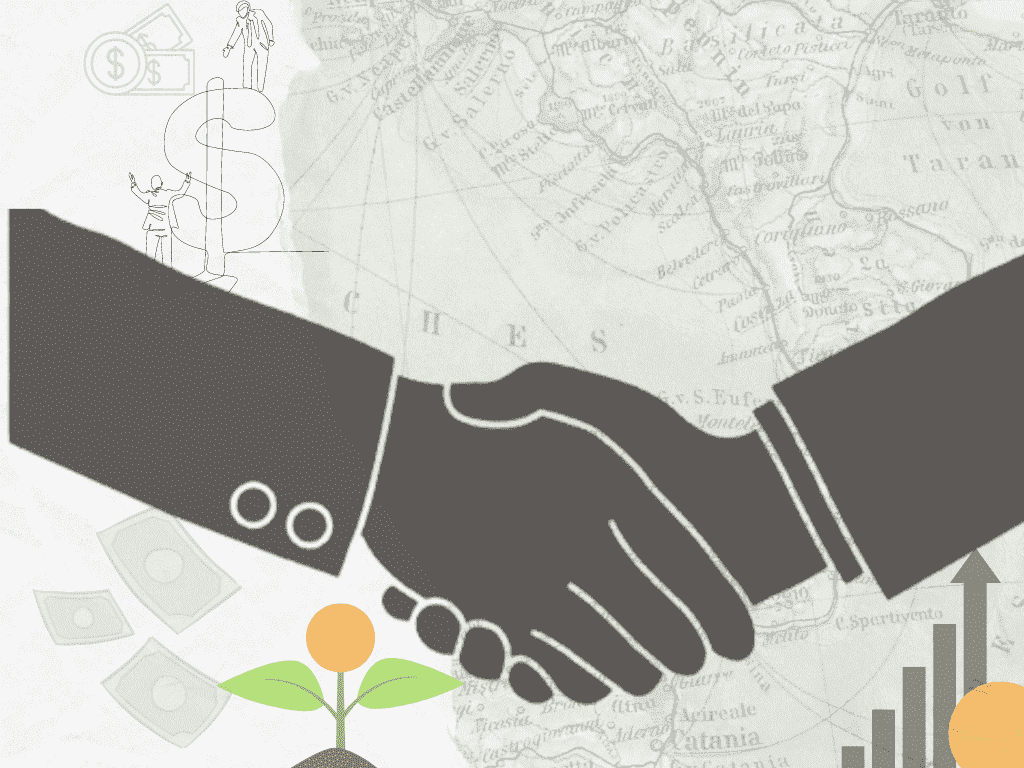Setelah melewati periode tidur panjang, apa yang dipuji sebagai ‘kebangunan demokrasi’ di negeri ini seperti berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Benih demokrasi yang ingin disemaikan, setelah berpuluh tahun dihimpit rapat-rapat, kini malah dicemari oleh kepentingan jangka pendek yang menepikan segala prinsip. Peluang bagi demokrasi yang sehat telah dihegemoni oleh pemenuhan hasrat yang tak putus-putus akan kuasa dan harta.
Kita belum memiliki hasil studi yang otentik dan memadai perihal relasi di antara ‘demokrasi baru’ dan korupsi di sini. Namun, kajian Olson (2002) di wilayah Eropa Timur pasca-komunis memberikan gambaran yang pesimistis. Korupsi mekar tidak ubahnya buah dari ‘kebangunan demokrasi’. Sembari bersaing, para elite kekuasaan berusaha ‘saling mengerti’ bagaimana masing-masing menghimpun sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan mesin politik.
Demokrasi yang diharapkan menjadi jalan bagi penguatan kembali rakyat yang berdaulat telah ditawan oleh mereka yang memanfaatkan kapital dan kemakmuran individu untuk membeli suara. Demokrasi yang diharapkan mampu membebaskan rakyat dari kungkungan trauma sejarah kehilangan momentum yang dibutuhkan untuk perubahan. Demokrasi ditawan oleh kepentingan kelompok, bahkan elite individu. Politik yang membebaskan, meminjam kata-kata filsuf Prancis Alain Badiou, menjadi sangat lemah.
Demokrasi kita juga ditandai oleh kehadiran politikus oportunistik yang begitu mudah berpindah-pindah partai—sebuah perilaku politik yang mencerminkan tidak adanya cita-cita perjuangan dalam berpolitik. Bagi mereka, partai politik adalah tunggangan dan rakyat hanyalah isu yang dijual menjelang hari pemungutan suara. Sesudah suara rakyat diperoleh, koneksi diputuskan. Berpolitik sebagai jalan untuk memperjuangkan suatu gagasan kini semakin langka.
Kita berada di dalam suatu kurun ketika gagasan menjadi sesuatu yang ganjil. Kita menapaki jalan, entah menuju ke arah mana, yang menyimpang dari rintisan para pendiri bangsa. Kita disibukkan oleh isu-isu yang tidak strategis dan tidak menjangkau masa depan. Kita direpotkan oleh isu-isu yang melelahkan, menyita waktu, energi, dan perhatian bersama padahal isu itu bukan yang utama dan mendasar bagi sebagian besar rakyat negeri ini—sebuah gambaran ‘the tragedy of the commons’ dalam pelukisan Garret Hardins (1968).
Kekuatan-kekuatan oligarkis terbukti lebih berpengalaman dalam mencuri peluang. Di tengah transisi dari rezim Orde Baru menuju konsolidasi demokrasi, kekuatan-kekuatan oligarkis telah menyelinap dan mengambil keuntungan dari situasi yang tidak pasti. Seperti dikatakan oleh Jeffrey Winters (2012), kejatuhan Suharto melahirkan efek ganda dengan konsekuensi saling bertentangan. Ketika transisi menuju demokrasi tengah diupayakan, saat itu pula berlangsung transisi oligarki sultanistik menuju oligarki penguasa kolektif yang tidak jinak dan tidak mampu dikendalikan oleh hukum.
Masyarakat madani (civic society), di mata Winters, terlalu lemah untuk menangkap peluang kembalinya demokrasi, sementara para oligark bergerak lebih cepat untuk mendominasi demokrasi. Demokrasi elektoral bahkan memberi cara baru bagi oligark untuk mengupayakan kepentingan mereka. Lembaga-lembaga demokrasi justru menyediakan arena bagi maraknya kerja sama dan persaingan antar oligark.
Studi Christian von Luebke (Democracy in Progress – or Oligarchy in Disguise?, 2011) menguatkan hal ini, bahwa kepemimpinan paska-Suharto bukan hanya dipengaruhi oleh karakteristik individual, tapi juga oleh ‘topografi’ kekuasaan, seperti konsentrasi dan konektivitas politik dengan aset sosio-ekonomi. Kejatuhan Suharto, menurut Robison dan Hadiz (Reorganizing Power in Indonesia, 2004), membuka jalan bagi oligarki bisnis-politik untuk menyusun kembali kekuasaannya melalui akomodasi baru dengan berbagai kepentingan populis dan predatoris di dalam masyarakat dan institusi-institusi baru di masa demokrasi.
Kekuatan oligarkis telah menguasai sebagian besar media, yang semula menjadi tumpuan harapan dalam ikhtiar memulihkan demokrasi. Dengan kekuatan kapitalnya, kekuatan oligarkis menguasai media dan partai politik sehingga menghimpun tiga sumber daya yang luar biasa di dalam satu tangan: bisnis, media, dan politik. Upaya melindungi forum publik dari dominasi para elite dan kepentingan khusus dengan agenda-agenda yang tidak konsisten dengan kepentingan publik kini menjadi tugas yang semakin sukar.
Dalam persaingan kuasa itu tidak berlangsung pertarungan gagasan mengenai Indonesia masa depan. Seperti apa Indonesia masa depan yang diimajinasikan oleh para elite? Ketika kata-kata berhenti menjadi jargon dan klise, kita pun kehilangan spirit dan cita-cita kebangsaan yang diimajinasikan oleh Soekarno, Hatta, Tan Malaka, dll. Sebagai bangsa, kita mengalami apa yang disebut oleh Jeffrey Goldfarb (Civility and Subversion, 1998) sebagai ‘systemic deliberation deficit’.
Lalu lalang percakapan tidak beranjak dari telaah yang dalam. Keriuhannya dipandu oleh refleks semata. Sebuah kecurigaan sanggup melontarkan debat berkepanjangan. Di titik itu yang disebut rakyat hanyalah penonton belaka dari lalu lalangnya percakapan yang tidak deliberatif. Laku politik sepertinya telah dikendalikan oleh apa yang disebut Bertrand Russell sebagai ‘slogan-slogan hampa yang tidak mengandung kebenaran’. Di saat seperti itu, sebagian besar inteligensia yang diharap dapat memberadabkan kontestasi politik dan mensubversi konsensus-konsensus yang hanya memuaskan kaum elite sendiri ternyata kian terpesona oleh kekuasaan.
Kita seperti kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara adab. Kekerasan semakin menjadi pilihan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan. Kita bagaikan dibimbing oleh rasa curiga, takut, dan marah dalam mengatasi persoalan. Kekerasan menjadi banal, lumrah, jamak, bukan saja di tingkat negara, massa, tapi juga individual dengan kualitas yang kian mencemaskan.
Rakyat nyaris kehilangan harapan karena hukum yang adil tak kunjung tegak. Massa telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan-kepentingan politikus, partai, elite ekonomi, dan bahkan otoritas keagamaan yang menghegemoni kebenaran. Massa bukan lagi persenyawaan orang-orang yang secara sadar memperjuangkan gagasan bersama secara mandiri.
Di tengah bangsa yang tanpa arah ini, solidaritas nasional tidak terwujud oleh karena tidak adanya kepemimpinan visioner yang sanggup merekatkan kembali ikatan-ikatan sempit yang mencuat dan menguat kembali. Pertikaian dan kekacauan telah memperlihatkan secara telanjang bahwa kepemimpinan yang lemah tidak sanggup mengemudikan arah perubahan. Ketidakmampuan mengambil prakarsa mendorong berbagai pihak bertindak atas kehendak sendiri. Wewenang yang besar terbukti tidak cukup punya arti di tangan kepemimpinan yang gamang. (Tulisan ini pernah dimuat di Koran Tempo, 13 Mei 2013; foto: tempo.co) ***
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.