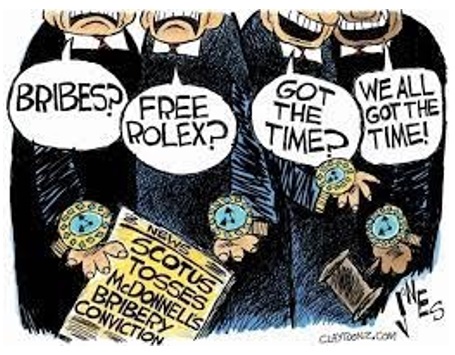Selendang Mama
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Di antara siang dan malam ada warna jingga yang membias kala senja, warna perpaduan merah dan kuning menjadi oranye.
#Novel Vivian Zen
Kisah sebelumnya: Kekasih Terbaik
Pikiranku blank. Berjam-jam duduk di depan komputer dan tidak melakukan apa-apa. Bolak-balik membaca naskah skenario dan tidak masuk-masuk. Badanku di sini, entah pikiranku ke mana. Rasaku kembali hampa.
Suara teve dari luar kamar membuatku segera bangkit.
Zakia sedang menonton teve yang sedang membahas kasus mama. “Kakak sudah bilang jangan nonton teve,” kutekan tombol off di remote control.
“Aku bosan, Kak. Dan belum ngantuk.”
“Kamu bisa melakukan hal lain. Baca komik.”
“Udah kubaca berulang-ulang komiknya. Udah bosan.”
“Kamu bisa main game.” = “Bosan juga dengan game yang itu-itu aja.”
“Udah mau jam sembilan. Yuk kakak temani tidur. Besok pagi kamu harus sekolah.”
“Zakia kangen mama.”
“Jadi itu alasanmu menyalakan teve?”
“Iya,” wajah Zakia muram.
“Yuk kakak tunjukkan sesuatu,” kuambil selendang warna biru milik mama di dalam laci. “Ini selendang, papa yang beliin pas mama ulang tahun. Setelah papa meninggal, mama sering memakai selendang ini dan mama selalu merasa bersama papa. Sekarang selendang ini milikmu,” kusampirkan selendang ke leher Zakia.
Zakia mendekap selendang itu dan naik ke atas kasur.
“Oke. Kamu bobo, kakak menemani kamu sambil mengetik.”
Zakia mengangguk kemudian memeluk guling.
Aku kembali tenggelam dalam pekerjaanku. Aku harus konsentrasi. Aku ada di sini saat ini, aku hidup dalam momen sekarang, bukan di masa lalu atau di masa depan. Dan ketika kuputuskan untuk konsentrasi, aku mengambil posisi duduk tenang dan mulai mengedit.
Kenapa banyak yang berubah begini plotnya. Kenapa Akbar tidak bilang padaku. Ceritanya datar, tidak menarik.
Langsung saja kutelepon Akbar. “Akbar, plot awalnya kok tidak sesuai dengan yang kita sudah diskusikan?”
“Aku ubah. Romi setuju. Pak Jimmy maunya cepat, itu dibuat dalam keadaan buru-buru. Aku sambil menangani kasus juga, Romi juga tambah kesibukan baru di kampusnya. Memang jadinya gak maksimal.”
“Kita kan sudah punya timeline? Pak Jimmy berpegangan pada timeline kan?”
“Aku nggak sempat melakukan riset, lagi menangani kasus keluarga yang rebutan warisan.”
“Akbar, kok kamu berubah? Kok jadinya seperti mister seribu alasan?”
“Dan kamu bisanya marah-marah?”
“Sorry. Aku nggak marah, Akbar. Besok bisa ketemu? Kalau bisa, aku akan telepon Romi setelah ini.”
“Sore bisa.”
“Ok kita lanjutkan besok ya, Akbar. Maaf ya, kalau kamu merasa kumarahi. Jujur aku nggak marah, cuma kaget. Kualitas tulisanmu menurun dibanding sebelum-sebelumnya.”
“Iya tadi sudah kubilang, buatnya sambil buru-buru. Gak konsen. Ternyata kita berdua mengalami kesulitan tanpa kamu. Makanya aku senang kamu sudah kembali dan sudah bisa marah-marah lagi.”
“Aku nggak marah. Please deh Akbar.”
“Hahaha…. oke sampai besok.”
Berantakan semuanya. Naskah yang sudah ada ini tidak bisa dipakai. Ini sih klipingan google. Yang paling tepat adalah membuangnya ke tempat sampah, dan menulis yang baru dari awal. Aku harus menemukan cara untuk menghidupkan film ini.
The Money, The Money. Banyak konflik terjadi karena uang. Bahkan bagi sebagian orang, uang adalah berhala, tuhannya, disembah-sembar, dikejar-kejar dengan segala cara.
Sial! Kenapa aku jadi ingat bajingan itu. Om Fadil maksudku. Aku merasa hatiku mulai lunak dan bisa menyebutkan namanya, Om Fadil.
Pada Fedy, Gathan cerita, sedang terjadi masalah besar di perusahaan advertising tempat Om Fadil bekerja. Om Fadil mencium gelagat tidak beres pada bosnya yang membuat iklan layanan masyarakat dengan seseorang dari instansi pemerintah. Iklan layanan itu anggarannya jauh melampaui harga standar. Dan uang itu tidak masuk ke rekening perusahaan. Om Fadil mengancam bosnya, akan melaporkan indikasi kolusi dan korupsi itu ke KPK. Sebelum Om Fadil membuktikan ancamannya, mama dibunuh dan Om Fadil dijadikan tersangka.
Gathan cerita, Om Fadil sudah menyampaikan kesaksiannya itu, tapi dia hanya ditertawakan oleh polisi yang menginterogasinya. Bahkan aku pun tidak percaya, tapi sekarang… dan kalau ingat simbol P di lengan mama, ingat sikap Om Fadil yang sepertinya tulus, sama seperti Fedy, aku mulai skeptis dan mempertanyakan semua ini. Benarkah Om Fadil dijebak oleh sebuah konspirasi antara orang perusahaan dan orang pemerintahan? Sementara sekarang Om Fadil sudah jadi tersangka dan terancam hukuman mati karean tuduhan pembunuhan berencana.
Pada akhirnya aku tidak bisa menghindar. Mungkin ini jalan yang harus kulewati. Melibatkan diri dalam sebuah masalah besar yang aku tidak tahu apa-apa, dan aku harus mencari tahu. Aku tidak pernah mau mengangkat telepon Gathan dan Andika, dan sekarang aku merasakan mereka sama terpukulnya denganku.
Aku harus mulai dari mana.
Suster Margi, kenapa tiba-tiba menghilang dan polisi tidak menganggapnya penting. Padahal suster itu bisa menjadi saksi kunci. Suster Margi, aku harus menemukannya.
Aku harus mempelajari kasus mama. Kejalajahi portal-portal berita yang membahas kematian mama, termasuk beragam spekulasi yang mengiringinya, termasuk analisis orang-orang yang menamakan diri pengamat dan membuat asumsi-asumsi dari yang masuk akal sampai tidak masuk akal.
Tiba-tiba aku merasa bodoh dan harus menelepon Fedy. “Besok aku tidak bisa jemput Zakia, gimana ya?”
“Kamu sih suka memanjakan Zakia. Harusnya dia diajari naik kendaraan umum pulang pergi sekolah.”
“Fedy, Zakia baru saja diculik.”
“Huh sorry, tak terpikirkan.”
“Kamu lagi di mana sih?”
“Tadi habis latihan, temen-temen ngajak ngopi di kafe.”
“Sekarang udah pulang?”
“Masih sama temen-temen.”
“Sebentar lagi pulang kan?”
“Iyaaa. Besok mau ke mana kamu memangnya?”
“Ada yang harus kukerjakan. Ini soal pekerjaan.”
“Tidak bisakah kamu menjawab pokok pertanyaan? Tidak seperti diplomat?”
“Aku mau mencari Suster Margi.”
“Bukannya kamu percaya polisi?”
“Entah kenapa aku berubah pikiran.”
“Kamu membuatku cemas.”
“Aku punya rencana, dan tidak bisa dihentikan. Aku memikirkan ucapanmu yang meragukan Om Fadil adalah pelakunya. Baru saja aku memikirkan dengan serius, semua ucapanmu tentang cerita Gathan. Aku merasakan sesuatu, ini bukan pembunuhan biasa.”
“Jangan pakai perasaan.”
“Aku pakai pikiran juga.”
“Harus ada yang menemani kamu.”
“Aku bisa ajak Akbar atau Romi.”
“Jangan Akbar, Romi saja.”
“Jadi besok Zakia gimana?”
“Ada mobil jemputan kan di sekolahnya?”
“Ah ya bodohnya aku.”
Kadang aku terpaku pada masalah-masalah besar, tapi harus bertanya pada Fedy untuk urusan antar jemput Zakia.
Oke. Masalah Zakia terpecahkan. Tapi, kalau Zakia pulang ke rumah, dia akan sendirian.
“Fedy, aku gak tahu besok pulang jam berapa. Di rumah, Zakia nggak ada temannya.”
“Ke Pejaten aja.”
“Tidak apa-apa kan?”
“Sikapmu seperti orang lain, Vivian. Aku sudah nyaman sama kamu. Tapi kamu sedikit-sedikit merasa tidak enak, sungkan, tipikal wong Jowo.”
“Makasih, Fedy. Kamu mau pulang jam berapa?”
“Sebentar lagi.”
“Sebentarnya kamu kali ini berapa lama?”
“Kok sinis gitu.”
“Kamu perlu istirahat, Fedy.”
“Ya udah, aku pulang sekarang.”
“Nah gitu dong. Hati-hati di jalan ya.”
“Iya. Kamu hati-hati juga besok. Sudah mulai memasuki wilayah berbahaya lagi. Cari-cari masalah.”
“Fedy.”
“Apa?”
“I love you.”
“I love you.”
Kututup ponsel dengan perasaan lega. Aku merasa semua berjalan sebagaimana seharusnya. Ternyata benar kata Bu Fauziah, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu adanya di dalam hati dan pikiran kita sendiri, bukan tergantung apa pun yang di luar diri.
Masalahnya tetap sama. Mama menjadi korban pembunuhan, dan belum jelas siapa yang membunuhnya. Tapi, aku merasa lebih tenang sekarang. Ada sesuatu yang aku bisa kerjakan.
Bu Fauziah bilang, sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Aku berusaha mempercayainya. Walaupun sebenarnya aku tidak begitu yakin, kalau diri kita tidak mengusahakan sesuatu.
Kumatikan komputer dan aku tidur di samping Zakia. Memejamkan mata dan berdoa.
***
Pagi, aku bangun dengan keringat dingin. Badanku rasanya remuk redam. Aku bermimpi berada di pulau yang hilang itu. Paula dengan senapan di tangan mengejarku di tengah hutan. Aku tersandung batu dan jatuh. Saat Paula mau meledakkan senapannya, aku terbangun.
Oh God sudah jam tujuh.
“Zakia bangun. Kamu telat ke sekolah.”
“Bukan salah Zakia ya, ini salah kakak,” Zakia turun dari kasur.
“Udah nggak usah cari salah-salahan. Cepat mandi dan kita berangkat,” aku berlari ke dapur, membuat roti cokelat untuk Zakia sarapan di jalan.
“Aku malu datang terlambat, Kak. Udah seminggu lebih gak masuk, eh begitu masuk, telat.”
“Nggak apa, daripada nggak masuk.”
“Aku malu. Aku nggak mau datang terlambat.”
“Terus gimana?”
“Besok aja sekolahnya.”
“Terus kamu mau ngapain di rumah? Kakak mau pergi.”
“Aku ikut Kakak.”
“Tidak untuk kali ini.”
“Kenapa?”
“Jangan bertanya lagi dan cepat ke kamar mandi.”
“Kakak kok jadi galak. Nggak kayak mama.”
“Dan jangan banding-bandingkan kakak dan mama. Dan mulai besok, kamu latihan bangun pagi sendiri. Tidak harus menunggu dibangunkan kakak.”
“Kakak aja suka kesiangan. Giliran Zakia nggak boleh.”
“Cepat ke kamar mandi, dan jangan berdebat.”
“Aku nggak mau telat ke sekolah.”
“Aku nggak minta pendapatmu.”
“Uuh Kakak jahat,” Zakia bersungut-sungut dan akhirnya masuk kamar mandi.
Begini ya repotnya jadi orangtua. Biasanya ada mama, kalau aku kelelahan dan sulit bangun, mama akan membangunkan.
Setelah Zakia selesai mandi, giliran aku mandi dengan cepat.
Pagi yang serba terburu-buru. Huh, tidak enak rasanya.
Sepanjang jalan, Zakia ngomel terus, tapi yang penting dia mau ke sekolah. Dan sampai di sekolah, pintu gerbang sudah digembok.
Seorang satpam melihat kami dan membukakan pintu. Aku harus melapor pada petugas piket, menjelaskan kenapa Zakia telat.
Tapi ternyata reaksi orang-orang berbeda dari yang kubayangkan. Mareka heran kenapa Zakia sudah masuk.
“Saya baca berita, katanya Zakia syok, trauma, tidak apa kalau Zakia masih perlu istirahat,” kata Bu Neny, wali kelas Zakia yang langsung datang tergopoh-gopoh saat diberitahu entah oleh siapa, Zakia datang.
“Kami turut berbela sungkawa atas apa yang menimpa Bu Mayang dan Zakia. Semoga Vivian tabah menghadapi cobaan ini,” lanjut Bu Neny, “Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hamba-Nya. Artinya cobaan yang diberikan pasti sudah diukur, bahwa yang dicoba itu akan mampu menghadapinya.”
“Makasih, Bu Neny. Saya titip Zakia. Saya ada keperluan mungkin sampai sore. Nanti Zakia ikut mobil jemputan.”
Bu Neny mengiyakan membuatku bisa pergi dengan lega. Dan aku langsung meluncur ke agen penyalur suster di Joglo.
Kutemui Susanti, pemilik agen yang waktu itu merekomendasikan Suster Margi untuk menjaga mama. Susanti yang kupikir usianya 45 tahun itu menyambutku dengan dingin. Sepertinya dia tidak suka melihat kedatanganku.
“Saya tidak tahu di mana Suster Margi. Sejak peristiwa itu, dia tidak pernah ke sini, dan tidak bisa dihubungi,” Susanti bicara seperti itu sambil menulis sesuatu dalam buku besar, seperti enggan berpandangan denganku.
“Ada polisi yang sudah mencarinya ke sini?”
“Tidak ada. Tapi, nggak tahu ya kalau pas saya nggak di sini terus polisi datang. Agen saya kan punya beberapa cabang di beberapa tempat, jadinya tiap hari saya bekeliling dari satu cabang ke cabang yang lain. Tidak ngantor di sini terus.”
“Tapi Bu Susanti pemilik agen, polisi pasti perlu bertanya pada Bu Susanti.”
“Nggak tahu. Nyatanya nggak ada polisi yang mencari saya.”
“Saya minta semua data tentang Suster Margi. Alamat rumah, nomor telepon dan sebagainya. Semua hal terkait Suster Margi.”
“Sebentar ya, saya harus menelepon seseorang,” Susanti pergi ke ruangan lain untuk menelepon.
Kenapa dia tidak menelepon dari sini saja? Di meja kerjanya ada telepon. = Lama sekali, Susanti tidak muncul.
Ketika melihat sekeliling, kudekati seorang perempuan muda yang sedang berdiri di depan papan lowongan kerja tujuan luar ngeri.
“Kamu kenal Suster Margi?” langsung saja kutanya dia.
“Enggak. Saya baru datang kemarin.”
“Siapa yang lama tinggal di sini?”
“Mungkin itu, Bu Narti,” perempuan muda itu menunjuk seorang perempuan agak tua yang memakai daster dengan rambutnya yang dibando.
“Siapa Bu Narti?”
“Dulu TKW, sekarang jadi tukang masak di sini.”
Kudekati Bu Narti dan kutanyakan hal yang sama padanya.
“Suster Margi pernah ke sini sekali, setahu saya. Setelah itu dia tidak pernah kelihatan lagi.”
Kenapa Susanti berbohong? Apa yang dia tutupi? Aku bergegas ke ruang kerjanya.
Kira-kira lima belas menit kemudian Susanti datang dengan selembar kertas berisi alamat rumah Suster Margi. Sebuah desa di Depok.
Aku ingin mengatakan bahwa dia berbohong tentang Suster Margi, tapi entah kenapa aku justru menahan diri. Tanpa buang waktu, aku langsung meluncur ke Depok.
Orang yang tinggal di alamat Suster Margi itu tidak mengenal Suster Margi. Tetangga kiri kanan juga bingung saat kutanyakan tentang Suster Margi.
Susanti telah menipuku mentah-mentah! = Dan ini semakin menguatkan alasanku untuk mencari tahu di mana keberadaan Suster Margi.
Aku tidak akan memakai cara biasa. Aku harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk mendapatkan data yang benar mengenai Suster Margi. Aku menunggu malam untuk masuk ke dalam kantor Susanti. Tidak harus malam, tapi setelah Susanti tidak ada di kantornya itu.
Sambil menunggu, kunikmati bakso di warung di pinggir jalan. Kurasakan baksonya enak juga.
Aku harus mempelajari situasi kantor ini agar menemukan cara yang tepat dan aman.
Nah itu dia. Susanti sudah pergi meninggalkan kantor dengan mobil hitamnya.
Kuikat rambut panjangku ke belakang dan kupakai topi bisbol, dan kupakai kacamata.
“Saya datang dari jauh, dari Bandung. Saya mau mendaftar untuk bekerja lewat agen ini,” kataku pada seorang perempuan paruh baya berambut pendek.
Tanpa bicara, dia memberikan formulir berlembar-lembar yang harus kuisi tentang biodata diriku.
Di kolom nama, kutulis Rahayu Lestari, usia 30 tahun, dan seterusnya keterangan yang bukan diriku, asal-asalan saja. Kemudian kuserahkan formulir itu pada perempuan paruh baya yang aku belum tahu namanya itu.
“Kalau boleh tahu, nama ibu siapa? Saya Rahayu, nama lengkap saya Rahayu Lestari. Saya biasa dipanggil Tari.”
“Panggil saya Bu Jono,” perempua paruh baya itu sambil memeriksa formulirku.
“Jono itu nama suami Ibu?” aku menebak.
“Itu nama saya. Saya capek menjelaskan pada semua orang. Tiap kali baru bertemu, baru berkenalan, selalu saja mereka pikir Jono itu nama suami saya. Padahal saya belum menikah. Dan sialnya, saya sering mendapat undangan yang ditujukan kepada yang terhormat Pak Jono. Itu semua gara-gara keinginan orangtua saya punya anak laki-laki tidak pernah terwujud. Saya anak bungsu dari lima bersaudara perempuan, saya dipaksa jadi laki-laki.”
***
Foto ilustrasi: http://www.tsu.co/dailypicts
Bersambung
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Waktu Bisa Mengubah Segalanya
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Menangkap Suster Margi
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 97
97 0
0