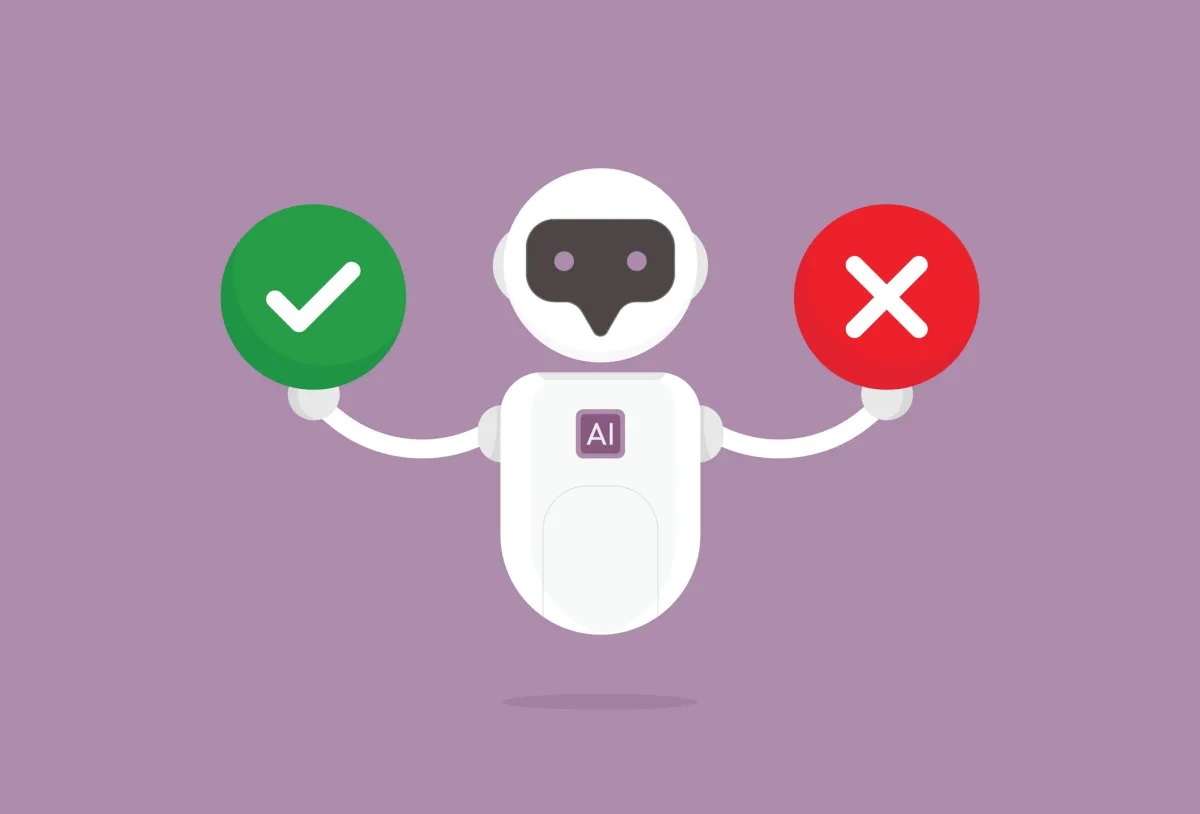Odisea Sejarah Banyuwangi
Rabu, 8 Mei 2024 07:30 WIB
Dari Blambangan menjadi Banyuwangi, tanah wong digdaya yang masih terus terjaga
Sejarah Banyuwangi terkait erat dengan riwayat Kerajaan Blambangan, yang merupakan salah satu kerajaan Hindu terakhir di Jawa. Asal usul kerajaan ini dan awal mula Banyuwangi masih menjadi misteri. Hingga periode bubarnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi, catatan sejarah Banyuwangi dan kerajaan Blambangan hanya dapat diperkirakan melalui cerita lisan, naskah kuno yang tidak lengkap, karya sastra, bahkan legenda atau cerita rakyat yang berbau mitologi.
Asal-Usul Nama Banyuwangi
Asal-usul nama Banyuwangi dapat ditemukan dalam Legenda Sri Tanjung. Konon, pada zaman dahulu, wilayah ujung timur Pulau Jawa diperintah oleh seorang raja yang bernama Prabu Sulahkromo. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh Patih Sidopekso, yang memiliki istri cantik bernama Sri Tanjung. Prabu Sulahkromo terpesona oleh kecantikan Sri Tanjung dan mulai merencanakan skema licik untuk memerintahkan Patih Sidopekso menjalankan tugas yang mustahil bagi manusia biasa.
Ketika Patih Sidopekso sedang menjalankan tugasnya, Prabu Sulahkromo berusaha merayu Sri Tanjung, tetapi upayanya sia-sia. Ketika Patih Sidopekso kembali, raja memfitnah Sri Tanjung dengan tuduhan tak beralasan bahwa ia telah menggodanya. Hasutan dari raja membuat Patih Sidopekso marah dan menuduh istrinya dengan penuh kemarahan.
Patih Sidopekso mengancam akan membunuh istrinya yang sangat setia. Sri Tanjung kemudian ditarik ke tepi sungai yang keruh. Sebelum Patih Sidopekso melaksanakan ancamannya, Sri Tanjung memberi pesan bahwa jika ia dibunuh, jasadnya harus dicampakkan ke sungai. Jika darahnya berbau busuk, itu berarti ia bersalah. Namun, jika air sungai berbau harum, maka Sri Tanjung tidak bersalah. Patih Sidopekso akhirnya menusukkan kerisnya ke dada Sri Tanjung dan membuang jasadnya ke sungai. Ternyata, air sungai yang keruh perlahan-lahan menjadi jernih dan berbau harum. Dari situ lahirlah nama Banyuwangi.
Kisah lain yang sering diceritakan mengenai Blambangan dan Banyuwangi adalah kisah Damarwulan dan Minakjinggo, namun kebenaran dan versi cerita ini masih menjadi perdebatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, seperti yang diungkapkan oleh I Made Sudjana dalam bukunya Nagari Tawon Madu: Sejarah Politik Blambangan Abad XVIII (2001), tidaklah mengherankan jika Blambangan sering dianggap sebagai wilayah yang misterius dan antah berantah.
Munculnya Nama Blambangan
Nama Blambangan pertama kali muncul dalam Kitab Negarakertagama yang ditulis pada tahun 1365 Masehi dengan sebutan “Balambangan.” Namun, informasi tentang hal tersebut terbatas. Menurut J.L.A. Brandes dalam Verslag over een Babad Balambwangan (1894), istilah ini diduga berasal dari dialek orang Osing, suku asli Banyuwangi.
Sementara itu, Atmosudirdjo dalam Vergelijkende Adatrechtelijk Studie van Oost Javase, Madoerezen, en Oesingers (1952), menyarankan alternatif bahwa istilah Balambangan terdiri dari kata “bala” yang berarti “orang” dan “mbang” yang artinya “batas.” Dengan demikian, Blambangan atau Balambangan dapat diartikan sebagai tempat di perbatasan, yang sesuai dengan posisi geografisnya. Wilayah Blambangan, terutama Banyuwangi sebagai bagian paling timur Pulau Jawa, secara langsung berbatasan dengan Samudra Hindia di selatan dan Selat Bali di timurnya.
Nama Blambangan jarang disebut dalam karya-karya sejarah Indonesia yang tersedia dalam berbagai referensi. Bahkan, buku-buku sejarah seperti Pengantar Sejarah Indonesia atau Sejarah Nasional Indonesia yang voluminanya sangat besar tidak membahasnya sama sekali. Perkembangan Kerajaan Blambangan tercatat seiring dengan keberadaan Kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu terbesar di Jawa pada masanya. Wilayah Blambangan diberikan kepada Aria Wiraraja oleh Raden Wijaya, pendiri pertama Kerajaan Majapahit, sebagai penghargaan atas bantuan yang diberikan dalam mendirikan Majapahit. Blambangan, pada masa lampau, juga dikenal sebagai Oosthoek yang memiliki arti Semenanjung Timur.
Setelah runtuhnya Majapahit pada abad ke-15, Blambangan menjadi satu-satunya kerajaan di Jawa yang masih menganut agama Hindu. Kerajaan Blambangan mengendalikan wilayah terluas di ujung timur Pulau Jawa yang sekarang terbagi menjadi lima wilayah administratif, termasuk Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo. Namun, wilayah yang sebenarnya menjadi milik Blambangan sering kali diserang oleh kerajaan-kerajaan lain. Blambangan menjadi sasaran dua fraksi besar, yaitu dari Kesultanan Mataram Islam di sebelah barat dan beberapa kerajaan di Pulau Bali seperti Buleleng, Mengwi, Gelgel, dan lainnya.
Menurut Sri Margana dalam Ujung Timur Jawa 1763-1813: Perebutan Hegemoni Blambangan (2007), situasi di Blambangan semakin rumit dengan masuknya misionaris Barat pada pertengahan hingga akhir abad ke-16. Dalam kekacauan ini, ada tiga agama yang bersaing mempengaruhi Blambangan, yaitu Hindu yang dianut oleh Kerajaan Blambangan dan kerajaan-kerajaan Bali, Islam dari Kesultanan Mataram, serta Kristen dari bangsa Barat.
Pada abad ke-17, konflik ideologi perang suci terjadi di Blambangan. Serangan dari Sultan Agung dari Mataram Islam berhasil menghancurkan wilayah tersebut. Kerajaan Gelgel, Buleleng, dan Mengwi dari Bali kemudian menjadi pelindung bagi wilayah Blambangan. Sementara itu, di bagian barat kerajaan, muncul dinasti baru yang dipimpin oleh Tawang Alun. Dinasti ini mencapai masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Tawang Alun II yang berhasil memulihkan kemerdekaan Blambangan dari penjajahan asing.
Namun sayangnya, pada tahun 1691 setelah Tawang Alun II meninggal dunia, terjadi pertarungan kekuasaan di antara para pangeran. Sebagai akibatnya, ibukota Blambangan dipindahkan dari Macan Putih ke Wijenan. Namun, tidak lama setelah perpindahan tersebut, ibukota kembali dipindahkan ke Lateng, yang sering disebut sebagai Rogojampi. Pemindahan pusat pemerintahan Blambangan tidak berhenti di situ. Kerajaan ini terus mengalami perpindahan ibukota, bahkan setelah berada di bawah kekuasaan Belanda.
Pada tahun 1767, Belanda berhasil menguasai Blambangan. Setelah mengatasi perlawanan dari pemberontakan Agung Wilis, Belanda memindahkan ibu kota ke Pampang. Perpindahan ini terjadi karena Lateng, yang pada saat itu menjadi ibu kota, dilanda wabah penyakit yang mematikan. Akibat wabah tersebut, banyak prajurit Belanda yang tewas. Oleh karena itu, ibu kota dipindahkan ke Pampang, yang juga lebih dekat dengan pelabuhan.
Belanda turut campur dalam urusan politik dan ekonomi di wilayah Blambangan. Kekuasaan Blambangan, terutama dalam hal suksesi raja, seringkali dipengaruhi oleh kehadiran orang-orang asing ini, yang menyebabkan konflik internal yang melemahkan kerajaan tersebut. Akhirnya, Kerajaan Blambangan mengalami kehancuran setelah terjadinya Puputan Bayu pada tahun 1771. Peristiwa tragis ini merupakan konfrontasi sengit antara rakyat Blambangan yang dipimpin oleh Pangeran Jagapati melawan VOC.
Menurut Cornelis Lekkerkerker dalam tulisannya Balambangan: Indische Gids II (1923), Puputan Bayu adalah pertempuran yang paling intens, kejam, dan merenggut banyak korban jiwa dibandingkan dengan semua pertempuran yang pernah dilakukan oleh VOC/Belanda di Indonesia. Dalam The History of Java (1817) karya Thomas Stamford Raffles, disebutkan bahwa sebelum terjadinya Puputan Bayu pada tahun 1750, Blambangan dihuni oleh lebih dari 80.000 orang. Namun, pada tahun 1881, catatan Raffles menunjukkan bahwa jumlah penduduknya hanya tinggal 8.000 jiwa.
Seorang pejabat Belanda, J.C. Bosch, seperti yang dikutip oleh Benedict Anderson dalam tulisannya yang berjudul Sembah Sumpah, Politik Bahasa dan Kebudayaan Jawa dalam Prisma (1982), mengomentari tragedi ini dengan mengatakan: “[…] daerah ini [Blambangan] mungkin merupakan satu-satunya wilayah di seluruh Jawa yang pada suatu waktu memiliki populasi padat yang kemudian dibasmi sepenuhnya,” ungkap Bosch. Puputan Bayu yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1771 ditetapkan sebagai Hari Jadi Banyuwangi.
Dari Blambangan Menjadi Banyuwangi
Setelah keruntuhan Kerajaan Blambangan, Belanda mendirikan kabupaten Kasepuhan atau Kabupaten Blambangan Timur. Bupati pertama yang diangkat adalah Bagus Anom Kalungkung pada tahun 1767-1768, dengan pusat pemerintahan di Kutha Ulu Pangpang. Kepemimpinan berikutnya diserahkan kepada Mas Bagus Sutanagara dari tahun 1768 hingga 1771, dengan pusat pemerintahan yang tetap sama. Namun, setelah itu, Tumenggung Raden Mas Kartanegara (Kartawijaya) mengambil alih kepemimpinan, tetapi hanya untuk beberapa bulan pada tahun 1771. Ia terpaksa kembali ke Surabaya karena meletusnya Perang Puputan Bayu.
Kepemimpinan kemudian diserahkan kepada Tumenggung Jaksanagara dari tahun 1771 hingga 1773. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Kutha Ulu Pangpang ke Kutha Benculuk Cluring. Setelah pusat pemerintahan dipindahkan ke Kutha Benculuk Cluring di bawah kepemimpinan Tumenggung Jaksanagara, Tumenggung Wiraguna I (Mas Alit) meneruskan kepemimpinan sebagai bupati kelima di Benculuk. Dalam buku Dari Balambangan Menjadi Banyuwangi, dikatakan bahwa di era kepemimpinan Mas Alit pada 1774-1782 terjadi pemindahan ibukota dari kutha benculuk ke kutha Banyuwangi.
Sepeninggal Mas Alit, kursi pemerintah di Blambangan diisi oleh adiknya yakni Tumenggung Wiraguna II atau Mas Sanget. Kala itu, penjajahan kolonial Belanda di Banyuwangi digeser oleh kekuatan Inggris. Barulah nama Kabupaten Kasepuhan atau Blambangan Timur diganti menjadi Kabupaten Banyuwangi di tahun 1812. Pemerintahan Mas Sanget berjalan hingga tahun 1818, yang artinya Ia sebagai bupati terakhir di Kabupaten Kasepuhan sekaligus bupati pertama di Kabupaten Banyuwangi.
Menurut Sri Margana (2007) dalam karyanya, citra Blambangan sebagai tanah wong digdaya (orang sakti) masih terus terjaga. Banyuwangi, yang merupakan nama saat ini untuk Blambangan, telah dikenal sebagai salah satu pusat keilmuan kekuatan supernatural di Indonesia.
Referensi:
Sudjana, I. Made. Nagari tawon madu: sejarah politik Blambangan abad XVIII. Larasan-Sejarah, 2001.
Abdullah, Ahmad Ferdi. “BLAMBANGAN PEOPLE’S RESISTANCE TO VOC YEAR 1767-1773.” Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora 3.2 (2019): 46-55.
Maria, Nur. “Gerakan Sosial Politik di Blambangan Tahun 1767-1768.” Patanjala 9.3 (2017): 291842.
Sandawara, TioVovan. Penciptaan Naskah Drama Jagapati Puputan Terinspirasi Dari Sejarah Perang Puputan Bayu. Diss. Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2015.
Rohmah, Muttafaqur. “STUDENT AND CULTURE: STORY OF BANYUWANGI.” Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya 6.2 (2019).
Margana, S. (2007). Java’s Last Frontier: The Struggle for Hegemony of Blambangan C. 1763-1813 (Doctoral dissertation, Universiteit Leiden).
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Odisea Sejarah Banyuwangi
Rabu, 8 Mei 2024 07:30 WIB
Nagini Lord Voldemort dan Mitologi Sastra Jawa Kuno
Rabu, 7 Februari 2024 08:21 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan







 99
99 0
0