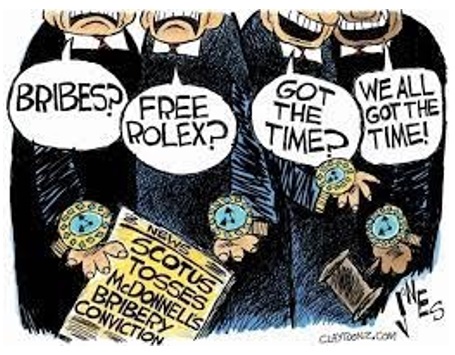Mengapa Engkau Menulis?
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
"Aku memiliki sekutu jauh yang tidak mengenalku dan bersama-sama kami merajut jejaring tanpa bentuk ini, merajut kekuatan untuk mengubah dunia."
“Seorang penulis harus terus menggunakan hak untuk berbicara perihal kesukaran.”--Nadine Gordimer
Banyak wajah sensor yang tak terlihat. Wajah-wajah itu mungkin mengendap-endap dari balik tembok dan mengintai: menunggu waktu yang tepat untuk meringkus. Tapi mengapa, dan sejauh mana, tulisan harus dilindungi? Apakah karena alasan seperti yang dikatakan Toni Morrison bahwa “Hidup dan karya seorang penulis bukanlah hadiah bagi kemanusiaan, melainkan kemestian baginya.”
“Memang aneh,” tulis Paul Auster, “menghabiskan hidup dengan duduk sendiri di suatu ruangan sepi dengan pena di tangan, jam demi jam, hari demi hari, tahun demi tahun, berjuang meletakkan kata-kata di atas secarik kertas.” Auster barangkali baru menyadari keanehan itu ketika sebuah pertanyaan sederhana diajukan kepadanya: mengapa menulis?
Andai saja, dan mungkin saja memang demikian, Auster merasa seperti David Grossman tatkala berbicara ihwal kesukaran. Dalam Writing in the Dark, Grossman menulis: “Ada kalanya saat aku bekerja... aku berpikir: Sekarang, saat ini, duduk pula penulis-penulis lain, yang tidak kukenal, di Damaskus dan Tehran, di Kigali dan Dublin, di Israel dan Palestina, di Chechnya dan Sudan, di New York dan Kongo... yang, seperti aku, terlibat dalam kerja penciptaan yang asing dan mengherankan, dalam realitas yang mengandung begitu banyak kekerasan dan keterasingan, ketakacuhan dan kekurangan. Aku memiliki sekutu jauh yang tidak mengenalku dan bersama-sama kami merajut jejaring tanpa bentuk ini, merajut kekuatan untuk mengubah dunia dan menciptakan dunia, kekuatan untuk memberikan kata-kata kepada yang diam.”
Auster dan Grossman, bersama John Updike, Russell Banks, Orhan Pamuk, Salman Rushdie, Nadine Gordimer dan sejumlah penulis lain merenungkan apa sesungguhnya yang tengah mereka lakukan dengan menulis. Renungan mereka, yang dihimpun dan disunting oleh Toni Morrison, membuat kita merenungi apa pentingnya perjuangan ‘menyusun kata-kata’. Ini bukan perkara agar penulis dapat terlihat di panggung, melainkan agar orang melihat apa yang selama ini tak terlihat, agar orang mendengar apa yang selama ini tak terdengar.
Franz Kafka pernah berkata, sebuah buku ditulis sebagai kampak untuk memecahkan lautan beku dalam diri kita. Novelis, yang duduk sendirian bersama kalimat-kalimatnya, senantiasa belajar dari setiap kalimat baru yang ia tulis untuk menyusun kalimat berikutnya. Ia mungkin berbicara bukan untuk orang lain, kata Russell Banks, melainkan untuk dirinya sendiri dan menulis semata-mata untuk menembus apa yang masih jadi misteri baginya, secara moral atau metafisikal ataupun sosial.
Lantaran itulah, tulis Banks dalam Notes on Literature and Engagement, dalam hampir 300 tahun sejarah sastra Amerika, teramat sedikit novel yang jadi kekuatan penting bagi perubahan sosial. Barangkali, novel Amerika yang paling dikenal memengaruhi masyarakat adalah Uncle Tom’s Cabin (1852), karya Harriet Beecher Stowe tentang perbudakan. “Inikah wanita kecil yang telah memicu perang besar?” tanya Abraham Lincoln tatkala Stowe diperkenalkan kepadanya di Gedung Putih.
Bila menulis hanya untuk diri sendiri, atau seperti guyonan Jurge Lois Borges yang menulis untuk teman-temannya, mengapa banyak despot merasa terganggu? Pada akhirnya, sebuah tulisan—fiksi, nonfiksi, sajak—bergerak melampaui penulisnya dan memasuki pikiran dan nurani pembacanya. Rezim-rezim diktator, tulis Toni Morrison, tidak satupun yang cukup bodoh untuk memberi ruang kebebasan kepada penulis pembangkang untuk mempublikasikan penilaian mereka atau mengikuti naluri kreatif mereka. Sebab, itu sama saja dengan menciptakan jebakan bagi diri sendiri.
Kendati begitu, kata Nadine Gordimer, penulis tetap harus menyatakan apa yang ia saksikan tentang ‘apa yang sebenarnya terjadi’. Di belahan bumi manapun senantiasa ada orang-orang yang memilih jadi saksi dan tanpa rasa takut mengisahkannya kepada dunia. Wole Soyinka di Afrika dan Alexander Sholzenitsyn di Uni Soviet di antaranya.
Di tengah penindasan, “sastra telah dan tetap menjadi alat bagi manusia untuk menemukan kembali diri mereka.” Gordimer tak sepakat dengan Sartre ketika penulis Prancis ini mengatakan ada saatnya seorang penulis harus berhenti menulis dan bertindak semata-mata melalui cara lain karena frustrasi atas konflik tak terpecahkan antara penderitaan karena ketidakadilan di dunia dengan pengetahuan bahwa cara terbaik yang ia tahu untuk dilakukan adalah menulis. “Seorang penulis harus terus menggunakan hak untuk berbicara perihal kesukaran,” kata Gordimer.
Di saat seperti ini, penulis di manapun akan merasa dirinya berdiri di atas konflik antara posisi penulis dan posisi negara-bangsa—sebuah tema yang dieksplorasi oleh Salman Rushdie dalam Notes on Writing and the Nation. Nasionalisme telah mengkorupsi penulis, kata Rushdie. Nasionalisme adalah ‘revolusi melawan sejarah’ yang berusaha menutup apa yang tidak bisa lagi ditutup. Nasionalisme memagari apa yang seharusnya tanpa tapal batas. Tulisan yang bagus, kata Rushdie, mengasumsikan bangsa yang tanpa tapal batas. Ia meyakini, “Penulis yang melayani tapal batas telah menjadi pengawal tapal batas.”
Ketika jutaan orang terancam eksistensinya, nilai-nilainya, kebebasannya, dan identitasnya sebagai manusia, penulis menjadi saksi sekaligus berjuang menemukan dirinya kembali di tengah segala kesukaran. Hampir setiap orang menghadapi ancamannya sendiri. Setiap diri kita merasa betapa ‘situasi’ uniknya bisa berubah cepat jadi jebakan yang merampas kebebasannya, rasa ‘pomah’ di negerinya sendiri, bahasa pribadinya, dan kehendak bebasnya.
Menjadi tugas sejati novelis, kata John Updike, untuk mendramatisasi mula-mula bagi dirinya sendiri dan akhirnya bagi yang lain tentang apa artinya menjadi manusia di zaman kita dan di sepanjang masa, apa maknanya menjadi manusia di tempat kita dan di setiap tempat. “Kita selalu bergantung kepada tukang cerita untuk menceritakan pada kita apa maknanya menjadi manusia.”
Dan mengapa ‘kata-kata’ yang terpilih untuk menunaikan tugas itu? Barangkali karena kekuatan biusnya yang memabukkan. Seperti tutur Nadine Gordimer, memiliki kata sama artinya dengan kekuasaan tertinggi, prestise, kekaguman, tapi terkadang bisa menjadi rayuan berbahaya.
Dalam Burn This Book, kita memperoleh sajian 11 esai yang menawan dari penulis yang menghadirkan pikiran dengan cara demikian beragam. Gordimer, Rushdie, Updike, Banks, Pamuk, Auster, Park, Grossman, Prose, Iyer, dan Morrison memperkaya pengertian kita tentang mengapa menulis dan bagaimana menjadi manusia. Membaca kitab ringkas ini menjadikan kita yakin pada apa yang dikatakan oleh Morrison bahwa “hidup dan karya seorang penulis bukanlah hadiah bagi kemanusiaan, melainkan kemestian baginya.” Atau dalam kata Auster, “Karena engkau harus melakukannya, karena engkau tak punya pilihan.”
Antologi esai ini memang tipis, tapi jangan berpikir bahwa ia kehilangan kekuatannya untuk mengingatkan kita bagaimana (seharusnya) menjadi manusia. (Foto dari kiri ke kanan: Nadine Gordimer, Derek Walcott, Wole Soyinka, Toni Morrison; sumber foto: news.harvard.edu) ***
Penulis Indonesiana
1 Pengikut

Di Musim Corona, Hati-hati Jangan Sampai Menghina
Selasa, 14 April 2020 05:33 WIB
Bila Jatuh, Melentinglah
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 98
98 0
0