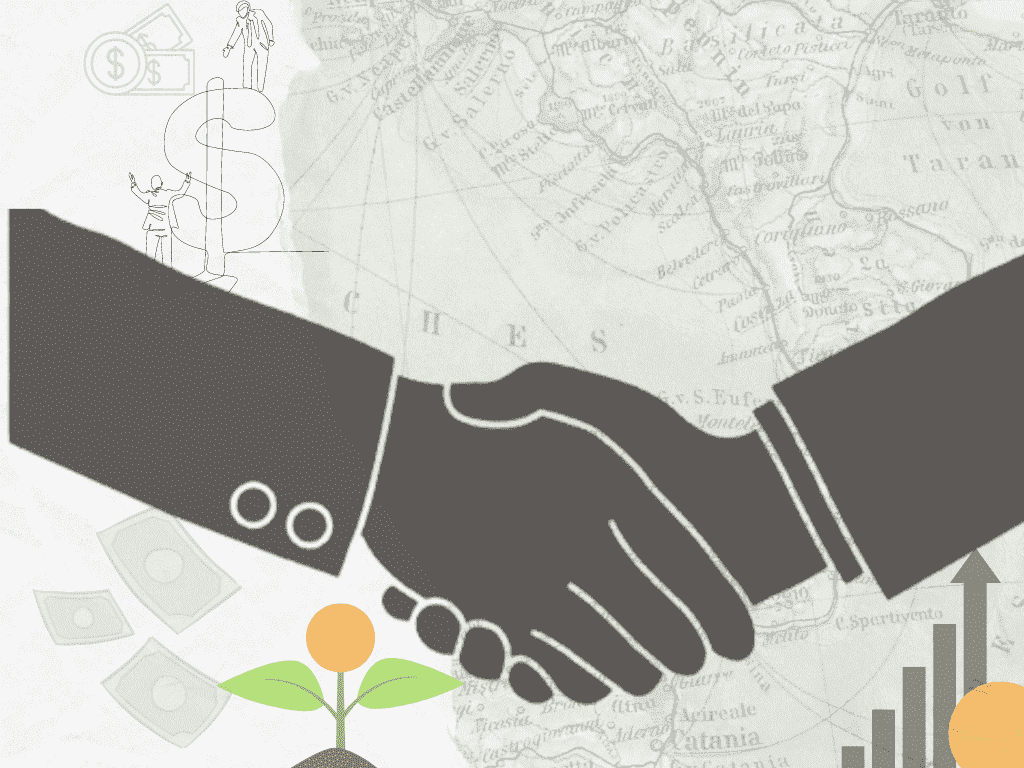Robert Toru Kiyosaki adalah pengusaha dan penulis buku masyhur Amerika Serikat. Saat berusia 46 tahun, dia mengambil keputusan pensiun dini karena asetnya memungkinkan dia hidup tanpa bekerja menjelang usia paruh baya. Kehidupan di sekolah menengah atas merupakan pengalaman traumatis bagi Kiyosaki. Akademi marinir yang dijalaninya keras dan kompetitif.
Di sekolah penerbangan, kisah cintanya dalam proses belajar bermula. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia kasmaran kepada belajar. Kecintaannya pada belajar selanjutnya tidak pernah padam. Sekolah penerbangan lebih dari sekadar mendidik. Sekolah itu mengubah, menantang secara mental, fisik, dan spiritual. Mengilhami siswa untuk belajar dan menjadi lebih baik.
Ia mendapat ilham untuk menghadapi rasa takut setiap hari. Ilham persiapan berperang. Instruktur memaksanya berlatih melakukan manuver darurat, bukan mencari perlindungan, bukan berdoa agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Instruktur sengaja merusak pesawat, bahkan mematikan mesin. Instruktur memaksa siswa menghadapi rasa takut, tetap bersikap tenang, dan terus terbang. Pelatihan sempurna untuk berperang konkret di Kuadran B (pebisnis kelas kakap) dan Kuadran I (investor dengan kekayaan triliunan).
Tugas guru dalam proses pendidikan adalah mengilhami anak dan mengeluarkan kejeniusan mereka. Kejeniusan dalam musik, kebun, kesehatan, seni, hukum, dan wirausaha. Bukan menghukum mereka karena tidak berhasil dalam ujian yang membuat mereka merasa bodoh.
Pendidikan tradisional berfokus pada konten: membaca, menulis, dan berhitung-kurang berfokus pada konteks siswa. Padahal, konteks menentukan konten. Salah satu alasan sebagian besar siswa unggulan kurang berhasil pada level tertinggi kerucut pembelajaran adalah mereka dikondisikan agar berpikir bahwa melakukan kesalahan itu buruk dan menunjukkan kesan bahwa mereka bodoh. Mereka lalu terbiasa menghindari risiko.
Masalah terbesar dunia sekolah adalah anak-anak diajari hidup di atmosfer benar atau salah. Di dunia nyata, kerap realitasnya lebih dari sekadar benar atau salah. Ada begitu banyak jawaban atau solusi di luar benar atau salah.
Di sekolah, hanya disediakan satu jawaban benar. Di sekolah, Anda disebut cerdas bila jawaban Anda sama dengan yang dimaksud guru. Benar-salah, itulah landasan dunia akademik. Anak-anak meninggalkan bangku sekolah dengan keyakinan dan persepsi dunia benar-salah. Hitam-putih. Pandai-bodoh. Padahal, "kemampuan memiliki dua gagasan yang bertentangan di benak pada saat yang sama" merupakan kecerdasan tingkat pertama.
Mungkin itu yang membuat Walt Disney, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Henry Ford, Rabindranath Tagore, dan Thomas Alva Edison meninggalkan bangku sekolah. Gagasan benar-salah jelas tidak mencerdaskan. Dunia ini tidak linear, melainkan lateral. Bukan sekadar menaiki bukit atau menuruni lembah. Kalau benak siswa terbuka bagi gagasan yang bertentangan, kecerdasan mereka akan meningkat. Jika mereka menutup diri terhadap gagasan yang berseberangan, kebodohan bakal memegang kendali. Sekolah seharusnya melatih kemampuan keluar dari jebakan dunia benar-salah yang telanjur berurat-berakar di dunia akademik, kemampuan melihat dunia dari sebanyak mungkin sisi dan perspektif.
Di sekolah, tidak ada ruang untuk kesalahan. Siswa ikut ujian. Guru mengurangkan angka jawaban yang salah dari yang benar, menentukan nilai dan kelas pun berlanjut. Melakukan kesalahan, dalam konteks sekolah tradisional, berarti bodoh. Nilai bagus memang penting di sekolah, tapi kurang penting setelah siswa lulus. Masalahnya, setelah lulus, siswa tetap terbelenggu keyakinan yang diajarkan sekolahnya pada masa lalu.
Tak mengherankan bila mereka seumur hidup terperangkap di dalam sirkuit balap tikus kehidupan. Mereka yang miskin cenderung bekerja di sektor bergaji rendah. Mereka cenderung berkutat pada level bertahan hidup. Orang miskin bisa menjadi tamak karena di dalam diri mereka tumbuh mentalitas berhak. Di Amerika dan Eropa, orang miskin mengharap tunjangan pengangguran. Tidak bekerja pun mereka tetap "digaji" pemerintah.
Kelas menengah menghasilkan lebih banyak uang. Umumnya, mereka punya lebih banyak pengeluaran. Mobil baru, rumah baru yang lebih besar, liburan eksotis, dan bersaing dengan tetangga. Mereka menjadi tamak karena menginginkan lebih banyak daripada yang bisa disumbangkan. Mereka bagai menggenggam granat di tangan, terjebak utang jahat. Bank menghasilkan keuntungan bukan dari tabungan nasabah, melainkan utang debitur. Warga kelas menengah yang bekerja sebagai birokrat umumnya mengalami perubahan mentalitas dari melayani publik menjadi melayani dan melindungi diri sendiri.
Itulah bahaya pendidikan tradisional yang mendewakan benar-salah. Membuat orang miskin tamak. Menyuburkan mentalitas berhak kelas menengah. Mentalitas yang menumbuhkan benih-benih korupsi yang membuat masyarakat menderita.
J. Sumardianta
Penulis buku Mendidik Pemenang Bukan Pecundang (2016)
*) Tulisan ini terbit di Koran Tempo edisi Jumat, 1 April 2016.
Ikuti tulisan menarik Redaksi lainnya di sini.