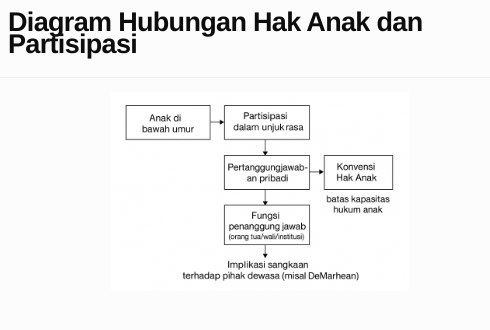POLEMIK: Rekonsiliasi Jangan Basa-basi
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Simposium mengenai tragedi 1965 digelar. Jika negara tak siap meminta maaf, lupakan saja rekonsiliasi.
Simposium nasional “Membedah Tragedi 1965” merupakan langkah penting dalam perjalanan bangsa. Sebuah ikhtiar yang hendak menyembuhkan luka. Tapi upaya ini tidak bisa dilakukan setengah hati.
Jempol layak kita acungkan kepada Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, penggerak simposium yang digelar pekan lalu itu. Ini pertama kali pemerintah mempertemukan sejumlah pihak yang berkaitan dengan tragedi 1965. Berbagai kubu yang berseberangan hadir. Penyintas, keluarga korban, akademikus, aktivis, juga tentara yang mendaki karier sejak awal Orde Baru, berada di satu ruangan. Begitu banyak orang berebut bersuara, menumpahkan gundah yang terpendam lebih dari setengah abad.
Simposium ini memang belum ideal. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan membuka dengan pernyataan aneh. “Minta maaf kepada siapa? Korban mana? Tak ada pikiran bahwa pemerintah akan ke sana-kemari minta maaf. Tak ada.” Ucapan ini menerbitkan pertanyaan: jika negara tak mau mengakui dan meminta maaf atas perannya “mendorong” kekerasan massal 1965, lantas mengapa pula ada gagasan rekonsiliasi? Bukankah langkah awal rekonsiliasi adalah mengakui kesalahan?
Beberapa pembicara dalam simposium juga terkesan mereduksi skala tragedi, dengan menyebut kejadian 1965-1966 adalah konflik horizontal. Pandangan ini dibantah dengan bagus oleh sosiolog Ariel Heryanto. Perjalanan sejarah membuktikan, selalu ada campur tangan negara dalam kekerasan yang begitu masif di berbagai penjuru negeri. Ratusan ribu orang dibunuh dan puluhan ribu orang dipenjarakan belasan tahun tanpa pengadilan.
Konflik horizontal dan vertikal bukan sekadar istilah, masing-masing punya konsekuensi berbeda. Konflik yang berkobar di kalangan masyarakat berlangsung sporadis, acak, dengan korban nyawa mungkin puluhan atau beberapa ratus orang. Namun, pada 1965-1967, ada mobilisasi kekerasan sehingga korban ratusan ribu dalam waktu singkat. Ada pelatihan, pembagian senjata, juga pengerahan logistik. Bahkan, setelah para tahanan pulang dari Pulau Buru, Presiden Soeharto masih melestarikan kekerasan dengan menerbitkan peraturan “bersih lingkungan”, 1981. Maka, berlanjutlah pengucilan bagi mereka yang terlibat PKI, yang dituduh PKI, juga keluarganya.
Rekonsiliasi memang tak bisa hanya berdasar saling-silang komentar, tapi harus berangkat dari fakta. Menteri Luhut pun menantang disodorkan data yang membuktikan peran negara dalam tragedi 1965. Sebetulnya ini tantangan yang tak sulit. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada 2009-2012, telah menginvestigasi kasus ini di seluruh negeri. Testimoni korban dan pelaku, penelusuran kuburan massal, menguatkan adanya mobilisasi kekerasan massal dan pelanggaran berat hak asasi manusia pada 1965 dan meluas hingga awal 1970.
Simposium ini memang bukan garis finish. Ini baru langkah awal. Jika sungguh-sungguh ingin menyembuhkan luka, negara perlu meminta maaf atas perannya di masa lalu. Perlu upaya pula mengungkapkan kebenaran dalam berbagai bentuk. Rehabilitasi nama orang-orang, terutama yang difitnah dan dijebloskan ke Pulau Buru tanpa pengadilan, adalah keharusan.
Jika pemerintah tak siap, atau tak punya nyali mengakui peran negara dalam tragedi 1965, sebaiknya lupakan saja gagasan rekonsiliasi. Tanpa pengakuan dan permintaan maaf, rekonsiliasi hanya akan jadi basa-basi.
***-/**
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Kematian Juliana, Sulit bagi Pemerintah Brasil Menuntut Indonesia Secara Hukum
Sabtu, 5 Juli 2025 19:42 WIB
Paska Tragedi Juliana, Gunung Rinjani Terlarang bagi Pendaki Pemula
Rabu, 2 Juli 2025 18:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 96
96 0
0