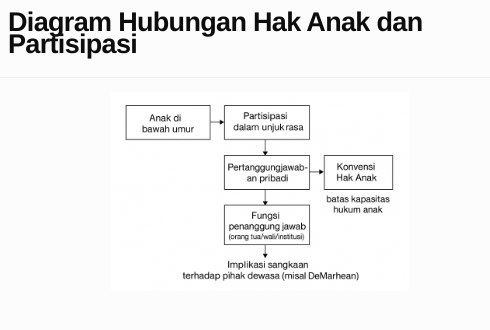REKONSILIASI, Mengubur Dendam di Pusara Kiai
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Dialah salah satu tokoh utama di balik Peristiwa Madiun, bentrokan barisan pendukung Partai Komunis Indonesia dan kelompok kanan.
PRIA sepuh itu sesekali tersenyum hangat, matanya berbinar, seraya mendengarkan dengan tekun. Di hadapannya, belasan warga setempat—beberapa pernah menjadi santri di Pesantren Sabilil Muttaqien, di Desa Takeran, Magetan, Jawa Timur, yang menjadi lokasi pertemuan pada akhir Agustus lalu itu—bergiliran bercerita soal pengalaman mereka lebih dari 50 tahun lampau.
Setelah semua yang hadir habis bercerita, Dahlan Iskan, kerabat pengasuh pesantren itu, membuka ”rahasia” identitas tamu yang dibawanya. ”Beliau ini dulu Gubernur Militer di Madiun,” kata direktur utama kelompok media Jawa Pos ini.
”Namanya Soemarsono. Beliau ini orang ketiga setelah Amir Sjarifuddin dan Muso,” kata Dahlan lagi. Dengan kata lain, dialah salah satu tokoh utama di balik Peristiwa Madiun, bentrokan barisan pendukung Partai Komunis Indonesia dan kelompok kanan yang ingin menghabisi tokoh komunis di sana, pada September 1948.
Semua yang hadir tertegun. Mereka baru saja lancar bercerita bagaimana orang tua dan kerabat mereka—yang rata-rata aktif di Masyumi—diculik orang-orang Partai Komunis Indonesia pasca-Peristiwa Madiun 1948. Lima kiai utama di Pesantren Sabilil Muttaqien bahkan dibunuh. Dan sekarang, di hadapan mereka, ada tokoh yang mewakili kubu ”musuh” saat itu.
Soemarsono tanpa ragu langsung angkat bicara. Suaranya jernih dan mantap. ”Kita semua korban. Anda korban, saya pun jadi korban. Apa yang terjadi saat itu adalah tragedi, saya minta maaf,” katanya tegas. ”Ada 30 ribu orang PKI yang mati di Madiun saat itu, tapi saya tidak mendendam,” katanya lagi. ”Saya tidak mau mempersoalkan siapa yang salah. Semua sudah lewat,” ujar pria 88 tahun ini.
Hening sebentar. Lalu perlahan suasana kembali cair. Guyonan mengalir lagi dan tawa akrab sesekali terdengar.
Seusai pertemuan, mereka beranjak ke kompleks pemakaman di dekat pesantren. Saat semua menundukkan kepala, Soemarsono tak ketinggalan. Dia merapalkan doa di pusara kiai pesantren itu.
KONTROVERSI soal apa yang terjadi di Madiun, September 1948, merebak sejak awal. Wakil Presiden Mohammad Hatta termasuk tokoh pertama yang mengutuk aksi PKI di Madiun dan menyebutnya pemberontakan melawan pemerintah yang sah. Namun tidak adanya perintah resmi pembubaran PKI pascaperistiwa itu, dengan gamblang, mencerminkan kegamangan Presiden Soekarno.
Akibatnya, PKI pun seolah-olah mendapat angin. ”Di parlemen, D.N. Aidit terus menuntut agar ada klarifikasi atas Peristiwa Madiun, agar PKI tidak dituduh memberontak terus-menerus,” kata Soemarsono saat ditemui pekan lalu. Aidit adalah Ketua Komite Sentral PKI pasca-Pemilihan Umum 1955.
Menurut Soemarsono, yang terjadi saat itu justru aksi bela diri PKI. Ketika itu, mereka tengah diserang dari banyak penjuru. ”Sebelumnya, sejumlah tokoh PKI di Solo sudah diculik dan dihabisi,” katanya. Dalam suasana psikologi massa seperti inilah bentrok Madiun pecah.
Latar belakang politik saat itu, kata Soemarsono, juga menjadi faktor yang memicu berkobarnya konflik besar. Setelah penandatanganan Perjanjian Renville pada Februari 1948, kabinet Amir Sjarifuddin (Partai Sosialis Indonesia) dijatuhkan dengan mosi tidak percaya oleh Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. Presiden Soekarno kemudian meminta Hatta menjadi perdana menteri merangkap wakil presiden. ”Dia dilantik hanya tiga hari setelah Amir mundur,” ujar Soemarsono.
Setelah Hatta naik menjadi perdana menteri, angin berbalik. ”Tekanan atas keberadaan kelompok kiri di kabinet terasa makin kuat. Padahal kami juga bagian dari pejuang kemerdekaan,” kata Soemarsono. Tekanan ini lambat-laun berubah menjadi ancaman fisik, berupa penculikan dan pembunuhan.
Setelah gerakan pemuda berkobar trengginas, Soemarsono tak tinggal lama di Madiun. Dia pindah ke Siantar, Sumatera Utara, berdasarkan perintah langsung Aidit. ”Ketika itulah, saat pemimpinnya tak ada, bentrok massa di lapangan jadi sulit dikendalikan,” katanya menyesalkan jatuhnya banyak korban di Madiun. ”Saya jamin tidak ada perintah resmi PKI untuk menculik atau membunuh musuh-musuhnya.”
INISIATIF pertemuan di Magetan itu datang dari Dahlan Iskan. ”Semua berawal secara tidak sengaja,” kata wartawan senior ini. Agustus lalu, Dahlan sedang membenahi buku-buku di rumahnya ketika terlihat sebuah buku berjudul Negara Madiun? karya Hersri Setiawan, mantan Ketua Lekra Jawa Tengah.
”Buku itu sangat menarik buat saya,” kata Dahlan. Kebetulan, narasumber utama dalam buku itu adalah Soemarsono. Dahlan langsung membayangkan tokoh ini bakal jadi narasumber yang amat menarik bagi koran yang terbit di Surabaya seperti Jawa Pos.
Tak mau membuang waktu, Dahlan segera melacak keberadaan Soemarsono. Beberapa hari kemudian, dia sudah duduk di ruang tengah rumah putri Soemarsono di bilangan Jakarta Selatan. Meski memegang paspor Australia, pejuang Angkatan ’45 itu lebih sering berdiam di Indonesia.
”Saya langsung kagum melihat sosoknya: bicaranya lantang, alurnya baik dan tertata, dan pendengarannya bagus,” kata Dahlan. Tapi yang paling memikat hati Dahlan adalah sikap dan pembawaan Soemarsono. ”Sepanjang wawancara, Pak Soemarsono tidak menunjukkan sama sekali nada ingin menonjolkan diri atau ingin diakui perannya,” kata Dahlan. Tak terasa lima jam mereka berdua berbincang panjang-lebar.
Seusai pertemuan itu, Dahlan mengajak Soemarsono menapak tilas perjalanan hidupnya di Surabaya. Soemarsono menyambut undangan itu dengan antusias. ”Saya menganggap pertemuan saya dengan Pak Dahlan adalah berkah,” ujar Soemarsono.
Mereka berdua, kata Soemarsono, percaya bahwa untuk maju bangsa Indonesia perlu memaafkan masa lalunya. Persatuan bangsa minus PKI bukanlah persatuan dalam arti sejati. ”Bangsa yang terus memelihara dendam masa lalunya tak akan pernah bisa maju,” ujar Soemarsono dengan bersemangat. ”Semua sudah lewat,” katanya lagi sambil tersenyum.
Wahyu Dhyatmika, Kukuh S. Wibowo (Surabaya)
Catatan: Tulisan ini sudah dimuat di Majalah Tempo edisi 14 September 2009
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Kematian Juliana, Sulit bagi Pemerintah Brasil Menuntut Indonesia Secara Hukum
Sabtu, 5 Juli 2025 19:42 WIB
Paska Tragedi Juliana, Gunung Rinjani Terlarang bagi Pendaki Pemula
Rabu, 2 Juli 2025 18:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 96
96 0
0