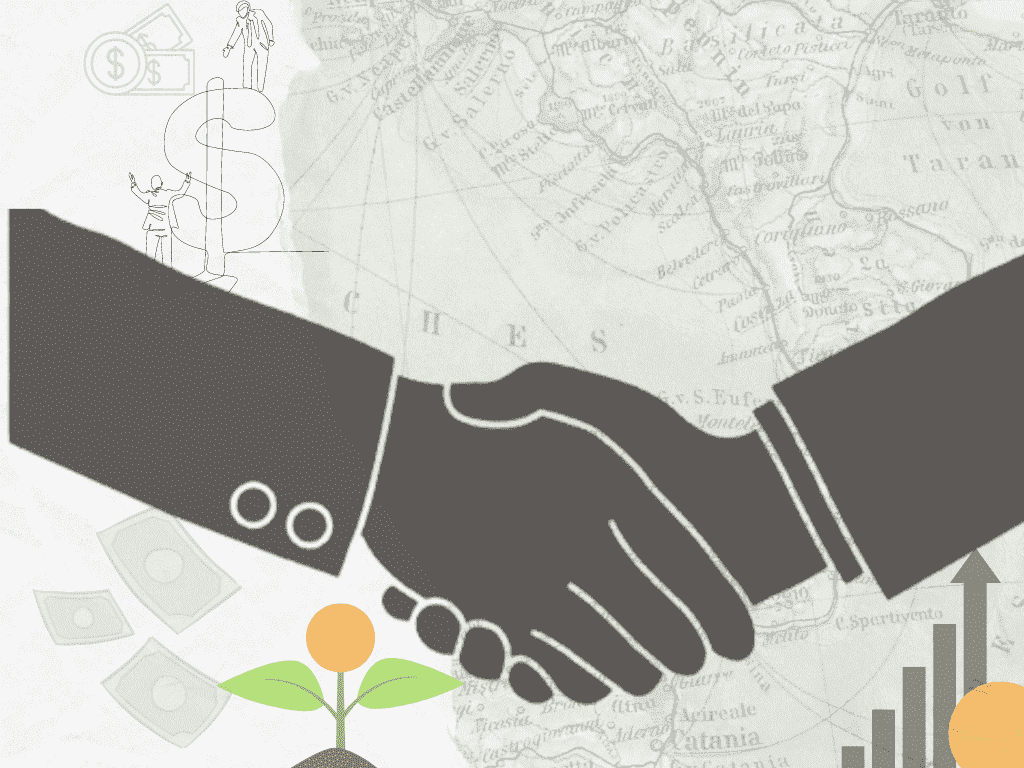Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.
Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai ultimum remedium, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.[1]
Berbicara ultimum remedium juga akan bersinggungan langsung dengan tujuan pemidanaan yang antara lain menurut Cesare Beccaria Bonesana (1764) dikatakan ada dua hal yaitu untuk tujuan prevensi khusus dan prevensi umum. Tujuan pemidanaan hanyalah supaya si pelanggar tidak merugikan sekali lagi kepada masyarakat dan untuk menakuti-nakuti orang lain agar jangan melakukan hal itu. Menurut Beccaria yang paling penting adalah akibat yang menimpa masyarakat. Keyakinan bahwa tidak mungkin meloloskan diri dari pidana yang seharusnya diterima, begitu pula dengan hilangnya keuntungan yang dihasilkan oleh kejahatan itu. Namun Beccaria mengingatkan sekali lagi bahwa segala kekerasan yang melampaui batas tidak perlu karena itu berarti kelaliman.
Selain itu, tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :[2]
- Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
- Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Namun alih-alih memahami bahwa hukum pidana harus selalu diposisikan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan hukum (ultimum remedium), Indonesia justru banyak mencantumkan ketentuan pidana di 154 dari 563 undang-undang yang disahkan pada periode 1998-2014. Tidak kurang dari 1.601 perbuatan telah dikategorikan sebagai tindak pidana dan 716 perbuatan di antaranya merupakan tindak pidana yang baru diperkenalkan dalam hukum pidana Indonesia. Dari 1.601 perbuatan, 738 diantaranya memiliki ancaman sanksi diatas 5 (lima) tahun yang menjadi syarat dapat ditahannya seorang tersangka.[3] Bahkan dalam Penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa pidana dapat menjadi primum remedium, bukan ultimum remedium.
Penggunaan asas subsidiaritas dalam praktek perundang-undangan ternyata tidak berjalan seperti diharapkan. Hukum pidana tidak merupakan ultimum remedium melainkan sebagai primum remedium. Penentuan pidana telah menimbulkan beban terlalu berat dan sangat berlebihan terhadap para pelaku tindak pidana dan lembaga-lembaga hukum pidana.[4] Kenyataan yang terjadi dalam praktek perundang-undangan adalah adanya keyakinan kuat di kalangan pembentuk undang-undang bahwa penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang yang disertai dengan ancaman pidana berat mempunyai pengaruh otomatis terhadap perilaku anggota masyarakat.
Dalam upaya menanggulangi kasus perjudian misalnya, pemerintah mengira, bahwa dengan perubahan sanksi pidana yang ringan menjadi sangat berat bagi bandar dan penjudi, lalu perjudian menjadi lebih tertib. Tapi kenyataannya, perjudian tetap merajalela sampai sekarang, begitu pula halnya dengan tindak pidana lalu lintas. Dari pengalaman-pengalaman itu kemudian muncul suatu keyakinan bahwa penghukuman yang keras tidak mengendalikan kejahatan. Oleh karenanya mereka kembali menggunakan asas subsidiaritas.[5]
Hal ini mengakibatkan beberapa hal yaitu kondisi lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang melebihi kapasitas, pengeluaran anggaran negara yang lebih besar dan banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan. Hal mana akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Kondisi Lapas yang melebihi kapasitas
Penuhnya penghuni lapas mungkin menjadi salah satu penyebab dari beberapa kerusuhan yang terjadi di berbagai lapas di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) per tanggal 3 Juli 2016, hanya 6 wilayah saja yang tidak berlebihan kapasitasnya yaitu di daerah DI Yogyakarta, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Barat. Jumlah tahanan dan napi yang ada pada saat ini adalah 186.867 orang dari kapasitas yang hanya 111.975 orang. Dari data tersebut lapas saat ini telah kelebihan 74.892 orang atau 67%. Dari data tersebut, 62.493 orang yang menjadi tahanan, sedangkan 124.374 orang telah menjadi narapidana.[6] Diluar kecenderungan aparat penegak hukum kita untuk menahan seseorang, apakah dengan memasukkan seseorang ke dalam penjara/lapas sebagai efek jera merupakan hal yang efektif? Martin Moerings melihat keberhasilan kebijakan tersebut dengan mengukur angka residivis yang terdapat di Belanda. Kenyataan yang dihasilkan ternyata pidana penjara tidak berhasil untuk menekan tingkat residivis dimana 70% dari mantan narapidana dalam periode enam tahun kembali bersentuhan dengan pihak berwajib.[7]
2. Pengeluaran anggaran yang lebih besar
Apabila kita lihat jumlah tahanan dan narapidana berdasarkan data diatas, telah terjadi kelebihan kapasitas lebih dari 50%. Negara untuk setiap orang yang dipidana mengeluarkan Rp. 14.000-Rp. 22.000 per orang setiap harinya.[8] Sedangkan untuk orang yang ditahan baik oleh Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN) ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), negara harus mengeluarkan biaya Rp. 32.000-Rp. 55.000 per orang setiap harinya.[9] Bayangkan apabila kita hitung berapa biaya yang harus di keluarkan setiap harinya untuk membiayai orang-orang tersebut. Apabila kita ambil biaya terendah, untuk seluruh orang yang ditahan, negara harus mengeluarkan sebesar Rp. 32.000 x 62.493 orang = Rp. 1.999.776.000 per harinya atau hampir 2 Milyar Rupiah. Sedangkan untuk orang yang telah dipidana/narapidana, negara harus mengeluarkan sebesar Rp. 14.000 x 124.374 orang = Rp. 1.741.236.000 per harinya. Sehingga apabila dijumlahkan, untuk membiayai tahanan dan narapidana, negara harus mengeluarkan 3,5-4 Milyar Rupiah setiap harinya, angka yang cukup fantastis bukan?
3. Banyaknya perkara ringan masuk ke pengadilan
Berdasarkan data pada tahun 2013, perkara pidana yang masuk ke pengadilan negeri berjumlah total 3.376.303 perkara. Dimana sebagian besar perkara tersebut adalah perkara dengan pidana cepat seperti pelanggaran lalu lintas.[10]
Hukum pidana adalah suatu instrumen yang dampaknya jauh ke dalam kehidupan setiap orang yang bersentuhan dengannya. Karena itu satu prinsip penting bagi pendayagunaannya ialah bahwa baru akan diberdayakan bilamana sarana-sarana lain yang tersedia sudah diupayakan dan tidak berhasil (hukum pidana sebagai upaya terakhir atau sebagai ultimum remedium). Hal ini tidak hanya berlaku dalam bidang pembuatan aturan substantif dan prosesuil, namun juga dalam bidang penjatuhan pidana: apakah tersedia sanksi-sanksi alternatif lainnya di luar hukum pidana yang dapat didayagunakan?
Dalam hukum pidana Indonesia, sebenarnya sudah terdapat 2 (dua) alternatif pemidanaan selain penjara dan sebelum masuk ranah pengadilan yang harus dioptimalkan fungsinya, yaitu:
1. Pasal 82 KUHP
Pasal 82 KUHP menyatakan:
“(1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya”
Dari pasal tersebut sebenarnya suatu perkara sudah dapat selesai tanpa masuk ke pengadilan dengan membayar denda maksimum dari tindak pidana. Hanya saja sangat sedikit tindak pidana yang diancam dengan denda saja, padahal tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang ringan. Sebagai contoh dalam Pasal 281 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) mengemudikan kendaraan bermotor diancam dengan kurungan selama 4 (empat) bulan dan denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Contoh lainnya, Pasal 315 KUHP mengatur mengenai penghinaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu.
Selain sedikitnya tindak pidana yang hanya diancam dengan denda, hal yang menjadi permasalahan lainnya adalah besaran denda yang terlalu kecil. Ini terjadi karena tidak pernahnya pengaturan mengenai denda atau besaran denda tersebut di revisi. Padahal Mahkamah Agung sudah mencoba untuk mendorong dilakukannya revisi tersebut melalui Perma No. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
Mungkin dalam hal ini kita bisa mencontoh Belanda sebagai negara yang mana KUHP kita berasal. Apabila kita melihat pengaturan dalam KUHP Belanda saat ini sudah terjadi perubahan dimana dalam Pasal 74 KUHP Belanda diatur untuk tindak pidana dibawah 6 (enam) tahun dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan beberapa cara seperti membayar denda maksimum, penyitaan barang dari pelaku, ganti rugi hingga bekerja tanpa upah.
Dalam Revisi KUHP mengenai hal ini juga sudah terdapat perubahan, dimana RKUHP membaginya dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
- Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II. Apabila pelaku tindak pidana yang diancam dengan denda kategori II tersebut bersedia untuk membayar jumlah denda maksimum, maka Jaksa Penuntut Umum wajib untuk menyetujui.
- Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat menerima atau menolak keinginan dari pelaku tindak pidana untuk membayar denda maksimum.
2. Mediasi Penal
Pengaturan mengenai Mediasi Penal ini tidak diatur dalam peraturan yang setara dengan undang-undang, namun sebenarnya ada beberapa peraturan di bawah undang-undang yang telah mengaturnya, khususnya yang terkait kewenangan diskresi. Diantaranya adalah Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Namun dalam praktik mengenai mediasi penal ini masih jarang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam Surat Kapolri tersebut diatas ditentukan beberapa langkah penanganan kasus melalui ADR, yaitu:
- Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
- Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.
- Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.
Selain peraturan tersebut, mediasi penal juga terlihat dari yurisprudensi Mahkamah Agung. Misalnya Putusan MA No. 1644 K/Pid/1988[11], Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur No. 46/Pid/78/UT/WAN[12] dan Putusan MA No. 1600 K/Pid/2009[13].
Dari penjelasan di atas, patut dipertanyakan kebijakan hukum pidana Indonesia yang seakan-akan melihat hukum pidana dan pemidanaan sebagai suatu hal yang diutamakan yang mana dapat dilihat dari pengaturan dan berimbas pada jumlah penghuni Lapas. Padahal dalam Hukum Pidana dikenal asas Ultimum Remedium atau sebagai upaya terakhir apabila upaya lainnya telah gagal. Untuk itu perlu ditegakkan beberapa hal yaitu pengaturan mengenai Pasal 82 KUHP dan mediasi penal di Indonesia. Apabila terhadap kedua hal tersebut dapat di efektifkan kembali sebagaimana seharusnya, maka bukan tidak mungkin kerusuhan lapas akan berkurang, akan ada penghematan anggaran negara atau bahkan penambahan penghasilan negara yang berasal dari para pelaku pelanggaran.
[1] Andi Zainal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, (Bandung: Alumni, 1987), Hal. 16.
[2] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Eresco, 1989), Hal. 16.
[3] Anugerah Rizki Akbari, Press Release MAPPI FHUI: Aturan Pidana Menjamur Lapas Semakin Penuh, 2016
[4] Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G Peter, Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif,(Jakarta: Aksara, 1981), Hal. 28.
[5] Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia, 1990), Hal 50.
[6] Data diambil dari http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily pada tanggal 3 Juli 2016
[7] Martin Moerings, Apakah Pidana Penjara Efektif: Dalam Hukum pidana dalam perspektif, (Jakarta: Pustaka Larasan, 2012), Hal. 235.
[8] Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, Hal. 3.
[9] Ibid., Hal. 10.
[10] Mahkamah Agung, Statistik Perkara Pidana Tahun 2013, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2014).
[11] Apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian telah diselesaikan dengan diberikan sanksi adat, maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi sebagai terdakwa dalam Pengadilan Negeri dengan dakwaan yang sama.
[12] Adanya penyelesaian secara perdamaian maka perbuatan para pihak tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi.
[13] MA mempertimbangkan pencabutan pengaduan, walaupun pencabutan tersebut sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam aturan KUHP, dengan alasannya keluarga korban dan keluarga pelaku sudah berdamai.
Ikuti tulisan menarik Ade Rizky Fachreza lainnya di sini.