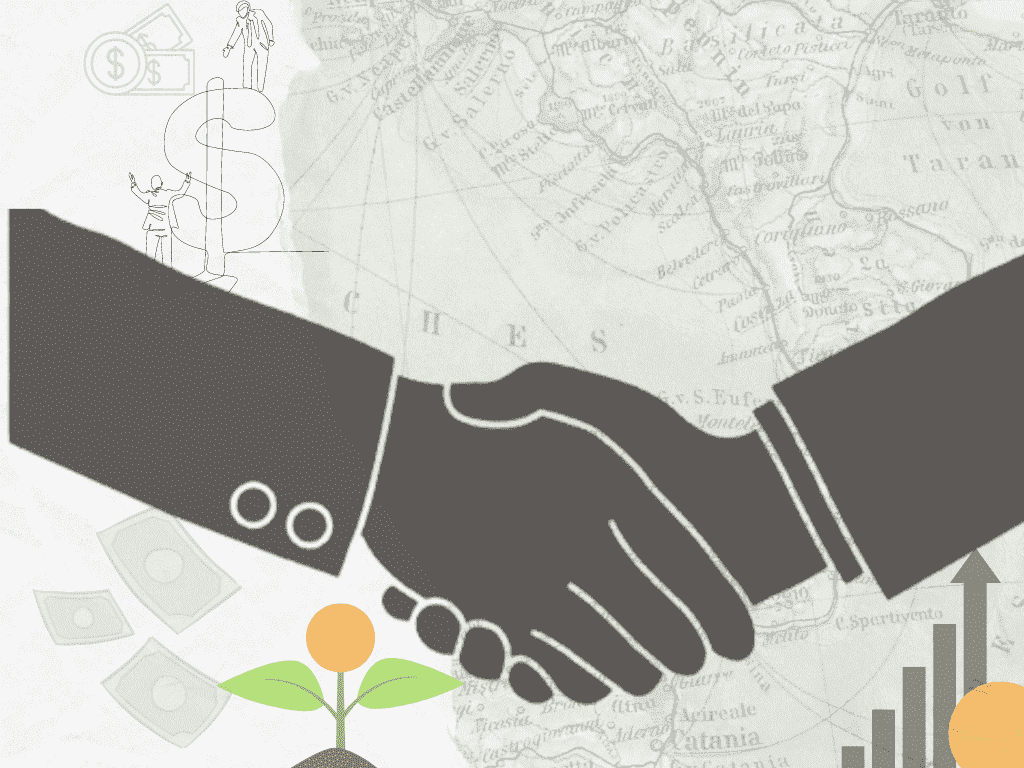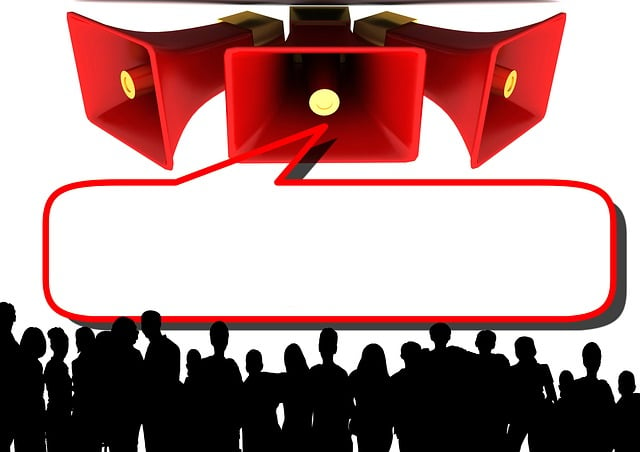Sikap toleran sudah seharusnya menjadi landasan bertindak dan bersikap di negara majemuk, seperti Indonesia. Apalagi dengan balutan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini sungguh menunjukkan betapa lemahnya kita menginternalisasi nilai-nilai kebhinnekaan.
Sikap toleran sudah seharusnya menjadi landasan bertindak dan bersikap di negara majemuk, seperti Indonesia. Apalagi dengan balutan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini sungguh menunjukkan betapa lemahnya kita menginternalisasi nilai-nilai kebhinnekaan.
Murni atau tidak niatan membawa pernyataan blunder Ahok terkait Surat Almaidah ke pengadilan, telah menciptakan perang opini yang dahsyat di media sosial. Perdebatan yang terjadi menunjukkan bibit-bibit keruntuhan persatuan. Banyak orang yang memanfaatkan kasus ini, terutama mereka pecinta perpecahan. Sayangnya, tak sedikit yang tersulut dan semakin menambah jumlah bumerang kerukunan. Ditambah lagi dengan kasus pemboman gereja di Samarinda. Kenapa kita tidak cukup toleran di negara yang majemuk ini?
Ada dua hal yang menjadi penyebab utama. Tak pernah mengalami menjadi minoritas dan tak pernah menyaksikan keteladanan.
Sebagai negara majemuk, Indonesia dihuni oleh enam agama yang diakui dengan statistik Islam (87,18%), Kristen (6,96%), Katolik (2,9%), Hindu (1,69%), Buddha (0,72), Kong Hu Chu (0,05), lain-lain (0,13) sesuai dengan sensus penduduk 2010. Penyebaran agama-agama ini tidaklah merata. Beberapa daerah dihuni mayoritas agama tertentu. Seperti Bali mayoritas penduduknya agama Hindu. Di Timur Indonesia mayoritas Kristen. Pulau Jawa dan beberapa daerah lain mayoritas Islam. Sehingga tidak sulit menemukan daerah-daerah yang benar-benar homogen atau hampir 99% masyarakatnya satu agama.
Kita juga mengenal sekolah-sekolah homogen, berdasarkan agama. Misalnya Sekolah Katolik Santa Maria, Sekolah Swasta Methodist, Sekolah Madrasah, dan lain-lain. Biasanya sekolah-sekolah ini berbentuk yayasan yang telah menyediakan tingkat pendidikan mulai dari TK hingga SMA. Siswa, guru, dan pengurus di sekolah ini biasanya semua beragama sesuai dengan aliran sekolah tersebut. Kalaupun ada yang beda agama, paling satu atau dua orang. Itupun harus menandatangani surat kesepakatan.
Maka dapat dibayangkan, seorang Katolik di Nusa Tenggara Timur yang belajar di Yayasan sejak TK hingga SMA, teman-temannya semua beragama Katolik. Demikian halnya dengan seorang Islam. Apalagi mereka masuk asrama di yayasan tersebut atau pesantren. Maka interaksi yang terjadi hanya sesama agama mereka.
Tahun 2013 lalu, pada sebuah kemah mahasiswa di Jakarta, saya berkenalan dengan seorang teman dari Universitas Islam Syarief Hidayatullah Jakarta. Ia mengaku baru berinteraksi dengan non Islam setelah jadi mahasiswa karena selama ini tinggal di lingkungan Islam dan belajar di sekolah Islam. Untungnya, dia orang yang mudah menerima perbedaan. Selama dua minggu kemah tersebut, interaksinya dengan peserta non Islam berlangsung baik, dialognya membangun.
Bayangkan berapa banyak orang Indonesia yang seperti dia, hanya berinteraksi di lingkungan yang homogen. Kalau mereka semua mudah menerima perbedaan, tidak masalah. Masalahnya tidak semua demikian.
Menumbuhkan sikap toleransi tidak semudah menanam ubi kayu. Seorang guru tidak akan cukup berhasil menanamkan toleransi hanya dengan mengatakan “hargai temanmu yang berbeda agama”, sementara siswanya tidak pernah melihat wujud yang berbeda itu. Di sisi lain stigma buruk terhadap agama lain telah ada sejak zaman dulu dan terus digemakan oleh orang-orang yang tidak suka perbedaan. Dan akan lebih parah lagi jika di sekolah siswanya tidak diajarkan sikap toleransi.
Mereka yang interaksinya hanya dengan orang-orang seagama tak akan pernah mengalami bagaimana rasanya menjadi minoritas. Parahnya, sudah tak pernah mengalami menjadi minoritas, tidak diajarkan bersikap toleran, dan dalam dirinya muncul etnosentrisme. Maka tidak heran, ketika berhadapan dengan minoritas, keangkuhan merajalela.
Seseorang dalam dinding facebooknya pernah menulis, “Wahai kalian kaum mayoritas, merantaulah dan menjadi minoritas. Agar terhindar dari rasa belagu dan kebanggaan semu.” Menjadi minoritas akan memberikan pengalaman bagaimana diperlakukan oleh mayoritas.
Kita pasti ingin diperlakukan orang lain seperti yang kita harapkan. Maka pengalaman menjadi mayoritas dan minoritas dapat menjadi jalan menuju sikap menerima perbedaan. Oleh karena itu, seperti kata orang Padang, merantaulah! Bagi sekolah-sekolah keagamaan, pertukaran pelajar bisa menjadi cara yang ampuh menumbuhkan sikap toleran.
Penyebab kedua adalah kurangnya tauladan. Tak banyak yang memberi contoh sikap toleran. Negara sama sekali tak bisa diharapkan. Mau berharap apa? Pelaku utama bahkan negara. Sebut saja kebijakan diskriminatif, pembagian agama diakui dan tidak diakui, peraturan pendirian rumah ibadah, dan lain-lain. Jadi memang, berharap adanya tauladan juga bak mimpi di siang bolong.
Dulu, kita masih punya Abudrahman Wahid atau Gusdur. Ia pernah berkata, “Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama. Ada enam agama yang diakui di Indonesia, jadi tolong hargai lima agama yang lain.” Ia sosok pluralis yang diteladani banyak orang. Para pengikutnya disebut Gusdurian. Semoga mereka terus mengobarkan semangat toleransi Gusdur. Tentunya ini tugas kita bersama demi kejayaan berbhinneka.
Sekali lagi, “merantaulah!”
Sumber foto: https://3.bp.blogspot.com/-rxIOFZf59aE/Vv6Vqc0rDUI/AAAAAAAACsI/u3qcHJgEoCYuJ3PzvgF_4lJqGDxv2gkAQ/s1600/photo_03-750x500.jpg
Ikuti tulisan menarik Martin Rambe lainnya di sini.