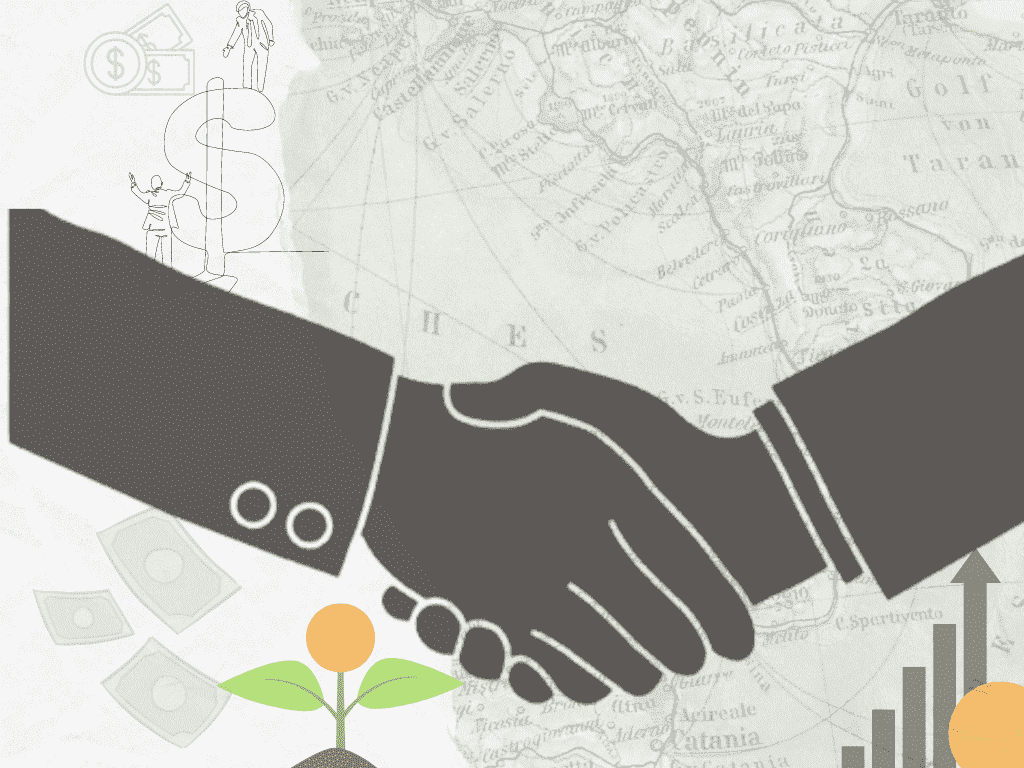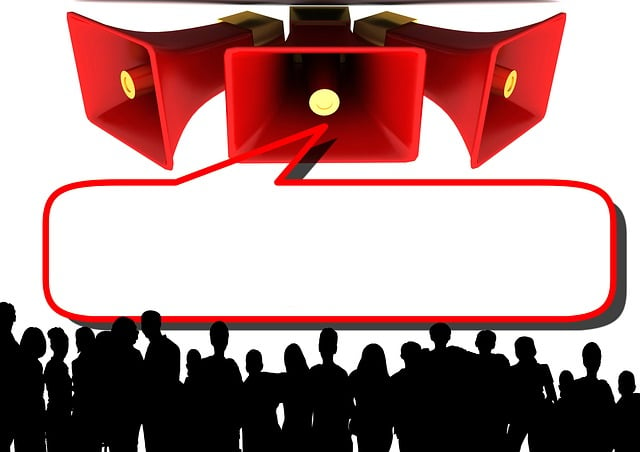Tindak kekerasan yang dilakukan oleh taruna senior kepada yunior kembali terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Cilincing, Jakarta Utara. Kali ini yang menjadi korban tewas adalah Amirullah Adityas Putra (18), taruna Tingkat I yang tewas dianiaya para taruna seniornya, Tingkat II. Jujur saja, sebagai orang tua yang juga punya anak seusia Amirullah, mendengar berita tersebut muncul perasaan kaget, sedih dan bercampur marah, geram, dan jengkel. Kaget karena terulang kembali. Bayangkan, Amirullah itu adalah anak kandung kita, yang susah payah mengandung, melahirkan, membesarkan, dan menyekolahkan. Giliran sudah dewasa, dibunuh oleh kakak kelasnya di kampus tempat dia mau meniti masa depannya. Inilah tragedi pendidikan yang memilukan. Pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia muda, dan melahirkan manusia-manusia yang berjiwa merdeka dan demokratis, tapi justru melahirkan kebiadaban. Ini tidak bisa ditolerir, apalagi terjadi berulang kali pada institusi yang sama.
Semula saya memperkirakan Dimas Dikita Handoko (19) yang tewas setelah dianiaya tujuh taruna senior di rumah kos (25/4 2014) akan menjadi korban terakhir tindak kekerasan di lingkungan STIP, karena saat itu para pejabat Kementrian Perhubungan, melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mencoba mencari masukan dari berbagai pihak untuk mencegah terulangnya kembali tragedi pendidikan yang memilukan itu. Mereka bertekad untuk menghilagkan kultur kekerasan yang ada di semua STIP, sehingga saat itu para pengelola STIP yang dibawah langsung Kementerian Perhubungan dikumpulkan untuk mencari format baru pengelolaan STIP yang anti kekerasan. Namun ternyata kultur kekerasan itu belum putus. Dimas Dikita bukanlah korban terakhir di lingkungan STIP, masih ada Roberto Tampubolon yang sempat dirawat di rumah sakit (2015) dan sekarang Amirullah Adityas Putra.
Respon pertama publik ketika mendengar kasus kekerasan terulang kembali di STIP adalah “bubarkan saja lembaga itu”. Respon spontan itu punya dasar kuat, kalau suatu tindakan yang sama terus terulang pada tahun-tahun berikutnya, berarti ada yang tidak beres di institusi tersebut. Sangat mungkin, fungsi kontrol tidak berjalan dengan baik. Sebab kalau fungsi kontrol berjalan dengan baik, maka akan mampu mencegah terjadinya pengulangan peristiwa serupa.
Namun, membubarkan institusi seperti STIP bukanlah jalan yang tepat mengingat STIP dibangun dengan menggunakan dana APBN ratusan miliar rupiah dan kehadirannya amat membantu industri pelayaran nasional maupun internasional. Dengan demikian, jalan penyelesaian yang tepat adalah mempertahankan keberadaan institusi STIP dengan perombakan mendasar mengenai paradigma pendidikan di STIP, sistem pengelolaan persekolahan, metode pembelajaran, serta relasi antara para pihak yang di dalamnya.
Sanksi Bukan Solusi
Secara managerial, tindakan yang diambil Kementrian Perhubungan sudah tepat, yaitu membebas-tugaskan Ketua STIP dan memecat para taruna pelaku penganiayaan, selain diproses secara hukum. Tapi sanksi itu belum merupakan solusi permanen, ibarat luka di tubuh kita, sanksi itu baru obat merah untuk mengobati luka sesaat guna mengurangi rasa nyeri dan sakit, setelah itu perlu obat lain yang lebih permanen, termasuk mampu membersihkan bekas-bekas lukanya. Yang diperlukan oleh Kementrian Perhubungan sekarang adalah obat permanen tadi agar bekas-bekas luka itu tidak tampak lagi. Sanksi itu penting untuk memberikan shock therapy kepada managemen maupun taruna agar tidak terulang kejadian yang sama. Meskipun masih ada yang keberatan terhadap sanksi pemecatan para taruna dengan alasan Negara rugi karena investasi mendidik para taruna yang dikeluarkan oleh Negara itu menjadi sia-sia, padahal kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pelayaran sangat tinggi; tapi menurut hemat penulis sanksi itu sudah tepat. Negara justru akan rugi semakin besar bila para taruna yang sudah memiliki naluri kekerasan itu tetap diperbolehkan melanjutkan pendidikannya di STIP.
Pertama, kultur kekerasan tidak akan hilang karena para pelaku kekerasan tidak dipecat, sehingga akan diprofuksi setiap saat. Kedua, tidak manusiawi dan melukai hati anggota keluarga korban, mereka telah kehilangan anak karena dibunuh seniornya, sementara si pembunuh diberi kebebasan untuk tetap bersekolah hingga tuntas. Ini betul-betul sangat tidak manusiawi. Ketiga, jika naluri kekerasan itu terus terbawa sampai dengan menjadi pelaut, maka bukan hanya akan merugikan diri sendiri saja, tapi juga merugikan orang lain dan Negara. Kasus pembunuhan yang dilakukan pelaut Visa Susanto terhadap kapten kapal Te Hung Hsing 368 milik Taiwan, terlepas dari alas an pembunuhan, telah merugikan Visa sendiri dkk., juga turut membuat Negara repot. Dengan kata lain, memecat taruna yang melakukan tindak kekerasan terhadap yunior itu jauh lebih aman dibandingkan dengan membiarkan mereka di kampus sampai lulus.
Mengubah Paradigma
Wajah institusi pendidikan amat tergantung pada impian yang kita bangun. Jika yang diharapkan lahir dari STIP itu adalah calon-calon nahkoda yang handal (Nautika), ahli mesin kapal (Teknika), atau orang-orang yang menguasai dokumen-dokumen kapal dan muatannya (Ketatalaksanaan dan Kepalabuhan), maka tentu saja wajah pendidikan yang tampil bukan wajah sangar penuh dengan otot kekar, melainkan kompeten dalam bidang masing-masing. Secara fisik untuk bidang neutika dan teknika memang harus kuat agar punya daya juang yang tinggi saat menghadapi emergensi. Kuat bukan dalam artian tahan menerima pukulan atau tendangan, melainkan sesuai kompetensinya. Bagi seorang nahkoda, dia harus memiliki daya tahan untuk menjalankan kapal dalam kondisi ombak yang tinggi sekalipun. Juga mampu melakukan perpindahan moda secara cepat di tengah lautan, dari kapal kontrol ke kapal besar misalnya. Sebaliknya bagi seorang teknika, kebutuhan fisik mereka adalah tahan menghadapi kondisi gelap dan pengab (karena mesin kapal mati), ombaknya besar, tapi tetap harus bekerja memperbaiki mesin kapal. Kemahiran berenang menjadi sangat penting bagi keduanya untuk menghadapi kondisi emergensi di tengah lautan.
Kompetensi dari seorang ahli Ketatalaksanaan dan Kepalabuhan berbeda lagi, lebih menuntut ketelitian, ketekunan, keakuratan, dan kecepatan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga keahlian tersebut tidak mensyaratkan adanya fisik yang tahan pukul dan tendangan, tapi fisik yang tahan menghadapi tantangan di lautan. Oleh karena itu, model-model pendidikan yang menggunakan kekerasan fisik tidak relevan sama sekali. BPSDM Kementrian Perhubungan perlu merumuskan kembali paradigma di STIP agar dapat memutus kultur kekerasan. Hal-hal yang tidak menunjang peningkatan kompetensi, sebaiknya dibuang saja, lalu fokus ke peningkatan kompetensi sesuai dengan program studinya.
Usulan lain dalah sistem asrama penuh selama kuliah itu perlu dievaluasi, mengingat tidak mudah mengontrol perilaku ribuan taruna setiap jamnya. Asrama lebih tepat untuk taruna tahun pertama saja, selanjutnya biarkan taruna mencari kos di luar kampus. Pengelolaan maupun pembinaan asrama pun tidak boleh melibatkan taruna senior, tapi hendaknya orang-orang yang sudah matang jiwanya. Kecuali itu, seleksi masuk ke STIP sebaiknya juga mendasarkan pada hasil psikotes agar calon taruna yang punya potensi konflik tinggi dapat dihindari. Dan belajar dari kasus perbudakkan terhadap pelaut-pelaut Indonesia di kapal-kapal tangkapan ikan Taiwan, maka materi tentang hukum perburuhan serta pelajaran bela diri sebaiknya diberikan pada semua prodi agar mereka kelak menjadi pelaut yang punya posisi tawar tinggi. Ironis sekali bila di dalam kampus jagoan, tapi di luar jadi budak kapal asing.
Darmaningtyas
Penulis Buku Pendidikan yang Menyengsarakan
Ikuti tulisan menarik Darmaningtyas lainnya di sini.