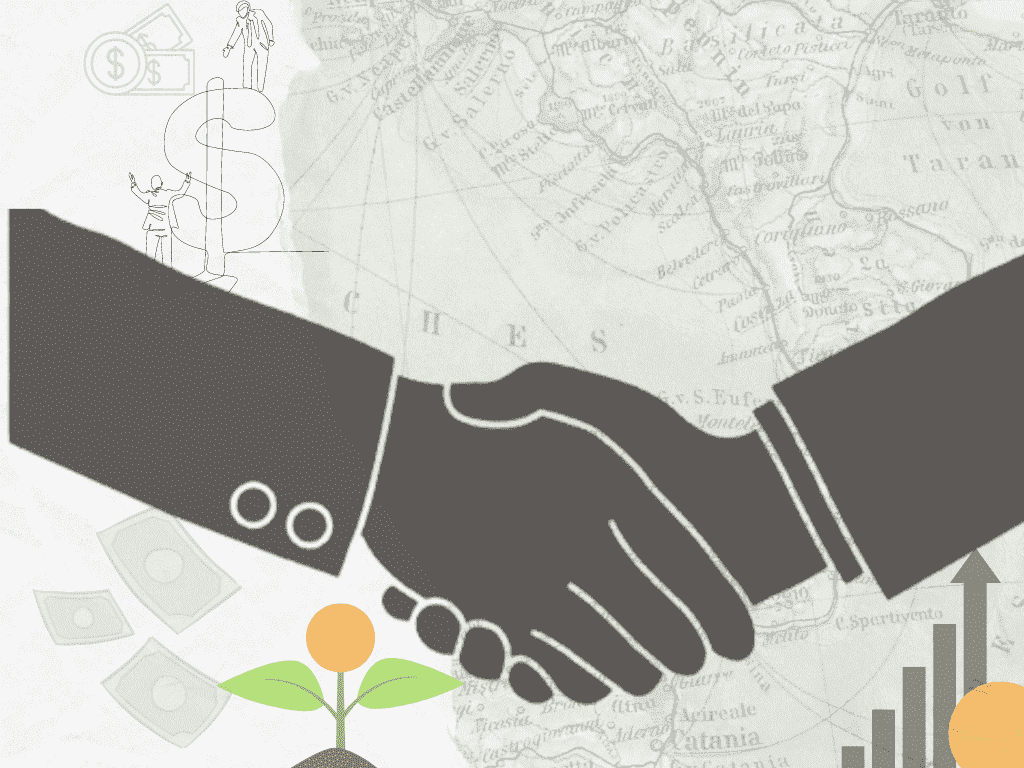Akhir-akhir ini diskursus tentang populisme ramai dibicarakan di kalangan akademisi maupun aktifis di tanah air. Terutama paska peristiwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Britain Exit) sampai keterkejutan dunia atas terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Orang juga menghubungkan kebangkitan populisme di kalangan Islam politik di Indonesia dengan gerakan Aksi Bela Islam yang menuntut pemenjaraan Basuki T. Purnama (Ahok) atas tuduhan penistaan agama.
Bagaimana sebenarnya kalangan akademisi memahami populisme ini sebagai ideologi gerakan politik? Sebab di kalangan ilmuwan politik sendiri sebenarnya masih sulit mendapatkan kesepakatan tentang definisi populisme. Salah satu problemnya adanya bias ideologi di kalangan akademisi itu sendiri.
Buku Jan-Werner Müller (2016) adalah contoh bagaimana akademisi berideologi liberal membangun serangkaian stereotype dari populisme. Memang, ideologi dan pemikiran ekonomi liberal menganggap populisme sebagai ancaman terhadap demokrasi dan keberlangsungan liberalisme. Kemudian yang tidak terlalu partisan pun, seperti Pappas (2016) mengajukan populisme sebagai democratic illiberalism.
Sementara itu, intelektual berlatar belakang gerakan keadilan sosial berada di antara simpati, seperti Laclau (2005), atau antipati terhadap populisme, seperti berbagai “sekte” pemikiran kiri (sosialis). Mereka yang antipati secara ideologis memandang populisme akan berakibat negatif terhadap kemajuan gerakan rakyat, karena menyebabkan terjadinya disorientasi gerakan dan ideologi massa.
Problem kedua, gerakan atau aktor politik yang dikategorikan populis juga sangat jarang menyebut dirinya sebagai pengusung populisme. Selain itu, identifikasi ideologi populis juga sulit karena gerakan politik populisme bisa melibatkan kedua sisi “kiri” dan “kanan” dan juga “tengah” dalam spektrum pemikiran politik.
Dalam studinya tentang perkembangan populisme di Amerika Latin, Roxborough (1986), mengatakan bahwa gerakan populis biasanya tidak diorganisasikan sebagai partai. Melainkan sebagai gerakan yang longgar dari seorang pemimpin dan para pengikutnya. Menurutnya populisme adalah sebuah gerakan politik yang tidak diorganisir menurut garis kelas.
Populisme membantah masyarakat terbagi dalam garis kelas dan membagi politik antara rakyat dan musuh-musuh rakyat, baik musuh dari dalam maupun dari luar. Meskipun populisme tidak menyatakan dirinya sebagai gerakan politik dengan identitas kelas, bukan berarti populisme dapat dipandang tidak mewakili kepentingan kelas.
Gerakan yang menegaskan dirinya bukan kelas bisa saja terdiri dari kelas-kelas atau sekurang-kurangnya dapat diidentifikasi dalam kaitanya dengan kelas dan kepentingan kelas. Dalam kasus populisme di Amerika Latin, populisme adalah suatu tanggapan atas situasi historis tertentu yaitu gagalnya model pertumbuhan yang berorientasi ekspor dan krisis negara oligarki yang menyertainya. Dalam situasi ini hegemoni harus berganti dari kaum oligarki kepada kaum borjuasi industri baru dan elite, yang mensyaratkan reorganisasi sistem politik dan aparatus negara.
Untuk kepentingan tersebut kaum borjuasi bersekutu dengan kelas menengah kota dan kaum buruh untuk mempertemukan kepentingan nyata di antara mereka. Populisme menautkan aliansi kelas ini dalam mengekspresikan kepentingan bersama kelas sosial. Dalam kasus Amerika Latin, populisme menjadi bentuk politik transisional dimana pada akhirnya akan memapankan hegemoni kelas borjuasi dan menyingkirkan elemen lainya.
Populisme dalam sejarah Indonesia, mempunyai karakter yang berbeda dengan kasus Amerika Latin. Di era Sukarno populisme justru bergerak ke arah progresif, menjadi alat konsolidasi populer menentang neokolonialisme dalam rangka mewujudkan mimpi Sukarno untuk menciptakan “sosialisme ala Indonesia”.
Populisme di tahun 1960-an berpuncak pada karakter dan peran simbolis Sukarno sebagai pemersatu bangsa dan proklamator kemerdekaan untuk menolak apa yang disebutnya dengan neokolonialisme dan neoimperialisme (neokolim). Populisme Sukarno ditopang oleh aliansi politik yang mendukung kepemimpinanya dalam konsepsi persatuan nasional yang disebutnya dengan Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom).
Jatuhnya Sukarno menandai periode panjang pembekuan populisme. Rezim Orde Baru Suharto secara sistematik telah memberangus demokrasi dan ekspresi-ekspresi populisme melalui depolitisasi dan de-Sukarnoisasi. Namun proses tersebut tetap gagal. Meski beku, populisme tetap berada di benak rakyat, membentuk alam pikiran politik yang menuntun sejumlah aktor politik menyeru dan memobilisasi rakyat. Letupan-letupan gerakan populis tetap muncul seperti dalam protes SDSB (1991), penolakan intervensi Orde Baru atas kemunculan Megawati di PDI, penolakan Pemilu 1997, dan periode panjang gerakan mahasiswa 1998-1999.
Di era Jokowi, populisme lebih bersandar pada figur Jokowi itu sendiri. Populisme politik itu dibangun karena kemuakan rakyat akan negara dan parpol yang diangap korup dan oligarkis. Kemuakan tersebut lalu ditransformasikan menjadi partisipasi elektoral mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu karena dipandang jujur, sederhana, dan bukan mewakili oligarki elit politik. Jokowi dianggap sebagai representasi masyarakat, seperti dalam slogan kampanye “Jokowi adalah kita”.
Kemunculan sosok Jokowi dalam membangun relasi dukungan personal oleh gerakan relawan yang tidak diikat dalam sebuah organisasi partai politik merupakan ciri dari sebuah gerakan populisme. Populisme politik Jokowi sudah dimulai dari proses pencalonan sebagai presiden, kampanye, pencoblosan hingga pelantikan, dimana telah terjadi persekutuan lintas kelas untuk membawa perubahan, mereorganisasi negara yang korup warisan Orde Baru.
Populisme Jokowi mulai dibangun saat jadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta melalui program populis di bidang kesehatan dan pendidikan untuk rakyat miskin. Populisme Jokowi ini makin kuat dengan pendekatan “blusukan” untuk mengetahui problem langsung masyarakat dan mendiskusikan solusinya dengan mereka. Kesan pejabat negara yang angkuh, birokratis, korup dan formal serta berjarak, ia runtuhkan dengan dialog dan informalitas. Dan pendekatan ini masih ia lakukan sampai hari ini sebagai “JokoWay” dalam menjalankan program Nawacita.*)
Penulis adalah Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden.
Ikuti tulisan menarik Eko Sulistyo lainnya di sini.